Syarat Capres, Piala Dunia, dan Rasionalitas
Konten dari Pengguna
1 Juli 2018 21:27 WIB
Tulisan dari Denny Indrayana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
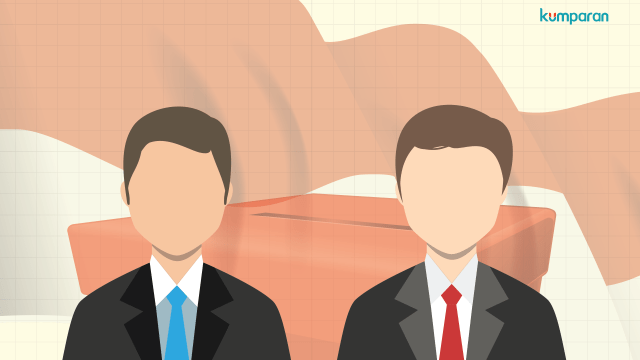
ADVERTISEMENT
Kali ini kami akan berbicara dua isu paling penting sekaligus aktual di jagad tanah air. Yang pertama adalah detik-detik menjelang pendaftaran Bakal Calon Presiden (dan Wakil Presiden) pada 4 hingga 10 Agustus 2018, sebagai bagian dari tahapan hajatan besar Pemilihan Presiden 2019, dan yang kedua, Piala Dunia sepakbola yang memasuki babak gugur 16 besar, sebelum final dan penentuan juara pada 15 Juli 2018.
ADVERTISEMENT
Terkait syarat capres, saat ini INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution and Society) sedang menjadi kuasa hukum bagi 12 tokoh nasional yang menggugat (lagi) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur syarat ambang batas dukungan parpol bagi calon presiden atau dikenal dengan istilah presidential threshold.
Rumitnya, di tengah iklim kontestasi menjelang Pilpres 2019, setiap ikhtiar selalu dipandang secara politis, padahal yang kami perjuangkan adalah hadirnya aturan main yang lebih adil bagi semua bakal capres dan rakyat pemilih. Namun, tidak sedikit komentar yang membaca permohonan ke MK tersebut sebagai dukungan kepada kubu capres yang satu, dan penolakan kepada kubu capres yang lain.
Posisi kami sebagai Wamenkumham (2011-2014) di era Presiden SBY, dianggap membawa kepentingan partisan. Tentu pandangan dan kecurigaan orang yang demikian tidak bisa dilarang. Ini negara bebas, setiap orang merdeka untuk berpikir dan berprasangka.
ADVERTISEMENT
Namun, atas kecurigaan demikian kami katakan, silakan dilihat tokoh-tokoh nasional yang menjadi pemohon: Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, Chatib Basri, Faisal Basri, Hadar Gumay, Rocky Gerung, Robertus Robet, Feri Amsari, Angga Dwimas Sasongko, Hasan Yahya, Dahnil Anzar Simanjuntak (Pemuda Muhammadiyah), dan Titi Anggraini (Perludem). Mereka adalah tokoh-tokoh nasional yang merdeka, dan tidak mungkin disetir oleh siapapun, apatah lagi oleh kami yang bukan siapa-siapa.
Beberapa hari ini sengaja diedarkan pendapat kami di sidang Mahkamah Konstitusi ketika menjadi Staf Khusus Presiden (2008 – 2011), yang dianggap membela presidential threshold dan bertolak belakang dengan permohonan kali ini yang menolak syarat ambang batas calon presiden tersebut.
Tidak kurang dari Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti, Para Ahli permohonan yang mengkonfirmasi hal tersebut langsung ke WA kami. “Den, ente mulai diserang”, kata salah satunya.
ADVERTISEMENT
Awalnya, kami ingin mendiamkan saja plintiran berita semacam itu. Pada saat awal mengambil inisiatif mendorong permohonan ini, kami sangat paham pasti akan menimbulkan reaksi. Namun, karena yang diserang adalah kredibilitas akademik, akhirnya kami putuskan untuk menjelaskannya dalam tulisan berikut. Alasan lain, kami tidak ingin plintiran opini demikian menimbulkan dampak negatif kepada permohonan uji materi yang sedang kami wakili di MK.
Sebenarnya, penjelasannya mudah. Posisi kami untuk syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)—ataupun isu hukum ketatanegaraan yang lain—selalu berdasarkan kajian dan pertimbangan akademik, bukan politik, apalagi politik praktis. Itulah bedanya niat kami, serta dua belas pemohon, dengan beberapa komentator yang mengatakan permohonan uji materi ini akan menguntungkan capres tertentu dan merugikan capres yang lain. Kami tidak berhitung untung-rugi politik elektoral demikian.
ADVERTISEMENT
Bagi kami, perjuangan ini adalah ikhtiar untuk menghadirkan ruang kontestasi yang lebih fair bagi makin banyak calon presiden, sekaligus memberikan pilihan capres yang lebih variatif dan berkualitas bagi rakyat pemilih.
Karena pertimbangan akademik itulah sedari awal posisi kami tidak semata menolak ataupun menerima presidential threshold, bukan posisi hitam-putih. Tetapi lebih melihatnya secara komprehensif, sebagai satu kesatuan membangun desain sistem pemilu yang demokratis.
Bagi kami ukurannya adalah rasionalitas sekaligus konstitusionalitas sistem pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, dalam hal presidential threshold yang berubah bukan posisi akademik kami, tetapi bangunan sistem pemilu kita sendiri. Dan, yang merubah bangunan pemilu itu adalah Mahkamah Konstitusi, bukan saya.
Putusan-putusan Mahkamah sebelumnya menggariskan bahwa pemilihan presiden dan legislatif adalah dua pemilu yang terpisah. Namun, pada putusan 2014, menjelang pemilu, Mahkamah merubah posisinya, dan mengatakan bahwa yang konstitusional adalah pemilu presiden dan legislatif yang dilaksanakan serentak, pada waktu yang bersamaan.
ADVERTISEMENT
Perubahan dari pemilu presiden dan legislatif yang awalnya berbeda waktu selang beberapa bulan, menjadi bersamaan di hari yang sama, itulah yang menyebabkan konsep syarat ambang batas capres, dari awalnya memungkinkan dilaksanakan (rasional) menjadi konsep yang tidak lagi konstitusional.
Itu sebabnya dalam keterangan pemerintah yang kami berikan di Mahkamah, posisi akademik kami melihat presidential threshold masih mungkin diterapkan, alias masih konstitusional. Dalam artikel kami “Mendesain Pilpres Antikorupsi” (Kompas, 29 Juni 2017), sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kami juga berpandangan presidential threshold memang konsep yang terbuka dan problematik.
Namun, setelah pasal 222 UU 7/2017 resmi diberlakukan, dan penghitungan presidential threshold didasarkan pada hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya, maka kami lebih menegaskan posisi akademik untuk menolak syarat ambang batas capres yang demikian.
ADVERTISEMENT
Kenapa pandangan kami bergeser? Jawabannya mudah. Pertama, karena sedari awal bagi kami soal presidential threshold bukan hitam-putih, pasti salah, atau pasti benar, tetapi tergantung keseluruhan sistem pemilu yang menyertainya.
Maka, pada saat sistem pemilunya adalah pemilu serentak (concurrent) antara pilpres dan pileg, presidential threshold menjadi sistem yang tidak lagi rasional untuk diterapkan. Mendasarkan penghitungan syarat ambang batas capres berdasarkan hasil pemilu DPR yang sudah berlangsung lima tahun sebelumnya, menurut kami bukan hanya irasional, tetapi lebih jauh telah menghilangkan esensi dasar penyelenggaraan pemilu yang salah satu alasan utamanya adalah pembaharuan mandat rakyat.
Dasar penghitungan dari pemilu DPR yang berlangsung lima tahun sebelumnya menafikan kemungkinan bergantinya mandat rakyat, dan karenanya tidak lagi sesuai dengan konstitusi.
ADVERTISEMENT
Jadi titik baliknya adalah pada perubahan sistem pemilu yang awalnya tidak serentak (inconcurrent) menjadi pemilu serentak (concurrent). Pergeseran posisi akademik itu justru adalah keniscayaan, karena berubahnya sistem pemilu berdasarkan putusan MK pada tahun 2014 tersebut. Yang aneh justru adalah pandangan yang tetap mempertahankan konsep presidential threshold, padahal sistem pemilunya sudah berubah menjadi serentak.
Mempertahankan konsep presidential threshold demikian bukanlah sikap konsisten, sebagaimana bergesernya sikap kami bukanlah sikap tidak konsisten. Pergeseran sikap akademik kami justru adalah tanggung jawab akademik kami atas sistem pemilu yang berubah. Lain halnya kalau sistem pemilunya tetap sama, tetap tidak serentak, dan kami berubah posisi, maka itu jelaslah inkonsisten.
Dalam situasi yang berubah, penyikapan yang berbeda bukanlah bentuk inkonsistensi. Justru, dalam hal ada perubahan situasi, tetapi responnya tetap sama, adalah hal yang cenderung aneh alias irasional. Ambil contoh, akhir pekan lalu, kami sekeluarga mengajak Ibunda ke Mount Buller (Melbourne) untuk bermain salju. Waktu tempuhnya adalah tiga jam lebih perjalanan berkendaraan.
ADVERTISEMENT
Dalam tiga jam itu, aturan kecepatan berubah-ubah, ada yang 100 km/jam di jalan bebas hambatan, 80 km/jam di jalan luar kota, 60 km/jam di jalan dalam kota, dan 40 km/jam jika ada perbaikan jalan.
Maka, bukanlah sikap yang inkonsisten jika kami merubah kecepatan kendaraan mengikuti rambu lalu lintas yang berganti-ganti, tergantung situasi dan kondisi jalan yang dilalui. Justru kalau terus berkendaraan dengan kecepatan sama 100 km/jam, maka kami keliru dan menabrak aturan lalu lintas yang berlaku.
Untuk lebih aktual, mari kita gunakan juga analogi aturan di sepakbola. Pada 2018, mulai diterapkan sistem Video Assistant Referee (VAR), yang belum pernah dilakukan dalam Piala Dunia sebelumnya.
Karena perubahan sistem perwasitan itu, maka semua insan sepakbola harus menyesuaikan diri dengan keputusan wasit yang bisa berubah-ubah tergantung VAR. Maka, hadirlah berbagai drama menegangkan ketika para pemain dan pelatih mendesak wasit untuk menggunakan VAR dalam memutuskan penalti, atau putusan-putusan krusial sejenisnya.
ADVERTISEMENT
Drama Piala Dunia 2018 bukan hanya rontoknya juara bertahan Jerman di babak penyisihan grup, bukan pula melulu soal gugurnya Argentina dan Lionel Messi, Portugal dan Christiano Ronaldo, ataupun Mesir dengan Mohamed Salah, tetapi adalah drama-drama keputusan wasit berdasarkan sistem VAR yang baru diterapkan.
Salah satu penentu menang dan kalahnya pertandingan saat ini adalah teknologi yang membantu kerja wasit tersebut. Setiap penikmat sepakbola harus menyesuaikan diri dengan perubahan sistem tersebut.
Penyesuaian demikian adalah keniscayaan karena aturan main yang berubah. Perubahan demikian bukanlah inkonsistensi, tetapi justru adalah adaptasi yang wajib dilakukan, adalah pilihan rasional yang harus diputuskan.
Demikian pula halnya dengan sikap akademik kami atas penerapan konsep syarat ambang batas pencalonan presiden. Awalnya kami berpandangan bahwa presidential threshold masih mungkin diterapkan karena sistem pilpres dan pileg yang masih tidak bersamaan.
ADVERTISEMENT
Namun sejak aturan baru diputuskan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014, bahwa kedua pemilu itu harus dilaksanakan serentak, maka kami melihat presidential threshold tidak lagi rasional dilakukan.
Memaksakan penerapannya adalah tindakan yang merusak sistem pemilu, khususnya hilangnya pembaharuan mandat pemilih, karena syarat capres dihitung berdasarkan hasil pileg yang dilaksanakan lima tahun sebelumnya.
Perubahan pandangan akademik kami yang demikian bukanlah sikap inkonsistensi, tetapi justru adalah adaptasi yang wajib dilakukan, adalah pilihan rasional yang harus dilaksanakan. Justru mempertahankan sistem presidential threshold dalam pemilu yang dilaksanakan serentak adalah pilihan yang irasional, dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, alias inkonstitusional.
Karena itu, kami mendorong Mahkamah Konstitusi untuk merubah posisinya atas konstitusionalitas syarat ambang batas capres. Perubahan putusan Mahkamah yang demikian bukan bentuk inkonsistensi, tetapi justru adalah konsistensi sikap Mahkamah untuk menjaga dan mengawal konstitusi, melindungi mandat rakyat pemilih dari sistem presidential threshold yang irasional, dan karenanya inkonstutisional. (*)
ADVERTISEMENT

