Sastra dan Bukan Sastra
Konten dari Pengguna
3 Agustus 2023 6:22 WIB
Tulisan dari Muhammad Ridwan Tri Wibowo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
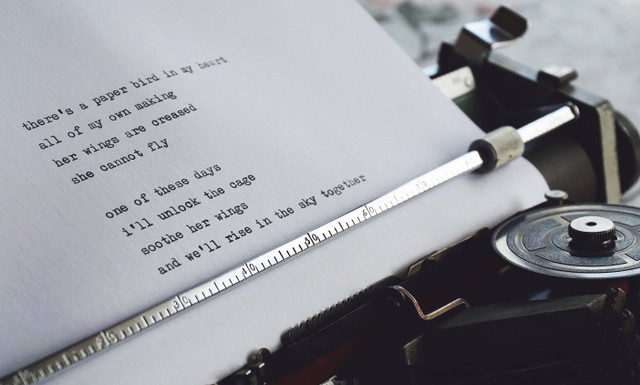
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sebagai orang yang berkecimpung di dunia sastra--entah dari akademisi atau penggiat sastra--kita pasti pernah bertanya; mengapa puisi mantra seperti Tragedi Winka dan Sihka karya Sutardji Calzoum Bachri (SCB) yang hanya menggunakan kata Winka dan Sihka dengan tipografi yang berbentuk zig-zag bisa diterima sebagai puisi.
ADVERTISEMENT
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat dengan oleh irama, matra, rima, serta penyunan larik dan bait. Dalam kasus SCB, terlihat jelas bahwa puisi Tragedi Winka dan Sihka tidak terikat oleh penyusanan larik dan bait.
Selain itu, SCB juga menulis puisi yang berjudul Luka; puisi itu hanya berisi kata, antara lain: /ha ha/ atau puisi yang berjudul Kalian; puisi itu hanya berisi kata, antara lain: /pun/.
Selanjutnya Danarto lebih ekstrim daripada SCB karena membuat puisi tanpa kata. Puisi konkretnya yang berjudul Petak Sembilan hanya berisi garis-garis yang membentuk sembilan petak.
Kemudian Remy Sylado dengan puisi mbelingnya. Ia berpendapat bahwa puisi bukan suatu hal yang serius apalagi agung, baginya puisi tidak lebih mulia dibanding naik kuda. Untuk itu, para penyair mbeling sering “mengejek” sajak “agung” yang telah dikenal masyarakat sastra dengan membuat parodinya.
ADVERTISEMENT
Mengutip buku Kesusastraan Indonesia Modern karya Sapardi Djoko Damono, Remy Sylado mengatakan bahwa membuat puisi itu gampang sekali, seperti orang yang meludah atau membuang ingus.
Tak berhenti di situ, Afrizal Malna membuat puisi dari daftar nama rempah-rempah yang diurutkan sesuai abjad dalam puisinya yang berjudul Jembatan Rempah-Rempah. Dan, Djenar Maesa Ayu malah membuat cerpen berjudul SMS, dan cerpen tersebut benar-benar bentuk seperti short message service (SMS).
Nah, mungkin dari kita akan bertanya mengapa puisi atau cerpen di atas bisa diterima sebagai karya sastra?
Bahasa Sastra dan Bahasa Sehari-hari
Kalau kita melihat perbedaan antara bahasa sastra dan bahasa ilmiah batasan sudah terlihat jelas: bahasa sastra memiliki segi ekspresif dan pragmatis yang dihindari sejauh mungkin oleh bahasa ilmiah.
ADVERTISEMENT
Lalu, bagaimana perbedaan bahasa sastra dan bahasa sehari-hari?
Menurut Wellek dan Warren dalam buku Teori Kesusastraan (Terjemahan Meliani Budianta), bahasa percakapan, bahasa perdagangan, bahasa resmi, bahasa keagamaan, dan slang anak muda termasuk dalam bahasa sehari-hari. Apa yang sudah disebut sebagai ciri bahasa sastra, juga terlihat dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
Misalnya, bahasa sehari-hari juga punya fungsi ekspresif—kadarnya beragam dari pengumuman resmi, orasi mahasiswa, sampai ratapan kesedihan pemuda yang dilandasi emosi. Bahasa sehari-hari juga penuh konsep yang irasional dan mengelami perubahan konteks sesuai dengan perkembangan sejarah bahasa.
Juga tidak bisa diragukan bahwa bahasa sehari-hari juga mempunyai tujuan mencapai sesuatu untuk mempengaruhi sikap dan tindakan. Kalau kita hanya membatasi fungsi bahasa sehari-hari pada komunikasi saja, bagimana dengan anak kecil yang mengoceh sendiran tanpa teman atau basi-basi orang dewasa yang tidak bermakna. Bukankah itu menunjukkan pengunaan bahasa yang tidak sepenuhnya dan tidak ditujukan terutama untuk komunikasi.
ADVERTISEMENT
Mungkin untuk perbedaan pragmatis antara bahasa sastra dan bahasa sehari-hari terlihat lebih jelas. Segala sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan tindakan langsung yang konkret, sukar kita terima bisa kita sebut sebagai puisi. Kalau pun kita terima, kita akan memberinya sebagai label retorik.
Jadi, pertama-pertama hanya secara kuantitatif saja dapat kita bedakan bahasa sastra dan bahasa sehari-hari. Dalam karya sastra, sarana-sarana bahasa dimanfaatkan secara lebih sistematis dari melihat suatu ”pribadi” yang lebih jelas sosoknya dan lebih menonjol dari pribadi orang yang kita jumpai dalam situasi sehari-hari. Ada tipe-tipe puisi tertentu yang dengan sengaja memakai paradoks, ambiguitas, pergeseran arti secara kontekstual, asosiasi irasional dengan menggunakan tata bahasa seperti gender dan tense. Bahasa puitis mengatur, memperkental sumber daya bahasa sehari-hari, dan kadang-kadang sengaja membuat pelanggaran-pelanggaran untuk memaksa pembaca memperhatikan dan menyandarinya.
ADVERTISEMENT
Cara-cara di atas banyak yang sudah dipakai dan ciptakan sebelumnya pada karya sastra berbagai generasi. Pada kesusastraan tertentu yang sudah sangat maju (dan terutama zaman-zaman tertentu), si penyair hanya mengikuti konvensi bahasa yang sudah mapan; boleh dikata, bahasalah yang memberikan muatan puitis pada karya si penyair.
Bahasa Puitis dan Bahasa Retorik
Menurut Al-Faribi dalam buku Putika karya Aristoteles (Terjemahan Cep Subhan), pernyataan yang sama sekali benar disebut demonstratif, pernyataan yang sebagian besar benar disebut argumentatif, pernyataan yang seimbang benar atau salahnya disebut retoris, pernyataan yang sebagian besar salah disebut sofistis, pernyataan yang keseluruhannya salah disebut puitis.
Kemudian Ibn Sina, menjelaskan tujuan umum puisi dan retorika ada tiga jenis, yaitu: pertimbangan yang mendalam, perdebatan dan deklamasi. Lalu yang membedakan, retorika hanya menggunakan penyajian obyektif, sementara puisi menggunakan representatif khayali.
ADVERTISEMENT
Tapi perlu kita sadari bahwa perbedaan antara seni dan bukan seni, antara ungkapan linguistik karya sastra dan non-sastra sangatlah cair. Fungsi estetis dapat terlihat dalam berbagai ujaran. Konsepsi kita terhadap sastra akan menjadi sempit kalau kita mengeluarkan semua jenis seni.
Pada berbagai periode sejarah, kawasan fungsi estetis tersebut bisa meluas dan menyempit; pada periode-periode tertentu surat-surat pribadi dan khotbah dianggap sebagai bentuk sastra. Wellek dan Warren dalam buku Teori Kesusastraan (Terjemahan Meliani Budianta), menjelaskan beberapa hal yang menjadi pembeda sastra dengan bukan sastra, salah satunya, yaitu organisasi.
Organisasi Berperan Penting dalam Menentukan Sastra
Dalam memahami sastra, kita sebagai akademisi atau penggiat sastra harus menguasai berbagai konvensi dalam sastra; baik itu bahasa, sastra, ataupun budaya. Dalam KBBI, bahasa memiliki arti yakni sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipakai oleh sebuah anggota atau suatu masyarakat untuk berinteraksi dan bersosialisasi.
ADVERTISEMENT
Siapa yang menetapkan aturan bahwa puisi ditulis dalam bait dan baris? Aturan itu disebut konvesi, yakni kesepakatan yang sudah diterima banyak orang dan sudah menjadi tradisi. Aturan dan konvensi bukan hanya berubah dari zaman ke zaman, tetapi juga berkaitan dengan konteks budaya pada masanya.
Menurut A. Teeuw dalam buku Sastra dan Ilmu Sastra, berpendapat konvensi dalam sastra bukan sesuatu yang mapan, tetapi dapat berubah terus, dapat dilanggar, dirombak, dan diperbarui lagi.
Jakob Sumarjo, seorang pelopor kajian filsafat Indonesia dan pemerhati sastra mengatakan bahwa sebuah karya sastra akan ditampilkan sesuai pada zamannya. Lalu, ia mejelaskan bahwa sastra pengaplikasian dari alam pikiran manusia, peristiwa kultural, dan adat istiadat yang memiliki nilai-nilai yang tinggi.
ADVERTISEMENT
Sebagai contoh, mengutip penutup buku kumpulan puisi Aku Ini Bintang Jalang: ChariL Anwar yang dikumpulkan oleh Pamusuk Eneste, Sapardi Djoko Damano menuliskan bahwa organisasi membawa peran penting dalam menentukan mana sastra dan bukan sastra—begitu juga sastra yang baik atau tidak.
Pada tahun 1965, komisaris dewan mahasiswa sebuah fakultas sastra menyatakan bahwa gagasan kepenyairan Chairil Anwar bertentangan dengan paham Sosialisme Indonesia dan Amanat Berdikari yang digariskan Bung Karno; pernyataan itu kemudian dibenarkan oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan, bahkan kemudian menolak tanggal 28 April--hari kematian Chairil Anwar--sebagai Hari Sastra.
Lalu setelah komunis runtuh, Islam berkembang semakin pesat di masyarkat Indonesia—khususnya pulau Jawa. Pada tahun 1968, majalah Horison dicekal oleh pemerintah dengan tuduhan melakukan penistaan agama atas diterbitkannya cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Pandji Kusmin. Kejadian inilah yang menjadikan dunia sastra gempar dan menjadi sorotan semua orang, maka kemudian disebutlah masa "Heboh Sastra". Peristiwa heboh sastra merupakan peristiwa pertama dalam karya sastra yang menjadi masalah pidana di pengadilan.
ADVERTISEMENT
Akhirnya ketika memasuki tahun 1970-an karya sastra yang dianggap baik pada tahunan tersebut adalah karya sastra yang bersifat transendental (keagamaan). Sebagai contohnya kita bisa membaca puisi ala-ala sufi Abdul Hadi W. M., Ahmadun Yosi Herfanda atau cerpen ala-ala sufi dari Darnato.
Mengutip esai Ahamadun Yosi Herfanda yang berjudul Reaktualisasi Fitrah Religuis Sastra, ia menuliskan bahwa semangat religius adalah semangat sastra yang paling fitrah (hakiki). Sebab, seperti diyakini oleh Iqbal dan kalangan penyair sufi--juga ditegaskan oleh Mangunwidjaja dalam buku Sastra dan Religiusitas (1981)--pada mulanya segala sastra adalah religius. Karena itu, religiusitas dapat dianggap sebagai fitrah sastra.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sastra dan bukan sastra--bahkan untuk menentukan sastra yang baik atau tidak--dibentuk oleh kesekapatan bersama antara seniman (sastrawan) dan masyarakat dengan perkembangan zaman. Dan, organisasi yang berkecimpung di dunia seni (sastra), sosial dan budaya sangat berperan penting dalam menentukan arah kesusastraan kita.
ADVERTISEMENT

