Murai Mencari Terang
Konten dari Pengguna
31 Juli 2021 6:00 WIB
·
waktu baca 6 menitTulisan dari vendo olvalanda tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
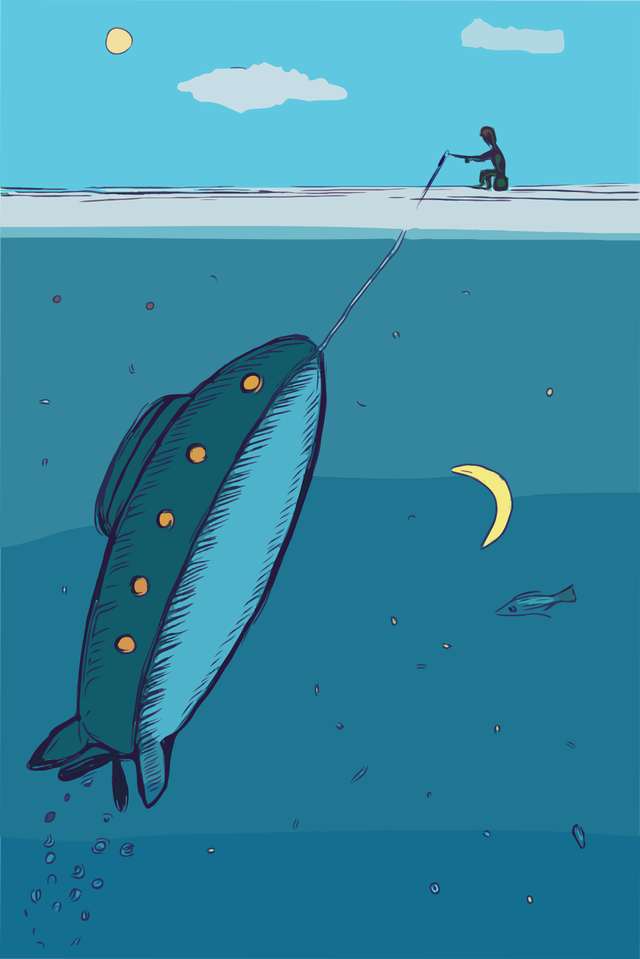
ADVERTISEMENT
Semua orang suka terang. Apalagi terang benderang di malam yang kelam. Pun dengan Murai, seorang anak lelaki Suku Asmat Papua. Bertahun-tahun ia hidup di tengah malam tanpa cahaya. Bertahun-tahun pula ia didongengkan kakek betapa indahnya malam yang terang. Sehingga Murai benci kelam, kelam di saat malam.
ADVERTISEMENT
Murai benci bergelap-gelapan di saat malam tiba, seperti ia membenci orang-orang kota. Mereka yang berjanji membantu orang-orang Suku Asmat hidup berterang-terang selepas senja. Lalu pergi membawa hasil alam mereka dengan tertawa.
Murai dan anak-anak Suku Asmat memang sudah hidup dengan cahaya. Namun cahaya api yang membara-bara. Cahaya yang membuat hidungmu hitam lalu sesekali menyesakkan dada. Sebuah obor yang terbuat dari rotan dan buahnya.
Benar, jika Suku Asmat tak begitu peduli dengan lampu dan cahaya. Bukankah mereka sudah dan akan tetap hidup tanpa hal-hal semacam itu? Mereka punya bulan yang sesekali menyapa, mereka punya api yang bisa dihidupkan sesuka hati, dan mereka tinggal tidur jika tak lagi bisa melihat apa-apa.
Namun bukan keadaan semacam itu yang diinginkan Murai dan kawan-kawannya. Mereka yang sudah cukup cerdas agar tidak sekedar dikenal manusia buas. Mereka yang sudah belajar membaca, menulis, berhitung, dan bersandiwara. Mereka yang subur ditanami harapan dan cita-cita.
ADVERTISEMENT
Bertahun-tahun yang lalu. Seorang peneliti dan rekan-rekannya mengadakan riset. Mencari kebenaran atas mitos dan dugaan-dugaan menakutkan Suku Asmat Papua. Berupaya menemukan dan mengenal sisi baik kehidupan mereka seutuhnya. Tanpa ada niat lain–semoga saja.
Saat itulah, mereka menemukan Murai dan keluarga besarnya. Sesuatu terjadi. Mereka dikepung seolah akan dikebiri. Atau dijadikan santapan saat malam tiba. Sepertinya, merekalah yang menemukan peneliti dan rekan-rekannya.
“Apa yang kalian cari?”
“Kalian.”
“Lalu?”
“Hanya itu.”
Satu batang rokok dibakar.
“Hisaplah.”
“Lalu?”
“Hanya itu.”
Peneliti dan rekan-rekannya mengepulkan asap dari rokok-rokok itu. Lalu terbatuk-batuk karena gugup. Orang-orang suku dalam tertawa lepas, puas. Mereka mengolok-ngolok orang-orang kota yang tengah ketakutan setengah mati.
Kesan pertama yang amat menarik. Peneliti dan rekan-rekannya membuktikan sendiri. Buas, tidak selayaknya mereka dinyatakan seperti itu. Liar, yang paling kuatlah yang bisa bertahan di alam. Tidak ada yang salah. Kita saja yang seringkali menduga-duga, itulah kesalahannya.
ADVERTISEMENT
Tiga bulan berlalu. Peneliti dan rekan-rekannya hidup menyatu. Mereka mempelajari banyak hal dari Suku Asmat Papua. Suku Asmat pun belajar dari mereka. Anak-anaknya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Cerdaslah mereka, Murai satu di antaranya. Pun satu-satunya yang paling dekat dengan orang-orang kota, seperti keluarga sendiri. Tak ada kebohongan, tak ada rahasia.
“Jadi kalian orang titisan dewa?
“Benar.”
“Dewa apa?”
“Fumeripitsy!”
Orang-orang kota terkecoh. Banyak hal yang ingin diungkap. Namun begitu sedikit bekal yang dibawa. Satu tahun berlalu. Pendanaan mereka terhenti. Mereka tak bisa keluar masuk hutan lagi–benar-benar sesekali.
Banyak sekali janji yang diumbar. Tak banyak yang bisa ditepati. Terutama janji pada Murai dan kawan-kawannya. Anak-anak Suku Asmat yang tidak hanya menjadi harapan orang tua mereka. Namun suku mereka.
ADVERTISEMENT
“Bapak janji?”
“Tentu, Murai dan kawan-kawan bisa belajar sampai pagi. Sampai kalian bosan!”
“Kapan?”
“Nanti, saat saya kembali.”
“Tidak bohong?”
“Sampai ketemu lagi, Samurai!”
Sejak hari itu, peneliti dan rekan-rekannya tidak pernah kembali. Sudah satu tahun. Orang-orang kota itu berbohong. Semua janji mereka dusta. Mereka menghancurkan harapan anak-anak tak berdosa. Harapan Suku Asmat Papua.
“Mereka tak akan kembali.”
“Aku tahu.”
“Jadi untuk apa?”
“Agar kita tetap bisa menikmati apa yang orang kota nikmati”
“Kenapa?”
“Kenapa tidak!”
Saat burung hantu bergelut dengan waktu, saat itu pula Murai merangkak dari rumahnya. Membawa bekal alakadar dan beberapa barang yang dianggap perlu. Murai ingin menebus dosa. Dosa yang hadir karena dendam pada orang-orang kota.
ADVERTISEMENT
Murai melangkah keluar rimba – untuk pertama kalinya. Di benaknya, ada banyak utang yang mesti dibayar lunas. Semakin jauh, langkahnya semakin cepat. Semakin cepat, tak ada mata yang bisa melihat. Murai mulai berlari, sembari mengingat-ingat wajah-wajah penipu itu. Tiba-tiba.
“Mau ke mana?”
“Lepaskan tanganku!”
“Jawab dulu”
“Aku buru-buru”
“Keluar hutan?”
“Bukan urusanmu!”
“Aku? Bodoh! Ini urusan kita bersama”
Awalnya satu. Lalu dari balik gelap mereka menampakkan diri. Empat orang kawan setia menghentikan lajunya. Tentu, mereka pun sudah tahu isi otak Murai. Tak ada maksud menghentikan niat. Tak ada niat memperlambat langkah. Mereka karib, sejak dalam kandungan ibu.
“Kami ikut!”
Berhari-hari, bermalam-malam. Mereka berlari menuju ruas kota. Tapak kaki setebal besi, kini meroyak bak borok tak bernanah. Mereka lupa punya ibu, yang akan memekik menyadari anak tak di rumah. Ingatan mereka hanya tertuju pada peneliti dan rekan-rekannya – yang tak pernah kembali. Jangankan satu, dua buku baru. Batang hidung pun tak lagi tampak.
ADVERTISEMENT
“Itu mobil peneliti!”
“Dan itu?”
“Itu motor teman-temannya!”
“Bukan. Itu orang lain”
“Kau benar. Mereka orang-orang kota”
“Benar-benar serupa cerita tetua”
“Hanya kita saja yang belum memilikinya”
Satu per satu umpatan keluar dari mulut Murai dan kawan-kawannya. Mereka tepat berada di tengah-tengah kota. Mereka menemukan apa saja yang tidak ditemukan di hutan. Dan mereka, ingin memiliki – semuanya!
Di sebuah kantor di sudut kota, ada keheningan yang muncul tiba-tiba.
“Tidak mungkin!” tidak satu pun bibir yang tidak mencicipi air mata.
“Maaf, Nak. Kami lebih berduka”
“Jadi peneliti kembali?” isakan mereka tak menghentikan berjuta-juta tanya.
“Tentu. Bukankah beliau berjanji?”
“Benar. Ia berhutang.”
“Kami benar-benar meminta maaf.”
“Mari kita pulang!” untuk pertama kali, Murai tak digubris kawan-kawannya.
ADVERTISEMENT
***
Kini, Murai dan kawan-kawan semakin cerdas. Setiap bulan mereka mendapatkan buku baru. Banyak pengajar yang membantu. Rumah mereka sudah terang benderang di saat malam tiba. Walau tak seperti orang-orang kota, namun mereka bahagia. Murai dan kawan-kawannya menemukan terang yang tak menyilaukan.
Mereka jarang tertinggal informasi. Lebih-lebih tentang Suku Asmat di berbagai belahan negeri. Tentang kehidupan serta hutan mereka. Mengenai pembakaran yang menyesakkan dada. Perihal penghilangan secara paksa. Mereka bersyukur bisa hidup lebih tenang–entah di kemudian hari.
Di sebuah rumah di sudut hutan. Murai dengan senyum tipisnya membawa kabar. Selepas menghela napas teramat panjang, seorang kawan tergesa-gesa bertanya.
“Dari sana lagi?”
“Iya.”
“Sudah bisa mengingatnya dengan jelas?”
“Kali ini aku mencatatnya.”
ADVERTISEMENT
“Ayo cepat sampaikan!”
Murai membawa sesuatu yang membuat siapa saja yang berada di sana terdiam dengan telinga condong ke depan. Ada yang mulutnya menganga, ada pula yang menopang dagu. Semuanya menunggu.
“Bronisław Kasper Malinowski”
Tak satu pun yang tak terkagum-kagum mendengar namanya. Lalu serta merta seseorang bertanya.
“Itu saja?”
Murai termenung untuk sesaat. Setelah memainkan bibirnya beberapa kali. Ia mendeham.
“Satu lagi! Almarhum.”

