Catatan Jelang Debat Perdana Pilpres 2019
Konten dari Pengguna
17 Januari 2019 11:16 WIB
Tulisan dari Yunarto Wijaya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Momentum menyambut debat antar-kandidat pada pilpres 2019 sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu dengan intensitas pembicaraan yang lebih tinggi dari dua pilpres sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Topiknya beragam, dari mulai soal penggunaan bahasa Inggris dalam berdebat, pasangan kandidat bisa mengajukan usulan topik debat, bocoran kisi-kisi pertanyaan, kesepakatan pembatasan pertanyaan, revisi visi-misi, hingga soal pencoretan panelis.
Hal ini mengindikasikan, debat antar-kandidat tak lagi sekadar dianggap sebuah seremoni dalam rangkaian kampanye, tetapi telah menjadi peristiwa besar. Ia menjadi sesuatu yang dinanti-nanti layaknya atau bahkan lebih besar daripada tayangan seperti final piala dunia sepak bola atau final super bowl untuk kasus Amerika Serikat, misalnya.
Mempersuasi Pemilih
Menurut Benoit (2014), debat merupakan sarana para kandidat mempersuasi pemilih melalui dua hal: menunjukkan siapa mereka (karakter) dan apa yang dilakukan/direncanakan (kebijakan). Persuasi itu dilakukan dengan cara membuat pengakuan, menyerang kompetitor, dan atau melakukan pembelaan.
ADVERTISEMENT
Ketiga pendekatan tersebut dalam praktiknya bisa dikombinasikan dalam satu rangkaian pernyataan. Bush dalam debat perdananya dengan Al Gore (2000), umpamanya, tak hanya membela diri dari tudingan tak berpengalaman, tapi juga sekaligus menyerang balik kompetitornya.
Kata Bush, " ...Look, I fully recognize I'm not of Washington. I'm from Texas. And he's got a lot of experience, but so do I. And I've been the chief executive officer of the second biggest state in the union. I have a proud record of working with both Republicans and Democrats, which is what our nation needs."
Selain itu, kandidat perlu cermat menjalankan ketiga pendekatan ini karena bisa jadi bumerang buat dirinya. Ini, umpamanya, dialami John Kerry ketika ditanya sikapnya soal homoseksual.
ADVERTISEMENT
Kata Kerry,"We're all God's children, Bob. And I think if you were to talk to Dick Cheney's daughter, who is a lesbian, she would tell you that she's being who she was, she's being who she was born as." Dalam pemberitaan pasca-debat, Kerry lebih banyak mendapatkan peliputan dengan tone negatif ketimbang Bush.
Dalam kasus di Indonesia, pendekatan menyerang tak hanya dilakukan dengan mengkonfrontasikan posisi kompetitor pada satu isu, tapi bisa juga melalui pertanyaan yang spesifik. Jokowi pada debat pilpres 2014 lalu, misalnya, menanyakan soal TPID untuk menunjukkan Prabowo tak memahami seluk-beluk pemerintahan.
Mempersoalkan Format

Meski demikian, format debat saat ini (satu moderator, panelis, atau town hall meeting) dianggap tak mewakili karakter debat yang sesungguhnya. Mengutip pendapat JJ Auell, secara tradisional debat sepatutnya menghadirkan konfrontasi antar-kandidat secara langsung, kesamaan dan kecukupan waktu untuk berdebat, kesetaraan kandidat dalam berbicara, pengetahuan, persiapan), ada satu tema utama yang diperdebatkan, memfalitasi audiens untuk membuat keputusan tentang satu isu (Jamieson dan Birdsell, 1988).
ADVERTISEMENT
Dalam kasus di Indonesia, meski menyediakan mekanisme pendalaman terhadap sebuah isu, tetapi rentang waktu yang disediakan relatif singkat (totalnya tidak lebih dari 5 menit). Bandingkan dengan format debat satu moderator pada pilpres di Amerika Serikat yang menyediakan waktu untuk mendalami satu isu hingga 15 menit dan itu pun dinilai kerap kurang memadai.
Sudah begitu, topik yang dibahas selama ini terkadang terlalu luas atau permukaan alias tak mengkonfrontasikan posisi para kandidat pasa satu isu yang spesifik. Akan sangat menarik jika Kamis (17/1), moderator dan atau panelis mengajukan topik soal kebebasan berpendapat. Seperti diberitakan, Prabowo menilai, kebebasan berpendapat di Indonesia sedang terancam.
Sebaliknya, Jokowi berpendapat, kebebasan berpendapat itu tetap ada batasannya karena harus mengikuti aturan yang berlaku. Di sini, peran moderator penting dalam melakukan elaborasi kepada kandidat. Jika ketentuan waktunya masih seperti debat sebelumnya, niscaya elaborasi akan sulit dilakukan.
ADVERTISEMENT
Karena waktu yang terbatas dan topik yang sangat beragam, maka debat kerap jatuh menjadi ajang adu soundbyte. Ungkapan seperti: “Tak ada lagi yang kelaparan”, “Tol Laut”, “Cabut Peraturan Bersama 2 menteri soal rumah ibadah”, “Pertanian 4.0”, “Setop impor pangan”, “Kriminalisasi Ulama”, atau “Pajak akan Diturunkan”, jelas enak didengar tetapi sekurangnya mengabaikan dua hal.
Pertama, kandidat punya definisi tertentu yang belum tentu sama dengan yang dipahami kompetitornya maupun pemirsa. Ini merupakan peluang tetapi sekaligus beban, tergantung kelihaian masing-masing kandidat dalam mempresentasikannya dalam debat.
Kedua, keterbatasan waktu menyebabkan kandidat mendapat pemakluman dari pemirsa untuk tidak menjelaskan bagaimana usulannya itu bisa dilaksanakan. Ini membuka ruang untuk memajukan usulan atau gagasan yang tidak masuk akal atau sulit diimplemetasikan.
ADVERTISEMENT
Lebih daripada itu, dalam kasus di Amerika Serikat, besarnya kuasa jurnalis selaku moderator atau panelis dalam memilih isu dan atau melontarkan pertanyaan juga dipertanyakan karena dianggap mengabaikan minat pemirsa atau pemilih.
Untuk Indonesia, pilihan panelis selalu jadi persoalan, salah satunya karena keraguan terhadap netralitas panelis tersebut. Atau juga karena kurang fokusnya topik yang dibahas.
Efek Menonton Debat
Karena hal-hal tersebut di atas, debat-debat pilpres yang disiarkan secara langsung oleh televisi kerap dicibir sekadar sebagai konferensi pers bersama. Meski begitu, debat tetap dianggap momen penting dalam pemilu karena adanya harapan debat bisa menjadi pengubah peta persaingan.
Ini mengandaikan debat punya efek terhadap pengetahuan maupun perubahan preferensi pemilih. Masalahnya, para ilmuwan politik belum punya kesimpulan yang konklusif mengenai efek debat ini.
ADVERTISEMENT
Soal akuisisi pengetahuan, misalnya, temuan (Abramowitz, 1978; Gottfried dkk, 2014) menunjukkan adanya peningkatkan pengetahuan penonton terhadap isu yang dibicarakan dalam debat. Namun, kecenderungannya bersifat menguatkan dan bukan menggeser preferensi.
Selain itu, juga ada temuan Turcoitte dan Goidel (2014) yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran ini lebih kuat kecenderungannya pada topik-topik yang kurang dikenali pemilih.
Terkait perubahan preferensi pemilih, umpamanya, hal ini lebih besar peluangnya terjadi pada debat di pemilu pendahuluan daripada pemilu umum (Benoit dkk, 2010) atau pada debat perdana pilpres daripada debat-debat berikutnya (Holbrook, 1999).
Selain itu, pergeseran preferensi pemilih lebih besar peluangnya terjadi jika masih banyak pemilih yang belum memutuskan pilihannya dan atau kontestasinya berlangsung ketat (Chaffe, 1978; McKinney dan Warner, 2013).
ADVERTISEMENT
Pasca-Debat Menentukan
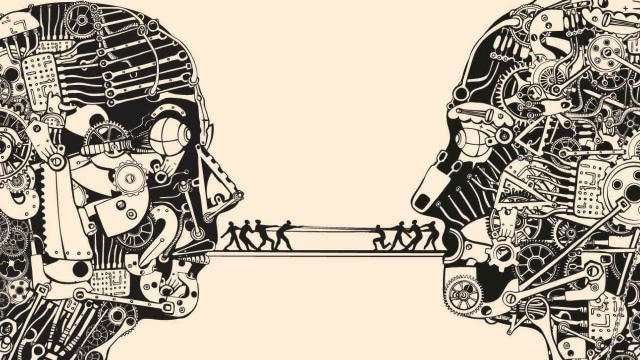
Yang perlu dicermati, paparan debat tidak berhenti ketika debat berakhir. Paparan terhadap jalannya debat berlanjut melalui ulasan-ulasan dalam pemberitaan di media massa yang pada gilirannya membentuk penilaian tertentu pada kandidat.
Kandidat yang mendapat peliputan negatif cenderung juga dinilai negatif (Fredkin dkk, 2008). Ataupun melalui pembicaraan dengan orang-orang yang sepreferensi dengan pemilih yang bersangkutan dan karenanya bersifat meneguhkan preferensinya (Cho dan Ha, 2012).
Dalam konteks pilpres 2019, paparan pasca-debat diprediksi akan berlangsung secara stimulan dalam berbagai medium sekaligus: dari mulai media massa, media sosial (Facebook, Twitter, dll), hingga media percakapan (WhatsApp).
ADVERTISEMENT
Di ranah media massa, konstelasi ulasan amat dipengaruhi oleh pilihan narasumber yang dipilih media. Sebaliknya, di ranah media sosial dan media percakapan, ulasan lebih banyak didasarkan pada ulasan-ulasan individual dan untuk sebagian berhulu pada konten-konten yang termasuk dalam kategori kabar bohong (hoax).
Dengan konstelasi seperti itu, apapun penampilan kandidat di televisi sangat boleh jadi menjadi kurang relevan. Analisis-analisis buatan individu per individu sangat boleh jadi memberi tafsir baru dan bahkan berlawanan, termasuk membangun narasi apalogis bila ternyata kandidatnya melakukan blunder.
Yang lebih penting lagi, analisis-analisis ini dan kabar bohong akan mendapat perlakuan yang sama: dipercayai sebagai sesuatu yang faktual dan diteruskan selama kontennya menguatkan preferensi pada kandidat yang ia pilih.
ADVERTISEMENT
Jika ternyata ada perbedaan posisi isu antara pemilih dengan kandidat yang jadi preferensinya, pemilih memilih jalan mengadopsi posisi isu kandidat. Dengan kata lain, preferensi pada capres-cawapres lebih kuat pengaruhnya daripada posisi isu yang diinginkannya (Abramowitz, 1978).
Contohnya, seorang pemilih bisa saja punya sikap bahwa perlu ada UU yang memberi perlidungan terhadap ulama. Tapi, karena capres yang diusungnya berada dalam posisi sebaliknya, pemilih tersebut mengadopsinya dan kemudian membangun narasi untuk membenarkan posisi barunya tersebut.
Jika situasi paparan pasca-debat akan berlangsung seperti diuraikan di atas, jelas merupakan kabar buruk bagi harapan hadirnya pemilu yang berkualitas. Dan, semoga hal tersebut tidak terjadi.
Selamat menonton!

