Julia Kristeva, Filsuf Feminis yang Menolak Feminisme
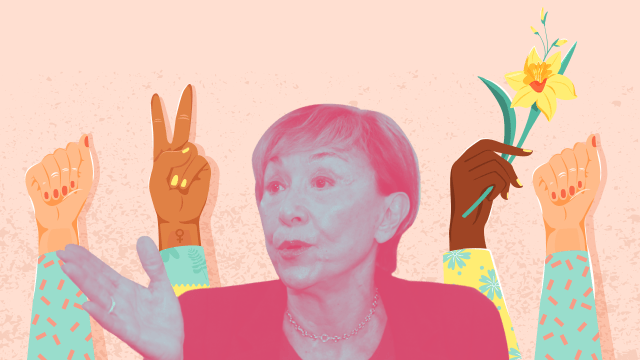
ADVERTISEMENT
Ide menolak feminisme baru-baru ini viral di media sosial. Ide itu disuarakan akun Instagram Indonesia Tanpa Feminis.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, penolakan semacam itu sebetulnya bukan barang baru. Seorang filsuf feminis dari Prancis bernama Julia Kristeva lebih dulu menolak feminisme.
Meski berdarah Bulgaria, perempuan yang lahir pada 24 Juni 1941 itu mulai mengawali hidupnya di Prancis pada pertengahan 1960-an. Dia begitu meminati filsafat, marxisme, psikoanalisis, linguistik, dan feminisme.
Namun, meski menulis soal feminisme, dia enggan dilabeli sebagai seorang feminis. Bahkan, dia menolak feminisme itu sendiri.
Posisi filosofis Kristeva itu lantas menuai polemik. Sebagian akademisi memandang bahwa penolakan Kristeva merupakan kritik yang berguna untuk feminisme. Sementara, sebagian lainnya menilai, penolakan Kristeva akan menjadi amunisi para politikus sayap kanan untuk membredel perjuangan feminisme.
Meski tentu saja, sejumlah akademisi mengelompokan Kristeva sebagai feminis. Pemikiran Kristeva malang melintang di sejumlah buku feminisme.
ADVERTISEMENT
Kristeva dan Penolakannya terhadap Feminisme
Sebagaimana yang dielaborasi Kelly Oliver dalam jurnal berjudul ‘Julia Kristeva’s Feminist Revolution’, Kristeva tak sepakat jika feminisme mengatur bagaimana cara menjadi seorang perempuan. Upaya pendefinisian perempuan feminis ideal itulah yang ditolak Kristeva.
Memang, dia mengakui, gerakan feminisme bermanfaat dalam banyak hal. Seperti kala organisasi feminisme mengubah wajah dunia yang dahulu sangat tidak adil, menjadi lebih adil.
Kristeva juga mengakui, melalui feminisme, perempuan memperoleh hak atas pendidikan, politik, dan hak lainnya yang setara dengan laki-laki. Dia pun paham betul bahwa semua itu tak akan terjadi tanpa adanya kesadaran kolektif mengenai ketidakadilan.
Persoalannya, Kristeva melihat bahwa gerakan feminisme dapat tergelincir pada suatu dogmatisme baru. Dogmatisme itu berupa pelenyapan keunikan individu oleh identitas kelompok yang mengatasnamakan feminisme.
ADVERTISEMENT
Contohnya, para feminis Afrika-Amerika yang frustasi dengan proyek feminisme di Prancis. Kala itu, gerakan feminisme di Prancis memberikan syarat kepada perempuan manapun yang ingin menjadi feminis.
Salah satunya, permintaan agar perempuan Afrika-Amerika melepaskan seluruh kekhasan dan keunikan budaya yang mereka miliki. Pendek kata, menurut Kristeva, feminis Perancis telah mengucilkan mereka yang berbeda.
Melalui fenomena seperti itu, Kristeva menyimpulkan, feminisme yang dahulu memiliki tugas mulia, kini justru terjebak pada politik identitas. Artinya, feminisme menjadi biang masalah baru ketika tidak bisa menerima keunikan individu.
Menurut dia, kala feminisme tak bisa menerima perbedaan, feminisme hanya akan menciptakan eksklusivitas. Sehingga tak lebih sebagai gerakan yang diisi oleh orang berkulit putih dan berasal dari kelas menengah.
ADVERTISEMENT
Memikirkan Kembali Feminisme
Menurut Kristeva, feminisme bukan sekadar perjuangan terhadap ketertindasan perempuan. Lebih dari itu, feminisme merupakan perjuangan yang lebih luas dari pendefinisian atas perempuan itu sendiri.
Kristeva lalu mengkritik sejumlah pemikiran feminisme yang kandung berkembang di dunia barat. Kala itu, pemikiran tentang feminisme telah mencapai dua generasi yang bagi Kristeva, menyimpan permasalahan yang cukup serius.
Kritiknya terhadap feminisme itu pun ditulis dalam sebuah esai berjudul ‘Women’s Time’. Esai itu diterbitkan pertama kali dalam bahasa Perancis pada 1981 dengan judul ‘Le Temps des femmes’.
Singkatnya, Kristeva melihat bahwa pemikiran feminisme generasi pertama terlalu sibuk berfokus pada kesetaraan universal antara laki-laki dan perempuan. Padahal, kesetaraan universal hanya akan melenyapkan fakta tentang perbedaan tubuh. Soal perbedaan tubuh ini yang luput dari pemikiran para feminis generasi awal.
ADVERTISEMENT
Belum lagi mengenai upaya feminisme generasi awal menguniversalkan masalah perempuan. Padahal, menurut Kristeva hal itu tak tepat lantaran perempuan selalu ada pada peradaban, struktur psikis, dan budaya yang berbeda satu sama lain.
Selanjutnya, kritik juga dia alamatkan pada feminisme generasi kedua. Dalam generasi kedua ini, feminisme menciptakan jurang pemisah yang lebar antara feminitas dan maskulinitas. Antara yang bersifat perempuan dan yang bersifat laki-laki.
Jurang pemisah ini menjadi masalah, lantaran feminisme menjadi begitu simplifikatif. Dengan menciptakan jurang yang lebar, feminisme memposisikan perempuan sebagai lawan dari laki-laki dalam struktur biologis.
Untuk itulah Kristeva mengajukan jalan ketiga. Berupa pengakuan terhadap tesis dasar bahwa manusia pada dasarnya tidak sendirian. Manusia selalu masuk ke dalam kontrak sosial dan berbaur dalam komunitas.
ADVERTISEMENT
Dengan cara seperti itu, Kristeva ingin mengembalikan persoalan feminisme dalam bingkai perbedaan. Tepatnya perbedaan yang dipostulasikan atas individu yang memiliki kekhasannya masing-masing.
Kristeva pun menawarkan, setiap perempuan dapat menjadi feminis dengan caranya masing-masing. Jika dahulu menjadi seorang ibu rumah tangga dicap sebagai representasi dari budaya patriarki, maka di tangan Kristeva pemaknaannya berubah. Selama itu dilakukan tanpa paksaan, maka tak jadi soal.
“Hasrat untuk menjadi seorang ibu yang dianggap mengasingkan dan bahkan reaksioner oleh generasi feminis sebelumnya, jelas tidak menjadi standar untuk generasi sekarang,” tegas Kristeva dalam esainya.
Bukan cuma itu, Kristeva juga menentang larangan pemakaian jilbab yang terjadi di Perancis. Sikapnya itu dia tunjukan saat insiden pengusiran sekelompok perempuan muda arab dari sekolah karena jilbab.
ADVERTISEMENT
Dalam sebuah suratnya kepada Ketua Komnas HAM Prancis pada 1990, Kristeva menyebut, perlu adanya heterogenitas komunitas nasional dan politik di Perancis. Gagasan tentang nasionalisme Perancis yang saat ini dianut tak lebih dari mitos yang menindas, didorong oleh dogmatisme, dan merupakan pandangan yang picik.
Bagi Kristeva, insiden ini berbicara tentang sikap represif Eropa terhadap perbedaan budaya dan agama. Khususnya, tentang Prancis yang selalu cemas mengenai infiltrasi identitas nasionalnya oleh imigran Islam.
Identitas Seksual dan Jalan Memutar Atasnya
Untuk tiba pada kesimpulan semacam itu, Kristeva menempuh jalan psikoanalisis Lacanian. Yakni studi tentang ketidaksadaran yang dikembangkan pemikir Perancis, Jacques Lacan.
Dengan menggunakan kerangka psikoanalisis Lacanian, Kristeva mengkontraskan apa yang disebutnya sebagai tahap ‘semiotik” dan ‘simbolik’. Kedua istilah tersebut merujuk pada upaya manusia dalam berkomunikasi dengan yang lain.
ADVERTISEMENT
Sederhananya, tahap semiotika adalah fase manusia mengkomunikasikan sesuatu tanpa membahasakannya. Semiotika sendiri berarti segala hal yang berkaitan dengan ekspresi perasaan. Tahapan ini paling jelas dapat dilihat pada bayi, yang menggunakan bahasa tubuh seperti tangisan dan gerak tubuh untuk berkomunikasi .
Berkebalikan dengan semiotika, tahapan simbolik merupakan fase di mana manusia membahasakan sesuatu. Tahapan ini tunduk dalam hukum-hukum bahasa yang objektif. Sebagaimana kita menyimbolkan fenomena air yang turun dari langit sebagai ‘hujan’.
Pengkontrasan ini menjadi menarik lantaran Kristeva melihat bayi yang dilahirkan senantiasa berkomunikasi dengan ibu. Kala si anak belum bisa membedakan ‘aku’ dan ‘yang lain’, tubuh maternal mendahului segala macam fase simbolik, termasuk mendahului hukum ayah.
Meski demikian, ada satu titik kala si anak mulai memisahkan diri dari tubuh ibunya. Pemisahan itu merupakan gerbang bagi anak untuk mengidentifikasi dirinya di masyarakat. Termasuk mengidentifikasi identitas seksual yang dia miliki. Proses ini dinamai sebagai abjeksi (abjection). Sebuah term psikoanalisis yang belum ada padanannya di dalam KBBI
ADVERTISEMENT
Celakanya, abjeksi tersebut tidak berjalan mulus. Penolakan atas tubuh ibu yang dilakukan anak laki-laki berbuntut terciptanya diskriminasi. Diskriminasi itu timbul lantaran si anak laki-laki ingin membedakan dirinya dengan perempuan.
Terlepas dari hal itu, abjeksi yang terjadi juga telah menghasilkan satu konsekuensi lain. Yakni, identitas seksual bukanlah dibawa sejak lahir, melainkan tercipta manakala subjek bersentuhan dengan tatanan simbolik. Pendek kata, esensi tentang apa itu laki-laki dan perempuan sebetulnya tidak pernah ada, yang ada hanyalah representasi.
Sejak identitas seksual dipahami sebagai representasi, maka feminisme pun tidak bisa mengklaim bentuk perempuan yang ideal. Setali tiga uang, representasi mengakibatkan derajat feminitas maupun maskulinitas kandung terdapat pada perempuan maupun laki-laki.
Tidak mengherankan jika Kristeva selalu mempertanyakan apa itu perempuan. Itu karena penanda perempuan sangat cair. Begitu terbuka pada konteks budaya dan historis yang beragam.
ADVERTISEMENT
Perjuangan untuk menggapai keadilan di muka bumi ini lantas bergeser. Kini menjadi sebuah perjuangan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam memahami identitas seksualnya.
“Aku punya keyakinan mendalam bahwa setiap orang memiliki seksualitas yang sangat khusus,” kata Kristeva dalam ‘Revolution in Poetic Language’.
