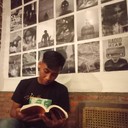Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Pertanian Modern: Kemajuan yang Mundur
14 Juli 2023 9:22 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Alfian Eka aditya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Pertanian dan petani merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia, pertanian masih menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 40,64 juta pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2022.
ADVERTISEMENT
Jumlah tersebut menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan utama lainnya. Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya.
Akan tetapi, di Indonesia khususnya, petani dan pertanian selalu dipandang sebelah mata. Sebagaimana diungkapkan Eric R Wolf, seorang antropolog yang membuat studi tentang petani, menyebut secara historis petani selalu diilustrasikan sebagai manusia kalah, baik kalah karena ketergantungan pada alam maupun kalah dalam proses terbentuknya lembaga serta sistem kekuasaan dan politik yang ada di dalamnya.
Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seringkali tidak dianggap berpihak kepada petani, seperti pengurangan dan pencabutan pupuk subsidi, serta mendorong masuknya produk impor pertanian. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan petani.
ADVERTISEMENT
Selain daripada itu, pemerintah juga secara tidak langsung mencekik dan mengeksploitasi petani. Hal yang ada di pikiran pemerintah semata-mata hanya agar sektor pertanian membuahkan hasil maksimal, mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan mendapatkan keuntungan finansial. Seakan-akan tidak peduli terhadap keberlanjutan kondisi lingkungan ataupun lahan pertanian.
Hal tersebut dikarenakan penggunaan pestisida maupun pupuk kimia yang berlebihan untuk memaksa meningkatkan produktivitas panen. Mengapa pemerintah yang disalahkan? Pertanyaan tersebut mungkin terbesit di benak pembaca.
Jadi seperti ini, sebelum mengenal konsep bertani modern, para petani di Indonesia memanfaatkan metode pertanian tradisional. Pertanian tradisional yang dimaksud di sini adalah pertanian yang menggunakan bahan-bahan organik dalam proses budidayanya, tanpa adanya penggunaan pupuk sintetis, pestisida kimia, ataupun benih-benih hibrida.
ADVERTISEMENT
Sejak tahun 1970-an dengan dalih revolusi hijau, pemerintah mulai mengubah sedikit demi sedikit sistem pertanian di Indonesia. Pemerintah berusaha mengubah sistem pertanian tradisional ke pertanian modern. Hal itu semata-mata agar pemerintah dapat melakukan swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Memang benar saja, pada tahun 1984 Indonesia telah mampu berswasembada pangan terutama beras. Akan tetapi dampak dari gencatan revolusi hijau tersebut tidak hanya memberi dampak positif bagi Indonesia untuk mampu berswasembada pangan.
Sejak mulai direalisasikannya gerakan revolusi hijau oleh pemerintah, mulai masuk benih-benih ajaib yang konon katanya unggul seperti IR-64, IR-36, IR-5, dan seterusnya. Benih-benih tersebut didatangkan demi terciptanya swasembada beras di Indonesia.
Pada akhirnya benih-benih tersebut bukan menjadi suatu keajaiban lagi bagi petani. Hatta, benih-benih hibrida tersebut mulai menggusur dan membuang jauh-jauh keberadaan benih-benih lokal.
Berbeda dengan benih lokal, benih hibrida memang pada awalnya menghasilkan produksi panen yang relatif lebih tinggi. Akan tetapi, benih hibrida tidak bisa diturunkan, sehingga hanya bisa sekali tanam. Sehingga, petani dituntut untuk selalu membeli benih baru ketika musim tanam.
ADVERTISEMENT
Pada akhirnya, akan terjadi monopoli benih oleh perusahaan produksi benih hibrida dalam rangka untuk mensukseskan gerakan revolusi hijau. Dalam hal ini, agaknya benar bahwa “siapa yang menguasai benih, maka menguasai kehidupan”.
Maka kembali lagi, petani lagi-lagi yang dijadikan tumbal dan korban. Biaya dalam pelaksanaan budidaya akan semakin meningkat. Belum lagi fakta di lapangan bahwa benih hibrida memerlukan pupuk yang lebih banyak dibandingkan dengan benih unggul lokal. Sehingga modal yang diperlukan petani akan berkali lipat semakin bertambah.
Untuk semakin memantapkan dan menjamin keberhasilan revolusi hijau, pemerintah juga mulai mendorong masuknya perusahaan multinasional atau Multinational Corporation (MNC) yang bergerak di bidang pestisida pertanian. Artinya, semakin meluas pula penggunaan pestisida dalam budidaya pertanian.
ADVERTISEMENT
Meluasnya penggunaan pestisida, berarti meluas pula peracunan dalam tanah maupun tanaman. Selain itu, juga berpotensi menjadikan resistensi hama terhadap pestisida yang akan berdampak pada pengendalian hama.
Dengan terjadinya resistensi hama terhadap pestisida, maka hal termudah yang biasanya dilakukan oleh petani yaitu menambah dosis penggunaan yang artinya pengeluaran biaya semakin membesar. Belum lagi dari penggunaan dosis pestisida yang kian bertambah akan merusak kesuburan tanah. Sehingga, mau tak mau petani akan menambah intensitas pemupukan untuk menambah kekurangan unsur hara yang berada di dalam tanah.
Fakta di lapangan juga dapat diketahui bahwa tanaman hasil benih hibrida memerlukan pupuk yang lebih banyak dibanding padi unggul lokal. Maka, tanpa disadari penggunaan pupuk berlebih akan berdampak buruk bagi lingkungan, serta dibarengi pula dengan penggunaan pestisida yang menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem yang mengakibatkan matinya spesies lain selain hama dan penyakit tanaman.
ADVERTISEMENT
Kegiatan ini, sama halnya dengan lingkaran setan. Maka kembali lagi, perusahan penyedia pestisida ataupun pupuk akan semakin diuntungkan karena permintaan pasar yang kian bertambah dan melonjak.
Namun petani akan semakin dirugikan karena jumlah modal yang harus dikeluarkan kian banyak. Apalagi setelah dicabutnya beberapa pupuk subsidi oleh pemerintah yang berimplikasi pada semakin tingginya biaya produksi dalam usaha tani.
Sedikit dari permasalahan yang diuraikan tersebut, baru membicarakan mengenai dampak dan pengaruhnya bagi lingkungan, belum lagi dampak dari penggunaan pestisida ataupun pupuk kimia terhadap kesehatan manusia. Maka pembahasan akan semakin panjang dan masalah-masalah yang ditimbulkan semakin banyak.
Oleh karena itu, siapa yang patut disalahkan akan sumber timbulnya masalah ini? Pemerintah dengan gerakan revolusi hijau nya? Perusahaan yang bergerak di Industri pupuk dan pestisida? Atau petani yang sebagai pelaksana di lapangan? Mungkin sudah agak telat untuk memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi.
ADVERTISEMENT
Namun apa salahnya jika semua petani mulai sadar dan mau berbenah diri untuk melakukan pengurangan terhadap ketergantungan penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam proses budidaya. Dan seharusnya pemerintah juga melakukan introspeksi diri mengenai kerusakan lingkungan dari program yang telah direncanakannya.
Demikian tulisan ini dibuat, lebih-kurangnya saya ucapkan terima kasih. Maju terus pertanian Indonesia, bersama petani membangun negeri!