Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Konten dari Pengguna
Membalikkan Hierarki Kekuasaan dalam Kebijakan Ekonomi
25 April 2025 11:48 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Alvian Rizki P tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
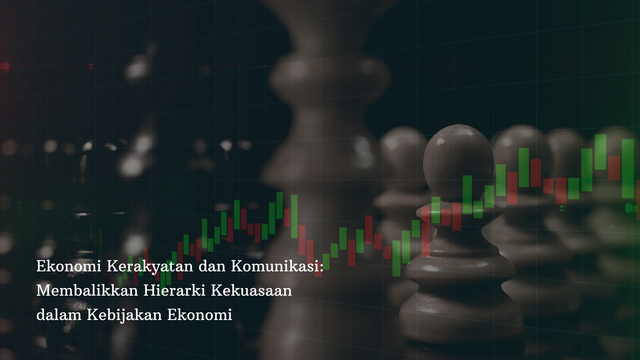
ADVERTISEMENT
Di tengah derasnya gelombang disrupsi digital dan proliferasi jargon “ekonomi inklusif,” konsep ekonomi kerakyatan kerap tereduksi menjadi discursive token, simbol retoris yang tampil cantik dalam pidato elite, tetapi minim implementasi substansial. Pemerintah mengklaim keberpihakan pada sektor informal, UMKM, dan koperasi, namun masih banyak kebijakan yang bersifat eksklusioner terhadap basis rakyat. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya menjadi medium penyampaian, tetapi berubah menjadi arena hegemonic contestation, pertarungan kuasa atas makna, arah, dan legitimasi ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
Ekonomi, dalam kacamata ilmu komunikasi dan ekonomi politik, tidak sekadar persoalan distribusi sumber daya, tetapi medan produksi dan reproduksi narasi. Ekonomi kerakyatan idealnya beroperasi sebagai deliberative process, bukan hanya policy output yang dirancang secara teknokratik dari atas ke bawah (top-down). Ia harus dilihat sebagai praktik komunikasi yang menumbuhkan civic agency, memfasilitasi public deliberation, dan membuka discursive space bagi rakyat untuk menegosiasikan kepentingannya secara otonom.
Pemerintahan Prabowo sejatinya telah menunjukkan sinyal keberpihakan terhadap ekonomi rakyat melalui kebijakan makro seperti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 yang menargetkan pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta PP No. 47 Tahun 2024 yang memberikan ruang untuk penghapusan piutang macet UMKM. Selain itu, dalam manifesto Ekonomi 5.0, Prabowo menegaskan pentingnya digitalisasi ekonomi rakyat melalui konsep cooperative capitalism yang berbasis solidaritas. Namun demikian, program-program tersebut belum menyentuh lapisan terdalam dari communicative empowerment, yakni partisipasi reflektif dalam mendefinisikan makna dan arah pembangunan.
ADVERTISEMENT
Sebagian besar program pemberdayaan yang ada masih mengandung karakter instrumentalist communication, komunikasi sebagai alat penyuluhan atau transmisi informasi semata. Akibatnya, banyak inisiatif gagal menjelma sebagai transformative praxis. Koperasi digital dibentuk tanpa media literacy, UMKM didorong masuk ke platform digital tanpa capacity building, dan kebijakan diumumkan tanpa dialog multisektor yang inclusive and reflexive. Alhasil, proses komunikasi bersifat vertikal, mengukuhkan relasi kuasa antara negara sebagai produsen makna dan rakyat sebagai konsumen pasif.
Di ruang publik yang dikuasai oleh algoritma dan corporate media narratives, narasi rakyat sulit mendapatkan resonansi. Discursive marginalization terjadi ketika kisah-kisah petani, nelayan, dan pedagang kecil tersisih oleh narasi hegemonik seputar startup, fintech, dan unicorn. Ini bukan sekadar masalah akses, melainkan persoalan epistemic injustice, ketidakadilan dalam pengakuan terhadap pengalaman dan pengetahuan lokal rakyat kecil.
ADVERTISEMENT
Namun demikian, ada titik terang. Koperasi berbasis komunitas di beberapa daerah, seperti koperasi petani organik di Bali atau perajin bambu di Kulon Progo, menunjukkan bahwa ketika relational communication dibangun melalui nilai, kepercayaan, dan dialog horizontal, ekonomi rakyat bisa tumbuh berkelanjutan. Mereka menjadi communicative communities yang tidak hanya bertahan, tapi juga mengartikulasikan nilai tandingan terhadap logika pasar.
Kita memerlukan paradigm shift dari komunikasi sebagai alat persuasi menuju komunikasi sebagai praktik demokratisasi. Negara, akademisi, jurnalis, dan civil society perlu membangun participatory communication ecology yang memungkinkan rakyat menjadi co-creators of meaning, bukan sekadar data points dalam laporan pembangunan. Komunikasi harus menjadi strategic enabler dari redistribusi kuasa ekonomi.
Selain itu, negara harus memperkuat counter-public spheres melalui media alternatif: radio komunitas, forum desa, kanal digital berbasis komunitas. Komunikasi yang berpihak tidak akan lahir dari pasar, tetapi dari keberanian kolektif untuk membangun dialogic infrastructure yang memulihkan agensi rakyat dalam menentukan masa depannya.
ADVERTISEMENT
Menumbuhkan ekonomi kerakyatan berarti mengkonstruksi ulang narasi tandingan terhadap market-centric ideology. Hal ini hanya mungkin jika komunikasi diposisikan sebagai critical praxis, sebagai kekuatan yang mampu membalik panggung: dari rakyat sebagai objek menjadi subjek. Ekonomi rakyat tidak bisa dibentuk oleh teknokrasi, tapi harus diperjuangkan melalui ruang diskursif yang membebaskan dan kolaboratif.
Kini, saatnya mengembalikan komunikasi ke fungsi dasarnya: sebagai medium emancipatory politics, bukan sekadar instrumen manajemen persepsi.

