Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Menjadi Redaktur Senin
29 Juni 2019 10:49 WIB
Diperbarui 6 Agustus 2020 13:18 WIB
Tulisan dari Anggi Kusumadewi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
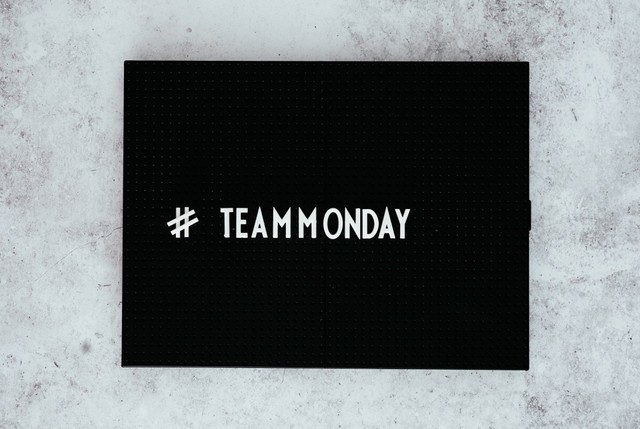
Di balik layar seorang redaktur—yang tak menarik-menarik amat.
ADVERTISEMENT
Dulu, di bangku sekolah, aku tak pernah terlalu suka hari Senin, terutama karena upacaranya. Aku cuma tak senang berdiri lama berpanas-panas. Hal lain, hari Senin yang notabene menjadi pembuka pekan kerap diawali dengan mata pelajaran yang relatif sulit—berat dan serius (buatku). Sebut saja Matematika atau IPA, pelajaran yang tak benar-benar pernah aku sukai (dan karenanya aku di kelas 3 SMA dengan mantap memilih jurusan IPS yang ketika itu bak jurusan buangan di sekolahku—sekolah favorit sekota Bogor dengan murid-murid terseleksi ketat berdasarkan nilai akademik; ehm, dulu belum ada sistem zonasi).
ADVERTISEMENT
Eh, tapi aku bukan mau cerita soal sekolah. Ini perkara hari. Hari Senin. Pembuka minggu. Pemula kesibukan, yang sering kali disambut masam sebagian orang yang masih merindukan waktu santai lebih lama tapi mau-tak mau harus berurusan dengan pelajaran/pekerjaan—yang mereka cinta tapi benci—karena jarum jam tak bisa dihentikan di hari Minggu kecuali kiamat datang hari itu.
Setelah sekian lama berdamai dengan Senin, mendadak satu setengah tahun terakhir aku dihantui hari Senin. Ini tak lain karena aku menjadi redaktur Senin. Rangkaian laporan timku tayang hari Senin, dan karenanya aku mesti menghabiskan libur akhir pekan sembari “jaga lilin”.
Seninku—dan tentu timku—jadi serius betul. Laptop kami, terutama para redaktur, tak pernah mati 24 jam penuh di akhir pekan. Apalagi laptopku. Daripada susah-susah menyalakannya lagi dan membuka satu per satu tulisan dan file yang perlu kuperiksa, kubiarkan saja dia menyala nyaris 48 jam (mungkin praktik ini tak begitu bagus buat barang elektronik itu, tapi aku sungguh tak mau merepotkan diri lebih jauh).
Bukan cuma aku yang “jaga lilin”. Biasanya, hampir seluruh anggota tim ikut berjaga bergantian. Terlebih bila ada peristiwa penting seperti sidang MK soal sengketa Pilpres atau kerusuhan Mei lalu. Anyway, kerja banting tulang macam ini terhitung biasa saja bagi wartawan. Itulah kenapa aku sering meliburkan timku di hari Senin sesudah artikel tayang. Karena semua butuh istirahat dan memastikan diri sehat untuk kembali berpikir dan bergerak.
ADVERTISEMENT
Mau kami sih semua selesai di Jumat malam sehingga Sabtu-Minggu bisa libur normal. Tapi harapan tak selalu sesuai kenyataan. Terlebih bagi kami yang masih belajar untuk menjadi lebih baik. Rasanya, waktu tak pernah cukup. Rentang Selasa ke Jumat tak menjamin seluruh bahan laporan terkumpul. Semua masih jauh dari sempurna.
Semakin sukar penelusuran, semakin sulit pula perburuan materi. Aku tahu betul berapa anak-anakku itu mati-matian berusaha melakukan yang terbaik tanpa pandang waktu, sampai-sampai aku sering bawel mengurusi kesehatan mereka—“Jangan lupa sarapan sebelum berangkat!”, “Jangan lupa tidur cukup!”, “Jangan lupa minum suplemen vitamin supaya tetap fit!”, “Jangan kebanyakan angin-anginan!”, “Jangan pesta sampai larut malam!”, dan “jangan”-“jangan” lainnya yang tersembur dari mulutku secara berkala.
ADVERTISEMENT
Aku jadi semacam redaktur satpam dengan peluit di bibir—dan hal ini mulai menurun pula pada editor-editorku yang kelihatannya makin lama kian cerewet sepertiku.
Senin pagi kami hampir selalu dipenuhi percekcokan, terutama ketika aku mulai mengecek menyeluruh laporan-laporan yang akan tayang. Aku memang sangat menyebalkan di hari Senin. Bayangkan saja, kepada penulis atau editor yang telah semalaman begadang membenahi laporan, aku masih tega berseru, “Jangan tidur dulu! Tunggu aku selesai mengecek!” Musababnya, kalau si penulis atau editor keburu ketiduran, aku tak bisa cepat bertanya dan mendapat jawaban segera bila menemukan keganjilan dalam laporan itu—baik kejanggalan bahasa, logika, atau fakta peristiwa.
Mereka yang betul-betul tak tahan dibekap kantuk dan minta izin tidur barang sejam, kuingatkan untuk “Jangan lupa pasang alarm!” Pokoknya, aku benar-benar Ratu Tega di Senin pagi. Baru sekali aku anteng di hari Senin, yakni saat aku tengah berada di Melbourne. Apa boleh buat, agendaku di sana bentrok dengan waktu tayang laporan timku, sehingga aku melepas penuh pengecekan. Di luar itu, selama bepergian dekat-dekat saja, aku selalu mengosongkan acara di Minggu sore ke Senin siang demi berjibaku bersama editor-editorku memeriksa laporan-laporan yang hendak tayang.
ADVERTISEMENT
Begini, aku punya satu penyakit bernama “perfeksionis”, dan sialnya separuh anggota timku juga dilanda penyakit serupa. Aku tak suka hasil jelek, dan karenanya aku selalu menyempatkan diri mengecek laporan-laporan itu—sesedikit apa pun waktu yang kupunya, sesibuk apa pun agenda yang menderaku.
Itu sebabnya, kala aku bepergian pun, aku kerap mengatur agar Senin subuh sudah bisa standby di depan laptop. Saat aku cuti seperti sekarang, misalnya, aku tetap saja mendedikasikan Seninku untuk “bersantai” di penginapan memeriksa laporan-laporan timku. Aku mengatur jadwal jalan-jalan dimulai di hari Selasa, dan membeli tiket pesawat pulang di Minggu pagi agar Minggu sore sudah bisa membuka laptop.
Kebiasaan ini merembet ke editor-editorku. Rina yang dulu biasa “mati sinyal” di Sabtu-Minggu, kini mengecek ponselnya berkala di akhir pekan. Ia, di sela membaca buku atau menonton bioskop/teater atau menjenguk ibu di kampung, tetap memeriksa bahan-bahan laporan dan mengedit tulisan di Minggu malam ke Senin pagi.
ADVERTISEMENT
Bila pikirannya kusut dan ia butuh waktu untuk “menghilang” atau “mati sinyal” alias tak bisa dihubungi untuk koordinasi, ia lebih dulu memberi tahu kami: “Aku izin pergi ngilang sehari saja, ya. Minggu sudah standby ngecek-ngecek lagi.”
Aku mengangguk, lalu berteriak, “Tio, jaga-jaga ya kalau Rina enggak balik tepat waktu. Kerjaannya jatuh ke kamu.” Dan Tio, asisten redaktur kami, langsung melotot, lalu melingkarkan lengannya di leher Rina seraya berkelakar, “Jangan berani-berani hilang sampai Senin.”
Huru-hara Senin pagi tak cuma berasal dariku. Advisor kami diam-diam tak kalah rusuh.
“Sudah jam segini, boleh naik loh,” ujarnya lewat pesan singkat, yang segera kubalas ringkas, “Belum siap, masih kucek.”
Aku bukannya tak tahu, kata “boleh” itu sesungguhnya bermakna suruhan, sehingga pembacaan kalimatnya menjadi: “Sudah jam segini, ayo publish!”
ADVERTISEMENT
Setengah jam kemudian, dia kembali berkirim pesan, kali ini lebih tegas: “Naikin dong, sudah jam segini.” Dan aku membalas pendek, “Oke”, tapi melanjutkan pengecekan selama beberapa waktu ketimbang langsung mematuhi perintahnya untuk segera menayangkan laporan.
Tak jarang kami berseteru sengit di Senin pagi—atau Senin siang sesudah laporan tayang—hingga aku sebal bukan main.
Tapi tenang, pertengkaran macam itu easy come, easy go. Aku tak memusingkan perdebatan sesengit apa pun asal berbasis argumen logis. Tak perlu semua perkara pakai hati kalau tak mau lekas pensiun. Tapi, jangan juga sampai tak berhati. Sebab dengan hati, semua bisa saling merawat, menjaga, dan mengerti.
Omong-omong, aku menulis ini Jumat sore sambil berdebat dengan rekan-rekanku di grup koordinasi kami. Hari Jumat, bagi kami yang diburu tenggat ketat hingga Senin, jadi semacam penentuan dan awal kerja keras lain menuju Senin. Maka, ucapan “Thank God It’s Friday” tidaklah berlaku buat kami.
Lalu bagaimana bisa berlibur?!
ADVERTISEMENT
Aku bukannya mandor kerja paksa. Mereka yang tercuri liburnya di akhir pekan bisa minta ganti libur di hari kerja atau menabungnya untuk memperpanjang cuti.
Tapi bagaimana dengan aku sendiri? Cuti saja masih monitor kerjaan?
Hmm, sepertinya aku sudah terbiasa begitu selama bertahun-tahun. Lagi pula, aku bukannya terikat di kursi dan tak melakukan hal-hal lain. Aku tetap rutin melakoni hobi berenangku, menulis suka-suka di luar pekerjaan (seperti ini), melamun tenang di sela perjalanan naik kereta komuter, menekuri “Cinta Tak Ada Mati”-nya Eka Kurniawan sembari pijat di salon, dan diam-diam menjadi juru potret bocah perempuanku yang untuknyalah cuti ini kupersembahkan—sebab dia sedang libur sekolah dan berhak ditemani bundanya pergi berlibur meski si bunda sambil bawa laptop as always.
Pernah jenuh?
ADVERTISEMENT
Berulang kali. Setengah mati. Kalau sudah begitu, aku akan memanggil rekan-rekan redaktur setimku dan bilang terus terang ke mereka: Aku sedang terserang jemu dan kehilangan separuh konsentrasi; aku perlu bantuan kalian untuk memantau segala perkara lebih ketat sementara aku cari cara memulihkan diri segera.
Mereka biasanya mengangguk, disusul tukar cerita di antara kami untuk berbagi sedikit beban pikiran agar hati terasa lebih lega. Tak selalu ada solusi, tapi yang penting saling mengerti.
Serupa, sebagian redaktur timku juga berkata blak-blakan kalau sedang memerlukan jeda. Seperti Rina yang izin untuk “menghilang” sehari semalam demi menyegarkan pikiran; atau Gota yang tegas berkata, “Akhir Juli aku cuti tak bisa diganggu gugat meski langit runtuh,” demi his significant other yang tengah turun dari Negeri Keju.
ADVERTISEMENT
Maka saat ini pasca-putusan MK, jadwal cuti para reporter dan redakturku sudah rapi tertata. Dari pekan pertama Juli hingga awal Agustus, separuh anggota tim cuti bergantian.
Sampai kapan mau bekerja seperti itu?
Tidak tahu. Biar garis nasib yang menentukan. Nanti ya nanti, sekarang ya sekarang. Siapa tahu masa depan orang? Seminggu, sebulan, setahun dari sekarang, aku bisa jadi apa saja, bisa tidak jadi apa saja, bisa kerja di mana saja, atau bisa tidak kerja di mana saja. Hidup hanya sementara, dan karenanya apa pun peranku dan di mana pun aku berada, aku tak mau serampangan bikin karya. Biar Senin gilaku tak hilang percuma ditelan prahara.
Dan apakah Seninku di bangku sekolah dulu hilang percuma?
ADVERTISEMENT
Tidak juga. Orang bijak bilang, tak ada yang sia-sia. Aku boleh saja masuk “kelas buangan” semasa SMA, tapi toh aku senang di sana dan lulus sebagai runner-up untuk nilai ujian jurusan IPS tertinggi sekota Bogor (yeah, tercium aroma pamer di sini, bukan?)
Pada akhirnya, nilai bukan segala-gala, dan proses lebih penting ketimbang angka. Dan proses yang baik tak mustahil merambah jalan menuju karya bermakna. Tak usah dengar desis ular yang menggerogoti jiwa. Pokoknya, dengan pengalaman sebagai guru berharga tempat ilmumu tertimba, serta kerja keras menerobos batas (atau kerja cerdas kata anak milenial) yang membuat mentalitasmu tertempa, kamu akan selamanya istimewa di mana pun kamu berada.
PS: 1) Ditulis Jumat sore usai berenang bersama anggota Brimob di kota kecil ujung timur Pulau Jawa, sambil menyiapkan energi dan mental untuk kembali menghadapi Senin bising, segera sesudah aku mendarat di Jakarta. 2) Teriring cium lecutan semangat untuk para reporter, redaktur, produser, dan desainer yang tengah berjibaku bersama.
ADVERTISEMENT

