Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional (HPN) dan Gelembung Citra Jokowi
9 Februari 2020 21:04 WIB
Diperbarui 6 Agustus 2020 13:17 WIB
Tulisan dari Anjas Ahmad Munjazi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
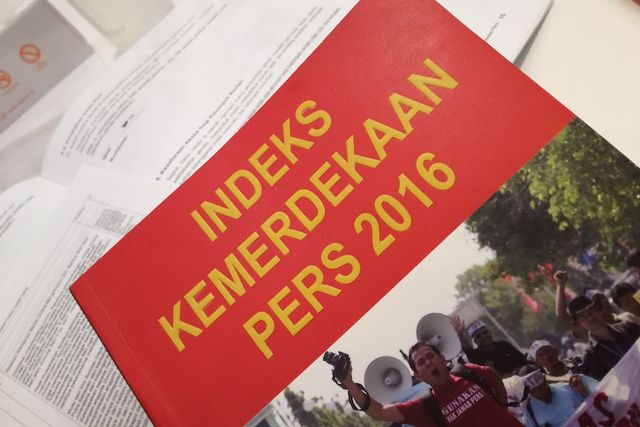
ADVERTISEMENT
Sepak Terjang Pers Indonesia
Pers sebagai ujung tombak demokrasi, memiliki peranan yang begitu vital dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pers dijadikan sebagai sarana perjuangan bagi pejuang Indonesia dalam menuangkan ide-ide politiknya tentang negara merdeka. Sebut saja koran Fikiran Ra’jat yang memiliki hubungan erat dengan Partai Indonesia (Partindo), partai yang didirikan oleh Ir. Soekarno pasca- Partai Nasional Indonesia (PNI) dilarang oleh Belanda. Di koran tersebut lah Soekarno menuangkan idenya tentang kemerdekaan Indonesia.
ADVERTISEMENT
Perkembangan Pers di Indonesia tidak pernah bisa lepas pada masa penjajahan negara Belanda dan Jepang. Pers Indonesia di zaman Belanda juga dikelola oleh para pemimpin gerakan kebangsaan dan keagamaan di Indonesia yang sekaligus merangkap menjadi pemimpin redaksi atau pembantu dari majalah atau surat kabar organisasi yang di pimpinnya.
Pers Era Kolonial
Pada masa penjajahan Belanda, pers Indonesia sudah mempunyai kantor berita yang disebut dengan nama “Aneta” yang kemudian pada tahun 1951 dibeli oleh pengusaha-pengusaha nasional dan melalui yayasan pers biro “Indonesia-Aneta” dengan “pers biro Indonesia” akhirnya dilebur menjadi satu dengan nama “Antara”. Aneta didirikan pada tanggal 1 April 1917 oleh Dominique W. Berrety, seorang yang berketurunan bangsa Italia dan Indonesia. Sebelum Aneta berdiri, setiap surat kabar di Indonesia mempunyai kantor beritanya sendiri yang memerlukan biaya sangat besar dan berita yang diterima tidaklah terlalu lengkap.
ADVERTISEMENT
Kalangan pers kolonial di zaman penjajahan Belanda ada kantor berita Aneta, di dalam kalangan pers nasional yang di tengah-tengah pergerakan dan pers kita menghadapi hantaman oleh pihak penjajah, maka pada tanggal 13 Desember 1937 berdirilah Kantor Berita Nasional “Antara” yang memegang peranan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia.
Jika Aneta menyiarkan berita- berita yang sifatnya membela segala prestasi dan segala kebaikan hati Belanda, maka dengan berdirinya kantor berita Antara dengan maksud untuk menandingi kantor berita Aneta dan juga sebagai untuk mengkoordinasikan dan mempersatukan kekuatan pers nasional dalam suatu bentuk sumber berita-berita yang tidak kolonial dan tidak nasional.
Walaupun dalam azasnya, “Antara” didirikan untuk menyiarkan berita-berita yang objektif dari segala penjuru tanah air.
ADVERTISEMENT
Tokoh- tokoh yang mendirikan “Antara” adalah Albert Manumpak Sipahutar sebagai pemimpin redaksi dan pendukung ide jurnalistik. Karena A.M. Sipahutar menderita penyakit paru-paru, maka diangkatlah Pandu Kartawiguna sebagai pembantu Sipahutar.Sumanang, dan Adam Malik sebagai direktur dan pendukung ide politiknya.
Pers Era Jepang
Perkembangan Pers Indonesia pada zaman penjajahan Jepang berlangsung antara tahun 1942 sampai tahun 1945 dengan pecahnya Perang Pasifik yang dimulai pihak armada Jepang pada tanggal 8 desember 1941 dengan pemboman Pearl Harbour oleh pesawat-pesawat Jepang.
Namun, baru satu bulan Jepang menduduki Indonesia, rasa senang ini berubah menjadi kekecewaan karena semua surat kabar Indonesia menemui ajalnya atau ditutup.Semua surat kabar yang tadinya berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu dengan pers jepang, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan tentara Jepang untuk memenangkan apa yang mereka sebut dengan “dai Toa Senso” atau perang Asia Timur Raya.
ADVERTISEMENT
Zaman pendudukan Jepang, pers adalah alat perjuangan Jepang serta karangan-karangan yang dimuat hanyalah yang mendukung Jepang semata.Walaupun demikian ada juga segi positif bagi karyawan pers kita pada masa ini. Jika di zaman Belanda oplah surat kabar kita tidaklah berarti, maka di zaman Jepang oplah rata-rata berkisar antara dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu eksemplar tiap hari. Hal ini antara lain disebabkan karena orang-orang Jepang menganggap bahwa orang yang tidak membaca surat kabar tiap hari adalah orang yang bodoh. Setelah melewati berbagai periode kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga Reformasi yang merupakan masa pencerahan datang terhadap kebebasan pers, setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Tumbuhnya pers pada masa reformasi merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat.
ADVERTISEMENT
Pers di Era Reformasi
Era reformasi tahun 1998 digulirkan di Indonesia, pers nasional bangkit dari keterpurukannya dan kran kebebasan pers dibuka lagi yang ditandai dengan berlakunya UU No.40 Tahun 1999.Berbagai kendala yang membuat pers nasional "terpasung", dilepaskan. SIUUP (surat izin usaha penerbitan pers) yang berlaku di Era Orde baru tidak diperlukan lagi, siapa pun dan kapan pun dapat menerbitkan penerbitan pers tanpa persyaratan yang rumit.
Dan juga Undang-undang No. 40 tahun1999 plus Kode Etik Jurnalistik (KEJ), memberi kebebasan seluasnya luasnya kepada para penulis untuk berkreasi melalui coretan pena wartawan, meskipun kritis, tapi tetap dalam koridor hukum dan kode etik yang telah ada. Pers dalam era reformasi tidak perlu takut kehilangan ijin penerbitan jika mengkritik pejabat, baik sipil maupun militer.
ADVERTISEMENT
Fenomena itu ditandai dengan munculnya media-media baru cetak dan elektronik dengan berbagai kemasan dan segmen.Keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru pers Indonesia, di era reformasi ini. Sampai pada konteks ini, publik harus tetap mendapatkan informasi yang benar, dan bukan benar sekadar menurut media. Pers diharapkan memberikan berita harus dengan se-objektif mungkin, hal ini berguna agar tidak terjadi ketimpangan antara rakyat dengan pemimpinnya mengenai informasi tentang jalannya pemerintahan.
Ada hal lain yang harus diperhatikan oleh pers, yaitu dalam membuat informasi jangan melecehkan masalah agama, ras, suku, dan kebudayaan lain, biarlah hal ini berkembang sesuai dengan apa yang mereka yakini.
Berkembangnya kebebasan pers di era reformasi ini juga membawa pengaruh pada masuknya liberalisasi ekonomi dan budaya ke dunia media massa, yang sering kali mengabaikan unsur pendidikan. Sebagai dampak dari komersialisasi yang berlebihan dalam media massa saat ini, eksploitasi terhadap semua hal yang mampu membangkitkan minat orang untuk menonton atau membaca pun menjadi sajian sehari-hari. Ada dua pandangan besar mengenai kebebasan pers ini. Satu sisi, yaitu berlandaskan pada pandangan naturalistik atau libertarian, dan sisi lain pada pandangan teori tanggung jawab social terabaikan dapat contoh sehari-hari banyaknya iklan dari perusahaan asing dan acara yang mengikuti tren dari luar.
ADVERTISEMENT
Kemerdekaan pers dalam arti luas adalah pengungkapan kebebasan berpendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia Masyarakat demokratis dibangun atas dasar konsepsi kedaulatan rakyat, dan keinginan-keinginan pada masyarakat demokratis itu ditentukan oleh opini publik yang dinyatakan secara terbuka.
Hak publik untuk tahu inilah inti dari kemerdekaan pers, sedangkan wartawan profesional, penulis, dan produsen hanya pelaksanaan langsung Tidak adanya kemerdekaan pers ini berarti tidak adanya hak asasi manusia (HAM) hal ini tidak diawasi dan dibuat hukum yang kuat maka ini bisa dipulangkan kembali kepada konsumen yang melihat pers menurut pandangan mereka.
Konseptualisasi Hari Pers Nasional (HPN)
Sebagaimana diketahui , tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Penetapan tanggal tersebut mengundang polemik dari beberapa komunitas/organisasi pers di Indoensia. Aliansi Jurnalis Independent (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) tidak menyepakati tanggal 9 februari sebagai Hari Pers Nasional. Selain tidak mencerminkan sejarah pers Indonesia,HPN mengacu pada hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto—penguasa Orde Baru yang menindas pers—melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Pada era itu, PWI adalah satu-satunya organisasi wartawan yang diakui dan diizinkan oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
Ide untuk membuat 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional sendiri sudah berlangsung lama. Tepatnya, di tahun 1978 saat kongres ke 16 PWI di Padang, Sumatera Barat. Saat itu ketua PWI dijabat oleh Harmoko, pemimpin redaksi Pos Kota yang kemudian menjadi menteri penerangan. Ide itu menjadi salah satu keputusan kongres, yaitu keinginan dari komunitas pers untuk memperingati peran pers Indonesia. Ide ini lantas diusulkan kepada Dewan Pers.
Meskipun sudah menjadi rekomendasi resmi dari PWI kepada Dewan Pers, pemerintah baru menetapkan ide tersebut 7 tahun kemudian. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1985, pada 23 Januari 1985 Hari Pers Nasional resmi diperingati setiap tahun di tanggal 9 Februari.
Dalam perjalanannya, eksistensi Hari Pers Nasional mulai dipertanyakan, khususnya sejak rezim Orde Baru jatuh di tahun 1998. Berbagai diskusi digelar dan perdebatan publik mengemuka. Sekelompok jurnalis dan penulis pada 7 Desember 2007 mendeklarasikan Hari Pers Indonesia di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Pemilihan tanggal 7 Desember didasarkan pada hari meninggalnya Tirto Adhi Soerjo, bapak pers nasional.
ADVERTISEMENT
Salah satu yang tokoh yang turut mendeklarasikan Hari Pers Indonesia adalah Taufik Rahzen yang juga menulis buku Seabad Pers Kebangsaan (2007). Dalam buku tersebut, Taufik menulis bahwa semestinya yang menjadi tonggak bagi kehidupan pers di Indonesia adalah Tirto Adhi Soerjo yang merupakan pemimpin redaksi Medan Prijaji, media pertama yang menggunakan bahasa Melayu.
Deklarasi dan penerbitan buku tersebut memicu banyak respons, salah satunya dari Suryadi, dosen dan peneliti di Universitas Leiden. Suryadi menyebut bahwa menggunakan satu nama koran atau tokoh sebagai penanda peringatan pers Indonesia sama artinya dengan mengabaikan peran koran-koran lain yang juga memiliki sumbangan besar dalam sejarah pers di Indonesia.
Dalam responnya tersebut, Suryadi menulis: “Pilihan Taufik Rahzen dkk. itu secara tidak langsung mengandung makna bahwa Medan Prijaji-lah pers pribumi yang paling berjasa dalam menyemaikan perasaan nasionalisme ke dalam dada kaum pribumi di zaman Kolonial, untuk tidak mengatakan paling ‘nasionalis’”. Perdebatan-perdebatan semacam ini hampir muncul setiap tahun hingga saat ini, sementara hari pers tetap diperingati pada 9 Februari. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo)
ADVERTISEMENT
Pers dan Jokowi
Pada peringatan HPN tahun 2019, Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan berupa medali kebebasan pers yang diberikan langsung oleh ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Medali itu diberikan karena Jokowi tidak pernah mengintervensi urusan pers. “Presiden memberikan ruang kebebasan kepada komunitas pers untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.”
Menurut penulis, “tidak pernah mengintervensi urusan pers” tidak bisa dipakai sebagai ukuran tunggal untuk mengevaluasi kondisi kebebasan pers. Ketiadaan intervensi pemerintah dalam kerja media hanya satu aspek dalam menjamin kebebasan pers. Reporters Without Borders memiliki tujuh kriteria untuk mengukur kebebasan pers suatu negara, yakni keberagaman opini yang direpresentasikan media, independensi media, lingkungan dan swa-sensor media, perundang-undangan media, transparansi institusi media, serta kekerasan terhadap media.
ADVERTISEMENT
Dalam hal keberagaman opini, ini menyangkut keberagaman pemilik media. Di Indonesia, konsentrasi kepemilikan media yang berpusar di segelintir konglomerat adalah faktor yang menghambat kebebasan pers. Monopoli media, tentu saja, tidak memungkinkan terjadinya keberagaman opini.
Sayangnya, semasa pemerintahannya Jokowi tidak pernah menunjukkan satu pun gestur untuk membenahi masalah ini. Padahal Jokowi menuangkan hal ini dalam Nawa Cita-nya: “Kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang (kartel) industri penyiaran”.
Dalam aspek lain, mari kita lihat kondisi provinsi paling timur di Indonesia sekaligus paling tertutup bagi pers: Papua. Terlepas dari pernyataan Jokowi pada Mei 2015 bahwa akses jurnalis internasional ke Papua Barat akan dibuka, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Proses birokrasi bagi jurnalis internasional untuk masuk ke Papua sangat rumit. Tidak hanya itu, meski izin telah terbit, kerja wartawan asing juga akan selalu diawasi. Mereka juga dilarang melaporkan isu hak asasi manusia dan politik.
ADVERTISEMENT
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sendiri berkata bahwa akses media asing ke Papua dilakukan dalam rangka memproduksi laporan yang tidak bertentangan dengan posisi pemerintah, dan menyebarkan pesan bahwa “kekerasan dan pelanggaran HAM tidak terjadi di Papua”.
Selain pembatasan akses bagi jurnalis, pemerintah juga melakukan pemblokiran situs di Papua. Setelah situs Suarapapua.com sempat diblokir pada November 2016, empat situs informasi Papua lainnya juga diblokir pada awal April 2017, yakni Infopapua.org, Tabloid-wani.com, Papuapost.com, Freepapua.com, dan Ampnews.org.
Dalam kasus kekerasan terhadap terhadap media, data pelaporan yang diterima AJI sepanjang tahun 2019 (setidaknya sampai 23 Desember 2019), terdapat 53 kasus kekerasan terhadap wartawan. Di bandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tahun ini mengalami penurunan. Tahun 2018 setidaknya ada 64 kasus kekerasan. Namun jika merujuk pada rata-rata kasus kekerasan dalam 10 tahun ini, jumlah ini masih di atas rata-rata. Meski lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kasus pada 3 tahun belakangan ini, namun itu masih di atas jumlah kasus pada tahun 2013 (40 kasus), 2014 (40 kasus), dan 2015 (42 kasus). Kasus kekerasan masih didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Setelah itu diikuti oleh perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), ancaman kekerasan atau teror (6 kasus), pemidanaan atau kriminalisasi (5 kasus), pelarangan liputan (4 kasus). Masih dominannya kasus dengan jenis kekerasan fisik ini sama dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu jenis kekerasan fisik tercatat ada 12 kasus, tahun 2017 sebanyak 30 kasus.
ADVERTISEMENT
Kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan masa lalu pun banyak yang tak terselesaikan. Jokowi bahkan sempat memberi remisi kepada otak dan pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali, Susrama. Meski remisi ini akhirnya dicabut setelah desakan dari berbagai pihak, langkah ini tetap menunjukkan kecenderungan Jokowi untuk membuka pintu toleransi lebih lebar bagi mereka yang mengancam kebebasan pers. Jokowi bahkan diam ketika sejumlah kader partainya sendiri, PDIP, menggeruduk kantor Radar Bogor 2018 lalu. Bahkan kabar terbaru di tahun 2020 ini, Jurnalis MNC Group Indra Yoserizal menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para petugas keamanan PT Nusa Wana Raya (NWR). Selain dianiaya, Indra juga sempat disekap. Kamera Indra dirampas dan dirusak.
Selain kekerasan langsung, berdasarkan pemantauan SAFEnet, terdapat 19 kasus pemidanaan terhadap jurnalis dan media menggunakan UU ITE, sejak 2015 hingga 2018. Meski UU penista kebebasan berpendapat ini sudah menjerat banyak korban, pemerintahan Jokowi tidak pernah berusaha untuk mengevaluasinya.
ADVERTISEMENT
Pada 2018, indeks kebebasan pers Indonesia yang dirilis Reporters Without Borders berada di peringkat 124 dari 180 negara. Reporters Without Borders sendiri menyatakan bahwa apa yang dijanjikan Presiden Jokowi di masa kampanyenya mengenai keterbukaan informasi dan komunikasi publik tidak ditepati. Selama masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang makin membatasi kerja pers dan hak publik terhadap informasi.
Fakta-fakta di atas adalah segelintir aspek dari hal yang harusnya dipertimbangkan oleh Dewan Pers dan panitia Hari Pers Nasional dalam mengukur kualitas kebebasan pers. Mengabaikan faktor-faktor lain yang menjamin iklim kebebasan pers adalah sikap yang menjunjung “kebenaran selektif”, yakni hanya mengambil fakta kebenaran yang menguntungkan dan membuang yang merugikan.
Pada akhirnya, sampai hari ini kasus intimidasi terhadap pers tidak pernah memiliki keadilan sampai tuntas dalam pengadilan. Dan penghargaan medali kebebasan pers kepada Jokowi hanya semata mata seperti gelembung, mudah dibentuk (menjadi besar atau kecil), tak memilki isi, dan mudah pecah. Dan sebaiknya kita tidak perlu menganggap Hari Pers Nasional (HPN) sebagai ajang progresif pers di Indonesia.
ADVERTISEMENT

