Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Apakah Pandemi Mempengaruhi Demokrasi?
28 April 2021 17:07 WIB
Tulisan dari A Satria Pratama tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Jika iya, bagaimana pandemi mempengaruhi demokrasi?
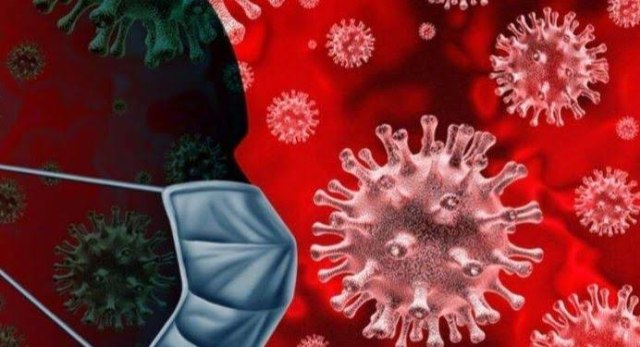
ADVERTISEMENT
Sebelum sampai pada situasi yang mampu menjelaskan bagaimana pandemi mempengaruhi demokrasi, saya ingin terlebih dulu sampaikan bahwa ketika tulisan ini saya susun, virus corona di Indonesia telah menjangkit lebih dari satu setengah juta penduduk. Jumlah yang seolah ingin mengingatkan kita bahwa pandemi belum benar-benar purna. Alih-alih tuntas, meski telah lebih dari dua belas bulan lamanya, faktanya, wabah masih terus mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Salah satunya adalah hubungan antara masyarakat dan negara dalam kerangka daily democracy. Pertanyaan lantas mengemuka, apa benar pandemi mempengaruhi praktik demokrasi? Jika iya, bagaimana pandemi bisa melakukannya? Melalui tulisan ini, saya berusaha untuk mengelaborasi pengaruh pandemi terhadap keberlangsungan praktik kehidupan demokrasi di Indonesia.
Saya berpandangan, pengaruh pandemi terhadap demokrasi bisa kita rasakan setidak-tidaknya di dua level. Tingkat pertama adalah bagaimana pandemi mempengaruhi kemapanan proses demokratisasi yang terjadi dalam hubungan vertikal antara negara dan masyarakat.
Ada pun tingkat kedua adalah bagaimana pandemi menantang praktik demokratisasi dalam hubungan horizontal antar masyarakat. Saya akan mengelaborasi dua pendalaman ini pada bagian selanjutnya. Namun demikian, keduanya hanya bisa dibicarakan setelah ketidaksiapan pemerintah dalam menangani COVID-19 saya elaborasi terlebih dulu.
ADVERTISEMENT
Ketidaksiapan Pemerintah
Menurut beberapa literatur, pandemi terakhir yang menewaskan korban secara global adalah flu spanyol yang terjadi pada 1918. Dengan demikian, COVID-19 yang terjadi (lebih dari) 100 tahun setelahnya, adalah pandemi yang sama sekali baru bagi masyarakat dalam rentang satu periode peradaban. Sampai-sampai, beberapa otoritas tampak demikian kesulitan dalam merespons kehadirannya. Apalagi melakukan pengelolaan terhadap risiko kebencanaannya.
Meskipun demikian, sebagai sebuah entitas politik super power, pemerintah sebetulnya memiliki segepok sumber daya yang bisa dihamburkan untuk rakyat. Jika logika awam boleh ditawarkan, maka solusinya hanya soal pilihan; karena wabah ini berangkat dari dimensi kesehatan, maka yang harusnya digunakan adalah pendekatan kesehatan. Dengan demikian, ketika di awal waktu para ahli merekomendasikan karantina wilayah sebagai pemecah kebuntuan, saya berpandangan bahwa pemerintah, mestinya, mengadopsinya menjadi kebijakan.
ADVERTISEMENT
Persoalan muncul ketika karantina wilayah harus diikuti dengan distribusi bantuan. Ini jelas merupakan amanat perundangan. Padahal di sisi ekonomi, pemerintah sedang sulit menghadiahkan kepastian. Maka lengkap sudah penderitaan; korban terus berjatuhan, tetapi resesi tidak terelakkan. Pemerintah sedang menjalankan pemerintahan dalam koridor yang sama sekali tidak diinginkan. Oleh karenanya, mengikuti kerangka berpikir dominan, kita jadi memaklumi pilihan kebijakan para eksekutif dan anggota dewan, untuk menjalankan tata kelola di atas dua keinginan; ekonomi dan kesehatan.
Masalahnya, pilihan tersebut bukan tanpa risiko. Sebagaimana kita ketahui, pilihan politik pemerintah untuk berdiri di dua kaki menyebabkan kurva COVID-19 tak kunjung menuju nol. Data yang ada akan dengan mudah menunjukkan bahwa alih-alih berakhir, pandemi justru terus-menerus memproduksi persoalan sosial politik.
ADVERTISEMENT
Kita bisa lihat di lapangan. Hari ini, masyarakat tidak lagi menggunakan cara yang mereka gunakan pada bulan Maret 2019 untuk merespons COVID-19. Ini menunjukkan bahwa, meski masyarakat telah melakukan penyesuaian gaya hidup, tapi kecemasan terhadap COVID-19 tampak berangsur menurun. Masyarakat sudah berbelanja, bekerja, bertemu, sekolah bahkan rekreasi seperti sebelum COVID-19 menghampiri. Kehidupan tampak biasa saja, meski dengan beberapa pembaruan seperti penggunaan masker dan hand sanitizer.
Benar bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Namun demikian, kita harus membuka mata bahwa penurunan kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 (meski kurva nya belum nol), juga terjadi karena pemerintah menginisiasi "titik pijaknya". Pemerintah memilih strategi pengendalian COVID-19 yang memproduksi dampak "abu-abu" bagi masyarakat.
Konsekuensinya, pemerintah tidak akan konsisten menegakkan peraturan. Dalam hal penindakan penyelenggaraan event yang memproduksi kerumunan, Pemerintah akan tampak pilih kasih. Penghukuman "berat sebelah" inilah yang akan menghasilkan implikasi pada praktik demokrasi kita. Faktanya, demonstrasi berbasis massa telah beberapa kali terjadi di tengah pandemi. Tetapi hanya sebagian yang ditindak. Akuntabilitas tata kelola pemerintahan dipertaruhkan.
ADVERTISEMENT
Tetapi ruang abu-abu yang dibuat oleh pemerintah, boleh jadi memberi kesan yang berbeda bagi relasi kuasa menguasai antarwarga sesama masyarakat. Ruang abu-abu berarti negara tidak hadir dalam bentuk utuhnya. Sebaliknya, ruang yang ada justru mengakomodasi tumbuh berkembangnya interaksi politik sesama masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan pandemi, studi soal daily democracy di ranah masyarakat menjadi relevan.
Pada saatnya, ketidaksiapan pemerintah tersebut memaksa kita untuk menggunakan cara baru berdemokrasi. Kita bisa menganalisanya dari dua jenis interaksi; antara negara dan masyarakat dan antara masyarakat dengan sesamanya.
Interaksi Vertikal: Negara dengan Masyarakat
Hubungan antara negara dan masyarakat dari perspektif demokrasi banyak bermuara pada proses akuntabilitas pemerintahan. Idenya adalah agar ada cukup ruang yang disediakan oleh pemerintah, dan di saat yang bersamaan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
ADVERTISEMENT
Sayangnya, pandemi membuat cara mereka menjalin interaksi menjadi "berat sebelah". Untuk mengelaborasi ini, saya menawarkan dua cara melihat hubungan aktual negara dan masyarakat dalam nuansa pandemi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
Pertama, pandemi membuat negara dan masyarakat sibuk dengan urusannya masing-masing. Dari sisi masyarakat, kesulitan hidup sedang menjadi tema sanubari. Mereka kehilangan pekerjaan, susah berjualan, tetapi tak semua mendapat bantuan. Padahal ada kehidupan yang harus terus diupayakan. Dapur harus bisa, bukan hanya bertahan, melainkan juga melawan. Kisah tentang orang yang secepat kilat berganti adegan kehidupan dari kemapanan karir perkantoran menuju percobaan jualan pinggir jalan tampak mendramatisasi media berpuluh-puluh pekan.
Dalam kondisi seperti itu, tidak mudah bagi mereka untuk memperhatikan "tindak-tanduk" negara melalui alokasi waktu khusus. Keluarga dan diri sendiri sedang menjadi objek perhatian nomor satu. Akibatnya, perhatian terhadap perilaku negara menjadi tidak sekuat biasanya. Kalaupun ada satu dua kali penyelenggaraan demonstrasi, tetap saja tidak akan sebombastis ketika dilakukan di luar pandemi. Musibah kali ini betul-betul menciptakan pola pikir masyarakat yang pasif politik. Ujungnya, tidak banyak upaya untuk mengingatkan pemerintah.
ADVERTISEMENT
Dari sisi negara, teknis-teknis recovery yang tampaknya berpihak ke ekonomi, sedang disusun dan dijalankan. Sambil menunggu penuntasan vaksin, negara tampak sibuk melakukan penyesuaian berbagai program kerja. Belakangan, penyesuaian tersebut lebih terasa sebagai pemadatan. Kalau sudah begini, proses deliberasi akan dikorbankan.
Kedua, pandemi, pada banyak situasi, memaksa negara dan masyarakat, alih-alih berhadap-hadapan, melainkan bekerja bersama. Ini berangkat dari dampak pandemi yang mengharuskan negara dan masyarakat seringkali berada dalam satu keinginan kolektif. Sudah tentu, keinginan itu adalah agar vaksin bisa segera terdistribusi secara menyeluruh.
Penuntasan proses vaksinasi jelas bukan hanya keinginan masyarakat, melainkan juga keinginan negara. Sebagian besar pihak bahkan menyebutnya sebagai satu-satunya solusi yang akan mengakhiri pandemi. Akibatnya, masyarakat merasa tidak punya persoalan karena toh negara telah menjawab yang mereka sedang sangat butuhkan saat ini; ketersediaan vaksin.
ADVERTISEMENT
Dengan demikian, apabila pemerintah telah mendistribusi vaksin, masyarakat tak akan banyak mempersoalkan hal-hal di luar itu. Di bawah hegemoni vaksin, negara dan masyarakat sedang tidak berbeda. Apalagi berhadap-hadapan. Praktik demokrasi, dalam arti pengawasan atas akuntabilitas, menjadi tak berlaku.
Interaksi Horizontal: Masyarakat dengan Masyarakat
Pada level horizontal antarwarga, unsur yang menurut saya tepat untuk digunakan sebagai alat uji adalah "kesetaraan". Dengan demikian, mari kita buktikan, apakah pandemi mengganggu demokrasi, dalam arti kesetaraan? Atau sebaliknya, pandemi memperteguhnya?
Namun demikian, saya berpandangan bahwa kesetaraan ini harus terlebih dulu kita kategorisasikan. Apakah yang dimaksud sebagai kesetaraan berkaitan dengan ekonomi, hukum, sosial, akses, hak politik, atau lainnya? Sebagai penulis, saya mencukupkan opini saya hanya pada dua dimensi; menguji kesetaraan pada ranah ekonomi dan sosial.
ADVERTISEMENT
Pertama, jika yang dimaksud adalah kesetaraan ekonomi, maka kajian tentang bagaimana pandemi secara teknis mempengaruhi daya beli, relevan untuk menjadi bahan diskusi. Mulai dari kampanye soal “di rumah saja”, semua sektor luluh lantak merespons dampaknya. Transportasi berhenti.
Otomatis, hampir seluruh sektor bisnis ikut berhenti. Dalam situasi yang serba tidak pasti, alih-alih membelanjakan uang, semua orang memilih menahan dana nya atas alasan emergency. Akibatnya, daya beli turun drastis. Sektor perdagangan terpukul hebat.
Benar bahwa kondisi ekonomi masing-masing orang tidak bisa disimpulkan secara seragam. Faktanya, orang kaya, melalui strategi bisnisnya, ada yang malah bertambah kaya. Tapi ada yang lantas jatuh miskin walau sebelumnya bekerja dengan mapan.
Beberapa bulan setelah ekonomi tak lagi bisa dibiarkan lesu terus-terusan, cerita soal orang-orang yang berjuang untuk menata ulang kehidupannya, tampak menghiasi pemberitaan dominan. Benar bahwa mereka di putus hubungan kerja, tetapi kehidupan harus tetap berjalan. Betul bahwa bisnis mereka gulung tikar, tetapi dapur harus tetap menghasilkan. Pada situasi ini, saya berpandangan bahwa masyarakat sedang berada dalam level yang setara. Suatu efek ekonomi luar biasa yang, meskipun tidak dirasakan oleh semua orang, namun demikian bisa menjadi persoalan kolektif yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat, dalam kesetaraan ekonomi, bahu membahu memperjuangkan hidup yang baru.
ADVERTISEMENT
Kedua, jika yang dimaksud adalah kesetaraan sosial, maka suasana batiniah yang menjadi faktor utama. Pandemi memaksa setiap dari manusia, sebagai bagian dari masyarakat, merasa senasib sepenanggungan. Sama-sama merasa sedang dalam ujian Tuhan, sama-sama merasa sedang berada dalam ketidakpastian.
Lagu-lagu bernuansa nasionalisme untuk menyemangati satu sama lain, berseliweran begitu seringnya. Iklan-iklan yang berusaha untuk menularkan spirit perjuangan juga lantas menggelora di mana-mana. Akhirnya, saya berpendapat bahwa kesetaraan sosial kita justru menemukan titik equilibrium nya selama pandemi.
Pandemi Mempengaruhi Demokrasi
Melalui opini sederhana, saya berpendapat bahwa pandemi mempengaruhi cara kita menyelenggarakan daily democracy. Namun demikian, pengaruh tersebut terjadi pada dua tingkat yang berbeda, dengan unsur yang berbeda sehingga menghasilkan dua kesimpulan berbeda.
ADVERTISEMENT
Pada level interaksi antara negara dan masyarakat, pandemi menantang unsur transparansi. Saya berpendapat, pandemi memaksa masyarakat dan negara untuk memprioritaskan cara bertahan hidup terlebih dulu. Karena masing-masing pihak fokus pada penyesuaian kehidupan baru, demokrasi menjadi terganggu.
Masyarakat terdepolitisasi, sementara negara nyaman dengan keleluasaannya. Pada level ini, pandemi menggoyahkan "transparansi dan akuntabilitas" tata kelola pemerintahan. Tetapi pada level masyarakat, saya berpandangan lain. Menurut saya, pandemi justru memperteguh kesetaraan kewargaan. Pandemi menyandera masyarakat satu sama lain untuk merasa senasib sepenanggungan. Ujungnya, "politik kesetaraan" menjadi daily tanpa sedemikian rupa dipromosikan. Akhirnya, sekaligus menutup tulisan, saya berpandangan bahwa pandemi mempengaruhi demokrasi sesuai level nya, sesuai konteksnya.

