Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
FOMO, Ketika Takut Ketinggalan Menjadi Gaya Hidup
14 April 2025 13:01 WIB
·
waktu baca 8 menitTulisan dari Ares Faujian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
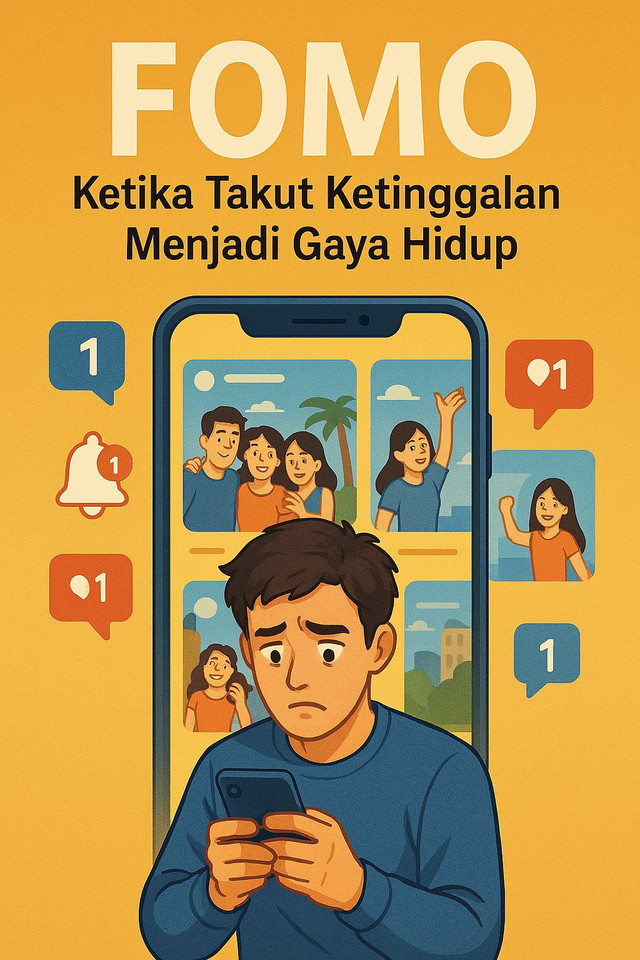
ADVERTISEMENT
Di era digital seperti sekarang, satu notifikasi di ponsel bisa membuat kita merasa FOMO. Lalu lintas informasi begitu cepat, dan hidup orang lain tampak selalu lebih seru di media sosial. Misalnya melihat orang lain dengan tren baju terbaru, menyaksikan orang-orang berbondong-bondong ke spot wisata lokal yang sedang viral, hingga penggunaan lagu di media sosial yang sedang populer pada warganet. Perasaan seperti ini dikenal sebagai FOMO—ketakutan akan ketinggalan. Tapi, apa sebenarnya penyebab di balik fenomena ini?
ADVERTISEMENT
Fear of Missing Out atau FOMO didefinisikan sebagai perasaan cemas yang muncul ketika seseorang merasa tertinggal dari pengalaman sosial yang berharga, sering kali terlihat di media sosial (Gupta & Sharma, 2021; Alabri, 2022), di mana individu merasa perlu untuk tetap terhubung dan mengetahui apa yang dilakukan orang lain (Franchina et al., 2018; Groenestein et al., 2024; LeRoy et al., 2023).
FOMO bukan hanya sekadar masalah teknologi. Ia adalah produk dari kebutuhan sosial yang dalam, cara kita diasuh, serta dinamika emosi yang kompleks. Bahkan dalam perspektif sosiologi, FOMO mencerminkan bagaimana individu membentuk identitasnya dalam masyarakat yang semakin terhubung, namun juga semakin kompetitif secara sosial. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya FOMO.
FOMO sebagai Kebutuhan Sosial
Setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan ini bukan hal baru—sosiolog klasik seperti Émile Durkheim telah menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga keseimbangan psikologis individu. Kebutuhan untuk merasa termasuk dalam kelompok sosial adalah prediktor utama FOMO. Kebutuhan ini dapat meningkatkan FOMO secara langsung dan melalui penggunaan media sosial (Alabri, 2022; Seker, 2022; Beyens et al., 2016).
ADVERTISEMENT
Ini sejalan dengan teori “looking-glass self" dari Charles Horton Cooley yang menyatakan bahwa identitas diri kita dibentuk melalui persepsi orang lain terhadap kita. Konsep ini menekankan bahwa pandangan kita tentang diri sendiri sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita percaya orang lain melihat kita (Siljanovska & Stojchevska, 2018; Lucksted & Drapalski, 2015; Silva et al., 2020). Maka tak heran, ketika melihat teman-teman mengunggah momen kebersamaan, liburan, atau prestasi, kita merasa perlu “ikut serta”—meski hanya secara digital.
FOMO sebagai Eksistensi Media Sosial
Media sosial menjadi arena utama tempat FOMO tumbuh subur. Setiap scroll membuka kemungkinan untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Penggunaan media sosial yang intensif sering kali dikaitkan dengan peningkatan FOMO. Media sosial memberikan akses konstan ke informasi tentang aktivitas orang lain, yang dapat memicu perasaan tertinggal (Bloemen & De Coninck, 2020; Nurhayati & Azhar, 2023; Buglass et al., 2017; Abel et al., 2016).
ADVERTISEMENT
Dari perspektif teori pertukaran sosial (social exchange theory), kita bisa memahami bahwa media sosial menjadi alat untuk menilai “nilai sosial” kita dibandingkan dengan orang lain. Pengguna media sosial menilai nilai sosial berdasarkan persepsi kegunaan, nilai ekonomi, dan nilai sosial yang mereka dapatkan dari interaksi di platform tersebut. Persepsi ini dapat memengaruhi niat mereka untuk menggunakan media sosial lebih lanjut (Dootson et al., 2016). Ketika kita merasa tidak cukup aktif, tidak cukup eksis, atau tidak cukup "update", maka muncul kecemasan akan kehilangan status atau hubungan sosial yang berharga terhadap orang-orang tertentu. Hal ini dikarenakan kita tidak mengetahui dan ikut terlibat pada aktivitas yang serupa.
FOMO Karena Keluarga dan Pola Asuh
Struktur keluarga dan gaya pengasuhan anak memainkan peran penting dalam perkembangan FOMO. Ihwal ini menjadi bagian dari keluarga yang tidak utuh, gaya pengasuhan ayah, dan hubungan berkualitas tinggi yang dirasakan dengan orang tua merupakan faktor pelindung untuk FOMO, sementara hubungan berkualitas tinggi yang dirasakan antara orang tua merupakan faktor risiko FOMO (Bloemen & De Coninck, 2020).
ADVERTISEMENT
Sosiolog Talcott Parsons menyoroti peran keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Menurut Parsons, keluarga berfungsi untuk sosialisasi primer anak-anak, di mana mereka belajar norma sosial dan nilai-nilai inti dari orang tua mereka, serta meniru perilaku orang tua mereka (Yee, 2023). Jika keluarga gagal menyediakan rasa aman, penerimaan, validasi dan mengontrol media sosial pada anaknya, maka anak akan mencarinya di luar—termasuk di media sosial. Di sinilah FOMO bisa tumbuh menjadi semacam "kompensasi sosial."
FOMO Karena Tekanan Sosial dan Validasi Diri
Ketakutan akan ketinggalan tren sosial dan keinginan untuk terlibat dalam percakapan teman mendorong seseorang untuk selalu online. Dalam dunia yang menilai “keberadaan” lewat aktivitas digital, media sosial menjadi sarana eksistensi. Nurhayati & Azhar (2023) menegaskan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan acap kali berkaitan dengan upaya mencari validasi dan kepuasan diri.
ADVERTISEMENT
Dari sudut pandang teori dramaturgi Erving Goffman, media sosial adalah panggung tempat individu menampilkan versi terbaik dirinya. Penggunaan media sosial sebagai panggung untuk menampilkan diri dapat menyebabkan konflik antara kehidupan nyata dan virtual, memengaruhi bagaimana individu memproyeksikan diri mereka (Tanwar & Pandey, 2022). Penampilan ini bisa jadi menekan: ketika kita merasa “pertunjukan orang lain” lebih menarik, kita diliputi rasa takut bahwa kita tak lagi relevan.
FOMO Karena Emosi Negatif dan Kesehatan Mental
Tak bisa dipungkiri, FOMO berkaitan erat dengan emosi negatif seperti kecemasan dan stres, hingga berefek pada hubungan sosial seseorang terhadap lingkungan sekitar maupun digitalnya. Li et al. (2020) menemukan bahwa FOMO tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis, tetapi juga berdampak pada kualitas tidur dan berpotensi menyebabkan kecanduan ponsel. Kecanduan ini mampu membuat seseorang menjadi individualis dan bisa melakukan bunuh diri jika kehidupannya tertekan karena tidak sesuai ekspektasinya.
ADVERTISEMENT
Ini memperkuat pandangan teori anomie Durkheim, bahwa disintegrasi norma sosial dalam masyarakat modern dapat menimbulkan perasaan terasing, gelisah, dan hampa. Anomie (perilaku tanpa arah dan apatis) dapat menyebabkan disintegrasi keluarga dan hilangnya sistem moral yang mengatur masyarakat, mengakibatkan masyarakat yang terpecah dan kehilangan arah (Qutami, 2023; Gupta & Gupta, 2018). FOMO, dalam bentuk ekstremnya, bisa menjadi cerminan krisis identitas di tengah gempuran ekspektasi digital.
Penutup
FOMO bukan sekadar fenomena sosial dari akibat perkembangan teknologi. Ia adalah cerminan dari struktur sosial, kebutuhan psikososial, dan dinamika interaksi digital yang terus berubah. Dengan memahami penyebabnya dari berbagai sudut pandang, terutama secara psikologis dan sosiologis, hingga kultural, kita bisa mulai membangun kesadaran diri untuk memilah antara kebutuhan sosial yang sehat dan tekanan sosial yang memenjarakan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang selalu hadir di setiap momen orang lain, tapi tentang hadir penuh di momen kita sendiri.
ADVERTISEMENT
Oleh: Ares Faujian
Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sosiologi Kab. Belitung Timur & America Field Service (AFS) Global Up Educator
Referensi
ADVERTISEMENT

