Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Sisi Gelap Filsafat Ibnu Sina dan Kegamangan Saiful Mustofa
24 November 2024 16:16 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Ahmad Natsir tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
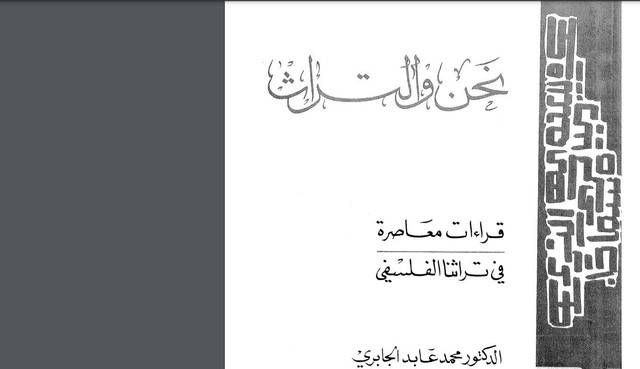
ADVERTISEMENT
Membaca kritik Saiful Mustofa atas tulisan saya, betul-betul menggelitik pikiran saya. Saya harus kembali merenungkan jawaban atas protes yang dia layangkan. Sangkaannya atas cacat logika yang saya alami, saya anggap tuduhan yang cukup serius bagi karir intelektual saya. Ehm ehm.
ADVERTISEMENT
Sebelum saya menjawab tuduhan tersebut perkenankan saya untuk mempersembahkan cerita masa lalu sekitar 11 abad silam yang cukup panjang. Cerita (baca: hasil analisis) ini saya sadur dari karya Abed al-Jabiri dalam bukunya Nahn wa al-Turath [Kita dan Tradisi] (1993) halaman 38 dan seterusnya.
***
Syahdan pada Abad ke-9 Masehi, pasca terjadinya revolusi kaum Sunni atas Muktazilah, terjadilah perpecahan yang melanda Dinasti Abbasiyyah. Perebutan kekuasaan terjadi begitu hebat di masa ini, antara dinasti Buwaihi, Hamdaniyah, dan kaum Syiah atas Sunni. Disintegrasi tak bisa dihindari, betapa pun sebelumnya, misalnya, Al-Mu'tadid (892–902 M) telah berusaha memulihkan otoritas Abbasiyah yang sempat melemah akibat konflik internal dan ancaman dari dinasti-dinasti kecil, namun usaha itu ternyata gagal di era khalifah selanjutnya.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya konflik kekuasaan, konflik ideologi pun juga terjadi dan mulai bercabang ke sana-sini. Berbagai konflik yang muncul ini jelas menjadi ancaman sendiri bagi otoritas kekuasaan saat itu. Adalah Al-Farabi (870-950 M) hidup dalam masa penuh konflik semacam itu. Namun, di tengah konflik semacam itulah pemikiran menyegarkan muncul dari buah karyanya.
Suasana disintegrasi Dinasti Abbasiyah dalam bidang pemikiran telah mencuatkan gagasan al-’aql al-kauni (nalar universal). Dengan ide ini dia telah melampaui pemikiran Muktazilah karena dirasa gagal dalam mendamaikan “perseteruan” antara wahyu dan akal. Al-Farabi menggagas peleburan agama dengan frasa agama adalah model ideal dari apa yang dikandung oleh filsafat (ma fi al-din mithal li ma fi al-falsafah).
Proyek selanjutnya yang digagas oleh Al-Farabi dalam rangka menyatukan kembali masyarakat yang kian terpecah belah. Dia menggagas kota utama (al-madinah al-fadilah), kota masyarakat ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf-raja yang bijaksana, yang memadukan akal dan wahyu untuk mencapai kebahagiaan bersama. Dalam masyarakat ini, setiap individu menjalankan perannya sesuai dengan keahlian dan sifatnya, sehingga tercipta harmoni yang memungkinkan tercapainya tujuan tertinggi manusia: kebahagiaan spiritual dan intelektual.
ADVERTISEMENT
Proyek kota utama al-Farabi adalah ideologis, yang pada saat yang bersamaan al-Farabi memeras pemikirannya dengan memanfaatkan ilmu-ilmu rasional yang berkembang saat itu. Memang benar bahwa proyek itu adalah proyek impian, hanya impian belaka, namun, proyek al-Farabi adalah proyek rasional khas karakter petarung intelektual sejati. Al-Farabi bukan hanya ilmuan yang duduk di belakang meja dengan penanya, namun juga sosok yang bergumul dengan masyarakat sembari memikirkan berbagai tantangan yang dia hadapi pada masa itu.
Yang mengherankan Jabiri kemudian adalah sedemikian revolusionernya al-Farabi mengapa pemikirannya seolah tenggelam saat ini? Bahkan sosok semacam Rousseau-nya Arab boleh jadi muncul dalam dirinya, mengapa tidak terjadi?
Adalah Ibn Sina (980-1037 M) divonis bersalah oleh al-Jabiri kali ini. Ibn Sina, sosok yang hidup di masa kekacauan Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya. Jabiri mengabarkan bahwa dia hidup di negara kecil yang mengarah kepada Persia baik dalam bidang ideologi maupun kebangsaan. Konteks keilmuannya hidup dalam masa pertarungan antara Maghribi dan Mashriqi. Kubu pertama yaitu Khurasan dan sekitarnya, sedangkan yang kedua adalah Irak, Suriah, dan sekitarnya ke arah Barat. Dalam konteks Persia kubu Maghribi adalah musuh utama mereka.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Ibnu Sina sebagaimana yang dia akui, hidup di masa pemerintahan keluarga Buwaihi yang berkuasa pada tahun 945-1055 M. Berbanding terbalik dengan al-Farabi di mana kota utamanya masih berupa impian, Ibn Sina membangun kotanya lebih nyata/kongkret. Maka maklum saja bila Ibn Sina tidak mengangkat kembali ide kota utamanya Farabi. Baso, dalam Jabiri Eropa dan Kita (2000) memberikan alasan menohok bahwa Ibn Sina sudah menikmati kota idamannya secara nyata dalam buaian kekuasaan Buwaihi.
Ibn Sina memang dibaca sebagai pengadopsi teori emanasinya (nazariyat al-faid) al-Farabi dalam menciptakan alam. Namun, bacaannya tidak dia pakai dalam konteks sejarah dan masyarakat walaupun hanya pada taraf impian. Bahkan, Ibn Sina seakan membuat jembatan (qintarah) ke langit kemudian menyegel pemikiran Farabi di atas sana sendiran tanpa jasadnya hingga akhirat yang menyelamatkannya. Gagasan al-Farabi dibuat imajiner sehingga tidak bisa dipraktikkan ke alam nyata.
ADVERTISEMENT
Hasil jerih payah Ibn Sina membuat Jabiri geleng-geleng kepala, hingga akhirnya dia mengatakan:
“Bukan ideologi Ibn Sina dan motifnya yang kita pikirkan. Lebih jauh lagi pengaruh yang dia hasilkan berimplikasi cukup besar yaitu filsafatnya yang berkarakter spiritual-gnosis telah mengebiri pemikiran Arab yang rasionalisme inklusif yang selama ini dibawa oleh Muktazilah, al-Kindi, hingga al-Farabi, hingga digantikan oleh berkembangnya irrasionalisme-gelap (la‘aqlaniyyah dzalamiyyah) yang mematikan yang justru disuburkan kemudian oleh Al-Ghazali, Suhrawardi, dan orang-orang sesudahnya dari berbagai kalangan.”
***
Cerita panjang tersebut menginspirasi saya untuk menjawab kritik Saiful Mustafa kepada diri saya. Saya bukan bermaksud menyamakan diri saya pribadi dengan al-Farabi atau semacamnya, atau bahkan menyamakan Saiful Mustofa dengan Ibn Sina, tidak. Untuk demikian saya jauh berada di bawah mereka semua para pendekar filsafat pada zamannya.
ADVERTISEMENT
Namun, mimpi saya akan negara ideal (bukan kota utama versi al-Farabi) di mana negara hadir mendamaikan kaum toleran dari intoleransi lewat kesepakatan hukum (resultante) sepertinya mempunyai nasib yang sama dengan kota utamanya al-Farabi, dibuang ke langit yang jauh, tanpa jasad dan disegel di sana sembari menunggu Satrio Piningit yang tidak kunjung hadir.
Sepertinya Mustofa lupa kalau negara dalam mengatasi intoleransi tidak melulu dengan cara intoleran yang sama. Cara pandang yang seperti inilah yang dia menganggap saya berpandangan oposisi biner. Negara sudah mempunyai perangkat yang memadai, untuk mengatasi intoleransi mulai dari mediasi, komunikasi yang persuasif, hingga cara lain yang dianggap perlu agar toleran dan intoleran bisa hidup “berdamai” dalam negara yang menurut saya ideal. Kalau bukan negara, siapa lagi?
ADVERTISEMENT
Tolong, Mas Saiful, jangan bangunkan saya dari mimpi indah yang telah saya bangun bersusah payah dan berpeluh keringat.

