Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Mengulang Austerity Inggris: Implikasi Pemangkasan Anggaran di Indonesia
5 Maret 2025 21:47 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Eva Fauzyah Rahmah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
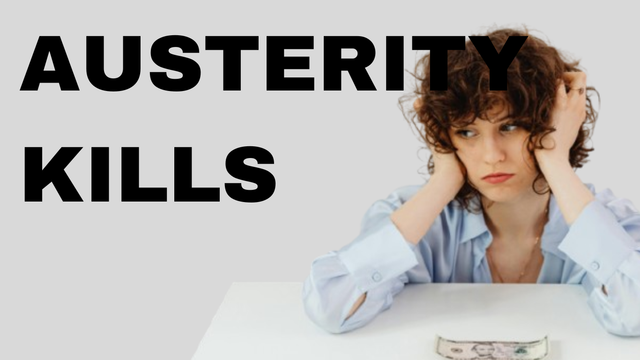
ADVERTISEMENT
Seorang guru honorer di pelosok Jawa Barat resah setelah pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan pemangkasan anggaran 20 persen. Kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan menghantuinya. Apakah efisiensi anggaran di Indonesia akan mengulang austerity Inggris?
ADVERTISEMENT
Instruksi presiden setebal enam halaman dapat membahayakan layanan publik esensial di Indonesia. Ketika sebuah aturan singkat berpotensi mengacaukan penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat, timbul pertanyaan: Efisiensi untuk siapa, dan dengan harga berapa? Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peningkatan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah menjadi langkah tegas pemerintah dalam mengoptimalkan belanja negara. Kebijakan ini menargetkan pemangkasan anggaran sebesar 20 persen melalui pengurangan belanja operasional dan transfer ke daerah. Namun, kebijakan yang hanya tertuang dalam enam lembar ini berisiko menghasilkan dampak kontraproduktif, terutama apabila pelaksanaannya mengabaikan dinamika lokal dan karakteristik birokrasi Indonesia yang kompleks.
Kekhawatiran utama muncul dari pendekatan pemangkasan anggaran yang bersifat seragam dan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik tiap daerah dan sektor. Pendekatan top-down yang hanya berorientasi pada angka ini dapat mengakibatkan pemotongan terhadap program yang justru bersifat vital, khususnya di daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih sangat bergantung pada dana transfer untuk mempertahankan layanan publik dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh, kebijakan ini dikhawatirkan memperparah fenomena 'survival mode' dalam birokrasi. Lanskap birokrasi Indonesia kerap diwarnai ego sektoral antar-kementerian dan rivalitas antar-divisi. Relasi kuasa yang hierarkis serta kinerja yang belum optimal menciptakan insentif bagi birokrat untuk mempertahankan program seremonial atau pencitraan yang dianggap aman guna mengamankan posisi dan menjaga persepsi publik. Hal ini justru bertentangan dengan semangat efisiensi yang semula ditujukan untuk mengurangi belanja yang tidak produktif.
Kondisi ini sejalan dengan temuan Cepiku dkk. (2015) yang meneliti dampak kebijakan penghematan anggaran (austerity) di berbagai negara. Studi tersebut mengungkap bahwa langkah pemotongan anggaran jangka pendek kerap meruntuhkan moral pegawai, menurunkan retensi tenaga kerja, mengikis keahlian manajerial, serta mengalihkan fokus birokrasi dari layanan inti ke sekadar bertahan hidup. Pemangkasan anggaran yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal dapat memperlebar ketimpangan akses terhadap layanan publik, khususnya di daerah dengan sumber daya terbatas.
ADVERTISEMENT
Pengalaman serupa terjadi di Inggris ketika pemerintah memberlakukan kebijakan penghematan anggaran pada 2010-an. Pemerintah Inggris memangkas anggaran pemerintah daerah secara signifikan untuk mengatasi defisit fiskal. Namun, riset Hastings dkk. (2017) menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi justru terkena dampak paling parah. Layanan publik seperti penitipan anak, kesehatan mental, hingga perpustakaan mengalami pemangkasan besar-besaran. Kebijakan pemangkasan yang tidak memperhitungkan kerentanan daerah ini justru memperlebar ketimpangan dan menurunkan kualitas layanan publik bagi masyarakat miskin.
Sebaliknya, studi Kiefer dkk. (2014) menunjukkan bahwa reformasi yang mendorong inovasi justru dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai, kepuasan kerja, serta keterlibatan pegawai. Inovasi dalam hal proses dan layanan baru dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan 'salami-slicing' atau pemangkasan merata yang sering kali hanya mengurangi semua aspek secara seragam tanpa mempertimbangkan prioritas.
ADVERTISEMENT
Kebijakan efisiensi anggaran juga diharapkan mampu mengatasi persoalan tenaga honorer yang selama ini membebani anggaran pemerintah. Namun, praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga honorer justru berpotensi semakin menguat di tengah tekanan efisiensi. Mereka yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan cenderung dipertahankan, sementara tenaga honorer yang kompeten tetapi tidak memiliki koneksi justru berada dalam posisi rentan. Wawancara dengan guru non-ASN di beberapa daerah mengonfirmasi kekhawatiran ini. Guru honorer di wilayah pedesaan di Jawa Barat, misalnya, mengungkapkan rasa cemas kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi. Saat berupaya mencari pekerjaan di sekolah lain, ia justru mendapatkan jawaban, "sudah ada titipan." Seleksi penerimaan tenaga honorer semakin ketat, sementara mereka yang tidak memiliki koneksi politik merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
Dalam sektor pendidikan, kebijakan efisiensi yang menyasar transfer daerah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) patut dicermati lebih dalam. Dana ini selama bertahun-tahun menjadi sumber utama gaji guru honorer di berbagai daerah. Meskipun secara nasional terdapat surplus guru, distribusi yang tidak merata membuat banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih sangat bergantung pada guru honorer. Pemutusan massal tenaga honorer tanpa disertai strategi rekrutmen yang jelas justru dapat melumpuhkan layanan pendidikan di daerah yang sudah kekurangan guru. Simulasi data di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa jika kebijakan efisiensi ini diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, mengandalkan guru ASN dan non-ASN yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) saja dapat menyebabkan rasio guru-siswa mencapai 40:1 hingga 50:1 di beberapa sekolah. Rasio ini jauh dari ideal dan berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Data agregat dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memang menunjukkan surplus guru di Aceh, tetapi distribusinya yang timpang mencerminkan risiko nyata dari kebijakan pemangkasan anggaran yang seragam.
ADVERTISEMENT
Tanda-tanda dampak negatif pemangkasan anggaran telah terlihat di berbagai sektor. Laporan Kompas (Februari 2024) menyebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghentikan sejumlah proyek riset akibat pengurangan anggaran. Perpustakaan Nasional mengurangi jam operasional, sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa pemotongan anggaran dapat memengaruhi akurasi informasi cuaca dan gempa. Kekhawatiran ini tercermin dalam perbincangan publik di media sosial dengan tagar #IndonesiaGelap, yang mencerminkan kecemasan masyarakat akan masa depan layanan publik, terutama terkait riset, pendidikan, dan keakuratan informasi kebencanaan.
Melihat berbagai kekhawatiran ini, revisi terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa langkah-langkah ini, efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah berisiko menjadi sekadar pemangkasan serampangan yang mengorbankan layanan publik dan tenaga kerja esensial, alih-alih menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan adil. Harapan terhadap efisiensi seharusnya beriringan dengan kepekaan terhadap kebutuhan daerah serta komitmen memperkuat birokrasi yang melayani, bukan sekadar memangkas.
ADVERTISEMENT

