Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Anak Baik Itu Capek: Tekanan Jadi Sempurna di Budaya Kita
11 April 2025 14:02 WIB
·
waktu baca 4 menitTulisan dari Ghefira Isyraq Kirana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
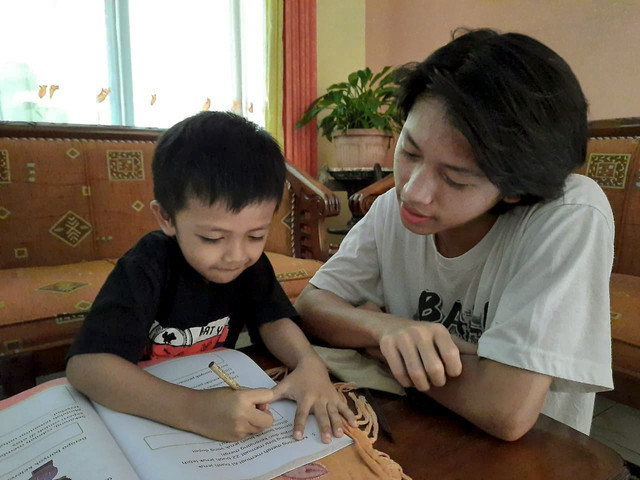
ADVERTISEMENT
Lirik lagu ini menjadi suara hati dari kita yang tumbuh dengan label “anak baik.” Sejak kecil, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri, mengalah dan tidak merepotkan. Ucapan seperti “anak baik harus nurut sama orang tua” atau “anak baik nggak banyak maunya” menjadi kalimat yang akrab di telinga. Tanpa disadari, kata-kata ini membentuk simbol sosial yang mengatur perilaku dan cara kita berkomunikasi.
ADVERTISEMENT
Dalam perspektif interaksi simbolik yang dikembangkan oleh Herbert Blumer, manusia membentuk makna melalui interaksi sosial. Identitas “anak baik” terbentuk bukan karena pembawaan individu, tetapi karena respon dari lingkungan. Anak yang penurut dan tidak banyak menuntut sering kali dipuji dan dianggap “berhasil.” Lama-kelamaan, ia belajar bahwa “baik” berarti menekan perasaan demi mendapat penerimaan. Komunikasi berubah dari sarana ekspresi menjadi cara mempertahankan ekspektasi.
Menurut survei dari UNICEF Indonesia (2021), 7 dari 10 anak muda merasa perlu menyembunyikan perasaan asli mereka di depan keluarga agar tidak dianggap "rebel" atau "tidak bersyukur" (UNICEF, 2021). Data ini sejalan dengan temuan American Psychological Association (APA) bahwa anak-anak yang tumbuh dengan tuntutan perfeksionisme berisiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi di saat dewasa (APA, 2019).
ADVERTISEMENT
Simbol ini diperkuat melalui ucapan yang tampak sederhana, namun sarat makna. Kalimat seperti “anak baik nggak bikin malu” atau “anak baik selalu bantu orang tua” menjadi penanda sosial dengan pola berulang. Jika dilihat melalui semiotika Roland Barthes, istilah “anak baik” adalah konstruksi makna yang tidak lagi netral. Di balik kata “baik,” tersimpan tekanan sosial, kontrol emosi dan penyangkalan terhadap kebutuhan diri. Hal ini menjadi mitos modern yang dibentuk oleh budaya, seolah-olah alami dan benar adanya.
Budaya komunikasi kita sangat bergantung pada simbol dan harapan tersirat. Label-label tersebut membentuk pola interaksi yang tertutup. Anak menjadi pandai membaca situasi, tapi tidak mahir mengungkapkan isi hati. Mereka belajar untuk menyenangkan orang lain terlebih dahulu, bahkan sebelum mengenali dirinya sendiri. Komunikasi bukan lagi tempat untuk tumbuh, tapi medan untuk bertahan.
ADVERTISEMENT
Pola ini menciptakan komunikasi satu arah yang tidak sehat. Anak mendengar, tapi tak didengar. Ia menyesuaikan diri, namun tak diberi ruang untuk jujur. Penelitian Yayasan Pulih (2023) menemukan bahwa 65% remaja Indonesia merasa tidak nyaman membicarakan masalah pribadi dengan orang tua karena takut dianggap "tidak sabar" atau "tidak menghormati" (Pulih, 2023). Temuan serupa dilaporkan Journal of Child Psychology and Psychiatry (2022): tekanan untuk menjadi "baik" secara sosial berhubungan dengan rendahnya kemampuan kontrol emosi pada remaja (JCPP, 2022).
Efek jangka panjangnya terasa ketika anak tumbuh dewasa. Banyak dari kita sulit berkata tidak, merasa bersalah saat menetapkan batas dan terbiasa menomorsatukan kenyamanan orang lain. Dr. Brené Brown, peneliti kerapuhan emosional dari University of Houston, menyebut pola ini sebagai "fawning"—kecenderungan mengorbankan kebutuhan diri untuk menghindari konflik (Brown, 2020).
ADVERTISEMENT
Kita perlu mendefinisikan ulang makna “anak baik.” Anak baik tidak harus selalu sabar, tenang dan memahami tanpa dijelaskan. Anak baik juga bisa kecewa, bisa marah dan tetap dicintai ketika berkata tidak. Komunikasi yang sehat harus memberi ruang untuk emosi yang nyata. Studi Harvard Graduate School of Education (2021) menegaskan bahwa keluarga yang mendengarkan tanpa menghakimi memiliki anak dengan ketahanan emosional lebih tinggi (HGSE, 2021).
Membangun komunikasi sehat bisa dimulai dari perubahan sederhana:
• Gantilah “anak baik nggak boleh ngeluh” menjadi “nggak apa-apa kalau kamu capek.”
• Gantilah “anak baik nggak boleh membangkang” jadi “boleh kok kalau kamu punya pendapat sendiri.”
Kata-kata membentuk dunia. Ketika simbol-simbol yang lebih inklusif hadir, komunikasi pun menjadi ruang aman untuk tumbuh bersama.
ADVERTISEMENT
Anak baik bukan anak yang selalu sempurna. Anak baik adalah anak yang merasa aman menjadi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa suaranya penting, emosinya diterima dan cinta tidak datang sebagai upah dari kepatuhan. Di situlah komunikasi menemukan makna sejatinya: menciptakan ruang, bukan sekat.

