Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Politik Anggaran dan Cita-cita Governance
20 Februari 2025 14:10 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Gustamin Abjan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
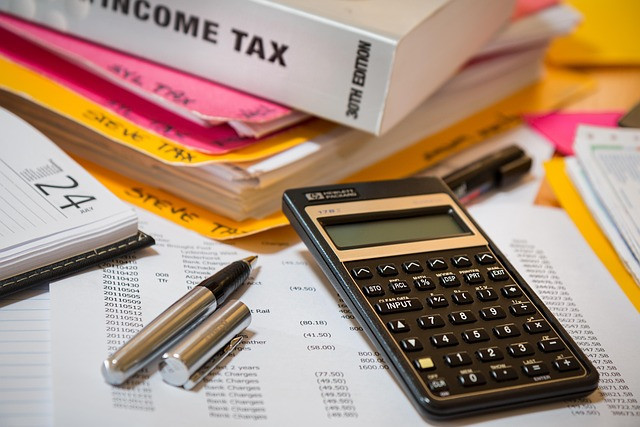
ADVERTISEMENT
Pengalaman di kota Porto Alegre, Brazil, pada tahun 1990-an dapat dipandang sebagai contoh terbaik dari politik anggaran yang berpihak kepada publik. Dengan menggunakan istilah pro kaum miskin (pro poor budget) atau participatory budget (PB), anggaran publik di sana kemudian menjadi best practice anggaran publik di berbagai negara karena sensitif terhadap kebutuhan kelompok marginal (poverty mainstreaming). Dengan PB, Warga miskin leluasa mengakses sumber daya pendidikan, air bersih, sistem pembuangan limbah, dan infrastruktur jalan. Keberpihakan itu membuat Bank Dunia memandang PB adalah anggaran publik yang tepat untuk menjalankan mandat demokratisasi anggaran publik di berbagai negara termasuk di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Namun di Indonesia PB tidak terlalu populer baik dalam wacana maupun praktis kebijakan. Tentu konteks historisnya berbeda. Di Porto Alegre, PB adalah wujud kemenangan politik kelas pekerja. PB diperjuangkan oleh Partido dos Trabalhadores (PT), partai beraliran sosialisme demokratik, yang ketika meraih kemenangan dalam pertarungan politik formal mereka kemudian menetapkan PB sebagai eksperimen politik kiri dalam mendesain belanja publik yang adil dan berpihak kepada warga. Sementara di Indonesia, wacana PB muncul dari kalangan para elite. PB melebur ke dalam arena politik yang didominasi oleh partai politik yang tidak memiliki ideologi yang jelas. Nyaris semua partai, alih-alih berpijak pada politik kerakyatan, mereka hanya dijadikan kendaraan bagi oligarki untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. Sehingga tidak aneh jika desain belanja publik di Indonesia tidak menyentuh kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
“Kepentingan rakyat” atau “kepentingan publik” hanya menjadi retorika politik. Istilah itu hanya bergemuruh di arena kontestasi lima tahunan dan sebatas keluar dari suara heroik pemimpin republik di panggung orasi. Namun saat ini nasib dan kepentingan publik terutama kaum miskin justru semakin tereliminasi dalam arena penganggaran publik di Indonesia. Atas nama efisiensi, anggaran publik yang berhubungan dengan kebutuhan publik mendasar dipangkas. Sebagaimana diketahui anggaran Pendidikan dasar dan menengah dipangkas sebesar Rp 8 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dipangkas sebesar Rp 22,5 triliun, kementerian agama dipangkas sebesar Rp 11,5 triliun dan masih banyak lagi. Hal itu berakibat pada berkurangnya aksesibilitas publik atas sumber daya publik. PHK membeludak, biaya barang/jasa publik seperti pendidikan dan Kesehatan berpotensi menjadi mahal. Efisiensi pada akhirnya mengubur cita-cita kemerdekaan di republik ini.
ADVERTISEMENT
Efisiensi Sebagai amanat Governance
Dalam diskursus akuntansi sektor publik, efisiensi adalah solusi utama untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik. Efisiensi dimaksudkan untuk mengoreksi struktur birokrasi yang kaku, hierarkis, korup dan penuh pemborosan. Dengan semangat manajemen publik baru (new public management), efisiensi diupayakan untuk membentuk tatanan sektor publik yang fleksibel, produktif, lintas departemen, dan berorientasi hasil. Suatu program disebut efisien jika program itu sukses dengan penggunaan anggaran yang serendah-rendahnya (spending well). Dalam hal ini efisiensi berarti meminimalisir struktur birokrasi, staf, upah, biaya administrasi atau biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.
Pada konteks itu negara Vietnam dapat menjadi contoh terbaik dari efisiensi anggaran publik karena dengan cara mengurangi jumlah Kementerian dan Lembaga, dari 30 tersisa 22. Efisiensi semacam itu selaras dengan amanat governance (tata kelola). Artinya, efisiensi mesti kompatibel dengan karakter institusi publik yang mengedepankan asas efisiensi, efektivitas, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan. Dengan efisiensi, warga negara leluasa mengakses sumber daya publik secara memadai dan berkualitas.
ADVERTISEMENT
Berbeda dengan Vietnam, efisiensi yang didengungkan oleh pemerintah Indonesia cenderung berseberangan dengan mandat governance. Sebab efisiensi yang dilakukan justru memangkas anggaran publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik tetapi jumlah kementerian/lembaga yang gemuk terus dibiarkan dan bahkan bertambah. Pada akhirnya, anggaran publik yang seharusnya memproyeksikan belanja sosial yang menyentuh kebutuhan kelompok marjinal, ia sekadar menjelma sebagai instrumen yang melanggengkan superioritas negara.
Politik Anggaran dan Moralitas Publik
Efisiensi anggaran publik saat ini tidak merepresentasikan kepentingan publik. Ia sekadar dikonstruksi untuk memenuhi syahwat politik para elite. Memangkas anggaran publik tetapi merekrut buzzer sebagai staf khusus adalah keputusan yang bertentangan dengan semangat efisiensi. Alih-alih menciptakan redistribusi anggaran publik yang adil kepada warga negara, dengan dalih efisiensi, anggaran publik semakin terkonsentrasi pada kepentingan pejabat negara. Artinya, yang tampak sebenarnya bukanlah efisiensi tetapi pemangkasan kalau tidak mau disebut korupsi. Sebab obsesi pemerintah atas efisiensi anggaran publik ini tidak sejalan dengan kehendak publik dan bahkan menghancurkan hal-hal yang publik (respublica): Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Dalam ajaran kepublikan, apa pun yang mengabaikan moralitas publik, merugikan kepentingan publik, atau menuntun publik menuju jurang penderitaan adalah korupsi.
Dalam karya Transnationalizing the Public Sphere (2014), Kate Nash menguraikan publik adalah ajaran luhur yang memungkinkan pertimbangan moral diutamakan dalam institusi demokratis. Makna publik semacam itu bagi Nash dapat diperas ke dalam tiga nilai penting, yakni publisitas, akal budi, dan kehendak publik. Kemudian publik dipandang sebagai arena, topik, dan hasil dari debat-debat yang demokratis. Oleh sebab itu kata publik yang melekat pada anggaran publik tidak semata kemasan retoris namun aspek moral yang menuntun bagaimana anggaran publik dikelola ( penuh transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adil dan berpihak kepada kepentingan warga negara).
ADVERTISEMENT
Di bawah ajaran kepublikan itu, penganggaran publik seharusnya dikelola secara kolektif dengan menghadirkan partisipasi bermakna warga negara selaku pemilik anggaran (owner). Pengelola anggaran, badan anggaran, atau pihak-pihak yang terlibat dalam ratifikasi dan implementasi anggaran publik, atau mereka yang berada dalam institusi politik formal merupakan subjek yang setiap geraknya harus dipandu oleh akal budi dan moralitas publik.

