Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Membaca Kolonialisme dari Novel Max Havelaar
25 Agustus 2020 9:11 WIB
Tulisan dari Grady Nagara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
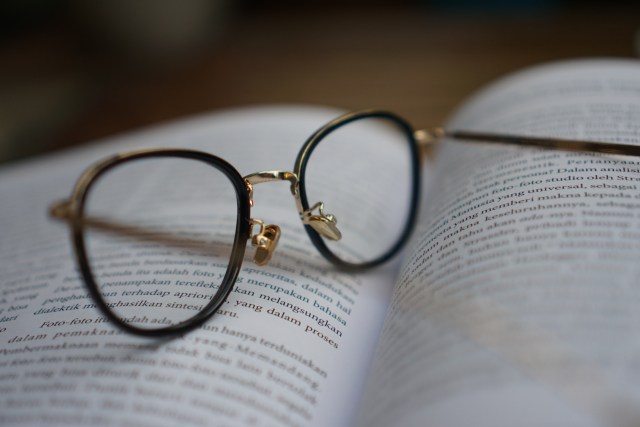
ADVERTISEMENT
Andai jiwa nasionalisme orang Indonesia diukur setiap bulan dalam sebuah indeks, saya yakin skornya paling tinggi berada di bulan Agustus. Semangat kemerdekaan Indonesia selalu terngiang di bulan ini: kibaran bendera merah-putih, lagu-lagu kebangsaan yang didengungkan, hingga pemutaran film-film perjuangan kemerdekaan. Jiwa nasionalisme kita akan bergetar taktala mendengar lagu “17 Agustus” sekalipun sedang leyeh-leyeh di atas kasur.
ADVERTISEMENT
Tapi jika ditanya apa yang kita ketahui tentang perjuangan kemerdekaan, penjajahan, ataupun kolonialisme, saya yakin pengetahuan kebanyakan masyarakat kita masih sangat terbatas. Imajinasi bangsa kita tentang kemerdekaan adalah penjajah Belanda dan Jepang yang jahat sekaligus bersenjata lengkap, sedangkan para pendahulu kita melawannya hanya dengan bambu runcing. Saya pikir hal ini wajar mengingat buku teks pelajaran sejarah kita hanya menggambarkan konflik vis a vis antara apa yang kita sebut “pribumi” dengan bangsa asing. Padahal, relasi dan struktur kolonialisme tidaklah se-hitam-putih itu.
Ada satu buku yang menurut saya perlu dibaca untuk memikirkan ulang imajinasi kita tentang kolonialisme: novel Max Havelaar. Kisah Max Havelaar yang ditulis Multatuli -- nama pena Eduard Douwes Dekker, seorang Belanda tulen sekaligus mantan pegawai pemerintah Hindia Belanda -- bukan hanya untuk menyenangkan mata pembaca dengan karya fiksi. Lebih dari itu, kisah Havelaar adalah gugatan terhadap kolonialisme, sekaligus gugatan terhadap mata dunia yang sengaja menutup diri. Novel ini akan memberikan perspektif baru dalam memahami penjajahan.
Novel ini sendiri ditulis setelah pemecatan Eduard dari jabatan terakhirnya sebagai asisten residen Lebak, Banten. Tentu saja, Max Haveelar yang jadi tokoh utama dalam kisah ini tidak lain adalah personifikasi Eduard sendiri saat masih bertugas di Lebak. Secara gamblang ia menyajikan bagaimana sistem kesewenang-wenangan itu telah menjatuhkan martabat manusia serendah-rendahnya. Tanam paksa, kerja rodi, dan perampasan adalah gambaran yang secara khas dikisahkan dalam novel ini. Jika kita membacanya, tampak banyak potongan kisah yang disajikan terpisah-pisah namun sebetulnya saling terkait satu sama lain.
ADVERTISEMENT
Jika membuka lembaran-lembaran pertama, kita akan diperkenalkan dengan sosok yang menyebalkan. Namanya Batavus Droogstoppel, seorang makelar kopi dari firma Last & Co -- dan tentu saja adalah orang kaya. Penulis menggambarkan sosok ini sebagai orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan pekerjaannya. Alih-alih merasa paling logis dan benar, Droogstoppel justru menyalahkan orang miskin karena kemiskinannya. Menurutnya, orang miskin pada akhirnya akan tetap miskin, bahkan dengan semena-mena ia menganggap bahwa orang miskin tidak diberkati Tuhan akibat ulahnya sendiri.
Droogstoppel adalah penggambaran umum kalangan Eropa penikmat hasil bumi yang dijarah dari tanah Jawa. Ia membanggakan bisnis kopi dan lelang musiman yang padahal rodanya digerakkan oleh sistem tanam paksa yang dibangun oleh pemerintah kolonial di negeri jajahan, tapi Droogstoppel membantah itu. Eduard ingin menyampaikan bahwa orang Belanda sendiri secara umum tidak mengetahui kondisi riil di tanah kolonisasi yang dikendalikan pemerintah mereka. Seperti pernyataan-pernyataan Droogstoppel di bagian akhir buku yang menyebutkan bahwa pemerintah mereka baik, bahkan dikatakan bahwa seharusnya orang-orang Jawa yang kafir itu (menurut Droogstoppel) berterima kasih karena pemerintah mereka telah membeli hasil bumi Jawa dengan harga yang mahal -- padahal sebaliknya.
ADVERTISEMENT
Lalu apa yang sebenarnya terjadi di tanah Jawa pada pertengahan abad 19?
Dalam novel itu dikatakan bahwa Max Havelaar memohon kepada Droogstoppel untuk menerbitkan "paket" miliknya yang merupakan kumpulan catatan Max Havelaar selama mengabdi di Hindia Belanda, khususnya saat menjadi asisten residen di Lebak. Meskipun Droogstoppel merasa jijik terhadap Max Haveelar -- yang ia panggil dengan Sjaalman (si lelaki pemakai Syal) -- tetap saja akhirnya paket Max Haveelar disusun dan diterbitkan. Alasannya karena Droogstoppel sudah terlanjur membuka paket itu, dan dengan kepribadian yang sangat ingin menjaga harga diri, terpaksa si tuan makelar kopi ini memenuhi permintaan Max Havelaar.
Bagian pertama yang disusun adalah gambaran tanah Lebak dan bagaimana birokrasi kejam itu bisa berjalin mesra dengan pejabat-pejabat lokal. Digambarkan bagaimana pemerintah kolonial memanfaatkan tradisi feodal yang telah mapan jauh sebelum kolonialisme itu hadir. Dalam sistem feodal, para raja-raja nusantara memanfaatkan rakyat yang dipimipinnya untuk melayani kepentingannya. Dalam novel ini digambarkan bagaimana rakyat -- khususnya di Jawa -- melayani kepentingan raja mereka. Mereka akan membawa persembahan yang biasanya berasal dari hasil panen sebagai bentuk loyalitas kepada raja, dan pemerintah kolonial memanfaatkan sistem ini.
ADVERTISEMENT
Untuk meningkatkan gairah pasar Eropa, pemerintah kolonial berupaya mengeruk hasil panen di Jawa sebagai komoditas ekspor negara melalui sistem feodal itu sendiri. Caranya, para elit lokal diberikan insentif yang besar jika mereka mampu memberikan "persembahan" terbaik kepada pemerintah kolonial.
Dari sistem feodal ini dibentuklah sebuah birokrasi modern. Pertama-tama pemerintah kolonial membangun sistem hukum di tanah jajahan mereka. Sistem hukum inilah yang dijadikan alat bagi aparat kolonial untuk membuat rakyat yang dianggap bersalah dihukum dengan kerja paksa tanpa bayaran. Kemudian para raja-raja lokal itu diangkat menjadi bupati di distriknya masing-masing.
Di setiap distriknya ada pegawai Belanda sebagai penanggung jawab yang disebut dengan asisten residen dibantu oleh seorang pengawas. Asisten residen ini bertanggung jawab terhadap Residen (setingkat provinsi), dan kemudian di atasnya lagi adalah Gubernur Jenderal yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan wilayah Hindia Belanda. Nantinya Gubernur Jenderal ini akan menjadi penghubung dengan pemerintah pusat di Eropa. Seperti inilah birokrasi kolonial dibangun. Dari penjelasan tersebut kita akan tahu betapa pentingnya posisi Max Haveelar sebagai asisten residen di distrik Lebak. Sekalipun demikian, sifatnya justru tidak mendukung cara kerja kolonialisme itu sendiri.
ADVERTISEMENT
Novel ini menggambarkan sifat Max Havelaar yang sangat berbeda dengan pegawai Hindia Belanda pada umumnya yang sewenang-wenang dan korup. Sosok Max Haveelar justru antitesis dari kenyataan itu. Misalnya, digambarkan dalam novel itu bahwa Max Havelaar sangat miskin meskipun ia adalah seorang pejabat sekali pun. Diceritakan bahwa Max Haveelar tidak mau menggunakan "hak" kemewahan yang biasanya digunakan oleh pejabat lain. Penolakan tersebut dilakukan karena kemewahan didapat dari kerja-kerja paksa orang Jawa yang menurut Max Haveelar sangat tidak pantas. Bahkan dalam kondisi miskin pun, Max Haveelar masih sangat dermawan. Berkali-kali ia membantu orang tertindas yang meminta pertolongannya, dan ia tidak bisa menolak. Hati nurani telah menggerakan tindakannya.
Dalam sistem kolonial, bupati sangat berperan penting. Sebab dari para bupati inilah pemerintah kolonial mendapatkan keuntungan. Pada kasus Lebak tempat Max Haveelar bertugas, bupati Lebak adalah gambaran pejabat lokal yang sangat keji.
ADVERTISEMENT
Secara terpisah, Eduard menyajikan kisah cinta Saidjah dan Adinda yang harus pupus akibat kesewenang-wenangan menantu Bupati Lebak di distrik Parang Kujang. Bagian ini, menurut saya sangat menyentuh nurani pembaca. Bukan karena kisah cinta Saidjah dan Adinda, melainkan bagaimana para petani hanya bisa menangis gigit jari karena kerbau pembajak sawah mereka di ambil paksa oleh bupati.
Bentuk kesewenang-wenangan lain yang digambarkan adalah tanam paksa. Pada sistem tanam paksa, para petani diharuskan menanam kebun sesuai dengan kebutuhan pasar Eropa: terutama kopi dan teh. Lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam padi justru digunakan sebagai perkebunan. Akibatnya, produksi beras menurun, kebutuhan konsumsi karbohidrat masyarakat pun menurun drastis. Dampanya adalah kelaparan hebat yang merajalela khususnya di Jawa.
ADVERTISEMENT
Meminjam istilah Hilmar Farid, sistem feodal ditambah kolonial menghasilkan akumulasi kapital. Dan pemerintah kolonial memiliki libido yang besar untuk mengakumulasikan kapital sebesar-besarnya demi menghidupkan pasar.
Rantai inilah yang dijelaskan secara gamblang oleh Multatuli tanpa tedeng aling-aling. Bahkan secara eksplisit penulis mengatakan bahwa para pejabat kolonial telah membuat laporan-laporan palsu mengenai kondisi di tanah jajahannya. Seperti kenyataan bahwa kelaparan merajalela, namun laporan ke pemerintah pusat sebaliknya dengan menyebutkan justru yang terjadi adalah over produksi beras. Oleh sebab itu wajar saja jika novel Max Haveelar ini membuka fakta yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat dunia pada saat itu.
Ada satu lagi bentuk kesewenang-wenangan, yaitu kerja paksa. Biasanya ini didahului dengan kriminalisasi masyarakat lokal. Dari kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat, mereka harus menanggung hukuman yang lebih berat dari pada kesalahannya sendiri. Mereka yang divonis bersalah, akan diminta untuk menjadi buruh kasar tanpa bayaran untuk membangun infrastruktur Hindia Belanda, atau memperhias istana pejabat mereka. Tentu saja, kenyataannya mereka yang dikriminalisasi sangat banyak mengingat pemerintah kolonial telah menetapkan hukum yang sangat ketat.
ADVERTISEMENT
Lalu apa respons Max Haveelar? Dengan sifatnya yang humanis ini, Max Haveelar berani melayangkan gugatan sebagai protes atas ketidakadilan di tempat ia bertugas. Ia menyurati residen Banten untuk menangkap bupati Lebak yang dianggapnya sudah keterlaluan. Sialnya, residen Banten justru membela Bupati -- karena memang sudah diketahui bersama peran penting Bupati untuk memastikan kelancaran arus kapital. Bahkan residen menyuap Bupati untuk berbicara fitnah terhadap Max Haveelar.
Pada akhirnya Max Haveelar dipecat sebagai bayaran atas tindakannya. Pemecatan secara tidak terhormat disampaikan langsung melalui surat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Max Haveelar dituduh sebagai pembangkang dan dipulangkan ke negerinya dalam keadaan melarat. Namun melarat sekalipun tidak menyurutkan rasa keadilannya untuk menyuarakan kebenaran. Jika tidak, mana mungkin novel Max Haveelar ini ditulis, yang disebutnya sendiri ditulis selama sebulan.
ADVERTISEMENT
***
Ada pelajaran, dan juga sudut pandang baru dari novel tersebut. Jika imajinasi kita tentang kolonialisme adalah bangsa asing yang keji, nyatanya pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Bukti paling terlihat adalah sosok Eduard sendiri, yang notabene “orang asing” justru berpihak pada bangsa Indonesia. Ia bahkan rela mengorbankan kursi nyamannya untuk ikut membela bangsa kita yang ditindas.
Sementara itu, orang-orang yang memiliki warna kulit dan bahasa seperti kita, justru ada yang berpihak pada penjajahan. Mereka adalah bupati ataupun pejabat lokal di era kolonial yang digambarkan Eduard. Para raja-raja lokal itu justru merampas hasil tanah rakyatnya untuk kemegahan dan kemewahan hidup pribadi, dan juga mereka berperan sebagai rantai kapitalisme terhadap pasar Eropa. Jika demikian, bukankah mereka yang ikut menghisap, sekalipun orang “pribumi” juga sama saja penjajah?
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, cara pandang kita terhadap kolonialisme semestinya melampaui batas-batas ras, suku, etnik, hingga agama sekalipun. Buat saya, novel Max Havelaar ini menggambarkan bahwa yang semestinya dilawan oleh bangsa-bangsa tertindas adalah ketidakadilan, yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun. Ya, musuh kita adalah ketidakadilan, bukan orang kulit putih, hitam, kuning, ataupun mereka yang bermata sipit.

