Petaka Revolusi Digital
Konten dari Pengguna
18 Oktober 2019 8:29 WIB
Tulisan dari Grady Nagara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
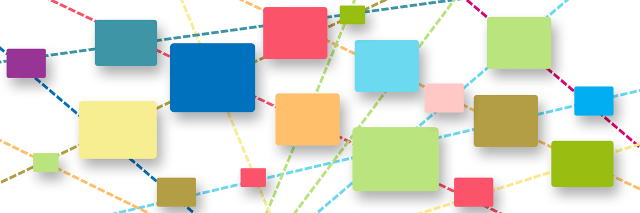
ADVERTISEMENT
Ibarat jalan raya, revolusi digital menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kita untuk menghadirkan ekspresi identitas, gagasan, dan pikiran yang levelnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bisa dibilang ini adalah demokratisasi yang sangat radikal, dan kita merayakan itu. Infrastruktur digital, terutama media sosial, adalah ruang publik di mana semua orang bisa saling berinteraksi tanpa batas. Kata ‘sosial’ dalam media sosial menunjukkan seolah platform digital yang satu ini memang tidak berkepentingan apa pun, kecuali menyediakan ruang sosial itu sendiri. Apalagi disediakan dengan cuma-cuma.
ADVERTISEMENT
Premis di atas seolah benar. Hampir tidak mungkin bagi kita untuk menghindar atau pun balik arah. Revolusi digitial, dan segala turunannya, adalah keniscayaan. Masalahnya, benarkah penyedia layanan digital itu memiliki sifat altruistik sehingga mau membagikan teknologinya dengan gratis?
Sampai di sini kita harus berpikir ulang, bahwa revolusi digital--yang membuat hampir seluruh lini kehidupan kita terdigitalisasi--tidak lepas dari kepentingan ekonomi dan hegemoni dari raksasa digital itu sendiri. Celakanya, kita hampir dibuat tidak sadar, bahwa di balik iming-iming akan kebebasan, ada eksploitasi yang dilanggengkan, ketimpangan ekonomi, hilangnya privasi, sampai dengan residu berupa polusi digital (e-pollution). Alih-alih demokratisasi, yang terjadi justru sebaliknya: Ada struktur yang sangat tidak demokratis di belakangnya.
Dari Eksploitasi Hingga Ketimpangan Ekonomi
ADVERTISEMENT
Kita ambil contoh kasus Google. Setidaknya di Indonesia, kita semakin bergantung pada media digital yang satu ini. Barangkali kita merasa beruntung bahwa Google telah banyak membantu dalam mencari informasi, posisi tempat yang ingin dikunjungi, spesifikasi barang elektronik yang akan dibeli, dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita peroleh dengan cepat dan cuma-cuma.
Padahal, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Raksasa Google telah mengeksploitasi kita, dan secara simultan kita sukarela melakukannya. Teknologi dan layanan yang terus dikembangkan Google telah menstimulasi kita untuk terus mengakses internet. Pada mulanya kita mencari informasi yang kita butuhkan, dan lama-kelamaan kita justru didikte oleh Google. Setiap kata yang kita ketik di mesin pencari, diolah melalui mekanisme machine learning yang menjadi kode algoritma tertentu.
ADVERTISEMENT
Algoritma yang berdasarkan pada data perilaku kita di internet, menyajikan langsung informasi yang relevan dengan kebutuhan kita sesaat kita mengaksesnya. Orang-orang yang sering mengakses konten pornografi, algoritma yang muncul adalah segala hal yang berbau konten pornografi juga. Dan jangan lupa satu hal juga, kita akan diserbu iklan yang sesuai dengan data perilaku kita pada platform atau media sosial lain yang memang bersinggungan dengan Google. Ketika saya mencari informasi di Google, ‘cara efektif menggemukkan badan,’ di beranda Facebook saya sering muncul iklan produk susu penggemuk badan.
Lalu di mana eksploitasinya? Bayangkan layanan Google adalah sebuah pabrik yang membutuhkan para buruh sebagai faktor produksinya. Hasil produksi yang dikerjakan melalui tangan buruh akan menjadi surplus ekonomi bagi pemilik modal. Setiap hari, dengan upah yang murah, para buruh itu melakukan pekerjaan yang sama: Mengoperasikan mesin untuk menghasilkan barang tertentu.
Begitu pun dengan layanan Google. Para penggunanya terlibat dalam moda produksi yang sesungguhnya eksploitatif. Setiap hari kita memberikan data kepada Google dengan informasi yang berbeda-beda. Seluruh data yang masuk akan diolah sehingga membentuk pola perilaku kita di internet. Pola perilaku ini menjadi hasil produksi yang kemudian bisa dijual kepada para pengiklan. Dari sana, Google mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Sedangkan kita menjadi ’buruh’ yang setiap hari menghasilkan data baru melalui mesin yang hampir semua orang memilikinya, yaitu telepon pintar (smartphone).
ADVERTISEMENT
Kita tidak sadar bahwa aktivitas kita di internet memberikan pundi-pundi keuntungan yang besar bagi korporasi digital, dan kita merasa senang dengan itu. Andai Karl Marx hidup menyaksikan ini semua, barangkali ia akan menempatkan relasi eksploitatif yang mirip dengan hubungan buruh-majikan ini sebagai salah satu bentuk kesadaran palsu (false consciousness) yang exist di tengah kita, para pengguna internet.
Dalam konteks ekonomi politik yang lebih luas, korporasi digital seperti Google--diikuti Facebook--adalah raksasa yang hampir mustahil ditandingi. Secara global, berdasarkan catatan Zenith Media ; Google, Facebook, Baidu, Microsoft, Yahoo, Verizon, dan Twitter mendulang keuntungan akumulatif sebesar 132,8 miliar dolar AS pada 2016. Angka ini secara global, setara dengan 73 persen dari belanja iklan digital, dan 29 persen dari belanja iklan untuk semua jenis media.
ADVERTISEMENT
Di sini timbul pertanyaan baru. Bagaimana dengan nasib media jurnalistik daring yang juga mengais keuntungan dari iklan? Mari kita lihat faktanya di Indonesia. Berdasarkan data e-Marketer tahun 2015, total belanja iklan di Indonesia mencapai Rp 163 triliun untuk semua jenis media. Iklan digital angkanya mencapai Rp 12 triliun atau setara dengan 7,3 persen dari total belanja nasional. Kenyataan ini memang menunjukkan bahwa posisi media lama terutama televisi masih cukup kuat. Barangkali kita akan menduga bahwa keuntungan media jurnalistik daring juga tetap besar dengan tren porsi iklan digital yang semakin meningkat tiap tahun.
Padahal, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Dari total Rp 12 triliun itu, 70 persennya dinikmati oleh Google dan Facebook, sedangkan 30 persen sisanya yang dinikmati media jurnalistik daring. Ini menunjukkan tidak hanya ketimpangan ekonomi yang luar biasa, melainkan juga raksasa digital itu telah mengeksploitasi media jurnalistik daring itu sedemikian rupa.
ADVERTISEMENT
Google dan Facebook jelas tidak memiliki wartawan atau pun buruh lapangan yang mencari informasi. Dalam hal ini, mereka tidak bisa memproduksi informasi sendiri. Yang terjadi adalah, raksasa digital itu memanfaatkan informasi dari media jurnalistik daring, dan individu penggunanya untuk meningkatkan traffic. Semakin tinggi traffic, keuntungan yang didapat semakin besar. Padahal, media jurnalistik daring juga menjalankan logika yang sama. Hanya saja, media jurnalistik daring itu perlu bekerja keras meski keuntungan yang diraih lebih sedikit. Sebaliknya, Google bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar tanpa perlu repot-repot bekerja keras.
Ada semacam love-hate relationship antara media jurnalistik daring dengan korporasi digital seperti Google dan Facebook. Di satu sisi, media jurnalistik daring membenci Google karena relasi eksploitatif dan ketimpangan ekonomi yang besar. Bagi media jurnalistik daring, Google tak lebih dari plagiator yang seenaknya menggunakan konten dan informasi mereka untuk meraup untung. Di sisi yang lain, media jurnalistik daring juga sangat butuh Google untuk meningkatkan traffic.
ADVERTISEMENT
Tak bisa dipungkiri, Google adalah aggregator informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses konten media jurnalistik daring. Hampir sebagian besar orang mengakses media-media daring itu dari Google. Itulah mengapa kebanyakan media daring mengejar pengunjung melalui clickbait, dan berusaha untuk menampilkan copywriting yang ramah mesin pencari. Padahal, tuntutan untuk clickbait, lalu bagaimana agar search engine optimized, adalah mekanisme yang disiapkan oleh raksasa digital sebagai skema arena pertarungan. Media-media yang bisa menyumbang keuntungan lebih besar bagi korporasi digital jelas adalah pemenangnya.
Digitalisasi global memang membawa petaka baru bagi negara-negara yang sejak awal tidak punya kapasitas industri digital yang mapan. Hampir sebagian besar korporasi digital itu dikendalikan Amerika Serikat. Dari hulu ke hilir, korporasi digital raksasa itu memonopoli faktor-faktor ekonomi, tanpa ada ruang yang memadai bagi pesaing lain untuk ikut menikmatinya. Revolusi digital bergerak pada logika winner takes all. Dengan demikian, raksasa digital bisa terus mengembangkan inovasi dengan kapasitas finansial yang luar biasa, namun itu tidak berlaku bagi para pesaing seperti media jurnalistik daring.
ADVERTISEMENT
Di Indonesia, kedaulatan negara juga hampir terganggu dengan revolusi digital yang timpang ini. UU pers yang ada tidak bisa mengatur mesin pencari, media sosial, atau e-commerce. UU penyiaran juga tidak bisa menjangkau YouTube. Media-media baru itu beroperasi di ruang publik, tapi tidak bisa dihukum publik. Saat hoaks bersebaran di mana-mana, hanya produsen hoaks yang bisa dihukum, sedangkan pemilik media sosial tidak bisa dihukum padahal mengambil keuntungan dari persebaran hoaks itu.
Masalah lainnya adalah, kedaulatan fiskal kita juga dipertaruhkan karena negara belum mampu menjadikan raksasa digital itu sebagai objek pajak, padahal mereka meraup keuntungan di negara kita. Bahkan tidak hanya di Indonesia, isu kedaulatan fiskal di tengah arus digitalisasi ini menjadi isu global. Tanpa pajak, raksasa digital itu bisa memberikan layanan yang murah sehingga yang terjadi iklim persaingan yang tidak sehat. Media-media nasional kita dikenakan pajak, namun betapa sulitnya untuk mengenakan pajak yang layak kepada korporasi digital itu.
ADVERTISEMENT
Kabinet baru Jokowi dihadapkan dengan tantangan tersebut. Tentu, hal ini menjadi isu penting yang harus segera dihadirkan solusinya oleh pemerintah. Bagaimana negara berperan dalam mengentaskan ketimpangan di antara pemilik media melalui serangkaian regulasi yang tepat, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah: bagaimana pemerintah bisa berinovasi agar industri digital dalam negeri bisa tumbuh pesat.
Grady Nagara. Manajer Program Next Policy. Wakil Ketua Center ILUNI 4.0 Ikatan Alumni UI 2019-2022.

