Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Konten dari Pengguna
Anomali
30 Desember 2021 10:47 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Hasmawati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Jakarta, seribu cerita.
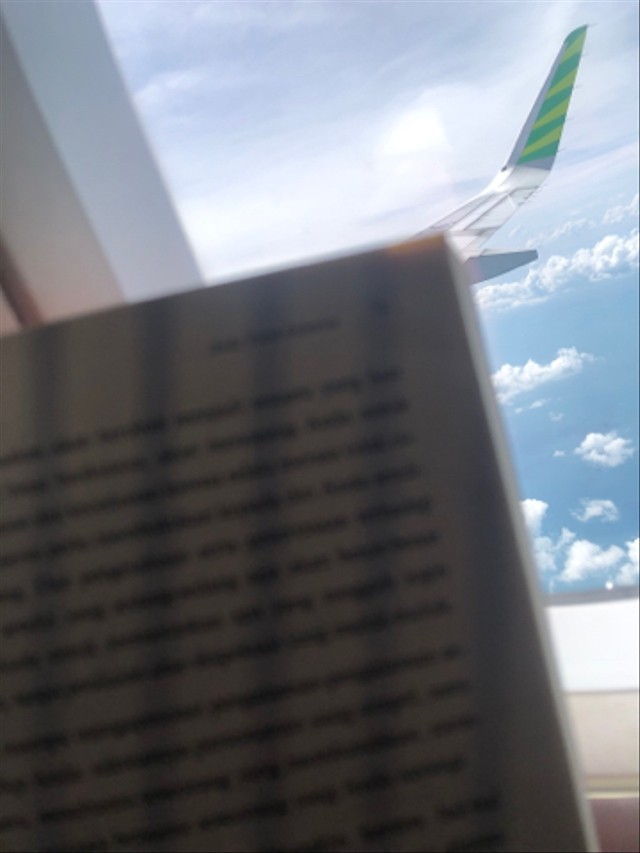
Aku masih bertanya-tanya mengapa aku ada di sini, dalam sebuah maskapai penerbangan menuju ibu kota ini. Namun seperti biasanya aku hanya menggeleng dan tersenyum menikmati situasi yang sedang kualami. Penat rasanya bila semua harus dianalisa, semestinya beberapa hal tertentu dibiarkan mengalir begitu saja.
ADVERTISEMENT
Sesampainya di bandara dalam perjalananku menuju titik penjemputan hatiku serta-merta diserbu rasa rindu. Luasnya bangunan, beberapa area yang menyerupai gedung-gedung yang kebanyakan menyerupai Singapura sontak mengingatkanku bahwa sudah hampir dua tahun aku tak bertandang ke sana. Pandemi sialan ini hendak memaksakan diri saat kini perbatasan mulai dibuka rasanya seperti tidak ikhlas. Singapura yang dulu cukup ditempuh dengan 35 menit perjalanan kini menjadi begitu jauh dengan bekal uang yang tak sedikit. Mana bisa lagi ke sana dengan hanya berbekal 50 dolar Singapura? Ah, sungguh sangat sialan.
Tapi sepertinya kerinduanku akan Singapura sedikit terobati dengan banyaknya gedung tinggi di Jakarta. Mataku liar berkelana berpindah-pindah antara satu gedung ke gedung lainnya. Menikmati langit yang menjadi latar bangunan tinggi tersebut. Meski otak dan mulutku sibuk meladeni pembicaraan dengan pemuda baik yang menjadi penjemputku hari itu, Aries. Pemuda dengan usia dan zodiak sama sepertiku. Hidup astrologi!
ADVERTISEMENT
Setibanya aku di apartemen daerah Kuningan yang akan menjadi tempat bermalamku hari itu, kuhubungi teman yang beberapa bulan ini kerap menyambangi fikiran di sela-sela kesibukanku. Akhirnya hari ini bila ia bersedia aku dapat mengverifikasi fisik yang ada dalam memoriku. Maklum saja perjumpaan pertama kami pada malam hari di bar rooftop hotel kotaku kala itu terasa samar ditambah dengan otakku yang masih berkabut.
"Iya aku mampir ke sana seusai aku bekerja." Sepotong kalimat darinya mampu melambungkan harapan sehingga menyenggol sudut-sudut bibir membentuk senyum, yah semoga saja tidak sampai menjadi seringai.
Kuputuskan untuk sedikit berbenah, mandi untuk menyegarkan diri dengan sedikit kebingungan mencari tombol mengaktifkan pancuran. Kenapa pula yang menyala hanya keran untuk mengisi bathtub? Ah, padahal bathtub itu adalah kemewahan mahal yang jarang kuizinkan untukku mengingat banyaknya air yang akan terbuang sia-sia. Ditambah, air Jakarta daerah sini terasa payau di lidahku. Air tanah y? Kenapa tidak dikasi kaporit berlebih sih seperti di daerahku? Kan jadi sehat sekali kalau hanya menjadi air tanah tanpa zat kimia seperti ini.
Setelah menunaikan ibadah salat Zuhur dan Ashar yang kujama' qashar, aku turun ke bawah mengisi perut di restoran yang ternyata penyajiannya fine dining. Hah! saatnya menerapkan etika makan yang kupelajari dari bacaan dan petatah petitih teman-temanku yang berkutat di dunia boga. Aku hanya memesan salad signature dan sepotong daging dimasak medium rare sesuai dengan jiwa kanibal pemangsa sesama mamalia dalam diriku. Sendiri, ditemani buku Seni untuk Bersikap Bodo Amatnya Mark Manson, yang sedianya akan kubaca sembari makan sendirian namun urung kulakukan karena, yaah, sepertinya restoran fine dining haruslah dengan suasana temaram agar selera makan meningkat karena indera penglihatan ditumpulkan sehingga tersembunyi segala cacat. Sendirian, namun tak lupa meminta bantuan pramusaji mengabadikan momen sendiriku. Dalam hatiku membatin "kurang romantis bagaimana lagi aku terhadap diriku sendiri?"
ADVERTISEMENT
Sekembalinya aku ke unit apartemenku, kuhabiskan dengan membaca ditemani televisi yang menayangkan the wonderful world of Komodo Islandnya National Geographic. Sungguh benar apa dikata orang, suasana mempengaruhi jiwa. Tontonan yang bila kulihat di kediamanku sendiri biasanya menghadirkan ketakjuban dalam diri kini terasa abai, ketinggian unit ini lebih menarik minatku untuk mengamati persekitaran. Kendaraan yang bersileweran di bawah, rinai hujan yang menerpa dinding kaca apartemen. Pantas orang berebut ingin ke atas, sensasi perasaan berkuasa atas yang lain memang memabukkan. Menghadirkan ilusi keberhasilan semu. Gawaiku berdenting "Kamu belum tidur kan? aku sudah deket." tak lama, masuk telepon darinya mengatakan ia telah tiba. Bergegas ku raih kartu kamar dan turun ke lobi bawah. Saat kulihat seorang pemuda yang duduk di salah satu sofa, aku tak yakin, kutelepon nomor whatsappnya. Benar pemuda itu, kulambaikan tangan dengan senyum meleret-leret di sebalik masker. Ia pun membalas lambaianku, juga tersenyum. Pakai masker, tetapi tetap saja matanya terlihat bukan? Saat ia bangkit dan berjalan ke arahku, batinku mengumpat, celaka, ia tinggi sekali. Benarlah malam itu bukan saja otakku yang berkabut, nampaknya mataku pun sedikit jereng sampai imaji dirinya terekam salah besar dalam benakku. Kukatakan padanya bayanganku akannya sama sekali berbeda, dia hanya tertawa.
ADVERTISEMENT
Kami menyambung obrolan di dalam unit apartemen. Luapan ketakjuban darinya akan kesomplakanku jauh-jauh dari daerah demi menyambanginya terasa pasang surut. Kegiranganku akan seorang baru dan berbeda dunia denganku juga membuncah. Kami saling bertanya dan menjawab. Berulang kali dia menggelengkan kepalanya tatkala kukuak sedikit demi sedikit caraku hidup. "Kamu sangat beruntung." itulah kalimat darinya yang lekat di kepalaku. Mungkin...
Dia yang tumbuh di kerasnya kota besar dengan segala pandangan buramnya akan kehidupan juga membuatku kerap membelalakkan mata. Ternyata cerita-cerita akan kelamnya manusia yang banyak kubaca benar ada. Paranoia, bisa jadi dia telah menyentuh nilai itu. Kepercayaannya pada manusia mencapai titik nadir. Otaknya bagai sekumpulan algoritma menilai situasi. Barangkali tuntutan pekerjaannya. Dia harus senantiasa awas dan siap bertindak untuk semua kemungkinan. Canggih sekali. Dia bagaikan anomali dalam hidupku, daya ledak fikirnya luar biasa terasa di sel-sel kelabu yang semakin menua ini. Barangkali mengapa Bung Karno memerlukan hanya pemuda kini dapat kumengerti kiranya.
ADVERTISEMENT
Malam itu aku senang mendapat pembelajaran baru. Banyak hal darinya yang kutakjubi dan bisa kuterima dengan lapang dada. Aku merayakan perbedaan kami, mengakui prinsipnya tanpa menghilangkan prinsipku, mengutarakan keyakinanku tanpa memaksa dia menerima. Kami hanya saling bercerita, mendengar, terkejut, dan sesekali bermain tebak-tebakan. Entah mengapa, keyakinanku untuk senantiasa mencari sisi terang pada setiap makhluk membuatku memujinya. "Kamu adalah seorang yang hangat, hatimu baik." Beberapa kali kukatakan itu padanya. Dia terlihat sanksi, tapi apa peduliku? Toh, aku tak perlu validasi.
Keesokan harinya aku kembali ke kotaku dan mengirimkan kabar padanya bahwa aku telah tiba. "Welcome back to reality." Balasan kalimatnya seakan menutup serunya momen pertemuan kami. Tak mengapa. Bagiku cukuplah momen kami menjadi semacam bola kaca salju yang menyimpan berjuta warna di dalamnya. Indah dengan segala bentuk yang dapat dipandang dan dinilai dari banyak sisi. Bola yang bila kuguncang akan melambungkan butiran-butiran kecil kebahagiaan. Semoga dapat kukeluarkan sewaktu-waktu saat aku jenuh akan pola kehidupanku. Dan semoga bola kaca itu tidak hilang di kedalaman ceruk lubuk hatiku.
ADVERTISEMENT

