Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Hukum vs Moral: Apakah Semua yang Legal Itu Etis?
4 Februari 2025 9:43 WIB
·
waktu baca 6 menitTulisan dari Ingrit Dilla Farizna tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
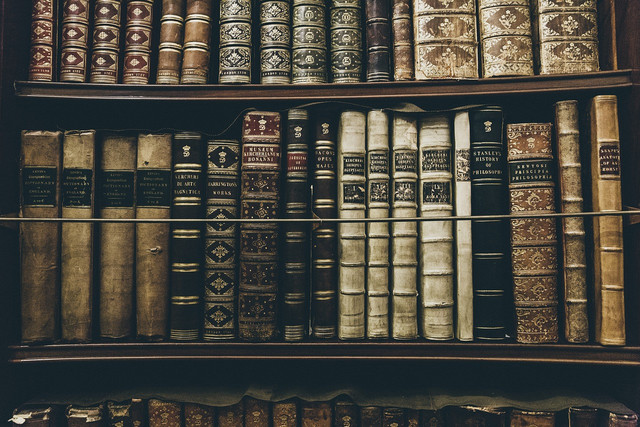
ADVERTISEMENT
Perdebatan tentang hubungan antara hukum dan moral telah menjadi kajian utama dalam filsafat hukum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dan moralitas sering kali dianggap berjalan berdampingan dalam mengatur kehidupan manusia, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar yang telah menjadi bahan kajian dalam filsafat hukum.
ADVERTISEMENT
Perbedaan keduanya terletak dari makna dan fungsinya masing-masing, Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah (seperti negara) untuk mengatur perilaku masyarakat, dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum bersifat objektif, tertulis, dan memiliki daya paksa. Sedangkan Moralitas, di sisi lain, adalah seperangkat nilai dan prinsip yang menentukan mana yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat. Moralitas lebih bersifat subjektif, tidak selalu tertulis, dan bergantung pada nilai-nilai budaya, agama, serta keyakinan individu atau kelompok.
Hukum dan moral adalah dua konsep yang sering kali berjalan berdampingan, tetapi tidak selalu selaras. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat, dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Sementara itu, moral adalah seperangkat nilai dan prinsip yang menentukan apa yang dianggap baik atau buruk oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.
ADVERTISEMENT
Pertanyaannya, apakah semua yang legal itu selalu etis? Jawabannya tidak selalu. Ada banyak contoh dalam sejarah dan kehidupan modern di mana hukum memperbolehkan sesuatu yang secara moral dipertanyakan. Misalnya, pada masa lalu, perbudakan dan diskriminasi rasial dilegalkan di beberapa negara, meskipun secara moral banyak orang menentangnya. Saat ini, ada juga undang-undang yang memungkinkan perusahaan besar menghindari pajak dengan celah hukum, meskipun tindakan tersebut dianggap tidak etis oleh sebagian masyarakat.
Sebaliknya, ada pula tindakan yang secara moral benar tetapi secara hukum dilarang. Contohnya adalah seseorang yang melanggar hukum untuk menyelamatkan nyawa, seperti memasuki properti orang lain tanpa izin untuk menolong korban kecelakaan. Dalam kasus seperti ini, hukum bisa saja menjatuhkan sanksi, tetapi secara moral tindakan tersebut dapat dibenarkan.
ADVERTISEMENT
Perbedaan antara hukum dan moral ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu menjadi standar akhir dari apa yang benar atau salah. Hukum dibuat oleh manusia dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga aspek moralitas dalam merancang undang-undang agar hukum yang dibuat dapat mencerminkan keadilan dan kebaikan bersama.
Sepanjang sejarah, para filsuf hukum telah memperdebatkan hubungan antara hukum dan moralitas. Ada yang berpendapat bahwa hukum harus selalu mencerminkan moralitas agar sah dan adil, sementara yang lain berargumen bahwa hukum adalah sistem aturan yang berdiri sendiri, terlepas dari nilai moral. Perbedaan pandangan ini mencerminkan bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan politik.
ADVERTISEMENT
Para filsuf hukum dalam tradisi positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan tidak perlu selalu mencerminkan moralitas. Mereka berfokus pada legalitas hukum, bukan pada apakah hukum itu adil atau bermoral.
John Austin menegaskan bahwa hukum adalah "perintah dari penguasa yang berdaulat", yang didukung oleh ancaman sanksi. Moralitas tidak menentukan apakah hukum itu berlaku atau tidak. H.L.A. Hart membedakan antara hukum primer (aturan yang mengatur perilaku) dan hukum sekunder (aturan yang mengatur bagaimana hukum dibuat dan ditegakkan). Hart mengakui bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh moral, tetapi moralitas bukan syarat mutlak bagi keberlakuan hukum. Jeremy Bentham, dengan teori utilitarianismenya, menilai hukum berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat, bukan berdasarkan apakah hukum itu sesuai dengan prinsip moral absolut.
ADVERTISEMENT
Golongan positivisme hukum berpandangan bahwa hukum tetap sah meskipun tidak sesuai dengan moralitas. Golongan ini berpendapat bahwa moralitas bersifat subjektif, sedangkan hukum memiliki kepastian yang lebih jelas serta sistem hukum yang baik adalah yang efektif dan rasional, bukan yang hanya mengikuti moralitas.
Berbeda dengan positivisme hukum, para pendukung teori hukum alam berpendapat bahwa hukum harus selaras dengan prinsip moral universal. Hukum yang tidak mencerminkan keadilan dan nilai moral dianggap sebagai hukum yang tidak sah, seperti Aristotle yang percaya bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan keadilan dan kebajikan yang bersifat universal. Kemudian, Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog abad pertengahan, berpendapat bahwa hukum yang benar adalah hukum yang mencerminkan kehendak Tuhan. Jika suatu hukum bertentangan dengan hukum moral yang lebih tinggi, maka hukum itu tidak wajib ditaati.
ADVERTISEMENT
Golongan filsuf hukum alam memandang bahwa hukum yang tidak adil atau tidak bermoral tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Hukum harus didasarkan pada prinsip moral universal yang lebih tinggi. Mengingat tujuan hukum bukan hanya mengatur masyarakat, tetapi juga menciptakan keadilan.
Pendekatan realisme hukum menekankan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam praktik. Mereka percaya bahwa moralitas memang bisa memengaruhi hukum, tetapi keputusan hukum lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Oliver Wendell Holmes berpendapat bahwa "kehidupan hukum bukanlah logika, tetapi pengalaman". Ia menekankan bahwa hukum berkembang berdasarkan keputusan hakim dan kondisi sosial, bukan sekadar teks hukum tertulis.
Realisme hukum memandang bahwa hukum tidak hanya teks tertulis, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Keputusan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk moralitas, tetapi juga kondisi sosial dan kepentingan politik. Hakim dan aparat hukum memiliki peran besar dalam menafsirkan hukum berdasarkan realitas yang terjadi.
ADVERTISEMENT
Dalam perspektif teori kritis hukum, hukum tidak selalu mencerminkan moralitas atau keadilan, tetapi sering kali digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Karl Marx melihat hukum sebagai alat kelas penguasa untuk menindas kelas pekerja. Baginya, hukum tidak netral, melainkan mencerminkan kepentingan ekonomi dan politik dari kelompok yang berkuasa. Hukum tidak selalu mewakili moralitas yang benar, tetapi sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan.Hukum harus terus dikritisi dan diperjuangkan agar lebih adil bagi semua golongan masyarakat. Keadilan hukum tidak bisa dilepaskan dari analisis politik dan ekonomi.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah hukum harus selalu mencerminkan moralitas atau cukup sebagai seperangkat aturan yang memastikan keteraturan masyarakat, adalah masalah yang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.
ADVERTISEMENT
Dalam beberapa konteks, hukum yang baik bisa saja tidak selalu mencerminkan moralitas yang universal, tetapi lebih pada praktik sosial dan budaya yang ada. Namun, dalam jangka panjang, semakin banyak masyarakat mengakui bahwa hukum yang adil adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai moral yang mendasar, seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.
Oleh karena itu, hukum dan moralitas tidak harus dianggap sebagai dua hal yang terpisah atau saling bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

