Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.101.0
Konten dari Pengguna
Generasi Millennial Membaca Wiji Thukul
19 Januari 2017 13:39 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:19 WIB
Tulisan dari Kalis Mardiasih tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT

Memasuki kampus pada awal 2009, di sebuah lembaga tua yang melegitimasi ilmu pengetahuan dengan ijazah dan gelar itu, tidak nampak sebuah jargon “buku, pesta dan cinta” seperti yang dideskripsikan dalam buku-buku memoir para aktivis.
ADVERTISEMENT
Semua itu hanya selisih lima tahun dengan kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib, dan terpaut sebelas tahun dengan tahun hilangnya Wiji Thukul, seniman sekaligus aktivis Partai Rakyat Demokratik.
Pada tahun itu pula, persoalan perihal Munir tidak banyak diperbincangkan. Tidak ada munir di selasar sekretariat organisasi gerakan mahasiswa, tidak ada Thukul pula pada pojok-pojok kajian strategis.
Ya, itu baru lima tahun selepas kepergian Munir.
Lalu, apa daya kami untuk menangkap suara-suara sebelas tahun silam? Bagaimana nasib idealisme muluk pihak penuntut keadilan bagi para penyintas 65?
ADVERTISEMENT
Beberapa di antaranya seperti tulisan “Wiji Thukul dan Orang Hilang” yang menjadi salah satu bagian dalam buku “Dari Jawa Menuju Atjeh” karya Linda Christanty, ulasan khusus majalah Tempo, dan lewat buku sajaknya yang sering dikutip aktivis gerakan setengah matang dengan percaya diri.
Selebihnya, lewat Fajar Merah, anaknya yang beberapa tahun lalu giat menyosialisasikan musikalisasi Sajak Bunga dan Tembok dari panggung ke panggung maupun lewat kanal semacam soundcloud.
Dan yang paling sering, Fitri Nganthi Wani. anak sulung penyair bernama asli Widji Widodo ini ada dalam daftar pertemanan saya di Facebook.
Tetapi, sekali lagi, jika saya bisa dengan mantap menyatakan kekaguman pada Munir, saya tidak bisa semudah itu menyatakan kekaguman pada Thukul.
ADVERTISEMENT
Bagi saya, tentu mudah mendaftar alasan kagum kepada Munir untuk kemudian menanamkan duka akan kepergiannya. Munir dikenal sebagai pemuda Muslim yang taat dan mantan aktivis HMI.
Selain berbagai tulisan ideologisnya tentang perjuangan selalu ia kaitkan dengan alasan-alasan keimanan, kematian Munir jelas: ia mangkat di ketinggian 35.000 kaki di atas Eropa setelah diracun arsenik di dalam pesawat Garuda yang menerbangkannya ke Belanda.
Alasan besar mengapa Munir dihabisi, kita tentu tahu, bahwa Munir tengah menyiapkan tesis yang berisi sejumlah data orang-orang yang dihilangkan pada masa Orde Baru.

Saya tak bermaksud membandingkan keduanya, kecuali memberikan sebuah ajuan awal tentang bagaimana generasi saya mesti memahami Wiji Thukul.
Thukul merupakan seorang aktivis (kiri?) yang kematiannya hingga kini masih menjadi misteri. Sebagian menyebut hilang di Jakarta, sebagian menyebut hilang di Timor Leste.
ADVERTISEMENT
Tahun lalu, akun Path Ndorokakung sempat tersandung masalah ketika menulis desas-desus keterlibatan Thukul dalam pembuatan bom terkait usaha pembebasan Timor Leste.
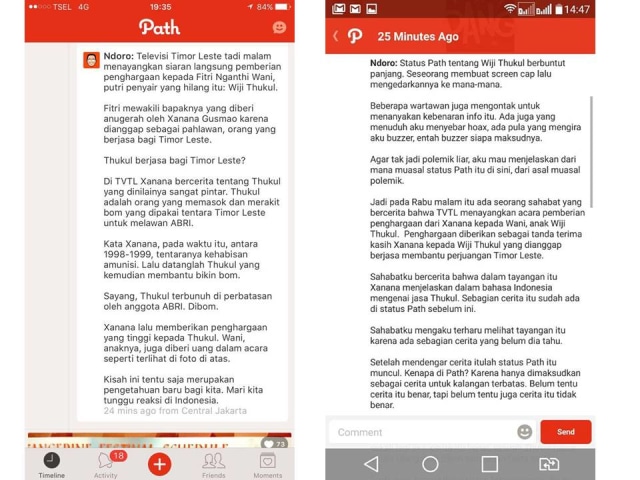
Ketika itu, Fitri Nganthi Wani menolak diwawancara oleh media massa dengan tegas berteriak dari balik pintu rumahnya. Ia bilang:
Jelasnya,misteri hilangnya Thukul, selamanya barangkali tidak akan pernah tuntas. Reformasi tidak membuat Negara ini lepas dari aroma Orde Baru, baik sejak rahim ide maupun fungsi hingga strukturnya. Syahdan, manusia semacam Wiji Thukul, barangkali memang lebih dilabeli sebagai musuh dibanding pahlawan.
Dengan apa generasi saya harus membaca aktivis kiri bernama Wiji Thukul?
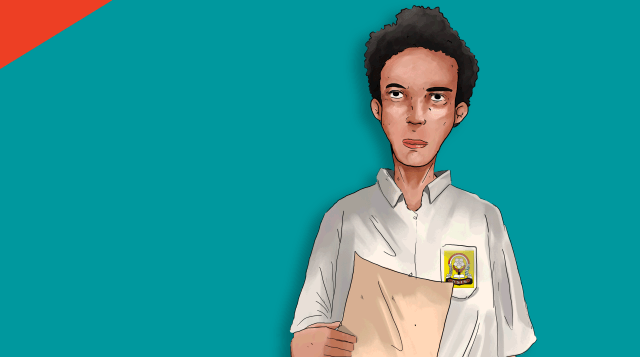
Hal paling aman memang membaca Wiji Thukul sebagai seniman. Sajak dalam goresan Thukul adalah deretan kalimat lugas yang memiliki suara tegas untuk melawan.
ADVERTISEMENT
Nah, di sini barangkali poinnya.
Ia membawa puisi-puisinya itu ketika mengajar anak-anak tetangga dalam Sanggar Suka Banjir yang ia dirikan. Anak-anak miskin kampung pinggiran Solo itu belajar menggambar, membaca, menyanyi, menulis dan bermain teater dengan gratis di bawah asuhan Thukul.
Thukul juga turut mengajarkan para buruh untuk mengerti makna penindasan dan perlawanan. Buruh-buruh pun diajar berteater dan berorasi.
Ingat saudara, itu zaman Orde Baru di mana era pembangunanisme sedang kencang-kencangnya. Buruh diupah rendah, jam kerja tinggi, media massa tak punya hak bicara.
Seorang seniman yang hadir dengan kerelaan dan keberanian untuk menjalankan agitasi lewat kesenian, berhadap-hadapan dengan senjata dan lars tentara, nampak macam hal heroik sekalian sia-sia.
ADVERTISEMENT
Lewat pembacaan semacam ini, kita boleh coba menggelitik anak-anak kiri kekinian yang menjadi idealis sebatas arena gigs band-band alternatif seperti Efek Rumah Kaca, JRX, dan lain-lain itu. Kita bawa anak-anak rebel itu pada larik Thukul dalam Sajak “Peringatan”:
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
Dituduh subversif dan mengganggu keamanan
Maka hanya ada satu kata: lawan!
Kita boleh ingatkan anak-anak muda masa kini apa makna agitasi, orasi dan propaganda, serta memaksa mereka untuk kembali pada ruang diskusi yang mereaktualisasi gerakan di abad milenial.
ADVERTISEMENT
Tidak penting lagi berkubang dalam debat soal Thukul, entah ia seorang pahlawan atau pemberontak. Tetapi, fakta sejarah soal 32 tahun tirani politik yang banyak mewariskan duka itu harus tetap diperbincangkan sebanyak mungkin, kapanpun dan di manapun.

