Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.97.1
Konten dari Pengguna
Komunitas Zero Waste Jogjakarta, Sebuah Oase di Tengah Gurun Darurat Sampah
20 September 2022 10:15 WIB
·
waktu baca 7 menitTulisan dari Y Krisna Wardhana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
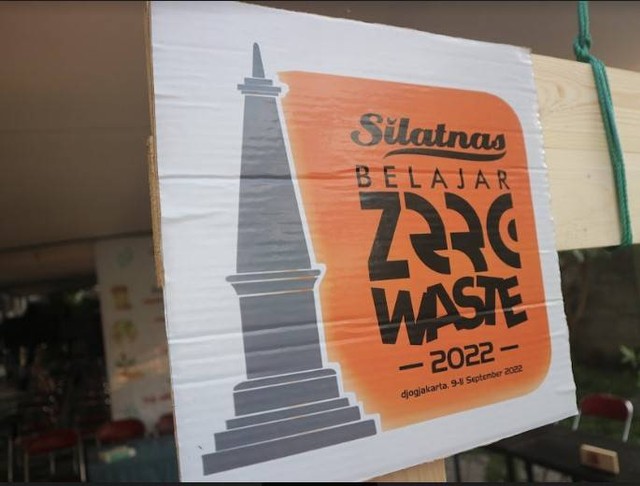
ADVERTISEMENT
Di bawah guyuran hujan yang turun di langit gelap Banguntapan malam ini, aku duduk bersandar di pos keamanan yang tak berlampu di sebelah homestay Cendana, letak di mana event silaturahmi nasional belajar zero waste yang digagas komunitas belajar zero waste Jogja (IG: @belajarzerowaste_id ). Rehat satu jam kumanfaatkan buat beristirahat sejenak setelah sejak pagi bertugas sebagai fotografer dalam event tersebut. Pak Nardi dan Mas Tomo yang bertugas sebagai tenaga keamanan menjaga kendaraan peserta dan panitia yang terparkir, turut menemaniku duduk bergelap-gelap didampingi teh panas dan setoples rengginang. Jajanan tradisional ini ternyata masih mampu bertahan di tengah gempuran makanan instan pabrikan yang semakin merajalela.
ADVERTISEMENT
“Cocok nih, hujan dingin begini ada teh panas dan rengginang.” Aku berseloroh membuka keheningan pos itu setelah berlari-lari kecil menahan gempuran butir-butir air hujan yang sepertinya merindukan bumi Banguntapan.
“Benar mas, cocok sekali. Tapi nggak tahu ya kalau pak Nardi, masih kuat tidak giginya buat makan rengginang?” sambung Mas Tomo sambil berkelakar pada Pak Nardi, yang memang paling tua di antara kami berdua.
"Ooo... jangan mengejek aku Tom, begini ini aku masih bisa kok buat menghabiskan satu toples sendirian." Bantah Pak Nardi disusul tawa yang menggelegar dari kami bertiga di pos gelap itu. Sayangnya gelegar tawa kami tak mampu mengalahkan gelegar suara petir di angkasa sana.
"Hujan dan rengginang, ini mengingatkanku saat menyopir lewat daerah Piyungan pas warga memblokir akses menuju TPA. Coba bayangkan, TPA seluas itu tak lagi mampu menampung sampah kiriman se Jogjakarta." Pak Nardi menceritakan pengalamannya sekitaran Mei lalu, kala warga setempat menolak truk-truk pengangkut sampah yang akan memasuki TPA Piyungan. Sudut-sudut depo pembuangan sampah kota Jogja dibanjiri sampah yang gagal dikirim ke Piyungan.
ADVERTISEMENT
"Aku dulu sampai bingung pak, akhirnya sampahku ya kubakar saja. Kalau dihanyutkan ke sungai, nanti khawatir jika malah terjadi banjir," Mas Tomo terseret dalam ingatannya kala Piyungan ditutup di masa itu.
Mendengar celoteh mereka berdua, anganku pun mau ndak mau ikut juga mengingat masa-masa suram tersebut. Dari beberapa berita yang pernah kubaca ternyata kota Jogja sendiri menghasilkan 370 ton sampah dalam sehari saja! Sementara pemandangan luberan sampah yang tak tertampung di depo-depo dan pembuangan sementara di sekitar pemukiman melonjak hingga 1600 ton. Gila!! Beberapa media elektronik nasional sampai menyebut beritanya dengan tajuk "Jogja darurat sampah". Sebuah tajuk yang mengerikan menurutku, sebagai kota destinasi pariwisata nasional dan bahkan internasional kenapa gagal menemukan solusi masalah sampah. "Siapa yang mau berwisata ke Jogja jikalau sampahnya bertebaran dan menumpuk di semua penjuru kota?”
ADVERTISEMENT
Aku menghentikan lamunanku dan kemudian berkata kepada mereka berdua, "Kok yo kebetulan ya pak, acara di dalam homestay itu juga diselenggarakan oleh komunitas minim sampah."
"Lho, ada ya mas komunitas seperti itu?" tanya Pak Nardi dengan mimik wajah keheranan, menjadi lucu karena tak ada penerangan yang mencukupi di pos tanpa lampu ini.
“Itu sebenarnya apa sih mas?" Mas Tomo menimpali.
"Aku sebenarnya juga tidak begitu tahu dan paham. Pokoknya semacam kumpulan orang-orang yang peduli masalah sampah." Jawabku tak meyakinkan. Namun karena rasa ingin tahu mereka berdua yang kurasa cukup besar, akhirnya aku berusaha menjelaskan semampuku. Itupun hanya melalui apa saja yang kuperhatikan dari penglihatan mataku semenjak event dimulai hingga istirahat malam ini.
ADVERTISEMENT
Aku melihat beberapa keunikan yang sebelumnya tak pernah kutemui di acara-acara yang melibatkan orang banyak. Yang pertama adalah tidak adanya suguhan yang berbungkus plastik. Mulai jajanan pasar yang tak ada bungkus plastiknya, sebagian dibungkus menggunakan daun pisang. Biasanya semua itu dibungkus plastik bening per bijinya, tentu saja dengan alasan higienis. Ternyata para peserta membawa sendiri wadah-wadah makanan dengan berbagai macam material, yang bisa kutangkap adalah wadah-wadah tersebut bukanlah kemasan sekali pakai dan kemudian dibuang.
Begitu juga dengan minuman, tak ada ceritanya saya menemui air minum mineral dalam kemasan botol ataupun gelas plastik yang biasa digunakan dalam acara-acara hajatan. Semua peserta, tamu undangan hingga panitianya membawa sendiri botol-botol dengan berbagai macam material, sekali lagi kesamaannya adalah bisa dicuci, digunakan lagi dan bukan sekali pakai. Andai ada minuman berupa teh atau minuman herbal yang ada, oleh panitia disediakan gelas kaca yang bisa dicuci ulang dan digunakan lagi.
ADVERTISEMENT
Satu lagi yang paling mencolok adalah tidak tersedianya kertas tisu. Para hadirin dengan tertib lebih memilih menggunakan saputangan atau handuk mini untuk mengelap tangannya setelah mencuci tangan.
Di beberapa sudut, disediakan tempat sampah yang berbeda-beda kegunaan dan fungsinya yang berbeda-beda. Ini memudahkan para peserta event memilah dan memasukkan sampahnya sesuai dengan kriteria dan jenis sampah itu sendiri pada tempatnya. Dan sampah yang paling banyak dihasilkan adalah pada wadah sampah organik, itupun hanya dua pertiganya saja yang terpenuhi hingga jelang acara selesai.
Sampai di sini, dengan tingkat pemahaman saya yang terbatas ini, saya melihat keunikan yang begitu kontradiktif apabila dibandingkan dengan acara-acara hajatan dan rapat-rapat yang bahkan dilaksanakan di hotel berbintang lima sekalipun. Coba saja lihat bagaimana kondisi tempat sampahnya,
ADVERTISEMENT
Cara mengeceknya gampang saja, buka tempat sampahnya, lihat dan perhatikan berapa banyak sampah yang dihasilkan, apalagi semuanya tercampur menjadi satu tanpa dipisah terlebih dahulu. Sepertinya ini akan menjadi PR tersendiri ya bagi para petugas sampah nantinya. Panjang umur para pemulung dan petugas sampah! (Namun berapa banyak sih jumlah mereka dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan Jogja? Imbangkah? Tidak! Kalo njomplang sih iya. Banget!)
"Oh, jadi ini ya maksudnya jargon cegah-pilah-olah yang sering digemborkan para penggerak komunitas minim sampah," tanpa sadar saya saya manggut-manggut sendiri dalam lamunan angan di sela-sela cerita yang saya sampaikan ke Mas Tomo dan Pak Nardi. Ini juga mengingatkanku pada cerita Mister Nakagawa, bos Jepang pemilik pabrik tempat kerja saya pernah mengais-ngais rupiah sebagai buruh. Di Jepang, melalui regulasi pemerintahnya mewajibkan masyarakatnya memilah sampahnya sendiri, apabila tak memilahnya maka sampahnya tak akan diangkut oleh petugas pengumpul sampah. Budaya malu dan disiplin sangat ketat pada masyarakat Jepang, jadi bisa dibayangkan apabila anda gagal memilah sampah anda sendiri maka sampahmu akan mangkrak di depan rumahmu, selain menerima sanksi sosial dari tetangga kiri kanan, lama-lama anda juga akan dikenai sanksi oleh pemerintah setempat.
ADVERTISEMENT
Itu di Jepang, tentu saja berbeda dari yang ada di Jogja. Pemerintah Jepang menekan rakyatnya untuk hidup bersih dan disiplin dalam bertanggung jawab akan sampah rumah tangga. Itu menjadi budaya baik yang perlu diadopsi. Sementara di Jogja sini, belum ada regulasi semacam itu. Kebijakan top-down yang 'memaksa' warganya untuk disiplin tertib olah pilah sampah. Meski terkesan keras, tapi ya hasilnya jelas untuk kepentingan bersama.
Mungkin karena dirasa tidak cukup mempunyai kekuatan untuk membuat regulasi melalui kebijakan pemerintah, maka komunitas ini lebih memilih berjuang secara bottom-up melalui kampanye minim sampah yang berbasiskan melalui unit terkecil masyarakat, ...keluarga!
Di bawah gerimis hujan yang tak kunjung berhenti ini, saya membayangkan betapa beratnya perjuangan para 'Defender of the Earth' (saya menyebut mereka begitu karena mengingatkan akan seri kartun dengan tokoh Flash Gordon dan Phantom di masa saya masih kecil) dalam menghadapi gempuran 'Jogja darurat sampah' seperti tajuk berita yang sempat membuat bulu kuduk saya berdiri kala membacanya dulu.
ADVERTISEMENT
Namun, mungkin ada cerita Mister Nakagawa yang perlu diperhatikan bila kita tarik benang merah antara kondisi di Jepang dengan gerakan minim sampah yang ada di Jogja ini. Di Jepang dulu juga menemui banyak kendala dalam menggerakkan penyadaran masyarakat agar peduli akan sampahnya masing-masing, baru di pertengahan tahun 1970-an muncul gerakan masyarakat yang disebut sebagai chōnaikai. Chōnaikai sendiri sebenarnya adalah semacam komunitas desa yang bergerak dalam kepedulian lingkungan, salah satu sumbangsih terbesarnya adalah gerakan peduli lingkungan melalui mengurangi pembuangan sampah, menggunakan kembali barang yang bisa digunakan, dan daur ulang. Ada kota zero waste bernama Kamikatsu yang berada di distrik perfektur Tokushima, Jepang. Di Kamikatsu tersedia laboratorium kolaboratif dan pusat studi zero waste yang bisa digunakan pengunjung kota itu untuk belajar hidup minim sampah, dimulai dari budaya dan pengetahuan akan sampah itu sendiri.
ADVERTISEMENT
Meskipun begitu, pemerintah Jepang sendiri baru mengesahkan undang-undang soal pengolahan dan pemilahan sampah di tahun 2000. Butuh setidaknya seperempat abad! Ya, butuh seperempat abad mulai dari pergerakan masyarakat yang bersifat bottom-up , sangat terbatas hingga akhirnya bisa menghasilkan kolaborasi dengan pemerintah melalui peraturan yang bersifat top-down.
Ya, kita pastinya menghadapi karakter dan budaya masyarakat yang jauh berbeda antara Indonesia dan Jepang. Namun di era digital dan masanya generasi Z unjuk gigi ini, harapan itu akan tetap ada.
Apakah gerakan belajar zero waste Jogja juga akan bisa seperti Chōnaikai di Jepang?
Siapa yang tahu? Tidak ada yang tak mungkin.

