Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
ADVERTISEMENT

“Joke kita waktu itu, kalau mau bikin film politik, banyakin adegan seksnya biar seksnya yang dipotong. Kalau bikin film seks, adegan politiknya dibanyakin,” kata Abduh Aziz, mengenang masa saat Orde Baru masih kuat mengekang.
Pemerhati film dan Direktur Utama Produksi Film Negara itu melontarkan kelakar khasnya tersebut saat berbincang dengan kumparan (kumparan.com), Senin (27/3).
Sebagai seseorang yang pernah mengecap “manis” Orde Baru, Abduh paham betul dengan berbagai kekangan ekspresi yang dibuat oleh pemerintah zaman itu. Salah satunya ialah sistem sensor.
“Kalau bercerita mengenai sensor di Indonesia, sejarahnya panjang,” kata Abduh. Sejarah itu bahkan terentang sebelum Indonesia merdeka.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan catatan Lembaga Sensor Film, perfilman nusantara mulai menujukkan geliat pada masa penjajahan Hindia Belanda tahun 1900.
Kehadiran bioskop menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda yang kala itu bercokol di nusantara. Mereka khawatir bioskop-bioskop rakyat menampilkan konten film yang “tak layak” alias memberi pencerahan bagi penonton pribumi.
Wajar, sebab sudah tentu Belanda sebagai penjajah tak ingin “renaisans” terjadi di nusantara.
Tahun 1916, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi yang mengatur tentang film dan cara penyelenggaraan usaha bioskop atau ”gambar idoep” lewat keberadaan lembaga bernama Commissie voor de Kuering van Films atau Komisi Pemeriksa Film (KPF).
Seperti yang disebutkan dalam Film Ordonantie No. 276, sistem penyensoran dilakukan pada proses praproduksi melalui deskripsi film. Tetapi jika dianggap perlu, film ditunjukkan langsung kepada KPF.
ADVERTISEMENT

Kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda menguat ketika bioskop nyata membawa pengaruh atas kehidupan masyarakat pribumi, yakni menyebabkan perubahan pandangan penduduk pribumi terhadap para penguasa kulit putih.
Mata warga pribumi kian terbuka soal bangsa kulit putih, termasuk kelemahan mereka. Padahal sebelum kemunculan bioskop, pribumi tak tahu hal-hal soal keburukan dan sejarah jatuh-bangun bangsa-bangsa Eropa.
Dengan kemunculan dampak buruk bioskop yang mengancam kewibawaan supremasi putih, Ordonansi 1916 berkali-kali mengalami pembaruan, misalnya perubahan mengenai aturan nilai yang boleh atau tidak boleh disematkan dalam film yang akan dikonsumsi oleh masyarakat pribumi.
Semua hal yang berbau kesusilaan, tata krama, menganggu ketertiban umum, tidak boleh diangkat dalam film. Dan tentunya, white supremacy menjadi nilai utama yang ditekankan dalam setiap film yang diproduksi.
Hingga akhirnya Belanda bertekuk lutut pada pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam peralihan penguasaan ini, Jepang juga menggunakan film sebagai alat propaganda untuk memperkuat semboyan “Nippon Cahaya Asia” di Indonesia. Salah satunya dengan melarang konten film Hollywood, kecuali jika film itu mengandung cerita kejahatan Barat atau persahabatan dengan Asia.
ADVERTISEMENT

Jepang juga menekankan kehebatan militer, budaya, dan tujuan pemerintahan mereka dalam film-filmnya. Pada masa kedudukan Jepang, Film Commissie bentukan Hindia Belanda dibubarkan, diubah menjadi Dinas Propaganda Tentara Pendudukan Jepang (Sendenbu Eiga Haikyuu Sha) pada Desember 1942.
Penggunaan film sebagai alat propaganda dianggap cukup efektif oleh penguasa. Nilai-nilai propaganda dibawa dalam tiap film yang diproduksi, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan kepentingan politik penguasa dibabat habis.
Ketika Jepang angkat kaki dari Indonesia, badan yang berhak untuk menyensor film pun beralih pada Panitia Pengawas Film (PPF). Pemerintah Indonesia lewat Dewan Pertahanan Nasional juga membentuk Badan Pemeriksaan Film (BPF).

Memasuki masa Orde Lama, fungsi propaganda dan reduksi nilai yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah tetap menjadi pekerjaan utama PPF dan BPF.
Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1952, instruksi sensor film semakin diperkuat dan ditekankan pada pelarangan film yang mengandung adegan atau percakapan berisi anjuran perang, pelanggaran asas ksatria, penggunaan senjata dan adegan perang yang berulang-ulang, serta usaha untuk menjatuhkan pemerintahan sendiri.
Untuk memperkuat identitas bangsa yang baru merdeka, pemerintah Indonesia selalu berupaya menjaga agar tidak ada kontaminasi propaganda asing yang bisa menggoyahkan upaya mereka membangun bangsa.
Pada 5 Agustus 1964, diterbitan Penetapan Presiden Nomor 1/1964 yang menegaskan aturan bahwa film Indonesia yang dibuat harus mendukung ideologi Pancasila, menggambarkan hal-hal yang mengandung pemberitaan kebijaksanaan pemerintah, dan memperlihatkan syarat-syarat ketertiban umum yang berlaku.
Sementara film yang diimpor tentu tak luput dari sensor. Film impor tak boleh mengandung konten yang bertentangan dengan Pancasila, menjadi alat propaganda pihak lain, dan harus sesuai dengan syarat ketertiban umum Indonesia.
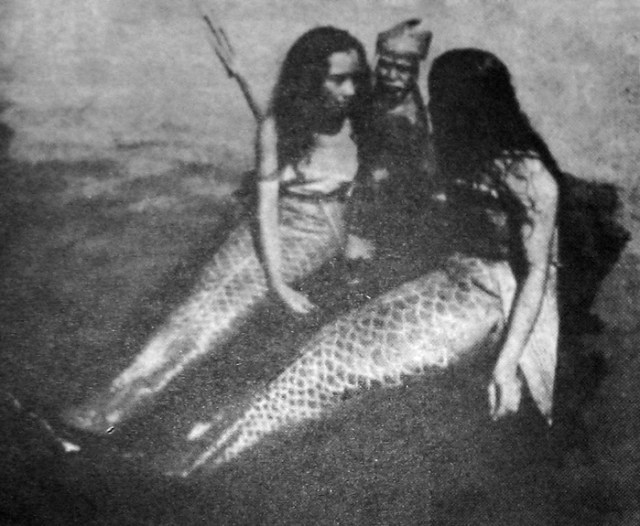
Memasuki Orde Baru, berbanding terbalik dengan perekonomian dan pembangunan Indonesia yang naik tajam, kebebasan berekspresi amat dikekang, hak asasi manusia diabaikan, dan korupsi merajalela.
Berbagai film yang dirasa tak sesuai dengan ideologi rezim Orde Baru langsung diberedel atau dipaksa diubah agar sesuai dengan roh Orde Baru. Semua tugas itu dilakukan oleh Departemen Penerangan dan Komite Sensor Film --yang kini beralih nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF).
Kreativitas sineas Indonesia lantas dipasung dengan berbagai cara, mulai lewat pengawasan ketat pada proses praproduksi hingga pascaproduksi film. Misalnya, judul film tidak boleh menggambarkan ideologi komunisme, baik tersurat maupun tersirat.
Film yang pernah diubah terkait dengan aturan tersebut adalah Kanan Kiri OK karya Deddy Armand (1989) yang harus diubah menjadi Kiri Kanan OK. Perubahan diperintahkan dilakukan karena diksi “kiri” dianggap identik dengan komunisme.
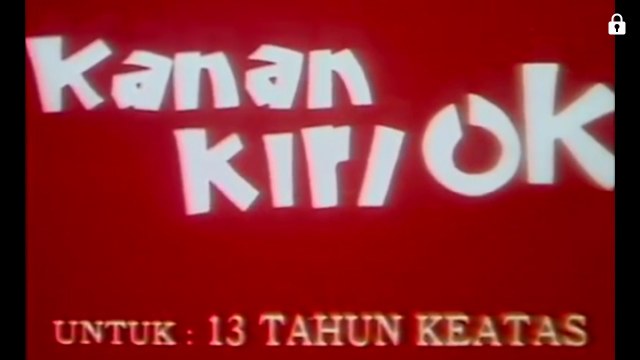
Pada masa ini, masyarakat disuguhi lebih banyak film dengan konten percintaan atau horor ketimbang film politik. Terang saja, sebab film politik saat itu kerap terkena sensor bahkan akhirnya diberedel karena dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa.
“Kalau diperhatikan, film tahun 1980-an lebih banyak tentang cerita remaja, horor, percintaan, karena begitu masuk ke hal-hal berbau politis, beberapa film jadi korban sensor. Ada Max Havelaar, Yang Muda Yang Bercinta, Djakarta 1966,” kata Abduh.
Sistem sensor jadi salah satu bentuk kuasa mutlak pemerintahan. Pemerintah yang paham betul bahwa kekuatan film dapat membentuk cara pandang masyarakat, lantas membuat film dengan varian dan ideologi seragam.

Tumbangnya Orde Baru pada 1998 akhirnya meruntuhkan kekangan yang menyandera para pegiat industri kreatif perfilman. Perfilman Indonesia --yang tak perlu lagi menggunakan surat izin penyiaran-- berkembang pesat.
Perkembangan ini tak hanya didukung oleh teknologi yang makin maju, tapi juga keragaman ide dan gaya pembuatan film yang makin bebas.
Perkembangan teknologi turut mendorong perubahan terhadap peraturan Undang-Undang yang telah dipakai sejak rezim Orde Baru. Perubahan ini diakomodasi dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam UU ini, konten yang dilarang telah berubah mengikuti dinamika politik bangsa.
Jika dulu film dilarang menampilkan nilai yang dianggap bertentangan dengan pemerintah dan semata-mata digunakan sebagai salah satu bentuk propaganda, kini konten tersebut tak lantas ditolak mentah-mentah.
Keleluasan dalam eksplorasi ide pun diakomodasi dalam UU, hanya tidak lantas keluar dari koridor norma sosial yang didefinisikan dalam aturan untuk tidak: menonjolkan pornografi; memprovokasi pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan; menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; merendahkan harkat dan martabat manusia.
Kebebasan berekspresi itu akhirnya mendorong lahirnya berbagai film yang mampu membawa nilai alternatif untuk disuguhkan pada masyarakat. Nilai alternatif ini dihadirkan dalam film-film yang mengangkat momen atau hal yang dianggap terlarang, seperti pembunuhan massal tahun 1965, penggulingan Orde Baru tahun 1998, hingga kisah cinta sesama jenis yang muncul dalam beberapa film.
Sebut saja misalnya film Arisan yang rilis pada 2003, menceritakan kisah pertemanan dan percintaan homoseksual. Hanya berselang lima tahun dari runtuhnya orde baru, film Arisan mampu menarik perhatian hingga 100 ribu penonton.
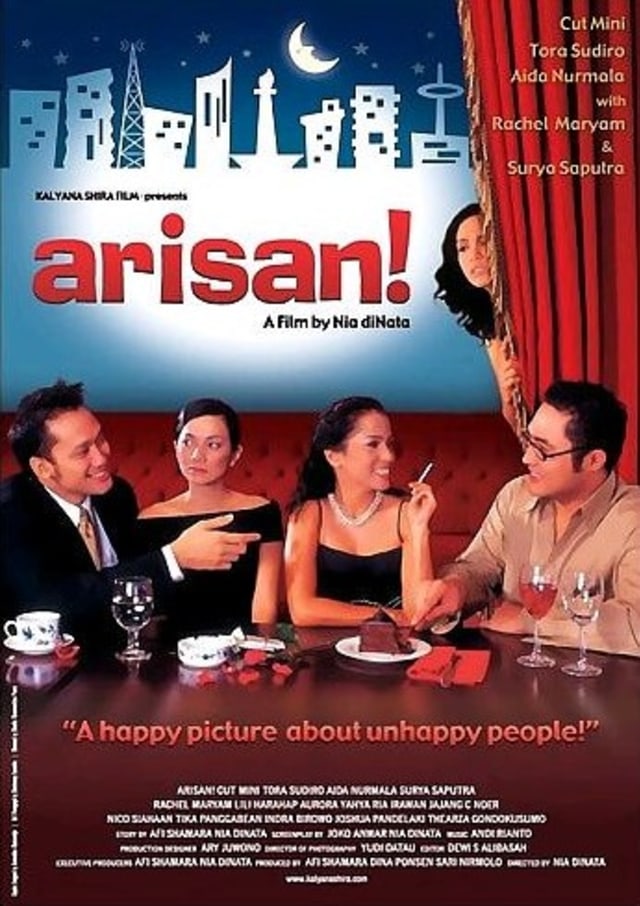
Namun, apakah kebebasan itu betul bisa dipertanggungjawabkan? Sebab tak jarang film yang mengandung elemen kekerasan atau adegan percintaan berlebih, ternyata lolos sensor.
Paparan sinema-sinema di layar kaca --bioskop maupun televisi-- yang relatif tak disensor lantas juga jadi konsumsi anak-anak. Akibatnya, anak-anak SD saling bertukar surat cinta dan mendeklarasikan hubungan cinta.
Untuk itu, penting untuk menggalakkan literasi media agar khalayak bisa lebih bijak dalam memilih konsumsi konten, karena telah mengetahui dengan baik isi dan dampak dari konten yang ditontonnya tersebut.
“Di zaman screen culture ini, makin penting media literacy. Bayangkan kita berdiri di pulau yang terapung di antara lautan informasi. Zaman saya problemnya adalah akses terhadap informasi, sementara zaman sekarang adalah how to choose, how to pick the right thing --untuk diri sendiri,” kata Abduh.
Kalau menurut anda, bagaimana kondisi perfilman Indonesia?
ADVERTISEMENT
