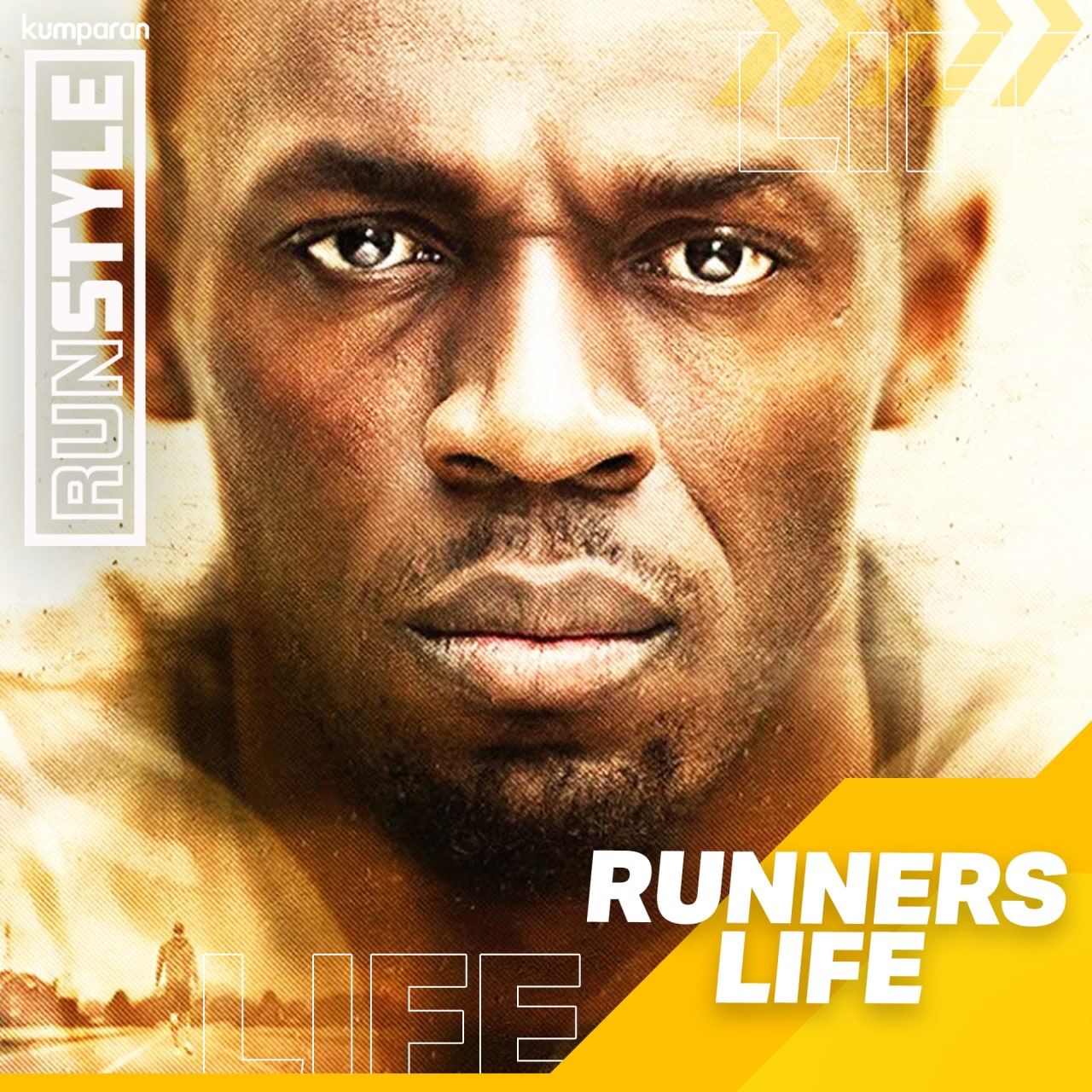
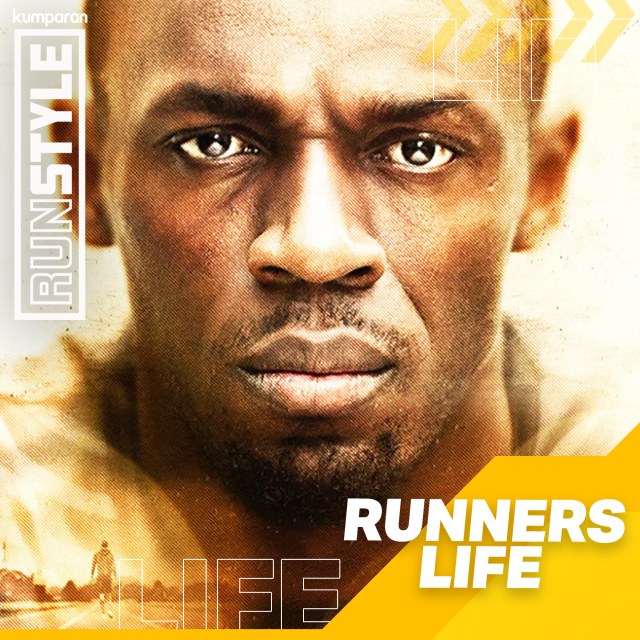
Virus corona menyebar dengan cepat. Tak cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Social maupun physical distancing alias mengambil jarak dengan orang lain merupakan cara yang efektif untuk menekan penyebaran virus corona.
Indonesia belum menerapkan lockdown, sih, tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya keluar rumah. Kalau memang tak penting, lebih baik beraktivitas di rumah saja untuk sementara waktu.
Bagi mereka yang terbiasa beraktivitas di luar rumah, termasuk para pelari, berdiam di rumah dalam waktu yang lama bisa memicu stres dan kejenuhan.
Berita baiknya, stres ini masih bisa diakali. Selain rajin olah tubuh, melakukan aktivitas kreatif, dan mengerjakan hobi, menonton film bisa jadi solusi.
Di edisi kali ini, RunStyle punya daftar film bertemakan lari yang bisa kalian tonton. Kalau kalian punya film yang lain, boleh banget, lho, berbagi di kolom komentar.
Saint Ralph (2004)
Film garapan sineas Kanada, Michael McGowan, yang rilis pertama kali di Toronto Festival Film pada 11 September 2004 ini mengisahkan tekad Ralph Walker untuk mengikuti Boston Marathon 1954.
Ia merupakan bocah 14 tahun yang bersekolah di St. Magnus Catholic High School di Hamilton, Ontario. Disiplin ketat ala sekolah Katolik ternyata tak menjamin bahwa segala sesuatunya bakal berjalan baik-baik saja buat Walker. Ia berulang kali mendapat perundungan karena dianggap lemah.
Walker juga menenteng nerakanya sendiri dalam wujud asal-usul getir. Ayahnya tewas di Perang Dunia II, sementara ibunya sedang koma di rumah sakit.
Kesialan Walker tak berhenti sampai di situ. Atas kasus indisipliner yang membikin orang geleng-geleng kepala, Walker dihukum dengan wajib masuk tim cross-country sekolahnya yang dilatih oleh Pastor Hibbert.
Pada masa mudanya, Hibbert merupakan atlet maraton yang hampir menjejak ke Olimpiade. Sayangnya, cedera menghantam sehingga ia tak bisa mencicipi rasanya berlomba di Olimpiade.
Hibbert sebenarnya sudah mendapat perhatian Walker bahkan sebelum masuk tim cross country. Bukan karena sejak awal Walker tertarik untuk menggeluti olahraga lari, tetapi karena sang pastor pernah memaparkan paham Friedrich Nietzsche dalam sebuah sesi pelajaran agama.
Dalam hari-hari latihan, Hibbert mengajar tiga konsep ini: Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Kemurnian hati, tetapi lembek dan gampang jatuh, sama dengan naif. Doa tanpa berserah sami mawon dengan memaksa Tuhan.
Pengertian seperti itu menjadi titik-titik yang dihubungkan oleh Walker, lalu membawanya pada kesimpulan bahwa ia harus mengikuti Boston Marathon 1954. Menurut Walker, semangat dan tekad seperti ini akan ‘menjalar’ kepada ibunya yang sedang bertarung melawan koma.
Tentu saja mewujudkan tekad tidak semudah memunculkan tekad. Jangankan berlomba, berlatih saja sudah setengah mati.
Film ini juga menunjukkan bahwa siapa-siapa yang ada di sekelilingmu dapat membentukmu menjadi seperti apa. Walker dikelilingi orang-orang tepat.
Tak cuma pelatih dan suster yang merawat ibunya, bahkan gebetan yang menolaknya pun punya andil. Cinta ditolak tak masalah, yang penting ilmu lari didapat. Sip, Dek Walker!
Walker bahkan memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolahnya untuk merengkuh mimpi terliarnya tersebut. Ia melahap buku biografi Tom Longboat, pelari Kanada yang menjuarai Boston Marathon 1907.
Hanya karena memiliki modal apik untuk mewujudkan tekadnya naik podium puncak Boston Marathon, bukan berarti masalah Walker selesai. Bahkan di hari perlombaan saja, ia masih berhadapan dengan persoalan ruwet.
Film ini mengarah ke tearjerker, sih. Namun, percayalah, ‘Saint Ralph’ bukan tearjerker murahan, bukan cerita yang sekadar mengumbar air mata dan mendewakan kesedihan.
Brittany Runs a Marathon (2019)
Apakah kamu termasuk tim rebahan yang buat beranjak dari kasur saja sulitnya minta ampun? Apakah kamu peduli setan dengan segala macam makanan yang masuk ke tubuhmu?
Atau apakah kamu memegang prinsip “Hidup itu mah seperti air, mengalir saja,” tanpa menyadari bahwa yang namanya air mengalir pasti bergerak ke tempat yang lebih rendah?
Brittany O’Neil awalnya pun demikian.
Paul Downs Colaizzo, penulis drama Broadway, punya alasan mengapa ia begitu ngotot mengangkat kisah O’Neil ke dalam film. Baginya, O’Neil alias Brittany dalam film ini adalah tokoh yang sangat personal.
Tokoh ini bukan fiktif belaka. Cerita yang diangkat oleh Colaizzo benar-benar terjadi, bahkan tak jauh dari kehidupannya karena Brittany merupakan salah satu kawannya.
Mirip Ralph Walker dalam ‘Saint Ralph’, Brittany bertekad untuk mengikuti salah satu ajang marathon terbesar di dunia, New York Marathon. Bedanya, Brittany tidak melakukannya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri.
Bagi Brittany, maraton merupakan jalan keluar dari gaya hidupnya yang amburadul. Untuk menjalani hidup yang baik, kau harus mencintai diri sendiri. Untuk mencintai diri sendiri, kau harus memperlakukan hidupmu dengan baik dan pantas. Yep, self love memang menjadi fondasi cerita.
Colaizzo menganggap Brittany spesial. Bayangkan, orang yang amburadul, sinis walau punya pandangan lucu tentang dunia, hidup semaunya, dan tidak sopan tiba-tiba memiliki tujuan hidup untuk berlomba di New York Marathon.
Kita semua tahu mempersiapkan diri untuk mengikuti maraton dan menjalankannya bukan persoalan sepele. Untungnya, Colaizzo tak melepaskan kisah Brittany yang bertungkus-lumus mewujudkan asanya itu dari humor.
“Saya adalah pria yang menulis cerita tentang wanita yang mengubah hidupnya dengan melibatkan masalah citra tubuh. Konsep dan pemahaman itu melekat pada saya. Saya tidak ingin ada nuansa yang hilang dalam interpretasi orang lain soal kisah ini,” kata Colaizzo kepada The Hollywood Reporter.
Sebagai seorang kawan, Colaizzo paham bahwa Brittany memang orang yang humoris. Jadi, mengapa harus menghilangkan wataknya yang satu ini hanya karena kisahnya inspiratif? Well, witty humor works.
Brittany dalam ‘Brittany Runs a Marathon’ diperankan oleh aktris yang akrab dengan film-film komedi, Jillian Bell. Film yang pertama kali tayang di Sundance Festival pada 29 Januari 2019 ini dapat disaksikan via layanan streaming Amazon Prime.
Marathon (2005)
Tidak ada manusia yang lahir tanpa anugerah. Masalahnya, tidak semua orang menyadari anugerah tersebut. Masalah lainnya, tak semua orang mau bersusah-payah menggunakan anugerah tersebut untuk hidup sehebat-hebatnya yang dia bisa.
‘Marathon’ rilis pada 2005. Film Korea Selatan garapan sutradara Jeong Yoon-chul ini mengangkat kisah Bae Hyong-Jin, yang merupakan seorang pelari. Bae spesial, ia mengidap autisme.
Kondisi ini membuat Bae kecil kesulitan mengendalikan diri sendiri. Ia sering mengamuk, sibuk dengan dunianya sendiri, dan menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain.
Ketika itu, hanya ada dua hal yang membahagiakan Bae: Zebra dan camilan bermerek Chocopie. Selebihnya, tak ada yang penting bagi Bae kecil.
Begitu memasuki usia dewasa, Bae akhirnya tahu apa yang ia ingin dilakukannya. Ia mau menjadi pelari. Babak baru dalam kehidupan Bae dimulai.
Jika sebelumnya ia ada di fase mencari apa yang diinginkan, kini ia ada di tahap mewujudkan apa yang diinginkan. Tentu saja untuk mewujudkan keinginan ini tidak mudah.
Setelah mengikuti lomba lari 10k, ibu Bae ingin agar anaknya menjajal full marathon. Masalahnya, tak semua orang pada awalnya memandang Bae dengan serius, termasuk sang pelatih.
Itu baru masalah pertama. Persoalan keduanya adalah Bae ingin menang, tetapi dia tak paham dengan pasti apa yang namanya kecepatan.
‘Marathon’ menjadikan pergulatan batin dalam memahami diri sendiri sebagai konflik utama. Pertanyaan yang berusaha dipecahkan adalah: Apakah menjuarai maraton merupakan keinginan Bae atau semata-mata hanya ambisi sang ibu?
Pacemaker (2011)
Istilah pacemaker tak asing bagi mereka yang menggeluti olahraga lari. Sederhananya, pacemaker adalah pelari yang bertugas untuk memandu kecepatan seorang pelari agar dapat mencapai target waktu yang diinginkan.
Tugasnya tak cuma itu. Pacemaker atau sering disebut pacer bertugas mengingatkan para pelari untuk menggantikan cairan tubuh saat berlari agar tidak cedera atau heatstroke. Pacemaker juga bertugas memberikan pertolongan pertama pada pelari.
Film ‘Pacemaker’ yang disutradarai Kim Dal-joong dan tayang perdana pada 2011 ini bercerita tentang kehidupan seorang pacemaker maraton bernama Joo Man-ho. Meski bertugas di lintasan lari maraton, seorang pacemaker seperti Joo hanya berlari sampai 30 km.
Pada suatu waktu, Joo didatangi oleh mantan pelatihnya, Coach Park Seong-il. Coach Park meminta Joo untuk kembali turun lintasan dan mendampingi anak didiknya, Min Yoon-ki.
Situasi ini ibarat pintu bagi Joo untuk mewujudkan keinginannya berlari sampai garis finis bersama atlet yang didampinginya.
Keinginan yang dipendamnya sejak lama itu tambah meletup karena pelari yang didampinginya kali ini tidak berlari di perlombaan kacangan, tetapi Olimpiade 2012 di London. Full marathon, Olimpiade pula.
Namun, berkhayal memang lebih mudah ketimbang berlari. Keinginan itu lebih mirip dengan angan-angan muluk jika melihat kondisi Joo yang berulang kali dihajar cedera. Itu belum ditambah dengan usianya yang dianggap tidak ideal lagi.
Konsep mengalahkan diri sendiri sebelum mengalahkan lawan sudah lama diperdengarkan di segala ranah, termasuk atletik seperti maraton.
Perlawanan Joo berbeda. Satu-satunya lawan yang harus dikalahkannya kali ini adalah dirinya sendiri.
Run, Fat Boy, Run (2007)
Berlari adalah hak semua orang, bahkan bagi mereka yang tak memiliki alasan khusus. Forrest Gump contohnya. Ia cuma ingin berlari. Ketika ditanya apakah ia berlari untuk misi perdamaian atau menebar inspirasi, Gump tak punya niat untuk menjawab.
Meski Dennis Doyle bukan Forrest Gump, ia juga tak punya alasan pasti mengapa berlari seumur hidup.
Jika ‘run, Forrest, run’ merupakan seruan bagi Forrest Gump; ‘run, fat boy, run’ adalah seruan yang ditujukan kepada Doyle yang hidupnya identik dengan lari. Oke, secara konotatif.
Film ini dibuka dengan keputusan Doyle untuk melarikan diri dari tunangannya, Libby Odell, di menit-menit akhir jelang upacara pernikahan mereka.
Setelah sejumlah fragmen, muncul adegan yang memperlihatkan Doyle berlari mengejar pencuri di supermarket tempatnya bekerja sebagai petugas keamanan.
Begitu mendengar Odell akan menikah, Doyle berlari lagi. Kali ini, di perlombaan maraton yang diikuti oleh Whit Bloom, calon suami Odell.
Apakah ini kebetulan semata? Oh, tentu tidak.
“Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun.” Keputusan Doyle untuk berlari di perlombaan yang sama dengan Bloom berkaitan dengan kata-kata yang diucapkan Odell untuknya itu.
Film ‘Run, Fat Boy, Run’ yang menampilkan Simon Pegg sebagai Doyle ini rilis pada 2007. Jangan khawatir, genrenya komedi. Sesulit-sulitnya maraton, tetap ada sisi humornya.
Sisi inilah yang ditonjolkan oleh David Schwimmer, sang sutradara. Humor slapstick, roman, dan melankolia diracik menjadi sebuah film berdurasi 1 jam 40 menit.
Meski ceritanya ringan, bukan berarti Schwimmer menjadikan film ini naif dan polos begitu saja. Tetap ada metafora yang menyentil, misalnya saat Doyle dan Bloom berjalan bersama Jake, anak Odell. Dalam fragmen tersebut, Doyle dan Bloom terlihat menarik-narik tangan Jake.
‘Run, Fat Boy, Run’ memang film yang mengisahkan cerita konyol. Namun, ‘Run Fat Boy’ Run menyimpan pesannya sendiri di balik selubung komedi. Bisa saja pesan tersebutlah yang perlu didengar oleh mereka yang membutuhkan alasan untuk berlari, bukannya melarikan diri.
I Am Bolt (2016)
Meski belum pernah berkenalan secara langsung, sebagian dari kita pasti ngeh dengan Usain Bolt. Di jagat atletik, rasanya muskil bagi siapa pun untuk menyalip superioritas Bolt yang punya koleksi delapan keping emas Olimpiade dan 11 medali emas Kejuaraan Dunia.
Untuk segala pencapaiannya di atas trek lari, tentu tak ada yang berhak kesal ketika melihat Bolt memamerkan kualitasnya dalam sebuah unggahan di Instagram.
Bolt sudah melakukan social distancing sejak lama. Kalau kata orang-orang, before it was cool. Sombong tidak dilarang untuk orang yang benar-benar jago.
Apa yang kita saksikan sekarang jika bicara soal Bolt hanyalah hasilnya. Ada begitu banyak proses behind the scenes yang tidak pernah kita ketahui.
Proses di balik layar itulah yang membentuk dan menempa Bolt. Kegigihan untuk menempuh perjalanan panjang yang sarat dengan tungkus lumus itulah yang membikin leher Bolt layak buat dikalungkan medali emas Olimpiade.
Perjalanan panjang itu pada akhirnya bisa kita saksikan lewat film biopik berjudul 'I Am Bolt'. Film yang rilis pada 2016 ibarat pintu yang mengantar kita pada kehidupan Bolt yang sebenarnya.
Bolt yang selama ini kita ketahui adalah Bolt seorang pelari. Akan tetapi, Bolt sebagai seorang sahabat dan anak juga tampak lewat dokumenter garapan Gabe Turner dan Ben Turner ini.
Tantangan terbesar menonton film dokumenter barangkali adalah melawan kebosanan. Jangan khawatir, film ini diproduksi oleh Fulwell 73.
Pernah menonton 'The Class of 92' atau 'In the Hands of the Gods'? Ya, rumah produksi Fulwell 73-lah yang menelurkan dua film tersebut.