Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
The History of Happiness dan Menggali Perasaan Zaman (I)
29 November 2017 11:57 WIB
·
waktu baca 8 menitDiperbarui 26 Maret 2022 21:51 WIB
Tulisan dari Mirza Ardi Wibawa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
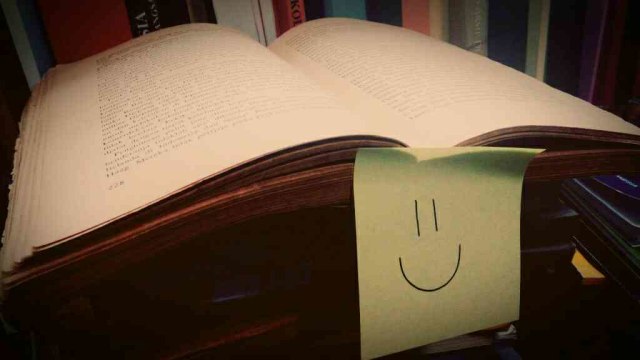
ADVERTISEMENT
Sekitar enam tahun lalu, kali terakhir saya membaca buku Richard Schoch berjudul ‘The Secret of Happiness’. Ada perasaan (selain nostalgia) untuk kembali membolak-balik halaman per halamannya, yakni rasa terusik untuk menginterpretasi ulang apa yang telah ditulis Schoch tentang ‘kebahagiaan’.
ADVERTISEMENT
Pemicu utama adalah judul yang dipakai Schoch: ‘The Secret of Happiness’. Kesan yang muncul tentang judul buku Schoch kiranya akan berisi tulisan klise motivator yang biasa berjejer sebagai 'best seller' di toko-toko buku. Namun, saya lebih setuju jika buku ini dimasukan dalam rak filsafat, atau sejarah, karena yang ditawarkan Schoch adalah ide-ide tentang kebahagiaan yang pernah dipikirkan manusia sejak masa Yunani Klasik hingga era Modern. Oleh karena itu pula, saya tergelitik untuk mengawali judul artikel ini dengan ‘The History of Happiness’ karena berkaitan dengan usaha manusia menguak rahasia kebahagiaan dalam lintas zaman.

Mari kita berangkat pada pemikiran bahwa kebahagiaan merupakan aset yang menuntut pemeliharaan seumur hidup dan tidak bisa dilepaskan dari seluruh aspek kehidupan manusia. Beberapa filsuf dan ilmuwan sosial -dari yang serius atau sekadar ‘iseng’- masih gemar berdisuksi soal ini. Namun karena kerumitannya, definisi tentang kebahagiaan bisa dipadatkan hanya menjadi satu kalimat, yakni “perasaan enak atau senang yang subyektif”.
ADVERTISEMENT
Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa menambahkan satu kata sifat lagi, yakni tenteram/damai. Kebahagiaan dalam filosofi barat juga sering digunakan untuk menggambarkan , 'kesejahteraan', ‘kehidupan yang baik’ atau ‘good life’, sementara Aristotles mengartikan kebahagiaan bukan hanya ‘keadaan’ atau ‘ekspresi emosional’, melainkan sebagai ‘tindakan’ (well-being dan doing well).
Kita simpan dulu pecahan puzzle di atas, karena apapun definisi yang sukar dilukis ini, kebahagiaan tetaplah dasar kebutuhan manusia. Sebagian lagi menganggap alasan manusia untuk tetap hidup.
Karena kebahagiaan adalah kebutuhan, maka 'generating happiness' menjadi simbol industrialisasi abad ke-21. Misal dengan iklan-iklan yang menampilkan kebahagiaan adalah komoditas mewah, terstandar dan bisa dibeli setelah mencapai kemakmuran finansial: "Minumlah pil, hilangkan kepedihan; lakukan Yoga, dapatkan ketenangan; sewalah seorang instruktur, raih kehidupan yang baik." Kata Schoch dalam bukunya.
ADVERTISEMENT
Kita masih bisa memperpanjang daftar tersebut dengan melihat perkembangan bisnis di sektor hiburan. Satu sisi kebutuhan hiburan akan berkembang diiringi dengan kesejahteraan ekonomi, namun apakah kita hanya memuaskan hasrat dan mengalihkan kepedihan yang bersembunyi di balik kesenangan?
Jeremy Bentham, filsafat hukum Inggris abad ke-18 sudah jauh-jauh waktu berpendapat bahwa kita bisa mengukur kebahagiaan dengan cara memaksimalkan kepuasan dan meminimalkan kepedihan. Maka pertanyaannya kita pertegas: Dengan cara-cara demikian, apakah kita benar-benar menikmati kebahagiaan? Dan benar-benar mengabaikan rasa penderitaan?

Schoch pada bagian awal sudah lebih dulu mengutarakan keresahannya. Benarkah gambaran masyarakat saat ini akan semakin memudarkan jalinan kontak dengan tradisi-tradisi lama yang kaya dengan ide-ide tentang kebahagiaan? Di era postmodern yang semakin luwes nilai dan mempertentangkan narasi besar, makna kebahagiaan memang terasa kian tipis dan lemah. Mempertanyakan ‘apa itu kebahagiaan sejati?’ tidak lebih penting dari menimbang ‘seberapa bahagia kita sekarang?’.
Namun, profesor sejarah kebudayaan ini, tetap memposisikan bukunya sebagai alternatif, karena bagaimanapun jalan yang dicapai, ‘gerbang kebahagiaan’ tetaplah subjektif.
ADVERTISEMENT
Ia juga secara terang-terangan mengatakan, berbagai ulasan mengenai macam-macam tradisi dan agama dalam buku ini bukan bertujuan untuk pengalihan (pindah keyakinan), melainkan pencerahan. Baginya, ide tentang kebahagiaan sama seperti ide-ide hebat lain, tidak peduli dari mana asalnya, karena mengalir dari pemikiran yang terbiasa dengan hal-hal universal dan terpacu oleh perhatian mendasar tentang eksistensi manusia.
Schoch menambahkan, walaupun kita tidak dapat sepenuhnya memasuki keyakinan orang lain, kita masih tetap dapat belajar dari mereka, karena jika kita mengejar kebahagiaan dengan terlalu picik, maka kita akan semakin jauh dari sesuatu yang bernilai. Kita pun bisa belajar dari pemikiran Bentham yang menganggap sumber kebahagiaan adalah dengan menjadi ‘hedonis’ (hedone dalam Bahasa Yunani kuno berarti ‘kepuasan’).
ADVERTISEMENT
Bentham menulis sebuah karya yurispundensi berjulul 'An Introduction to the Principles of Morals and Legislation' yang terbit tahun 1791. Judul tersebut menyesatkan, kata Schoch, karena sebagian besar karya setebal 300 halaman itu membicarakan bagaimana mendapatkan kebahagiaan melalui kepuasan yang rasional.
Bentham menyebut aspek-aspek kepuasan dengan istilah ‘utility’ (kegunaan), bukannya ‘satisfaction’ (kepuasan). Oleh karena kebahagiaan itu bisa diukur, maka Bentham menciptakan sebuah formula, yaitu ‘kalkulus kebahagiaan’ (felicific calculus). Intinya, untuk mengukur seberapa bahagia seseorang, dibuatlah sebuah rumus persamaan, yakni: ‘kebahagiaan = kepuasan - kepedihan’.
Selain itu, perlu juga menentukan skala dan mempertimbangkan beberapa variabel (seperti intensitas dan durasi tindakan). Kita bisa mulai dengan memikirkan hal yang ingin kita sebut bahagia, lalu kita menghitung bagian mana saja yang mendatangkan kepuasan dan kepedihan. Jika hasilnya lebih dari nol, maka kita bahagia, jika sebaliknya, kita menderita.
ADVERTISEMENT
Ukuran tersebut barangkali bisa dipraktikan pada lingkup individu, lantas bagaimana jika skalanya diperluas menjadi kebahagiaan secara komunal? Ini mungkin jadi kelemahan dari pendapat Bentham sendiri, bahwa akurasi kalkulus kebahagiaannya tidak bisa digunakan secara efektif dan fleksibel di masyarakat, namun bagi Bentham semakin banyak kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu tindakan, semakin disukailah tindakan itu.
Berbeda dengan Bentham, kepuasan yang hanya bergantung pada kuantitas, disebut John Stuart Mill sebagai pemikiran yang ‘konyol’. Sebagai penerus utilitarianisme, Mill mengkritik bahwa ada sesuatu yang lebih diinginkan manusia dari sekadar mencicipi masakan lezat, seks, dan kepuasan sensual lainnya.
Anggap saja kepuasan yang (menurut Mill) lebih tinggi ini membutuhkan kemampuan intelektual dan intesitas dalam mecapainya, misalkan makna (meaning), alasan (reason), imajinasi, sentimen moral dan lain-lain.
ADVERTISEMENT
Dengan begitu kita bisa melihat perbedaan seseorang dalam memilih kebahagiaan, dilihat dari cara memenuhi selera kepuasannya melalui substansi dan kualitas. Kita pasti akan dapat kesan yang berbeda ketika membaca satu novel penuh dibanding dengan membaca potongannya saja di media sosial; atau kesenangan saat menonton film di bioskop dengan hanya memutarnya di laptop.
Pemikiran tersebut bisa jadi pertimbangan dalam memilih kepuasan kita saat ini yang segalanya bisa digapai dengan gawai, sementara kpuasan yang memberi kesan dalam dan bertahan lama adalah yang dibubuhi nilai-nilai. Indera kita hanya mampu merespon kepuasan sensual dari gejala fisik, sementara yang menjadikan hal-hal tersebut lebih berharga, adalah nilai yang ada di dalam pikiran kita untuk memaknainya.
ADVERTISEMENT
Berbeda bagi para pemikir (terutama di masa lalu). Nilai dan segala hal yang berkaitan dengan ide, gagasan, ilmu pengetahuan, adalah prioritas hasratnya.
Akan tetapi, karena keterbatasan manusia dalam proses berpikir, ada kala hasrat intelektual tidak mampu lagi mengisi tabula ‘kebahagiaan’ mereka. Hal tersebut bisa dianggap sebagai ‘krisis jiwa’, dan untuk mencari jalan keluar, mereka meretas ke dunia hiper-rasional, bertransendensi melampaui akal, dan menuju alam pikiran spiritual.
Kita bisa mengambil beberapa contoh, misalkan Al-Ghazali, intelektual muslim dari masa keemasan Islam abad ke-11. Pada saat reputasinya di dunia akademis sedang memuncak, ia justru merenungkan bahwa pemikiran rasional saja tidak dapat mengungkap kebenaran terakhir yang dicari, utamanya tentang segala sesuatu yang tidak dapat diabstraksi pikiran. Sehingga ia memutuskan untuk mencari pengetahuan yang melampaui keraguan dan kebenaran rasio, dengan memilih jalan sufisme.
ADVERTISEMENT
Jalan tersebut ditulis dalam satu kumpulan karyanya berjudul ‘Kimiya-i-Sa’adat’ atau Kimia Kebahagiaan. Inti yang bisa dipelajari dari perjalanan sufisme Al-Ghazali dalam karya tersebut adalah dengan mencapai kesadaran terhadap hal-hal mistis yang lebih tinggi, dapat memfokuskan kita untuk hidup pada kejujuran dan ketenangan, bahwa di atas segala masalah dunia ada persoalan yang hanya bisa dipecahkan dengan melampaui rasio kita.
Penjelasan Bentham, Mill dan Al Ghazali bukan untuk menunjukan bahwa ada hierarki dalam mencapai kebahagiaan. Sebaliknya, benang merah ketiga ide mereka memudahkan pencarian makna kebahagiaan.
Berawal dari memenuhi kepuasan sensual melalui hal-hal yang kita anggap mendatangkan kesenangan fisik. Lalu dengan kemampuan intelektual, kita merekonstruksi moral, sehingga fondasi moral untuk memaknai kepuasan tersebut menambah nilai kebahagiaan.
ADVERTISEMENT
Pada akhirnya, kualitas kebahagiaan yang kita kejar akan membawa kita pada dua ‘gerbang kebahagiaan’, yakni ‘ketamakan’ (greed) atau ‘kebijaksanaan’ (wisdom).
Tentu kita tidak bisa membuat penghakiman karena sifat manusia dinamis. Seseorang yang dianggap tamak, bisa menjadi bijak hanya dalam sekian waktu (berlaku sebaliknya). Hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan menjadi tamak karena ketidakmampuan untuk memaknai kebahagiaan. Keadaan tersebut akan terasa menyakitkan bagi dirinya dan berpotensi membawa kerusakan untuk orang lain.
Barangkali karena itulah, Al-Ghazali atau para Guru di India dan Tibet lebih terpuaskan mencari kebahagiaan sejati dengan ketenangan jiwa. Beberapa cara didapat melalui sufisme, meditasi, atau (mungkin) Yoga.

Kebanyakan kita saat ini memahami dan melakukan Yoga untuk melengkapi gerakan fitness dengan mengatur pernapasan dan olah tubuh. Padahal tujuan orisinil Yoga adalah mencapai sebuah gebrakan kesadaran, pemusatan pikiran pada satu titik sehingga kita dapat mengontrol sepenuhnya alam kesadaran dan bawah sadar. Menemukan identitas dengan melampaui kesadaran diri adalah salah satu jalan yang digunakan Yoga demi mencapai kebahagiaan.
ADVERTISEMENT
Begitu banyak definisi dan begitu banyak cara untuk mencapai kebahagiaan. Kita bisa bilang bahwa kebahagiaan tidak hanya representasi kondisi pemuasan diri, namun juga bisa dirasa dengan kesadaran, atau dilihat dari perilaku dan tindakan.
Pecahan puzzle tentang kebahagiaan masih berserak dan hanya bisa disusun oleh kita sendiri. Buat apa kita menjadi bahagia kalau mentah-mentah meniru dan tanpa kesadaran mengikuti cara orang lain? Kita bisa meraih kebahagiaan sendiri; dari yang sederhana hingga melampaui angan; menjadi tamak atau bijaksana. Lalu muncul pertanyaan, ‘setelah bahagia lalu apa?’ Pertanyaan ini menantang saya untuk mencari kembali ‘sumur kebahagiaan’, dan lagi-lagi saya akan mencarinya di sebuah ‘kotak waktu’, yang berisi ‘perasaan zaman’.

