Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Resensi Buku : Filantropi Islam ; Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara
23 Desember 2020 9:25 WIB
Tulisan dari Nana Sudiana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
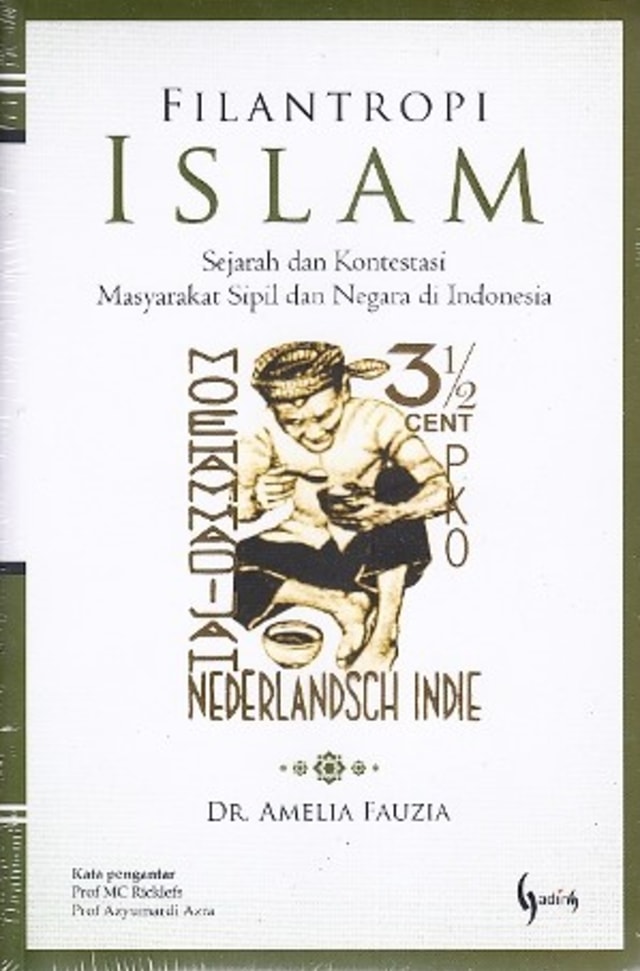
ADVERTISEMENT
Judul : Filantropi Islam ; Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia
ADVERTISEMENT
Penulis : Dr. Amelia Fauzia
Editor : Farid Wajdi dan Amirul Hasan
Penerbit : Gading Publishing, Mei 2016 Tebal: 375 halaman
Filantropi Islam semakin memiliki posisi penting, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang berimplikasi bukan hanya pada ancaman soal kesehatan, namun juga mengancam ekonomi masyarakat. Filantropi Islam adalah wujud kedermawanan yang dalam praktiknya, perilaku ini menjadi tindakan nyata untuk menolong dan membantu sesama manusia tanpa pamrih. Sikap ini semata-mata didorong oleh nilai-nilai luhur kemanusiaan. Wujud Filantropi Islam bisa berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam, sedangkan infak, sedekah dan wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia dan telah diamalkan secara luas dalam praktik kehidupan umat Islam sejak awal.
ADVERTISEMENT
Ditengah semakin pentingnya filantropi Islam, kajian serius tentang bidang ini ternyata masih sangat terbatas. Begitu pula para akademisi yang secara sungguh-sungguh mengkaji dan meneliti soal perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Di tengah kekosongan pengkaji dan peneliti ahli soal filantropi Islam, hadir salah satunya adalah Dr. Amelia Fauzia (kini telah bergelar Profesor) yang secara intens melakukan kajian dan penelitian soal filantropi Islam. Selain sebagai guru besar di UIN Jakarta, beliau tercatat sebagai fellowship researcher pada beberapa perguruan tinggi di luar negeri antara lain di UNSW Australia dan National University of Singapure (NUS). Pada tahun 2012 beliau mendirikan Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta dan menjadi Direkturnya hingga saat ini. Dalam catatan Google Scholar ada 54 karya tulis Amelia dalam bentuk paper, jurnal maupun buku yang telah dipublikasikan dan Sebagian besarnya soal Filantropi.
ADVERTISEMENT
Buku Filantropi Islam ; Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia ini semula merupakan disertasi penulisnya di Univeritas Melbourne. Pada awalnya buku ini berjudul Faith and the State A History of Islamic Philantropy in Indonesia yang diterbitkan Leiden and Boston, Brill, tahun 2013. Buku ini menjadi sangat penting bagi kajian filantropi Islam karena menyajikan penelusuran historis komprehensif mengenai perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Selain bagi pengkaji dan peneliti filantropi, buku ini juga menjadi rujukan penting para aktivis filantropi, amil zakat, hingga mahasiswa yang ingin memperluas wawasan sejarah dan perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Dalam buku ini, kita disuguhkan ulasan perkembangan filantropi Islam di Indonesia sejak awal abad ketiga belas hingga paska Orde Baru. Dari kajian awal yang dimulai dari abad Kesembilan Belas, kita akan disuguhkan bagaimana awal mulanya tahap Islamisasi dan perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Selanjutnya kita akan sampai pada fakta-fakta yang dipraktikan umat Islam dalam mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf secara berkesinambungan hingga berakhirnya Orde Baru dan berganti Orde Reformasi.
ADVERTISEMENT
Buku ini terbagi dalam 3 bagian yang didalamnya tercakup 7 bab. Bagian pertama berisi bab Pertama yang menguraikan filantropi dalam tradisi Islam dan bab Kedua soal Islamisasi dan praktik filantropi pada abad Ketiga Belas hingga ke Sembilan Belas. Bagian Kedua terdiri dari Dua bab, yaitu bab Tiga berisi tentang filantropi Islam masa kolonial dan bab Keempat soal Muhammadiyah dan filantropi modern sebelum kemerdekaan. Adapun bagian Ketiga terdiri dari bab Kelima sampai bab Tujuh. Bab Lima menjelaskan tentang organisasi filantropi berbasis negara dan berbasis komunitas paska kemerdekaan. Bab Enam bercerita soal gerakan filantropi paska orde baru ; quo vadis?. Dan bab Tujuh berisi kesimpulan : filantropi dan masyarakat sipil muslim.
ADVERTISEMENT
Bagian Pertama buku ini membahas awal bagaimana dimulainya proses islamisasi di bumi Nusantara, tepatnya mulai abad ketiga belas. Pada periode ini penulis mengelaborasi sejarah dan praktek filantropi pada masa awal kerajaan-kerajaan Islam hingga abad ke sembilan belas. Pada periode pra-modern, kelompok masyarakat independent seperti ulama, pengikut tarekat, lembaga wakaf, masjid serta perguruan tinggi telah berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim di jazirah Arab dan wilayah Islam di luar Nusantara. Praktik filantropi pada periode awal di Nusantara memperlihatkan adanya kesamaan dengan kondisi perkembangan filantropi di dunia Islam. Ketika kekuatan politik kerajaan-kerajaan besar Islam mengalami kemunduran (sebelum masa kolonialisme berlangsung), kekuasaan politik berangsur berpindah di tangan pemimpin lokal, termasuk pemimpin agama (hal.31).
Pada perkembangannya, filantropi Islam diperkenalkan di kepulauan Nusantara bertepatan dengan masuknya Islam. Dengan kondisi ini, perkembangan filantropi Islam seiring dengan pesatnya pengaruh Islam. Sejak awal perkembangannya, zakat, infak, sedekah dan wakaf dipraktikkan dan digunakan tidak hanya sebagai kewajiban agama, namun juga untuk tujuan-tujuan sosial ekonomi dan politik. Sedikit berbeda, zakat dipraktikkan dalam dua bentuk: ada yang dipraktikkan sebagai pajak keagamaan yang dipungut oleh negara (dan menjadi pajak non- keagamaan), dan ada yang dipraktikkan sebagai sumbangan sukarela yang dilakukan oleh umat Islam tanpa melibatkan negara. Hal ini tidak berbeda dengan praktik serupa di wilayah lain di dunia Islam.
ADVERTISEMENT
Namun para penguasa dengan orientasi keagamaan yang ortodoks cenderung menggunakan institusi zakat sebagai alat penguasa untuk memaksa. Namun demikian, mayoritas penguasa, tidak memberlakukan zakat sebagai peraturan penguasa, tetapi membiarkannya dipraktikkan secara sukarela. Di kesultanan Banjar, penguasa memberlakukan pajak--bukan zakat--untuk meningkatkan penerimaan negara yang lebih besar. Namun demikian, dalam situasi apapun, zakat sangat dianjurkan. Para penguasa saleh, yang membayar zakat dan fitrah serta memberikan wakaf, telah mendorong praktik filantropi Islam di Indonesia. Kita bisa meyakini bahwa pengumpulan zakat oleh negara tidak menghilangkan tradisi pemberian zakat dan fitrah secara pribadi, kendati tidak ada dokumennya di abad-abad awal perkembangan Islam itu. Di periode ini, filantropi Islam telah dipraktikkan oleh masyarakat Muslim lebih secara pribadi dan sukarela, bukan sebagai kewajiban kepada negara (hal.99).
ADVERTISEMENT
Pada bagian Kedua, buku ini mengelaborasi tentang filantropi Islam di bawah pemerintahan non-muslim. Periode ini adalah masa kolonialisme Belanda di Nusantara. Kita tahu bahwa ketika pada periode kerajaan Islam keberadaan masyarakat sipil beserta gerakan filantropi-nya sudah mulai terlihat. Walaupun aktivitas ini belum merata dan luas sifatnya, tetap saja menunjukan adanya geliat pertumbuhan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana masyarakat sipil bisa terus tumbuh dan berkembang saat berada pada periode pemerintahan kolonial yang dikenal represif terhadap gerakan-gerakan Islam.
Dalam bagian ini diungkap, bahwa di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang represif, masyarakat sipil Muslim justru menguat dan berkembang modern. Hal ini karena Pertama, sifat lembaga filantropi itu sendiri, di mana filantropi tetap menjadi faktor penting. Kedua, karena politik pemerintah Belanda yang tidak campur tangan terhadap urusan agama dan juga masalah filantropi. Di situasi ketika itu urusan filantropi menjadi domain personal (privatisasi). Zakat dan filantropi secara umum mengalami transformasi menjadi bersifat individu dan terpisah dari pengelolaan negara. Pemerintah kolonial ketika itu, tak mengurusi soal-soal keagamaan dan filantropi ini.
ADVERTISEMENT
Pada akhirnya, pesantren, masjid, dan berbagai organisasi Islam modern tumbuh dan berperan menjadi pusat-pusat kedermawanan masyarakat dan menjadi bukti atas munculnya masyarakat sipil--atau lebih spesifik-masyarakat sipil Muslim. Ada dua tipe tradisi kedermawanan yang telah menciptakan dua model masyarakat sipil yang berbeda. Pertama, tradisi saling berbagi (reciprocity) di lingkungan pedesaan yang berpusat di pesantren, masjid, dan ulama tradisional. Kedua, tradisi kedermawanan berbasis institusi modern perkotaan yang berpusat di lingkungan organisasi Islam modernis yang dimotori oleh Muhammadiyah. Kedua tradisi ini sama-sama memiliki sifat yang independen dari negara (walaupun tidak sepenuhnya) dan bertujuan mengislamkan masyarakat--bukan mengislamkan negara.
Dua karakter masyarakat sipil ini muncul sebagai respon terhadap situasi sosial dan politik di bawah pemerintah non-Muslim, di mana ketertarikan atau kecenderungan negara dan masyarakat dalam hal agama ketika itu bisa terpisah. Masyarakat Muslim memiliki semangat yang tinggi terhadap agama, namun negara sekuler berupaya menempatkan semangat itu menjadi urusan pribadi, bukan urusan negara. Namun pemisahan antara urusan negara (public) dan urusan pribadi (private), tidak dapat menghalangi ekspresi dan aktivitas keagamaan untuk tetap berada di bawah urusan pribadi, tapi merambah ke wilayah publik. Akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh juga muncul wacana baru seperti 'independensi', 'uang publik', dan aktivitas kedermawanan pribadi", sejalan dengan pertumbuhan praktik filantropi Islam di Nusantara. Kesimpulan pada periode ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil bisa tumbuh dengan baik di bawah pemerintahan negara sckuler, dengan syarat negara tidak turut campur dalam urusan urusan agama, termasuk urusan filantropi Islam (hal.103).
ADVERTISEMENT
Adapun pada bagian ketiga, buku ini membahas filantropi Islam pasca kemerdekaan Indonesia, masa orde lama, masa orde baru, hingga periode pasca reformasi. Dimana pada masa ini merupakan masa pergolakan politik dan ekonomi. Begitupula mulai ada pemaknaan ataupun penafsiran ulang terhadap zakat itu sendiri pada masa pasca reformasi. Pada bagian ketiga ini juga dibahas praktik filantropi Islam sejak akhir masa penjajahan Belanda (1942) hingga akhir periode rezim Orde Baru (1998), bahkan hingga melebihi batas tahun 1998. Dalam pembahasan yang ada, dijelaskan bagaimana keterlibatan negara dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam filantropi modern, terutama dalam pembentukan organisasi zakat.
Perhatian negara kepada filantropi Islam dimulai ketika pemerintahan Belanda digantikan oleh pemerintahan nasional yang didominasi oleh Muslim. Yang menarik, dalam bab ini kita menemukan fakta bahwa keterlibatan negara dalam filantropi Islam mendapat perlawanan dari kelompok organisasi masyarakat sipil Muslim, yang menolak lembaga filantropi berbasis negara dan kemudian membentuk organisasi filantropi berbasis masyarakat/komunitas (hal.183).
ADVERTISEMENT
Dalam periode inilah menandai awal kompetisi antara masyarakat sipil dan negara dalam mengendalikan praktik filantropi, terutama selama Orde Baru. Secara umum, ada kecenderungan yang meningkat dalam kegiatan filantropi Islam pada era pasca-kemerdekaan Indonesia. Kecenderungan ini dibangun oleh dua faktor utama, yaitu kondisi politik Indonesia dan kesadaran identitas Muslim. Situasi politik yang berdampak signifikan terhadap perkembangan filantropi Islam. Dalam kesimpulan periode pasca Orde Baru menyaksikan sebuah gerakan sosial filantropi yang mendukung oleh Muslim modernis dan revivalis. Gerakan ini telah didukung oleh kelas menengah Muslim terdidik yang mendirikan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan mendukung keterlibatan negara dalam filantropi.
Pada masa Reformasi, negara, yang pada mulanya sangat lemah, berhasil mendapatkan daya tawar dan menjadi aktor aktif dalam amandemen UU Pengelolaan Zakat. DPR akhirnya meloloskan RUU yang dibuat oleh Kementerian Agama. Dalam kasus ini, pada tahun 2011, negara telah memenangkan kontestasi hukum melawan masyarakat sipil. Begitu pula hasil judicial review yang diusulkan oleh masyarakat sipil (disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2012 dan baru ditetapkan hasilnya pada 31 Oktober 2013) masih lebih banyak memihak pada negara walaupun sebagian gugatan masyarakat sipil dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah satu dekade reformasi, DPR masih lemah. Perkembangan paska Orde Baru menunjukan kontestasi antara kelompok yang mencoba untuk melibatkan negara dalam mendukung filantropi Islam dan kelompok yang menentang keterlibatan negara masih ada. Dan kontestasi ini akan semakin kuat, baik secara tertutup atau diam-diam maupun secara terbuka (hal.269).
ADVERTISEMENT
Secara umum, kontestasi yang terjadi berpola pada ke “kiri” dan “kanan”. Ketika negara lemah, filantropi berkembang kuat. Sebaliknya, Ketika negara kuat, masyarakat sipil menjadi lemah. Walau begitu, mereka masih mampu menemukan cara untuk mengelola filantropi Islam demi perbaikan masyarakat dan melakukan perubahan social (hal.271). Namun ternyata ada pengecualian, yakni ketika masa Kolonial. Ketika itu negara kuat dan filantropi juga kuat. Hal ini karena pemerintah kolonial memiliki kebijakan tidak campur tangan dalam urusan agama, termasuk filantropi (hal.271).
Masukan dan Saran
Sejumlah pernyataan yang mengarah pada kesimpulan di buku ini, yang mengatakan bahwa “negara lemah filantropi akan kuat, negara kuat filantropi jadi lemah”, memang masih harus terus diuji di masa depan. Faktanya di dunia filantropi Islam sendiri hal ini cukup kompleks. Ada kerumitan-kerumitan yang ada di sejumlah organisasi filantropi Islam. Bila negara nantinya lemah, belum tentu filantropi akan menguat.
ADVERTISEMENT
Kesimpulan soal keseimbangan ini berisiko, seolah negara dan masyarakat sipil Islam tak bisa berdampingan secara damai, termasuk dalam urusan filantropi. Bukankah idealnya negara yang kuat, harus juga didukung oleh gerakan sipil yang kuat, sehingga organisasi filantropi Islam bisa lebih bekerja dengan baik dan dapat dukungan dari negara.
Buku ini memang tidak menjelaskan pola ideal keseimbangan yang ada, namun justru ini menjadi PR banyak pihak untuk mendorong titik temu yang akan menguntungkan kekuatan sipil Islam dan juga negara agar keduanya tumbuh, kuat dan bermanfaat besar bagi umat dan bangsa. Keseimbangan dalam supply and demand filantropi Islam harus didorong semua pihak agar ujungnya bermuara pada terciptanya kesejahteraan lahir dan batin. Maju masyarakatnya dan negara juga kuat.
ADVERTISEMENT
Penulis buku sebagian besarnya fokus pada sisi kesejarahan filantropi Islam di Indonesia, yang dimulai dari abad ketiga belas hingga orde reformasi terjadi. Juga pada rangkaian gambaran praktik-praktik filantropi yang cukup panjang membentang dalam sejarah kepulauan Nusantara. Kiranya alangkah sangat lebih baik apabila penulis buku menyampaikan sejumlah usulan atau gagasan positif untuk menemukan solusi agar terjadi keseimbangan yang baik bagi masa depan filantropi Islam di Indonesia. Bukankah kita semua berharap, bahwa kalau sama-sama untuk memperbaiki dan membuat rakyat sejahtera, pasti akan ada jalan tengah yang akan menyatukan posisi masing-masing sehingga bisa bersama-sama berbuat yang terbaik untuk umat dan bangsa. Semoga [].

