Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Lupakan Motivator, Sambutlah Demotivator
25 Juli 2017 16:57 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
Tulisan dari Eddward S Kennedy tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
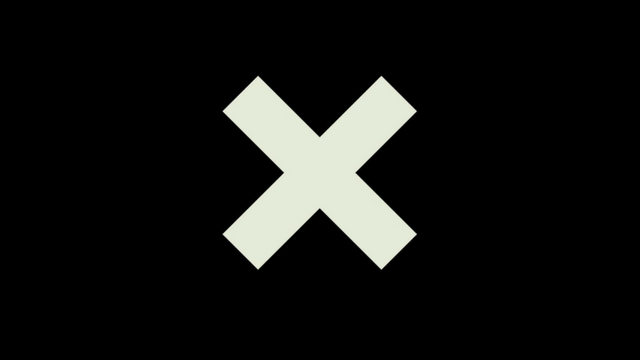
ADVERTISEMENT
Sebenarnya sudah tidak terlalu penting lagi untuk mengungkit kasus Mario Teguh dengan anaknya. Toh, walau bagaimanapun, kasus tersebut sudah terlanjur menghempaskan (atau justru menguatkan?) si motivator ke liang gelap kehidupannya. Lalu bagaimana hubungan keduanya kelak? Halah, persetan.
ADVERTISEMENT
Mario Teguh, Bung dan Nona sekalian, hanyalah satu dari sekian berjibun (bisnis) motivator yang muncul dari suprastruktur kapitalisme modern. Untuk mendapatkan penjelasan soal ini, Anda bisa merunutnya mula-mula lewat Althusser, misalnya, tentang bagaimana hegemoni sebagai ketundukan kelas pekerja atas kelas borjuis.
Lihat pula bagaimana postulat Gramsci atas mekanisme kontrol proses kerja yang mewujud dalam aturan tingkah laku praktis dan perilaku moral. Lainnya lagi: empat elemen dalam skema determinasi analisis kelas Erik Olin Wright.
Untuk membuatnya menjadi lebih saintifik, Anda juga bisa pula mencari data statistik bagaimana perubahan perilaku moral para die hard Mario Teguh antara pra & pasca mendengar ocehannya dalam menghadapi kehidupan modern. Apakah lebih baik, buruk, biasa saja, tak berubah, atau bagaimana?
ADVERTISEMENT
Ada banyak rujukan komperhensif, tapi tak usahlah kita bahas panjang lebar yang njilmet ini karena Anda harus mengasihani otak Anda sendiri. Saya kira, ada hal menarik lain yang dapat kita urai pasca kemunculan isu soal Mario Teguh dan anaknya yang dibuang itu.
Barangkali kelak malah bisa menjadi bisnis/profesi baru: demotivator.
Anda tahu, demotivator sejatinya tak berbeda jauh dengan motivator. Tentu saja, perbedaannya adalah pada pesan yang disampaikan. Jika motivator menghipnotis Anda untuk berbuat "positif" demi harapan hidup yang lebih baik, demotivator menjungkirbalikkan itu semua.
Contoh: Anda tak perlu kerja banting tulang-peras keringat-hingga berdarah-darah hanya untuk memiliki sebuah mobil mewah yang sebetulnya tak memiliki nilai guna selain menaikkan gengsi sosial di masyarakat.
ADVERTISEMENT
Toh, hidup pada akhirnya hanyalah soal menunggu ajal. Maka biarkan saja semua tanpa kontrol. Bekerjalah semaunya. Tak perlu taat-taat amat kepada bos atau perusahaan, merek baju atau segelas kopi mahal. Hiduplah semaunya, semerdekanya.
Yah, mirip-mirip pesan motivasional anarko gitu deh...
Dengan melihat sejarah, sejatinya ada beberapa rujukan tokoh yang, disadari atau tidak, telah memulai karier sebagai demotivator ini jauh-jauh hari.
Paul Lafargue, misalnya. Melalui kitab propagandanya yang berjudul "Hak untuk Malas", ia telah memperingatkan orang-orang (dalam hal ini kelas pekerja) untuk lebih menambah kuantitas bercinta dan mabuk ketimbang jam kerja dan jumlah rekening.
Tyler Durden, tokoh fiksi di Fight Club rekaan Chuck Palahniuk, dengan ekstrim malah menganjurkan orang-orang agar berkelahi saja ketimbang jadi budak korporasi.
ADVERTISEMENT
Saya bahkan belum menyebut Ted Kaczynski dengan konsep anti-peradabannya (saya kira Palahniuk menarik referensinya dari Ted), Joker (Heath Ledger) lewat tautologi chaos-nya, Comedian di Watchmen melalui prinsip "this is all a joke"-nya, Nietzsche dan nihilismenya, atau Camus dan martil absurditasnya (jawaban terbaik hanyalah bunuh diri. Halo, Sisifus?).
Dan nama-nama ini tentu masih bisa diperpanjang: Alan Moore, Bukowski, Max Striner, atau Gordias.
Ketika hidup makin kesini tak berubah lebih baik dan bahkan menjadi lebih tragis karena ocehan motivasional, maka, sejujurnya, kemunculan para demotivator ini sesungguhnya sudah amat diperlukan. Terlebih sekarang zamannya generasi millenial yang konon tak peduli apa-apa itu, makin tepat pula untuk mendesak bisnis ini agar segera beredar di pasar.
ADVERTISEMENT
Nah, barangkali Anda tertarik, berikut saya berikan satu resep khusus untuk melatih diri menjadi demotivator. Hanya satu, dan itu mudah sekali: menjadi jujur.
Bagaimana menerapkannya? Ini malah lebih mudah lagi.
Jika ada, misalnya, teman Anda yang curhat selalu tak pede mendekati gebetan karena kendala fisik dan ditambah pula tak punya kebanggaan secara finansial, katakan saja sejujurnya: "ha piye, raimu elek sih. Miskin meneh..." (Ya, gimana, mukamu jelek, sih. Miskin pula).
Dia mungkin marah kepada Anda, frustasi, depresi, atau justru tak peduli. Apapun efeknya, Anda tak perlu mempedulikannya. Toh, sebagaimana prinsip motivator, posisi Anda hanyalah sebagai "the messenger", "penyampai pesan".
Jangan pula merasa bersalah karena Anda telah jujur. Sebab kejujuran itu, kawanku, adalah sebaik-baiknya perbuatan. Betul?
ADVERTISEMENT
Mari bayangkan betapa suci dan menggiurkannya profesi demotivator ini kelak. Sudahlah jujur, dibayar mahal pula!
Anda tak perlu melulu memasang wajah ramah kepada lawan bicara atau pasien Anda, tak perlu pula belagak peduli dengan masalahnya. Sekali lagi, Anda hanya perlu jujur. Demotivator adalah jawaban atas segala permasalahan hidup sesungguhnya. Lenyap sudah kepura-puraan, semua orang bisa tampil apa adanya.
Peradaban dengan kemunculan para demotivator handal, saya kira, akan tampak seperti film The Invention of Lying.
Dalam film jenius rekaan Ricky Gervais tersebut, dikisahkan semua orang berbicara jujur dan tak mengenal kebohongan. Keadaan tetap baik-baik saja, meski orang saling sinis dan apatis. Kericuhan justru terjadi ketika Mark, si tokoh utama, mulai berbohong.
ADVERTISEMENT
Dan makin tambah ricuh ketika ia membual soal kehidupan setelah mati.
Bagaimana, tertarik menjadi demotivator, Bung dan Nona?

