Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Konten dari Pengguna
Janji Palsu Demokrasi
18 Oktober 2021 16:44 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Rino Irlandi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
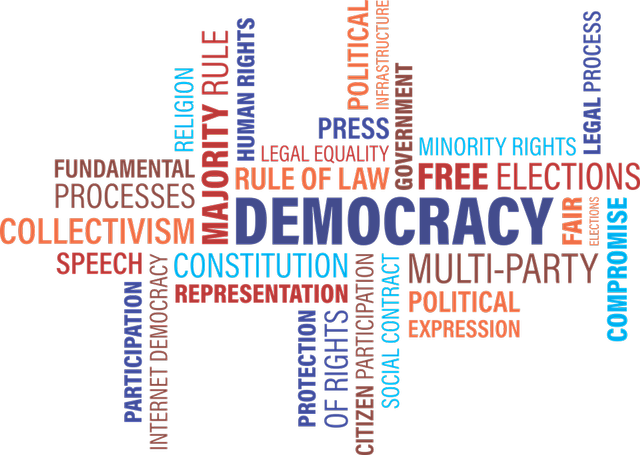
ADVERTISEMENT
Dalam sebuah serial tragicomedy berjudul "Waiting For Godot" sang penulis naskah, Samuel Beckett, menyajikan sebuah cerita yang cukup membuat penonton menggeleng-gelengkan kepala mereka. Serial ini menceritakan tentang sebuah ketidakpastian, penantian yang sia-sia dan harapan palsu.
Dua orang bernama Vladimir dan Estragon tengah menunggu Godot di sebuah pohon. Mereka berdua sengaja menunggu di sana karena hendak balas dendam pada Godot yang telah memukuli mereka berdua.
Lama menunggu di sana, mereka dihampiri oleh seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu datang membawa pesan Godot untuk mereka. dia berkata: "Godot tidak akan datang hari ini, tetapi besok dia pasti akan datang."
Esoknya, Vladimir dan Estragon kembali menunggu kedatangan Godot di pohon yang sama. Lagi-lagi, seorang anak laki-laki yang sama menyampaikan pesan yang sama dari Godot untuk mereka. Bahwa Godot tidak bisa datang hari ini, tetapi besok dia pasti akan datang.
Kejadian itu terus berulang pada hari-hari berikutnya. Vladimir dan Estragon setia menunggu karena harapan yang diberikan Godot melalui pesan anak laki-laki itu. Tetapi, dari hari ke hari yang dijanjikan tak pernah sekalipun batang hidung Godot kelihatan. Godot tidak pernah datang dan hanya memberikan harapan palsu.
Cerita karangan Samuel Beckett ini barangkali menjadi sebuah cerita yang menarik untuk diulas dan dikaitkan dengan upaya demokratisasi di negeri ini. Demokratisasi merupakan sebuah janji yang hendak diwujudkan pada era reformasi. Namun, hingga kini--23 tahun pasca reformasi--janji itu belum juga sepenuhnya ditepati.
Demokrasi selalu menjanjikan kebebasan berpendapat, pelibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan negara, hingga persamaan hak setiap warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Sayangnya, pada tataran praktik di negeri ini, janji-janji manis demokrasi seringkali bertolak belakang.
Misalnya, baru-baru ini aksi massa yang dilakukan mahasiswa di Tangerang harus berakhir tragis. Seorang mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat di depan Kantor Bupati Tangerang dibanting oleh seorang oknum polisi. Tindakan keji yang tidak seharusnya dilakukan kepada warga negara yang sedang menyampaikan pendapatnya di muka umum.
Kekerasan semacam itu bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2019 lalu, dua orang mahasiswa yang ikut dalam demonstrasi menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK di Kendari ditembak mati oleh oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, banyak demonstrasi-demonstrasi lain yang juga berujung pada tindakan kekerasan dan represif dari oknum pihak keamanan.
Padahal, di negara yang mengaku sebagai negara demokrasi seharusnya tidak boleh ada pengekangan terhadap hak kebebasan berpendapat. Apalagi, bentuk pengekangan itu berupa tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan dan nyawa warga negara.
Inikah demokrasi yang dijanjikan akan hidup di era reformasi itu?
Timsel KPU-Bawaslu baru saja dibentuk Pemerintah pada 11 Oktober kemarin. Tim ini bertugas melakukan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu yang akan menjabat pada tahun 2022-2027 nanti. Undang-Undang Pemilu mengamanatkan rangkaian proses seleksi harus dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Namun, pada tataran praktik, proses pembentukan timsel KPU-Bawaslu kali ini tidak menyediakan ruang bagi publik untuk terlibat. Keppres penetapannya tiba-tiba muncul tanpa ada waktu sanggah bagi publik untuk menilai, mengoreksi, dan menelusuri rekam jejak calon anggota timsel sebelum mereka terpilih.
Tidak adanya ruang bagi publik untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan negara juga terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Hal ini dibuktikan dengan: pertama, protes yang masif dari berbagai kalangan masyarakat. Dan, kedua, adanya permohonan uji formal dan materil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Inikah demokrasi yang dijanjikan akan hidup di era reformasi itu?
Belakangan ini, publik dikejutkan oleh berita diskon hukuman massal bagi para koruptor. Djoko Tjandra hukumannya disunat Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara. Jaksa Pinangki, yang awalnya dihukum 10 tahun penjara disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi hanya 4 tahun penjara.
Hukuman untuk koruptor secara umum juga tergolong ringan. Dalam catatan penelitian ICW, rata-rata besaran vonis (2020) bagi koruptor di tingkat Pengadilan Tipikor adalah 2 tahun 11 bulan. Di Pengadilan Tinggi (tingkat banding) rata-rata vonisnya adalah 3 tahun 6 bulan. Dan, di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung rata-rata vonisnya adalah 4 tahun 8 bulan.
Tentu tidak salah jika memperhatikan hak bagi para pelaku korupsi untuk mendapat pengurangan dan hukuman ringan. Namun, pada sisi lain, ada begitu banyak orang-orang "kecil" yang dihukum tidak setimpal dengan perbuatannya atas kejahatan yang "terpaksa" mereka lakukan.
Sebagai contoh, ada kasus Nenek Alma yang terjadi pada tahun 2009, kasus kakek Samirin yang terjadi pada awal tahun 2020, dan kasus yang dialami oleh Rica Maria, seorang Ibu Rumah Tangga yang mencuri demi tiga anaknya yang kelaparan pada masa-masa sulit pandemi COVID-19.
Lagi-lagi, inikah demokrasi yang dijanjikan akan hidup di era reformasi itu?
Berulang kali kita dijanjikan tentang negara demokratis di era reformasi ini. Di TV, media massa dan media sosial para elite politik sudah tidak terhitung berapa kali melontarkan janji-janji demokrasi. Namun, lagi-lagi, kejadian-kejadian seperti di atas terus berulang.
Mungkinkah demokrasi yang selama ini dijanjikan seroman dengan kisah tragis menanti Godot? Atau, cerita dari Samuel Beckett itu tidak cocok dengan impian kita semua tentang negara yang gemah ripah loh jinawi. Bahwa kita masih punya harapan untuk menjadi negara demokrasi "seutuhnya". Hanya saja, kegagalan-kegagalan yang kerap kita alami hanya butuh pendekatan perbaikan yang tepat. Semoga.
Rino Irlandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, anggota Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTN-SI)
ADVERTISEMENT

