Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Jejak Permulaan Politik Etis di Hindia Belanda
14 November 2022 17:19 WIB
Tulisan dari Rizki Aldi Cahyono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
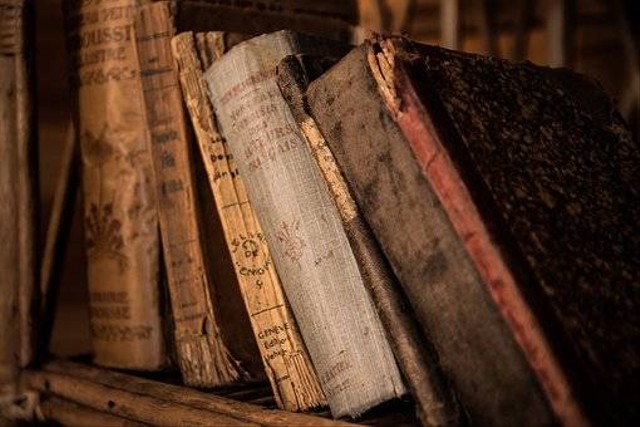
ADVERTISEMENT
KEHADIRAN POLITIK ETIS
Politik Etis, istilah yang sering digaungkan sebagai dasar pembentukan semangat pergerakan nasional. Diawali dari kemenangan partai liberal dalam pemilihan parlemen Belanda, yang mana mereka mendesak agar penyelenggaraan tanam paksa (culturestelsell) di negeri jajahan (Hindia Belanda) digantikan dengan kebijakan ekonomi liberal. Dalam ekonomi liberal pemerintah hanya bertugas sebagai pelindung warga, membangun sarana pendukung, dan mengatur tegaknya hukum. Sementara urusan perekonomian negara jajahan menjadi tanggung jawab penuh atas pihak swasta. Menurut pandangan kaum liberal, tanam paksa hanya akan menimbulkan eksploitasi berlebih atas material dan timbul kesengsaraan atas rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, politik ekonomi liberal juga mengatur mengenai status kepemilikan tanah dan tata cara kaum swasta dapat menyewa tanah tersebut sebagai bahan pengembangan usaha.
ADVERTISEMENT
Kebijakan Politik Etis tidak terlepaskan dari kecaman-kecaman terhadap pemerintahan Bangsa Belanda yang dilontarkan dalam novel “Max Havelar” tahun 1860. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai kemanusiaan dan keuntungan ekonomi serta dalam berbagai pengungkapan lainya mulai membuahkan hasil. Hingga suara Belanda untuk mengurangi penderitaan rakyat negeri jajahan pun banyak digaungkan. Selain novel karya Dowes Dekker (Multatuli), gaungan pengurangan penderitaan rakyat negeri jajahan juga disampaikan pada tulisan “Kontrak-Kontrak Gula” karya Frans de Puten. Akhir abad ke-XIX pemerintah kolonial berangkat ke Hindia Belanda dengan membawa pembaharuan atas isi novel itu di kepala mereka.
Sebagai tindak lanjut atas desakan parlemen Negeri Belanda, dibentuklah suatu Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengawasi keluar-masuknya keuangan negeri jajahan serta Undang-Undang Gula yang menyerahkan sepenuhnya atas monopoli tebu kepada pihak swasta, pada tahun 1864. Sementara Undang-Undang Agraria yang menjelaskan prinsip pembagian tanah dalam negeri jajahan ditandatangani pada tahun 1870. Dilanjutkan dengan Tahun 1871 Trakat Sumatera ditandatangani sebagai landasan yuridis pelaksanaan ekonomi liberal di negeri jajahan. Dalam trakat ini, Belanda diberikan kebebasan untuk memperluas daerah jajahan hingga negeri Aceh. Namun sebagai gantinya, Inggris harus diberikan hak untuk menerapkan investasi di Hindia Belanda dan mengganti ekonomi tanam paksa ke dalam ekonomi liberal.
ADVERTISEMENT
Kapitalisme swasta tidak hanya memainkan peran penting terhadap perekonomian negeri jajahan, juga sebagai dasar pengambilan keputusan atas ranah kebijakan negara kolonial Hindia Belanda. Industri Belanda melihat Hindia Belanda sebagai dasar potensial yang harus ditingkatkan standar kehidupannya. Revolusi keahlian tenaga kerja guna melancarkan kepentingan usaha kaum swasta mulai mendapatkan perhatian lebih pemerintah jajahan, tentu atas pertimbangan kaum swasta.
Seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Hindia-Belanda selama kurun waktu 1880-1897 menerbitkan artikel dengan judul “Een eereschuld” yang berarti “suatu utang kehormatan” dalam jurnal de Gids pada tahun 1899, beliau ialah C. Th. van Deventer (1857-1915). Dia mengatakan bahwa Negeri Belanda berhutang kepada negara jajahan Hindia-Belanda atas semua kekayaan yang telah diperas mereka. Utang ini hendaknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial. Tidak heran, jika ia adalah kampium politik Etis yang terkemuka serta menjadi penasehat pemerintah dan anggota parlemen.
ADVERTISEMENT
Ratu Wilhelmina (1890-1948) pada tahun 1901 yang mendengar kesengsaraan negeri jajahan akhirnya memerintahkan sutau penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa dan atas hasil penyelidikan itulah politik Etis kemudian disahkan secara resmi. Selang satu tahun kemudian, Alexander W. F. Idenburg ditunjuk sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan serta Gubernur Jenderal (1909-1916) mulai mempraktikan pemikiran-pemikiran politik etis. Dimana ada tiga prinsip yang dipercaya sebagai dasar kebijakan baru tersebut yakni pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Sementara dari segi finansial, pelaksanaan politik etis ternyata membutuhkan dana yang tidak murah. Oleh karenanya utang pemerintah kolonial yang mencapai 40 juta gulden diambil alih oleh Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran tanpa harus dibebani utang lagi. Politik Etis pun berjalan.
ADVERTISEMENT
PERANAN MAX HAVELAR DAN REALISASI MENENTANG KOLONIALISME
Tanggal 13 Oktober 1859, Edward Douwes Dekker seorang mantan pegawai Pemerintah Hindia Belanda ,menyelesaikan novel “Max Havelar” di Brussel. Pada penempatan awalnya di Sumatera Utara ia telah membela seorang kepala desa yang disiksa dan tanpa disadari dirinya berada di seberang ruang sidang dari atasnya. Atas pembelaan itu, ia dipindahkan ke Sumatera Barat di mana dia kembali memprotes pemerintah yang kemudian memicu benih konflik persiangan etnis. Dari Sumatera Barat beliau diberhentikan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melalui kantor Batavia. Namun selang beberapa waktu beliau dipanggil kembali atas karya-karya tulisnya dan ditempatkan di Lebak, Banten. Beberapa sumber menyatakan bahwa tatkala bekerja sebagai pegawai pemerintahan, ia sempat kecewa atas jalannya pemerintahan Lebak saat itu lantaran banyak terjadi praktik kesewenang-wenangan terhadap rakyat yang dimotori baik oleh pemerintah kolonial maupun aparat pemerintah pribumi setempat. Kekecewaan inilah yang kemudian membuatnya menulis surat kepada Gubernur Jenderal atas apa yang sebenarnya terjadi.
ADVERTISEMENT
Novel Max Havelar menceritakan tentang kehidupan sebenarnya yang terjadi di daerah Lebak, Banten atas kesewenangan pemerintah kolonial. Sang penulis bahkan menggambarkan kondisi di Kabupaten Lebak yang mengenaskan lantaran dicekik oleh penjajah Belanda dan ditambah paksaan oleh penguasa feudal pribumi yang kejam pada masa itu. (Film “Max Havelar”)
Angka tahun 1859 telah menggentarkan bumi Belanda khusunya seiring dengan terbitnya novel “Max Havelar” ini. Bahkan terdapat sebuah perumpamaan yang menyebut bahwa novel “Max Havelar” ini sebagai “Kabin Paman Tom” karena telah mendukung suatu perjuangan mewujudkan reformasi di Hindia Belanda layaknya pemberian amunisi kepada gerakan abolisionis di Amerika. Novel Max Havelar juga telah membantu gerakan kelompok kaum liberal yang bersemangat untuk mempu mempermalukan Pemerintah Negeri Belanda guna menciptakan gerakan sebagai apa yang kelak disebut “Politik Etis”.
ADVERTISEMENT
Multatuli memberikan paradigma baru atas praktik kolonialisme yang terjadi di negeri jajahan Hindia Belanda. Suatu pandangan baru yang mengantarkan penduduk Belanda terbuka pikirannya atas keadaan sesungguhnya di lapangan karena pada awalnya masyarakat Negeri Belanda berfikir bahwa praktik kolonialisme di negeri jajahan merupakan suatu kenormalan belaka. Ubaidillah Muchtar, seorang peneliti bahkan menyebut bahwa kehadiran ‘Max Havelar’ merupakan suatu bom yang menyadarkan kebobrokan kolonialisme Belanda. Terbitnya novel ini merupakan satu penyebab terjadinya ‘gonjang-ganjing’ di Belanda dan Eropa yang mengkritik perlakuan pemerintah Hindia Belanda atas rakyat jajahannya.
Dampaknya, kebijakan balas budi atas apa yang telah dikeruk pemerintah kolonial dari daerah jajahan disuarakan. Inilah yang menjadikan dasar dari adanya kebijakan politik Etis dengan tiga dasar program utama yakni edukasi, irigasi, dan perpindahan penduduk.
ADVERTISEMENT
Singkatnya, pada awal abad ke-20 sejumlah kecil orang Indonesia terutama anak-anak penguasa tradisional mulai merasakan dampak atas kebijakan politik Etis tersebut. Salah satunya yakni H. Agus Salim yang bersama dengan orang Indonesia lain yang terdidik Bahasa Belanda memupuk gerakan emansipasi dan kebebasan hingga membawa revolusi besar-besaran di angka tahun 1940-an. Tokoh lain yang menerima manfaat dari kebijakan politik etis ini ialah Hos Tjokroaminoto, Wahidin S yang kelak mewariskan dasar pemikirannya kepada Soekarno, Semaun, Kartosoewiryo, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya.
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF POLITIK ETIS
Politik Etis atau Etische Politiek merupakan jawaban nyata atas kewajiban pemerintah Hindia Belanda untuk memakmurkan dan mensejahterakan penduduk di tanah jajahanya. Melalui tiga program unggulan yakni edukasi, imigrasi dan perpindahan penduduk, politik etis menjelma ke beberbagai dampak baik positif maupun negative. Diantara dampak positif yang ditimbulkan atas kebijakan politik etis ini ialah mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat daerah pribumi yang dahulunya merupakan masyarakat tidak terdidik menjadi lebih terdidik dengan gaya pendidikan Belanda. Alhasil dari tingkat kependidikan inilah muncul golongan-golongan terpelajar atau priyayi berkat sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial.
ADVERTISEMENT
Politik Etis melalui program perpindahan penduduk juga telah meningkatkan suatu produktifitas masyarakat Indonesia dimana perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera (perkebunan, pabrik gula, dll) telah memberikan keleluasaan lahan dan kesempatan baru atas pribumi Jawa guna berkembang di Sumatera. Program irigasi yang dicanangkan pemerintah kolonial juga dinilai mampu meningkatkan hasil panen atas tanah Garapan yang dikelola. Hal ini dikarenakan negeri jajahan telah dibangun suatu sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian bangsa Indonesia.
Tujuan politik etis yang dicanangkan oleh pemikir Belanda memanglah amat mulia. Namun dalam prakteknya, kegiatan itu telah termonopoli di jalan. Pendidikan yang bertujuan meningkatkan pola pengetahuan akan semua kelas pribumi rupanya terjadi diskriminasi dalam perjalanannya. Dimana hanya golongan elit dan laki-laki yang diperkenankan mengikuti bangku sekolah. Sementara golongan miskin dan kaum perempuan tidak berbeda kehdiupannya dari jaman tanam paksa. Diskriminasi yang muncul tidak hanya berdampak pada kualitas pemikiran masyarakat pribumi saja, melainkan juga berdampak pada terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi antara lapisan-lapisan masyarakat Indonesia kala itu.
ADVERTISEMENT

