Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Tak Selamanya Pepatah "Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Langit Dijunjung" Berlaku
27 Juli 2020 10:05 WIB
Diperbarui 6 Agustus 2020 13:16 WIB
Tulisan dari Syamsul Maarif tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
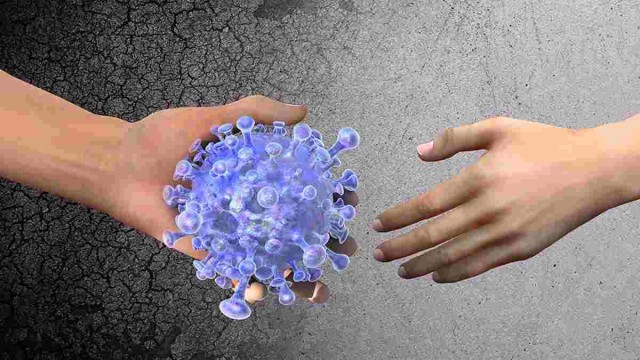
Malam itu, saya datang takziah ke salah satu teman akrab saya yang baru saja kehilangan saudarinya. Saya datang ke sana dengan tetap memakai masker seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Hanya saja, ketika di sana saya merasa ganjil, mengingat saya menjadi pusat perhatian orang-orang. Saya mencoba mencari-cari apa yang salah dengan saya? Lama-lama saya mengerti, pandangan mereka yang ganjil tak lain karena mereka merasa jengah dengan sikap "kaku" saya yang tetap memakai masker. Pertanyaannya, apakah yang saya lakukan itu etis? Siapa yang seharusnya berkompromi sebenarnya?
ADVERTISEMENT
Entah tiba-tiba dari kejadian itu saya langsung kepikiran pada etika. Tepatnya, etika dalam bermasyarakat. Bahwa ada peribahasa "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Kita sudah sangat memahami peribahasa itu. Hanya saja, apakah saat pandemik seperti ini peribahasa itu akan tetap berlaku?
Saya sendiri berpendapat peribahasa itu perlu kiranya dimodif hanya selama pandemik saja. Misalnya, ditambahkan: "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, syarat dan ketentuan tidak berlaku saat pandemik." Ini jauh lebih keren. Karena jika peribahasa ini tidak diubah selama pandemik, akan ada kekacauan antara kubu pendukung kesehatan dan kubu pendukung tradisi.
Memodifikasi tradisi
Ada cerita "unik" di balik ide ini. Saat itu, ada tetangga desa saya dinyatakan positif Corona. Yang cukup disayangkan, dari pihak keluarga duka tetap bersikukuh ingin mengadakan tahlil sebagaimana tradisi di sana. Tentu saya tidak sedang mencibir tahlilnya, karena saya sendiri dari keluarga NU. Hanya saja, yang ingin saya komentari, kenapa masih memaksa untuk tetap mengadakan tradisi tahlil pada saat keluarganya seharusnya mengadakan isolasi mandiri?
ADVERTISEMENT
"Tapi kan tradisi tahlil sudah turun temurun diadakan di desa ini?"
Tradisi tahlil tidak harus ditinggalkan kok, biarlah tahlil tetap ada hanya saja format acaranya berbeda. Mungkin tradisi itu bisa dilanjutkan dengan cara keluarga duka meminta bantuan kepada tokoh agama. Biarlah tokoh agama yang mengurus acara tahlil itu bersama sesepuh kampung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Memodifikasi tradisi berlaku juga untuk semua tradisi yang lain. Sedikit memodif bukan berarti menghilangkan. Sama seperti doa bersama yang dilakukan via online tetap itu disebut dengan doa bersama, hanya caranya saja yang sedikit dimodifikasi agar tetap bisa dilaksanakan di masa pandemik. Atau mungkin tahlil ingin diubah secara online, tidak ada masalah juga, bukan?
Tokoh Agama Menjadi Teladan yang Baik.
ADVERTISEMENT
Usaha dalam memodifikasi tradisi sepertinya ganjalan utamanya adalah fatwa tokoh agama. Saya masih ingat betul, sewaktu saya di rumah nenek dan mengikuti sholat Jum'at di masjid daerah sana, saya menemukan hal yang sangat "tidak lazim." Saya satu-satunya orang yang memakai masker di masjid itu. Iya, bahkan Imam masjidnya pun tidak menggunakan masker. Tentu saja saya menjadi pusat perhatian di masjid itu. Kedatangan saya di sana, mengundang banyak mata tertuju ke saya, bak melihat kedatangan mempelai putra dalam resepsi pernikahan. Hanya saja kali ini, tatapan mereka seakan ingin menertawakan. Hehe...
Saya tidak hendak menyalahkan orang-orang di masjid itu. Namun, ada hal yang membuat saya penasaran. Kenapa kok orang-orang begitu sehati untuk tidak memakai masker? Dan kenapa pandangan mereka begitu kompaknya tertuju ke saya? (Sebegitu gantengkah saya? Hahaha) Saya meyakini pasti ada sesuatu yang mendorongnya. Ternyata memang benar. Masyarakat bertindak kompak seperti itu, karena tak lain ada faktor tokoh agama.
ADVERTISEMENT
Hal yang sangat disayangkan, tokoh agama seringkali bukan menjadi penasihat supaya masyarakat selalu taat protokol kesehatan, namun justru seakan menjadi pemicu orang-orang meremehkan wabah ini. Fatwa yang sering didengungkan oleh tokoh agama:
"Jangan takut dengan Corona, kayak nggak punya iman saja, lagian umur sudah ada yang ngatur kok"
Meskipun tidak sepenuhnya sama kata-katanya, namun kurang lebih seperti itu intinya. Sehingga, tidak mengherankan banyak sekali orang betul-betul meremehkan wabah ini. Karena anggapan masyarakat soal memakai masker, menjaga jarak saat sholat, dan tidak bersalaman itu sama artinya "kurang" iman, sehingga mengikuti protokol pemerintah dianggap sesuatu yang hina di masyarakat. Masyarakat dalam melihat ukuran kuatnya iman seseorang hanya sekedar melihat apakah pakai masker atau tidak. Seakan ustadz yang tidak pakai masker dianggap lebih baik daripada ustadz yang memakai masker.
ADVERTISEMENT
Dampaknya jika ini dibiarkan, tidak mengherankan protokol kesehatan hanya dianggap sebagai angin lalu saja, sampai-sampai membentuk pola pemikiran dan tradisi yang diterima di tengah masyarakat bahwa menggunakan masker saat takziah ataupun mengindari salaman dengan orang-orang di masa pandemik selain dianggap kurang iman juga dianggap tindakan yang tidak sopan. Seperti ada nilai yang dibanggakan ketika tidak mengikuti protokol kesehatan. Tentunya ini sangat berbahaya.
Berdampak pada Penilaian Benar dan Salah
Dampak lebih buruknya, jika di masyarakat telah membentuk suatu nilai kesopanan yang ambigu. Nilai itu selain membuat masyarakat terpecah antara kubu protokol kesehatan dan kubu kesopanan, namun juga akan membentuk suatu nilai paradigma kesopanan baru. Nilai kesopanan ambigu yang tidak ada jalan tengah dan landasan ukurannya.
ADVERTISEMENT
Satu contoh, saya pernah melihat tetangga depan rumah saya, dicibir oleh orang-orang karena tidak mau salaman dengan tetangga di saat wabah. Saya mikir, apa yang dilakukan oleh tetangga depan rumah saya ini salah atau benar? Etis tidak tindakan tetangga depan rumah saya ini? Atau pertanyaannya saya balik, etis tidak orang-orang kampung itu yang sudah mencibir tetangga depan rumah saya? Atau mungkin saja etis tidak saya membahas ini?
Kesopanan yang ambigu ini tidak lepas karena masyarakat memandang etika tidak ada bedanya dengan masa sebelum pandemik. Sebelum pandemik tindakan tidak mau salaman dengan orang itu dianggap tidak sopan. Adalah kurang tepat bagi saya jika ukuran itu tetap berlaku saat pandemik. Karena di masa pandemik sudah seharusnya memasuki paradigma kenormalan baru (new normal) yang tentunya penilaian sesuatunya sudah berbeda. Mengadakan acara keagamaan secara besar-besaran adalah suatu hal yang bagus tapi jika itu diadakan saat pandemik dengan tidak mengikuti protokol kesehatan akan dipandang sebagai sesuatu yang cacat. Ini yang disebut dengan kenormalan baru.
ADVERTISEMENT
Lantas, jika kembali ke contoh awal tadi soal takziah, apa yang seharusnya saya lakukan? Menjunjung nilai-nilai yang sudah terbentuk di masyarakat menyoal kesopanan dengan cara saya melepaskan masker atau saya tetap mengikuti protokol kesehatan? Apakah salah jika saya tidak menghormati nilai-nilai kesopanan hanya ketika pandemik saja?
"Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, syarat dan ketentuan tidak berlaku saat pandemik." Salahkah saya berprinsip seperti ini?
***
Syamsul Maarif Guru Agama Islam dan Pengajar di Kampung Inggris

