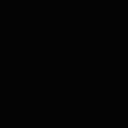Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Tiger Parenting, Bukannya Sukses Malah Stres
29 Desember 2022 17:50 WIB
Tulisan dari Tiara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun, tak hanya memotivasi, beberapa di antaranya mendorong anaknya terlalu keras dari batasan. Anggapan mengenai sukses masih berputar di situ-situ saja. Angka di kertas jadi prioritas utama. Lagi-lagi, akademik seakan menjadi tolok ukur keberhasilan nomor satu.
ADVERTISEMENT
Sayangnya, penilaian akan persoalan kesuksesan tersebut sangat berpotensi menjadi senjata perusak mental anak. Dorongan orang tua yang terlalu keras dengan hanya melihat pada satu poros akademik saja membuat mereka hilang arah. Penerapan tiger parenting pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan bagi orang tua konservatif. Bayarannya sudah pasti mental sang buah hati.
Melansir dari The Times, di Britania Raya, orang tua Ras Asia identik dengan gaya didiknya yang demanding terhadap anak. Tuntutan kesempurnaan di bidang akademik seakan menjadi hal terpenting bagi orang tua. Tiger parenting menjadi salah satu metodenya.
Pendapat tersebut sejalan dengan hasil data angka bunuh diri remaja yang cukup menggentarkan Seoul, Korea Selatan. Menurut data Rep. Chung Woo Taik dari People Power Party, angka bunuh diri remaja usia 20-an di Seoul pada tahun 2022 meningkat hampir sepuluh persen. Empat puluh persen di antaranya terjadi karena metode tiger parenting ini, yaitu tinggi tuntutan orang tua yang terlampau tinggi terhadap anaknya.
ADVERTISEMENT
Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara-negara Asia Timur termasuk Korea Selatan menanamkan jiwa ambisius, harus berhasil, dan selalu bertindak cepat atau ppalli-ppalli sejak dini. Ironisnya, tak sedikit orang tua yang acuh terhadap fakta bahwa tak semua anak bisa didik dengan cara itu. Keacuhan tersebut akhirnya menimbulkan kasus-kasus tragis seperti bunuh diri yang terjadi di Korea Selatan ini.
Tiger parenting digambarkan sebagai gaya ganas dalam mendisiplinkan anak-anak dan menempatkan nilai tinggi pada keunggulan akademik (Chua, 2011). Tiger mom tanpa rasa bersalah berhak meminta anaknya untuk mendapatkan nilai akademik tertinggi tanpa peduli dampak emosional dari hal tersebut.
Tak sampai di situ, anak dengan tiger parenting selalu dipaksa untuk mematuhi keputusan dan jadwal kegiatan yang ditentukan tanpa peduli apapun alasannya. Orang tua seakan dibutakan oleh angka di atas kertas. Dipaksa untuk selalu mematuhi keputusan ayah dan ibunya, membantah atau sekadar berkomentar tak diberi ruang. Pola asuh otoriter yang diterapkan secara berlebihan menjadi sebuah cara bullying yang dilakukan terus menerus tanpa sadar.
ADVERTISEMENT
Di Indonesia, penerapan tiger parenting sudah beririsan dengan teriakan dan perbandingan antar individu. Beberapa didampingi dengan penggunaan kata-kata yang mengolok-olok yang terkesan merendahkan kemampuan. Mempermalukan anak di depan orang yang kapasitas pencapaian lebih tinggi menjadi sebuah tradisi berulang yang tak kunjung kelar.
Dampak emosional banyak ditemukan pada sisi psikologis, seperti kurang bahagia, jarang bersenang-senang, hingga yang paling buruk adalah gejala depresi bahkan hingga bunuh diri.
Pembatasan dalam menentukan wewenang karena takut akan hukuman sudah menjadi realita yang tumbuh di tengah masyarakat. Kapasitas anak untuk terus menerima dorongan memiliki batasan tertentu yang berbeda satu sama lain. Menyamaratakan kemampuan adalah tolok ukur ketidakadilan nyata dalam proses tiger parenting.
Ambisi dalam meraih prestasi tidak timbul secara naluriah cepat atau lambat akan berdampak pada ledakan emosi. Orang tua tak lagi dipandang sebagai sosok mengayomi, tetapi justru sebaliknya. Orang terdekat adalah penyebab dari kehancuran psikologi yang dipupuk secara perlahan.
ADVERTISEMENT
Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Tiger parenting menjadi sebuah topik serius yang acap kali disepelekan karena dianggap tak berpengaruh besar. Tradisi dan budaya menyenangkan hati orang tua sudah sebaiknya berjalan beriringan dengan kecerdasan dalam mengelola mental.
Kesehatan mental adalah nomor satu. Kalau orang bilang orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, mari kita lihat dari perspektif anak. Apa ada anak yang ingin mengecewakan orang tuanya? Sebuah pertanyaan retoris yang tak perlu dijawab. Pun harus dijawab, sudah pasti jawabannya adalah “ya”.
Anak pun ingin memberikan yang terbaik bagi orang tua dan dirinya sendiri. Jelas sampai di sini bahwa kedua belah pihak setuju ingin mencapai kesuksesan. Yang jadi persoalan adalah di bidang apa ia akan meraihnya dan jalan apa yang dipilihnya untuk sampai di titik tersebut.
ADVERTISEMENT
Sosialisasi dan kampanye kesehatan mental dapat menjadi pilihan untuk mengurangi tindakan keras dan otoriter berkepanjangan. Pemberian apresiasi terhadap pencapaian sekecil apapun merupakan langkah awal yang tepat. Angka di atas kertas memang penting, tapi kesehatan mental buah hati tak dapat menyaingi hal lain.
Alangkah baiknya apabila persepsi kesuksesan yang berporos pada nilai akademik saja diharapkan dapat memudar seiring berjalannya waktu. Pemikiran tentang tahu apa yang terbaik selalu jadi alasan menghancurkan mental anak.