Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
Konten dari Pengguna
Di Balik Mitos Pesugihan
20 Mei 2021 13:37 WIB
Tulisan dari Anicetus Windarto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Kabar tentang penangkapan babi yang diduga sebagai wahana pesugihan bernama babi ngepet telah menjadi viral di berbagai media sosial, termasuk di media utama. Seperti di harian Kompas (6/5/2021) dengan judul “Pesugihan dan Manusia Indonesia Modern”, kabar itu dikaji dengan cukup serius terutama dalam konteks peradaban yang semakin modern dan canggih serta masyarakat yang semakin terdidik dan religius.
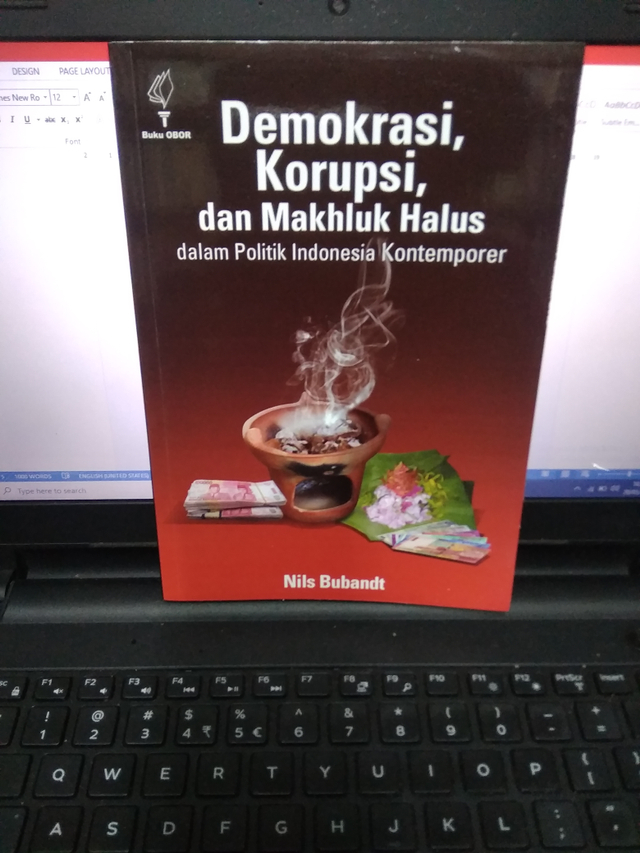
Pertanyaannya, kepentingan apa dan siapa sesungguhnya yang tersembunyi di balik mitos pesugihan? Bagaimana mitos itu dapat dibongkar dan dimaknai dengan tepat dan bermanfaat?
ADVERTISEMENT
Dalam buku biografinya berjudul Hidup di Luar Tempurung (Marjin Kiri, 2016), Benedict Anderson (1936-2015) mengutip sebuah cerita aneh namun memukau tentang Amangkurat II, raja Jawa di akhir abad ke-17. Diceritakan bahwa pada tahun 1703 saat sang raja wafat, beliau belum menunjuk siapa pewaris tahtanya. Namun tatkala para calon dan abdi dalem mengelilingi ranjangnya, salah seorang dari mereka, Pangeran Puger melihat bahwa penis sang raja yang wafat itu berdiri keras dan di ujungnya tampak setetes cairan berkilau. Ia pun segera meminum cairan itu, lalu penis itu pun melunak. Cairan itulah yang dinamai tédja, atau “wahyu keraton”, yang telah diturunkan kepada pangeran, yang bertahta dan berkuasa sebagai Amangkurat III.
Uniknya, cerita ganjil yang jumlahnya lusinan itu dituturkan secara khidmat oleh penulis babad-babad tentang raja Jawa. Bahkan oleh mendiang Soemarsaid Moertono (1922-1987) cerita-cerita itu dipakai untuk menulis bukunya yang berjudul Negara dan Kekuasaan di Jawa (KPG, 2017). Maka bukan masalah mitologi semata agaknya, jika masih ada kepercayaan dalam masyarakat kita tentang “larangan” membiarkan kucing yang tertabrak mati di jalanan. Tetapi, justu karena reaksi gampangan sebagian peneliti, pengamat, atau pembaca Barat yang beranggapan bahwa masyarakat kita, Timur umumnya, dari dulu hingga kini masih primitif. Sedangkan mereka tidak demikian, karena sudah dapat membuang segala yang “ilahiah” atau “gaib” dari pemikirannya.
ADVERTISEMENT
Hal itu seolah-olah menjadi tonggak diturunkannya rasionalitas Barat yang menandai kemajuan zaman dengan kehadiran sains modern dan peradaban mutakhir. Meski masih dapat dipertanyakan dari asumsi-asumsi macam apakah rasionalitas itu diturunkan, namun sebagian dari mereka, termasuk kita, terlanjur percaya bahwa tak ada “rasionalitas Jawa” misalnya. Padahal gagasan kuasanya yang begitu “konkret” masih tetap dipraktikkan di negara kita ini. Artinya, sesungguhnya ada konsep yang jernih tentang “kuasa” dalam budaya Jawa, sejenis mana atau tédja, yang terdeteksi dalam benda-benda gaib, ruh, dan manusia, termasuk organ seksnya.
Pun dalam diri mereka yang menganggap telah berbudaya modern, kepercayaan terhadap yang dipandang irasional toh masih juga belum punah. Masuk akal jika, mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagen tak pernah mengambil keputusan penting apapun sebelum istrinya menelepon dulu kepada dukunnya. Termasuk pucuk pimpinan Partai Komunis Tiongkok, yang hingga kini diketahui masih saja berkonsultasi dengan para ahli ramalan bintang dan suhu-suhu fengshui.
ADVERTISEMENT
Jadi, baik orang Barat, orang Jawa atau Indonesia maupun yang lainnya, satu sama lain adalah sama “rasionalnya”. Asalkan asumsi-asumsi dasar pemikiran dari masing-masing pihak dipahami, maka nalar atau rasionalitas dapat ditemukan. Kuncinya adalah mampu melakukan kajian perbandingan yang kaya dan mendalam dengan membuka setiap pintu kemungkinan untuk berimajinasi, bahkan berpolemik, tentang segala sesuatu yang dianggap mistik ataupun klenik.
Menarik bahwa meski Mochtar Lubis mencirikan manusia Indonesia dengan sebutan “percaya takhayul”, namun novel yang diterbitkan dengan judul Harimau! Harimau! justru berkisah tentang kehidupan masyarakat di Sumatera Barat yang serba supranatural. Hal itu menandakan bahwa imajinasi tentang manusia Indonesia yang disebutkan di atas sesungguhnya adalah nyata.
Maka, kepercayaan itu dapat dikonsepsikan bukan semata-mata sekadar sebagai “isme” lain, di samping animisme atau dinamisme. Tetapi, di situ juga terpendam sebuah daya emosional yang amat besar dengan kemampuannya untuk membuat orang rela berbuat apa saja demi apa yang dipercayainya itu. Itulah mengapa orang dengan mudah dapat dicengkeram, bahkan diperdayai, oleh kepercayaan yang masih sarat dengan mitos, terlebih yang punya kepentingan terselubung.
ADVERTISEMENT
Dalam konteks ini, kepercayaan yang dipandang mampu melumpuhkan nalar modern sama seriusnya dengan kenyataan politik dari nasionalisme, bahkan terorisme, yang beranggapan “jangankan nyawa orang lain, nyawanya sendiri pun bersedia untuk dikorban”. Di sini kepentingannya bukan lagi sekadar demi kemewahan dan/atau keserakahan, seperti terjadi pada mitos pesugihan babi ngepet di Depok, Jawa Barat, melainkan kesinambungan dan kelestarian sebuah “identitas nasional” yang purba. Entah itu atas nama komunitas religi, dinasti, ataupun mitos-mitos penguasa, identitas yang menentukan soal hidup atau mati itu masih menjadi kepercayaan yang dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun.
“NKRI Harga Mati” misalnya, seakan-akan telah menjadi kepercayaan yang abai terhadap nalar lain dan diperlakukan sebagai jimat belaka. Kenyataan seperti ini jelas akan membekukan dan membakukan jejak langkah nasionalisme kita yang dalam rumusan Sukarno muda di tahun 1928 bukan merupakan “nasionalisme negara” yang “menjerang-njerang dan mengedjar keperluannja” sendiri, melainkan “jang membuat kita menjadi ‘perkakasnja Tuhan’” (Dhakidae, 2001).
ADVERTISEMENT
Maka, perkara mitos yang sesungguhnya berakar kuat pada budaya masyarakat kita bukan semata-mata perkara nalar yang hilang, atau tidak ada lagi, di kepala. Tetapi, perkara itu justru menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak punya ide, apalagi kajian, yang sistematis dan historis tentang mitos.
Syukurlah, masih ada “Mas Moer”, panggilan akrab untuk Soemarsaid Moertono selama studi lanjut di Universitas Cornell, yang dengan tekun mengkaji aspek-aspek kekuasaan kerajaan Jawa tradisional. Dari kajiannya itulah, cerita ganjil di atas yang amat tidak masuk akal dapat dipahami asumsi-asumsi dasarnya yang terlanjur dianggap lumpuh daya nalarnya. Itulah daya imajinasi yang kekuatan emosionalnya dapat menyebar dengan cepat dan mendunia meski tak jarang berkubang dalam mitos, termasuk takhayul, yang melahirkan suatu kekonyolan.
ADVERTISEMENT

