Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Konten dari Pengguna
Menilik Debat 'Tilik'
25 Agustus 2020 9:41 WIB
Tulisan dari Ariel Heryanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
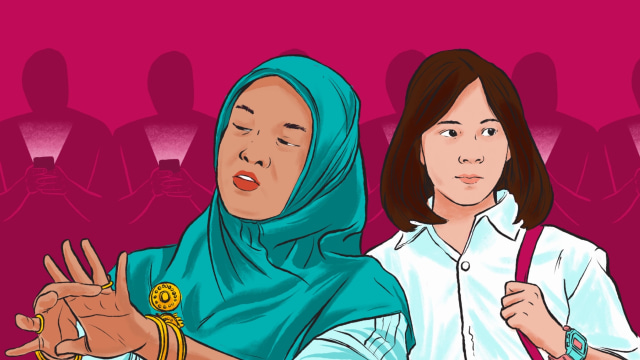
ADVERTISEMENT
Tayangan film pendek “Tilik” di YouTube menarik lebih dari 10 juta penonton dalam seminggu pertama. Ia juga telah membangkitkan debat bersemangat di media sosial maupun media arus utama.
ADVERTISEMENT
Dari perdebatan itu, ada tiga hal kritik utama pada “Tilik”. Bila disederhanakan secara ringkas ketiganya kira-kira begini.
Pertama, film ini dianggap meremehkan perempuan. Para tokoh perempuan di atas truk tampil sebagai tokoh-tokoh stereotip perempuan. Serba negatif. Mereka doyan gosip. Juga kepo. Menjelek-jelekkan kehidupan pribadi warga sekampung. Celakanya, korban gosip ini sesama perempuan bernama Dian, pemudi lajang yang jadi kembang desa.
Kedua, gosip itu bukan sekadar senda gurau iseng. Tetapi disampaikan tokoh utamanya, Bu Tejo, sebagai peringatan serius. Dian ditampilkan sebagai ancaman terhadap ketenteraman dan kerukunan hidup bersama di lingkungan mereka. Parahnya lagi, kebenaran berbagai gosip itu disahkan oleh Bu Tejo dengan mengandalkan apa kata orang lain di jaringan sosial media di telepon genggam!
ADVERTISEMENT
Ketiga, pukulan telak dirasakan para pengritik film pada penutup film. Di situ ditampilkan Dian duduk dalam mobil. Ia di samping pria, yakni mantan suami Ibu Lurah, yang duduk di belakang kemudi mobil. Dari segi usia pria ini lebih pantas menjadi ayah atau mertua Dian. Mereka berniat menikah. Adegan ini mengecewakan banyak pengritiknya, karena dianggap sebagai pembenaran bagi tuduhan Bu Tejo.
Apakah keberatan para pengritik itu beralasan? Sampai batas tertentu, ya. Sampai batas apa dan di mana, terbuka pada perdebatan tanpa batas. Sebelum membahas lebih jauh tentang soal ini, perlu ditimbang pandangan-tandingan terhadap berbagai kritik tersebut.
Banyak pembela “Tilik” yang menilai berbagai kritik itu tidak adil. Alih-alih menyanggah pokok-pokok kritik, pembela “Tilik” ini mengabaikan berbagai kritik tersebut. Mereka menganggap kritik itu tidak relevan. Menurut mereka, “Tilik” sebaiknya ditonton dan dinikmati santai saja sebagai hiburan. Bukan dianalisis dengan beban teori yang berat-berat.
ADVERTISEMENT
Sebagian pembela “Tilik” juga menyatakan film menampilkan kenyataan sehari-hari yang lazim dan akrab. Mengapa harus disangkal? Para pengritiknya sebenarnya bukan menyangkal, namun menggugat posisi pembuat film dan keberpihakannya kenyataan sosial. Menurut pengritik “Tilik”, dengan hanya menampilkan realitas sosial, film itu secara tersirat atau tak langsung memberikan pembenaran pada status-quo, alih-alih mengritiknya.
Jelas para penonton “Tilik” punya alasan, wawasan, dan tuntutan berbeda-beda. Bahkan mungkin bertolak-belakang. “Tilik” memuaskan sebagian, dan menjengkelkan sebagian penonton lain. Kita layak bersyukur “Tilik” telah membangkitkan sebuah perdebatan penting. Catatan ini berupaya membahas lebih jauh pentingnya perdebatan itu.
Sudah saya akui tadi, penggambaran atas debat dua kutub pandangan di atas merupakan garis besar dari debat yang terjadi. Setiap laporan ringkas terhadap perdebatan yang panjang-lebar tidak bisa tidak menyederhanakan masalah. Saya berharap, ringkasan dan penyederhanaan di atas cukup adil, dan tidak menyeleweng jauh dari apa yang terjadi.
ADVERTISEMENT
Untuk keperluan bahasan di sini, persoalannya bukan pada pernik-pernik detail perdebatannya. Ada dua pilihan alternatif. Minat besar saya berada jauh di luar perdebatan kedua kubu itu. Debat “Tilik” tidak harus dibatasi pada persoalan mana yang benar di antara dua kutub pandangan yang berseberangan.
Sebelum membahas ke situ, kita tengok ulang pertentangan kedua kubu. Masing-masing kubu punya pandangan yang sah, tetapi hanya hingga pada tahap tertentu. Keduanya ada benarnya, walau seakan-akan bertolak-belakang.
Para pengritik benar, sebagian besar adegan “Tilik” memanipulasi realitas sosial dengan membingkainya dalam stereotip tentang sosok perempuan. Apalagi fokusnya pada hal-hal yang sulit dibanggakan: kenyinyiran tokoh utama Bu Tejo bergosip. Juga keluguan mempercayai media sosial sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran.
ADVERTISEMENT
Namun, perlu dicatat “Tilik” juga menampilkan tokoh Yu Ning yang rasional dan kritis. Ia berkali-kali menyanggah dan menggugat sikap mau pun cara berpikir Bu Tejo.
Keberatan para pengritik pada adegan penutup film juga dapat dimaklumi. Ini bukan penutup yang menghukum Bu Tejo. Malahan sedikit berpihak pada Bu Tejo. Tapi tampilan Dian di akhir film mementahkan berbagai tuduhan ekstrem Bu Tejo.
Misalnya tuduhan Dian sok-pamer barang-barang mewah. Atau si genit yang suka menggoda pria untuk tujuan komersial. Ternyata Dian tampil di film sangat santun dan bersahaja dalam busana, tata-rias, dan nyaris tanpa perhiasan.
Juga sulit menilai adegan penutup sebagai pembenar bagi tuduhan Bu Tejo atas perilaku seksual Dian yang “tidak benar”. Dian berharap segera menikah secara sah dengan lelaki yang sudah cerai dari istrinya. Apa yang salah? Beda, seandainya di akhir film Dian bercumbu dengan suami Bu Tejo.
ADVERTISEMENT
Berbagai detail adegan “Tilik” terbuka pada tafsir dan perdebatan menarik yang membutuhkan ruang jauh lebih lebar daripada yang tersedia di sini. “Tilik” dapat dibaca lebih dari satu tafsiran. Saya ingin menutup tulisan ini dengan keluar jauh dari pernik-pernik detail adegan “Tilik”.
Debat “Tilik” dapat menghantar kita pada persoalan lebih besar, jika kita mau. Cendekiawan dari berbagai bangsa sudah berabad-abad berusaha merumuskan bagaimana persisnya kaitan antara karya kreatif dan gejolak masyarakatnya.
Sejauh mana karya kreatif berpijak pada realitas sosial? Sejauh mana karya itu mampu membujuk atau menghasut masyarakatnya untuk memelihara atau menggugat realitas tersebut?
Tak ada dan tak mungkin ada karya kreatif yang menampilkan realitas sosial secara netral, tanpa bias ideologi. Namun, hingga kini belum pernah ada rumusan politik atau ideologi yang mujarab membantu proses penciptaan karya seni dengan hasil yang memuaskan publiknya.
ADVERTISEMENT
Di Indonesia baru ada satu usaha terlembaga berlingkup nasional yang mencoba memecahkan persoalan itu, secara teori maupun praktis: LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat, 950-1965). Pada tahun 1963 lembaga ini punya ratusan cabang dan anggotanya sekitar 100 ribu. Usaha yang sama pernah dikerjakan pihak lain, tetapi tidak seluas, seintens, dan mendalam kerja LEKRA.
LEKRA tak sempat membuktikan diri gagal atau sukses. Usaha mereka gugur prematur sebagai korban pergolakan politik tahun 1965-1966. LEKRA dinyatakan terlarang. Para pengurus dan anggotanya dibunuh, dipenjara, atau diasingkan. Semua karya mereka, terlepas dari mutunya, dilarang pemerintah Orde Baru.
Hukuman tersebut tak pernah dicabut setelah Orde Baru tumbang. Tak banyak generasi muda yang kenal nama LEKRA. Untung, seorang sarjana Australia, Dr Keith Foulcher, pernah meneliti dan menerbitkan sebuah buku tentang seluk-beluk LEKRA. Ada kabar terjemahan buku itu dalam bahasa Indonesia akan segera terbit di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Kaitan antara karya kreatif seni film, sastra, atau tari dengan masyarakatnya sangatlah penting dan sekaligus rumit. Tetapi juga tak pernah dapat diabaikan. Perdebatan film “Tilik” hanyalah salah satu bukti paling mutakhir. Seakan-akan ia menggaruk-garuk kembali rasa gatal yang punya sejarah panjang dalam tubuh masyarakat. Namun tak banyak dikenal masyarakat mutakhir.

