Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Ronggeng Dukuh Paruk Antara Tradisi dan Tragedi
4 Mei 2025 14:31 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Indri Nuranggraini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
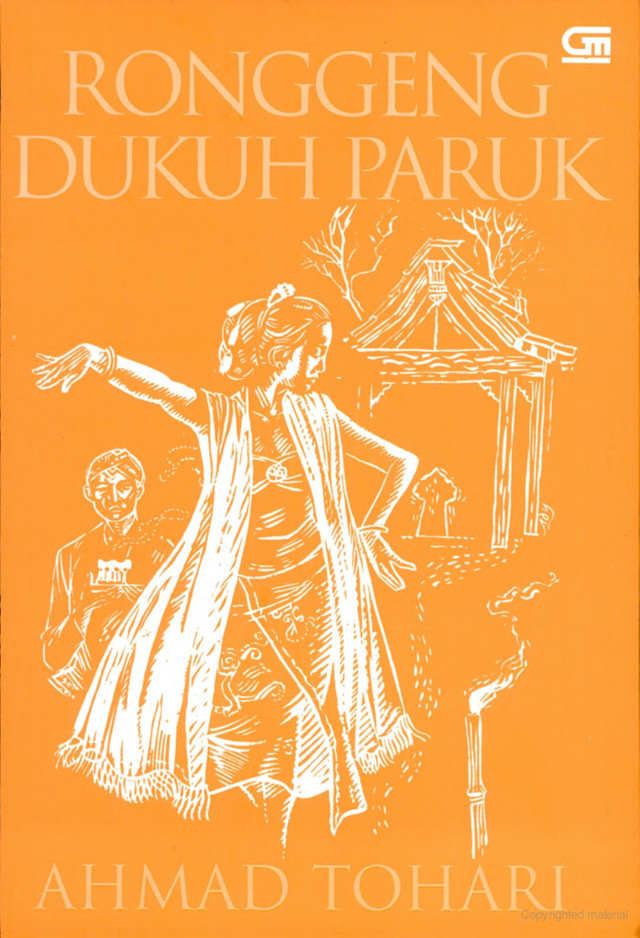
ADVERTISEMENT
Salah satu karya sastra Indonesia yang paling berkesan dan sarat makna adalah novel Ronggeng Dukuh Paruk oleh Ahmad Tohari. Dia lahir di Banyumas, Jawa Tengah, pada 13 Juni 1948. Ia adalah sastrawan yang terkenal karena kemampuan mereka untuk menggabungkan masalah sosial yang mendalam dengan bahasa yang indah. Kubah dan Bekisar Merah adalah karya lain selain Ronggeng Dukuh Paruk. Dia banyak menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan yang penuh dengan ketegangan antara adat istiadat, kepercayaan, dan perubahan sosial dalam karya-karyanya. Ahmad Tohari juga dikenal sebagai penulis yang menyuarakan kaum marjinal, terutama perempuan dan masyarakat kecil, dengan empati dan kedalaman. Gaya bahasanya puitis tetapi tetap mudah diakses oleh pembaca umum.
ADVERTISEMENT
Ronggeng Dukuh Paruk keluar pada tahun 1982 dan menceritakan kisah yang rumit, menyentuh, dan menggugah tentang perempuan, tradisi, dan politik dalam konteks budaya Jawa yang kuat. Fokus cerita adalah Srintil, seorang wanita muda dari desa kecil Dukuh Paruk yang ditakdirkan menjadi seorang ronggeng penari tradisional yang dipuja tetapi juga dikorbankan oleh masyarakatnya.
Masyarakat menganggap Srintil, gadis kecil yang tumbuh dalam kemiskinan, memiliki aura magis (berkaitan dengan sihir atau kekuatan gaib ) yang dianggap sebagai titisan ronggeng yang sebenarnya. Sejak kecil, ia telah menjadi penerus ronggeng setelah kematian ronggeng sebelumnya. Dalam adat Dukuh Paruk, ronggeng adalah simbol kesuburan, hiburan, dan, tragisnya, juga objek seksual bagi laki-laki. Ritual "bukak klambu", atau malam pertama yang harus dilalui Srintil, menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat menjadikan perempuan sebagai alat pelestari budaya tanpa mempertimbangkan martabat dan keinginan individu.
ADVERTISEMENT
"Menjadi ronggeng berarti menyerahkan tubuh, bukan hanya untuk menari, tetapi untuk desa. Itu harga yang harus dibayar."
Menurut Simone de Beauvoir, masyarakat, bukan dirinya sendiri, menentukan nilai perempuan, jadi kutipan ini menunjukkan posisi perempuan sebagai Liyan (The Other). Srintil menjadi ronggeng karena desanya, bukan kehendaknya. Keputusan itu hanya dipertanyakan oleh Rasul, kekasih masa kecil Srintil. Ronggeng dianggap sebagai perbudakan perempuan kontemporer, bukan warisan budaya. Tekanan sosial dan kekuatan budaya membuat Rasus tidak mampu menyelamatkan Srintil. Ia memutuskan untuk pergi dan menjadi tentara, meninggalkan Srintil yang lambat laun terseret ke politik kotor dan tragedi nasional tahun 1965.
Tragedi ini membawa Srintil ke dalam penjara, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dia sebagai ronggeng pernah terlibat dengan kelompok yang dicap kiri oleh rezim. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan politik bisa bersatu menghancurkan kehidupan perempuan.
ADVERTISEMENT
Novel ini berbicara tentang budaya sebagai pedang bermata dua. Ia bisa memperindah hidup, tetapi juga bisa mengurung dan menindas. Pembaca diajak untuk mempertimbangkan kembali gagasan bahwa tradisi harus dilestarikan tanpa kritik melalui Srintil. Ronggeng Dukuh Paruk adalah ajakan untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang diwariskan kepada kita. Ia mengkritik posisi perempuan dalam sistem sosial dan politik yang tidak adil, dan menekankan betapa pentingnya bagi perempuan untuk memiliki kemandirian atas tubuh dan pilihan hidup mereka sendiri.

