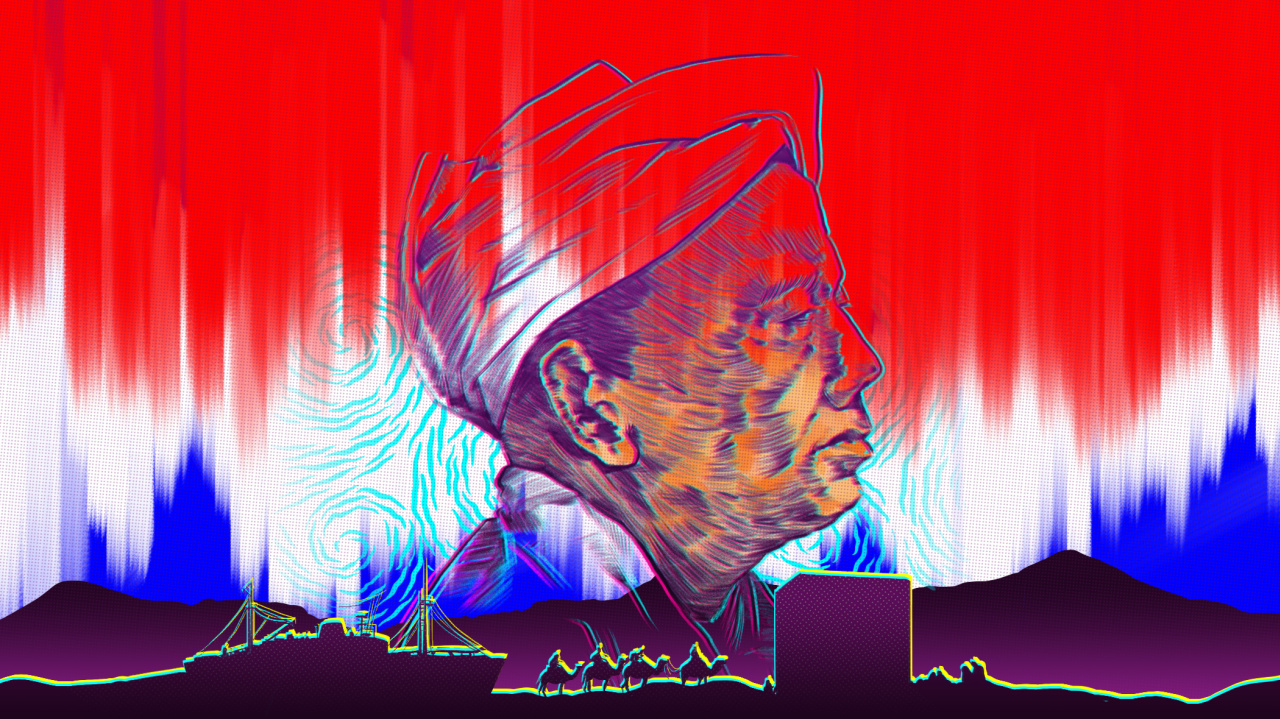
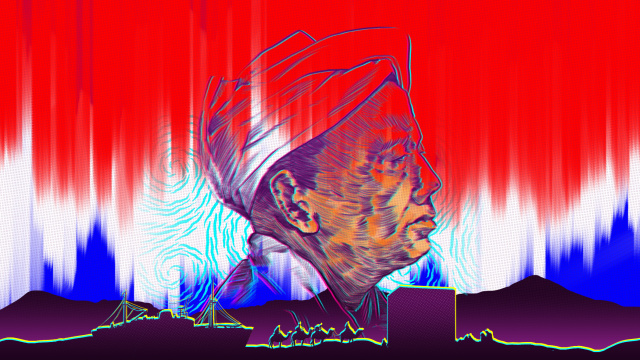
Berhaji di masa perang kemerdekaan bukan urusan mudah. Tak cuma masalah minimnya fasilitas dan keselamatan saat menumpang kapal laut berbulan-bulan. Haji di masa itu juga dijadikan siasat oleh Belanda untuk melakukan propaganda.
Rayuan Belanda dengan iming-iming pergi haji sempat membuat sebagian tokoh agama goyah. Namun sebagian lainnya justru semakin garang melawan, mereka rela menunda haji demi kemerdekaan negeri. Bagaimana kisahnya?
Haji di masa penjajahan jadi salah satu alat propaganda pemerintah Hindia Belanda untuk meraih simpati rakyat. Tawaran ibadah haji menggoyahkan beberapa tokoh agama yang sebelumnya menjadi garda depan perjuangan. Namun Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Kyai Haji Hasyim Asy'ari langsung bergerak mencegah propaganda itu.
Sabtu, 20 April 1946, KH Hasyim Asy'ari bersuara lewat siaran radio. Hasyim yang juga pimpinan tertinggi Masyumi, partai Islam di Indonesia, menyiarkan fatwa agar umat Islam menolak tawaran haji dari pemerintah Belanda. Ia melarang umat Islam di Indonesia melaksanakan ibadah dengan uluran tangan penjajah.
“Haram bagi umat Islam Indonesia meninggalkan Tanah Air dalam keadaan musuh menyerang untuk menjajah dan merusak agama. Karena itu tidak wajib pergi haji di mana berlaku fardu‘ain bagi umat Islam dalam keadaan melakukan perang melawan penjajahan bangsa dan agama,” seru KH. Hasyim Asy'ari.
Fatwa itu dengan cepat beredar lewat jejaring kelompok Islam yang mengakar kuat dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Bukan hanya di kalangan NU, tapi hampir seluruh organisasi Islam. Para tokoh agama kemudian mantap menunda ibadah haji dan kembali berjuang mempertahankan kemerdekaan.
“Banyak yang sudah mendaftar terus membatalkan. Waktu itu Belanda marah betul dengan kebijakan itu,” kata Kepala Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (LESBUMI) NU Agus Sunyoto kepada kumparan, Rabu (14/8).
Haji sebagai rukun Islam yang sejatinya menjadi ibadah yang sakral tak pelak masuk dalam ranah politik. Ismail Hakki Goksoy, profesor sejarah Islam di Fakultas Teologi Suleyman Demirel University, Turki, dalam paper akademik berjudul “Dutch Policy towards the Indonesian Haj, 1946-1949”, menuturkan jika ibadah haji digunakan untuk memenuhi keinginan Belanda mencaplok kembali Indonesia.
Netherlands Indies Civil Administration (NICA) benar-benar memainkan ibadah haji sebagai alat untuk meraih simpati rakyat. Seorang petinggi NICA bernama Van der Plas yang sebelum pendudukan Jepang 1942-1945 menjabat Gubernur Jawa Timur paham betul kelompok agama bakal punya peran penting dalam semangat mempertahankan kemerdekaan. Semangat perlawanan di Surabaya misalnya tak lepas dari Resolusi Jihad yang digemakan Rais Akbar Nahdhlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari, pada 22 Oktober 1945.
Untuk merebut hati kelompok Islam, Van der Plas yang juga penasihat isu Islam punya siasat agar NICA bisa memfasilitasi keinginan paling besar umat yaitu berangkat haji.
NICA kembali menghidupkan fasilitas haji yang digunakan pada masa sebelum kekuasaannya direbut Jepang pada 1942. NICA menyiarkan pengumuman ke wilayah-wilayah yang berhasil tunduk kepada Belanda seperti Kalimantan dan Sulawesi. Van der Plas bahkan turun langsung ke Kalimantan Selatan pada April 1946 untuk membujuk tokoh agama di sana. Harapannya agar keinginan berangkat haji yang sempat tak mungkin selama pendudukan Jepang bisa terobati.
“Akhirnya Van Der Plass membuat kebijakan akan memberikan angkutan untuk haji, dijamin keselamatan macam-macam, diberikan fasilitas-fasilitas agar rakyat Indonesia khususnya umat Islam simpati sama NICA,” tambah Agus.
Saat itu pemerintah kolonial Belanda menyediakan kuota haji untuk 3000 jemaah. Pengumuman pelaksanaan haji muncul di koran-koran. Biaya yang dibebankan kepada jemaah antara 170 pounds sampai 200 pounds, dengan fasilitasi transportasi dari Tanah Air ke Makkah hingga penginapan. Kerajaan Saudi yang masih berkompromi kepada Belanda mematok biaya haji sebesar 14,5 Pounds.
Infrastruktur penyelenggaraan haji juga disiapkan. Pemerintah Belanda lewat Konsulat Jenderal di Jeddah, Arab Saudi, kembali berfungsi untuk mengatur proses haji di Tanah Suci. Transportasi dan pendamping di Tanah Suci yang ditunjuk adalah perusahaan perkapalan yang tergabung dalam Kongsi Tiga.
Rayuan NICA untuk berhaji sedikit menggoda para tokoh Islam. Bahkan tokoh agama dari Jawa Timur yang masih punya semangat melawan paling heroik ikut berpikir ulang dan ingin berhaji.
Tak tinggal diam, tokoh agama yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan melawan balik. Harian Masyumi Al-Djihad membalas kunjungan Van der Plas ke Kalimantan Selatan sebagai "alat propaganda Belanda."
Propaganda Masyumi dan syiar Hasyim Asyari berhasil menggagalkan rayuan NICA. Tercatat hanya 70 jemaah dari 3000 kuota haji, yang akhirnya memilih untuk berangkat. Kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan dan Sumbawa, yakni dua wilayah yang sepenuhnya berhasil diduduki Belanda selama masa revolusi fisik. Sementara jemaah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang awalnya mendaftar kemudian membatalkan ibadah haji.
“Saat masa revolusi fisik, sejatinya Indonesia mengalami blokade darat udara laut. Alhasil semangat untuk berhaji menurun karena prioritasnya fokus kepada perjuangan melawan penjajah yang datang. Dan hal tersebut erat kaitannya dengan ulama-ulama dari pesantren yang menyerukan untuk mengutamakan mempertahankan kemerdekaan pasca Agresi Militer Belanda 1 dan 2 ,” jelas Kepala Studi Timur Tengah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Yon Machmudi.
Sementara mereka yang tak berangkat melanjutkan perlawanan. Sikap tidak kooperatif tokoh agama membuat Belanda marah, kemudian melancarkan Agresi Militer Belanda Pertama pada Agustus 1947.
Mereka yang berangkat menghadapi terbatasnya fasilitas Belanda. Goksoy mencatat bahwa ketidakstabilan ekonomi dan terbatasnya mata uang luar negeri jadi kendala. Kenyataannya, hal itu membuat fasilitas yang mereka sediakan tidaklah memadai.
Kondisi hidup para jemaah di atas kapal dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Menurut penuturan K.H Abdussamad dalam buku Naik Haji di Masa Silam tahun 1900 - 1950, banyak jemaah yang hanya mendapatkan ruang 60 x 100 cm saja.
“Masing-masing berusaha mencari tempat di bawah-bawah tangga, di balik-balik mesin pengangkat dan sebagainya. Bahkan jemaah haji kerap kali dimintai uang tambahan di luar nominal yang telah mereka bayarkan,” ungkapnya.
Dalam perkembangannya Belanda kemudian memperbaiki tata kelola haji. Perjalanan haji diorganisasi Departemen Dalam Negeri bersama Kongsi Tiga. Dibentuk pula badan-badan lokal untuk membagi kuota: Badan Pengoeroes Keselamatan Hadji di Indonesia Timur, Madjelis Oelama Islam di Kalimantan, sementara di Surabaya diserahkan kepada sebuah panitia beranggotakan lima orang.
Jumlah jemaah haji yang dikelola Belanda semakin meningkat seiring semakin banyak wilayah RI yang direbut. Data yang dihimpun Goksoy menyebutkan pada September 1947, jumlah jemaah haji melesat jadi sekira 4.000 orang. Kemudian pada 1948 menjadi 9.000 orang mayoritas berasal dari Indonesia Timur dan Kalimantan.
Lonjakan jemaah haji itu terjadi karena Belanda sudah mengendalikan wilayah-wilayah pedalaman. Menurut Goksoy situasi ekonomi dan politik saat itu lebih kondusif. Meskipun ada saja kalangan garis keras, terutama militer Belanda, yang tak senang dengan pengiriman banyak jemaah ke Mekkah karena para haji yang kembali ditakutkan dapat mengobarkan semangat perlawanan. Namun secara politis hal itu dilihat otoritas politik dan sipil masuk akal untuk tujuan propaganda, merengkuh hati rakyat di daerah pendudukan melawan Republik.
Belanda juga berusaha menancapkan pengakuan internasional atas penjajahannya dengan membawa tema ibadah haji. Sikap keras negara Timur Tengah yang mulai mendukung kemerdekaan Indonesia sebisa mungkin diredam. Belanda juga mengirim misi kehormatan (Emir Al-Hadj) untuk menemui Raja Ibnu Saud; dari Indonesia Timur dipimpin Menteri Agama Bachdim dan Kalimantan Barat dipimpin Sultan Pontianak Hamid II Alkadrie.
Namun sayang, misi kehormatan Belanda gagal dengan keberadaan Dr. H.M. Rasjidi, selaku Menteri Agama Indonesia yang berangkat ke Timur Tengah guna meminta dukungan dan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Raja Ibnu Saud pun menjamin pemerintah Saudi tak akan menunda pengakuan kepada Indonesia, yang akhirnya diberikan pada 22 November 1947. Sementara Bachdim dan Hamid sebagai perwakilan Belanda hanya mendapat kehormatan berupa hadiah pedang dari Raja Ibnu Saud.
Sementara itu, pergulatan Indonesia meraih kedaulatan penuh terus berlangsung. Pemerintah Republik lewat Kementerian Agama di Yogyakarta lewat siaran radio pada 25 Mei 1948 menyiarkan adanya kemungkinan mengirimkan jemaah haji.
Janji ini membuat pemerintah Belanda ketar-ketir. Belanda lewat Sekretaris Departemen Dalam Negeri P Bollen mengatakan jika pengiriman haji oleh pemerintahan republik tidak berdasar karena terganjal aturan. Belanda juga khawatir jika langkah ini berjalan, maka monopoli jalur perkapalan bakal terusik karena pemerintah Republik ditengarai bakal menggunakan jasa kapal dari negara lain.
Memasuki Agustus 1948 tidak tampak kejelasan dari pemerintah Republik soal pengiriman jemaah haji. Belanda merasa politik rayuannya berhasil. Apalagi, kepulangan rombongan jemaah haji pada Desember 1948 tidak menimbulkan gejolak politik yang berarti. Hal ini disebabkan karena mereka yang pulang berasal dari wilayah yang sejak awal tunduk pada Belanda.
Jumlah jemaah haji di tahun berikutnya menyusut. Untuk memenuhi kuota 8.600, Belanda masih mengandalkan wilayah-wilayah seperti beberapa wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Sementara kelompok Islam asal Jawa dan Sumatera memilih ikut perang gerilya usai Belanda menguasai ibu kota Republik di Yogyakarta pada Desember 1948.
Perlawanan demi perlawanan yang masih menggertak dan derasnya dukungan internasional meneguhkan kedaulatan, serta Konferensi Meja Bundar pada 1949 yang mengakhiri kedudukan Belanda, ikut memerdekakan jalur jemaah haji. “Sejak saat itu, kepentingan Belanda terhadap haji Indonesia ikut berakhir,” tulis Goksoy.
Tercatat hingga 1950, pemerintah Republik tidak langsung menangani urusan haji. Perusahaan shipping Belanda bersaing dengan perusahaan Inggris untuk menyediakan transportasi bagi sebanyak-banyaknya jemaah haji. Namun, mereka tidak memperhatikan kenyamanan dan keselamatan jemaah di perjalanan maupun di Tanah Suci. Makanan serta fasilitas di dalam kapal tidak diperhatikan dengan baik.
Minimnya kualitas layanan jemaah haji itu menyita perhatian Menteri Agama, Wahid Hasyim kala itu. Dia lalu mendirikan Indonesian Haj Comitee Foundation pada 21 Januari 1950 yang dipimpin KH M. Sudjak. Wahid juga menetapkan Dekrit Kementerian Agama No. 3170/1950 dan di Jogjakarta dan menetapkan Dekrit No. AAIII/648/1959, yang menetapkan Indonesian Haj Comitee Foundation sebagai satu-satunya organisasi resmi yang mengatur jemaah haji di Indonesia.
Wahid mengatur hal-hal yang berkaitan dengan haji, seperti kuota dari setiap provinsi, daftar harga yang harus jemaah bayarkan, serta menyediakan kapal untuk transportasi. Pada tahun 1951, pemerintah menyediakan kapal dari Kongsi Tiga dan Inaco. Namun, dua kapal itu masing-masing hanya mampu menampung 11.000 dan 14.000 jemaah. Untuk menampung sisanya, Wahid bersama timnya pergi ke Jepang untuk mencari kapal tambahan. PT Pelayaran Muslim pun dibentuk pada 1952.
Namun seiring berjalannya waktu, pergi hanya dengan menggunakan kapal mulai ditinggalkan karena durasi yang lama. Pada tahun 1952, perjalanan haji sudah mulai beralih ke transportasi udara.