Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
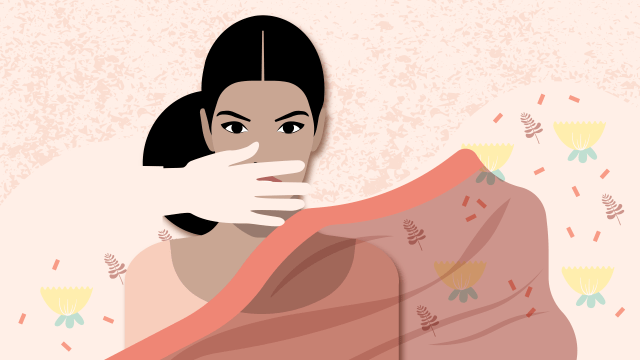
ADVERTISEMENT
Gerakan #UninstallFeminisme tengah berkembang di media sosial. Dimotori akun Instagram Indonesia Tanpa Feminis. Sebuah akun Instagram yang percaya bahwa Indonesia tidak butuh feminisme.
ADVERTISEMENT
Dalam sejumlah unggahannya, Indonesia Tanpa Feminis mempertentangkan ide feminisme dengan Islam. Mereka berkesimpulan bahwa feminisme merupakan produk Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Memang, tuduhan itu tidak salah jika dilihat dari perspektif sejarah. Alasannya, sebagai sebuah gerakan politik, kesadaran tentang feminisme muncul pertama kali pada tahun 1792 di Inggris. Yakni, lewat buku berjudul ‘A Vindication of the Rights of Woman’ karya filsuf Inggris, Mary Wollstonecraft.
Wollstonecraft menerbitkan buku tersebut usai revolusi Prancis meletus. Kala itu, dia melihat adanya partisipasi politik yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu, dia menilai, penggulingan monarki absolut seharusnya dapat menjadi momentum bagi perempuan untuk bergerak.
"Telah tiba waktunya untuk mempengaruhi sebuah revolusi melalui cara perempuan. Telah tiba waktunya untuk memulihkan kewibawaan perempuan yang telah hilang,” tulis Wollstonecraft.
ADVERTISEMENT
Menariknya, Wollstonecraft sama sekali tak menggunakan istilah feminisme dalam bukunya tersebut. Kala itu, kesadaran tentang ketidakadilan yang menimpa perempuan biasa diterjemahkan sebagai gerakan perempuan (women’s movement).
Sebab sebagai sebuah istilah, feminisme justru baru muncul pada tahun 1808. Istilah itu digunakan filsuf Prancis Charles Fourier untuk menggambarkan sosialisme utopis. Kala sekat antara perempuan dan laki-laki lenyap dalam relasi sosial.
Jauh sebelum Wollstonecraft maupun Fourier menggagas pemikirannya itu, nasib perempuan di Prancis memang tidak sebaik saat ini. Negara itu sudah sejak lama menomorduakan perempuan di segala bidang. Perempuan kerap berada di rumah sementara laki-laki berada di garis depan. Sejumlah negara Eropa lainnya pun mengalami situasi semacam itu.
Masyarakat Eropa kala itu teramat percaya bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pikiran semacam itu pun sebetulnya bukan barang baru, tapi sudah mengakar dalam peradaban barat selama ribuan tahun.
ADVERTISEMENT
Kedudukan Perempuan di Yunani Kuno
Sebelumnya, gagasan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki sudah ada sejak abad ke-4 SM. Masyarakat Yunani kuno menempatkan perempuan sebagai sosok yang inferior. Itu mengapa setiap ada pemilihan umum, perempuan tidak pernah dilibatkan. Perempuan dianggap tidak memiliki rasionalitas seperti laki-laki.
Bukan cuma itu, perempuan yang sudah menikah ditempatkan sebagai sosok yang harus tunduk terhadap suaminya. Hukum di Athena pun membiarkan seorang suami untuk bertindak sesuka hati. Termasuk, untuk berbuat zina dengan pelacur. Sebaliknya, jika perempuan yang berbuat zina, si suami berhak membunuh istrinya itu.
Soal warisan pun demikian. Perempuan tak berhak memperoleh warisan dari orang tuanya. Yang terjadi, justru perempuan itu sendiri yang menjadi barang warisan.
ADVERTISEMENT
Belum lagi mengenai pendidikan, perempuan tak pernah mendapatkan itu. Filsafat dan kebijaksanaannya pun hanya untuk laki-laki. Sementara perempuan, dituntut untuk berada di rumah dan mengasuh anak-anak mereka.
Praktik semacam itu tentunya aneh jika diterapkan saat ini. Namun, masyarakat Yunani kuno berpandangan bahwa tubuh perempuan adalah milik laki-laki. Ungkapan ‘My Body is Not Mine’ menemukan maknanya di masa itu.
Aristoteles pun tak menyangkal praktik sosial tersebut. Alih-alih membela perempuan, dia justru menegaskan bahwa perempuan bukanlah manusia yang sesempurna laki-laki.
Penegasan itu yang lantas dikentalkan menjadi sebuah karya filsafat, seperti dalam ‘Politics’. Sejak saat itu filsafat barat adalah filsafat yang berperspektif laki-laki.
Berbeda dengan Aristoteles, Plato justru menciptakan sedikit celah untuk kesetaraan perempuan Dalam Republic, guru dari Aristoteles itu mengungkapkan perempuan dan laki-laki berbeda dalam kekuatan dan virtue (keutamaan). Namun, dia percaya bahwa rasionalitas perempuan bisa menyamai laki-laki jika memperoleh pendidikan.
ADVERTISEMENT
‘Jika kita menginginkan perempuan bisa bekerja seperti pria, maka kita harus mengajarkan mereka hal yang sama,” kata Plato.
Tapi tentu saja, Plato tidak seradikal itu dalam merealisasikan pendapatnya. Malahan, Plato sebetulnya tetap merendahkan perempuan. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan Sena Iskigil dalam ‘A Study On Plato’s Attitude Towards Women’.
Dalam ‘Republic’ karya Plato pula misalnya, dia berpendapat bahwa pengajaran yang sama dapat diberikan kepada perempuan untuk menjadi pelindung negara. Sebagai seorang pelindung, perempuan lalu menjadi properti milik bersama para laki-laki. Properti yang pada saat itu bisa digunakan untuk apa pun, termasuk dalam urusan seks.
Dari Pemberontakan ke Perdebatan
Butuh ribuan tahun untuk menyadari bahwa perempuan ada dalam kondisi yang tak menguntungkan. Dalam perjalanannya, filsafat melihat situasi tak menguntungkan itu sebagai buah dari budaya patriarki. Suatu kebudayaan yang menempatkan laki-laki sebagai pusat segala hal.
ADVERTISEMENT
Maka, sosok seperti Wollstonecraft menjadi satu dari sekian banyak perempuan yang memiliki kesadaran itu. Mereka melihat, dunia ini bekerja secara tidak adil. Seperti halnya kala perempuan tidak boleh sekolah, tidak bisa mendapat upah yang sama dengan laki-laki, tidak boleh menentukan nasibnya sendiri, hingga pada kajian filsafat yang selalu didominasi laki-laki.
Feminisme lalu kian bertumbuh. Menjadi sebuah gerakan pemberontakan yang terorganisir. Mereka mendorong kebijakan yang sebelumnya tak adil menjadi adil. Hasilnya, sejumlah aturan yang mengekang kebebasan perempuan pun lambat laun dihapuskan.
Persoalannya, feminisme bukan sekadar gerakan politik yang terhenti pada pemenuhan hak dasar. Sebaliknya, feminisme merupakan cara pandang. Dalam hal ini, feminisme merupakan terminus filsafat yang definisinya bisa berbeda antara satu filsuf dengan filsuf lainnya.
ADVERTISEMENT
Tidak mengherankan bila perdebatan soal apa itu feminisme tak kunjung usai. Sejumlah filsuf saling silang pendapat dan itu wajar. Karena sebagai sebuah filsafat, feminisme akan selalu berada dalam tanda tanya. Tidak pernah final.
Berbagai Aliran Feminisme
Feminisme lalu memiliki banyak sekali aliran. Ada feminisme liberal, ekofeminisme, feminisme anarkis, feminisme marxis, feminisme radikal, feminisme post-modern, serta banyak lagi lainnya.
Agenda yang dibawa sejumlah aliran feminisme itu pun jadi kian beragam. Dalam feminisme liberal misalnya, isu yang diangkat adalah soal perempuan yang mesti punya peran dalam proses legislasi. Feminisme liberal memperjuangkan agar perempuan masuk ke dalam lembaga eksekutif maupun parlemen.
Di Indonesia, gagasan feminisme liberal itu terwujud dalam kuota 30 persen perempuan di kepengurusan partai politik. Saat mengajukan caleg, parpol pun dituntut untuk mengakomodasi kuota tersebut.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, feminisme radikal justru mengajukan gagasan untuk membongkar tatanan masyarakat. Feminis radikal percaya bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena budaya patriarki.
Victoria Arkhipenko dalam ‘Reconsidering The Conventional Private/Public Dichotomy: Examining The Femen Movement Through The Arendtian Lens of the Social’ melihat. contoh nyata dari feminisme radikal ditunjukan oleh organisasi FEMEN. Organisasi feminis asal Ukraina itu menggugat struktur sosial dengan cara bertelanjang dada.
Cara yang terbilang ekstrem itu dilakukan FEMEN demi merobohkan budaya patriarki. Feminisme yang dicontohkan Femen adalah kebebasan mutlak. Hal itu dilakukan sebagai penegasan bahwa tubuh perempuan adalah milik perempuan itu sendiri.
Meski percaya bahwa otoritas tubuh perempuan milik perempuan, FEMEN tidak mengizinkan anggotanya untuk menutup aurat. Sebaliknya, aurat dianggap sebagai manifestasi dari budaya patriarki. Di tangan FEMEN, perempuan berhijab yang mengaku feminis pun akan dicap sebagai musuh.
ADVERTISEMENT
Pendefinisian feminisme yang seperti itu jelas bukan tanpa kritik. Filsuf feminis Prancis Julia Kristeva misalnya, yang mengatakan kebebasan di dalam feminisme justru terletak pada individu, bukan kelompok. Selama perempuan memilih untuk berhijab atas kesadarannya sendiri, serta tanpa paksaan, maka itu tak jadi soal.
Otoritas tubuh yang dipahami Kristeva barangkali terdengar lebih bijak. Dalam sebuah suratnya kepada Ketua Komnas HAM Prancis pada 1990, Kristeva menyebut, pemerintah Prancis bertindak menindas dengan tak mengizinkan pelajar untuk mengenakan hijab.
Pada akhirnya, gagasan feminisme bukanlah hal yang final. Konsep feminisme akan terus berkembang sebagai ikhtiar untuk mendekati keadilan. Yang terbaik lantas bukan menolak feminisme.
Itu karena, tanpa ada istilah feminisme pun perjuangan perempuan terhadap keadilan tak dapat dibendung. Ini persis seperti Wollstonecraft yang mendeteksi adanya ketidakadilan, meski dia tak menamakannya sebagai feminisme.
ADVERTISEMENT
