Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.101.0
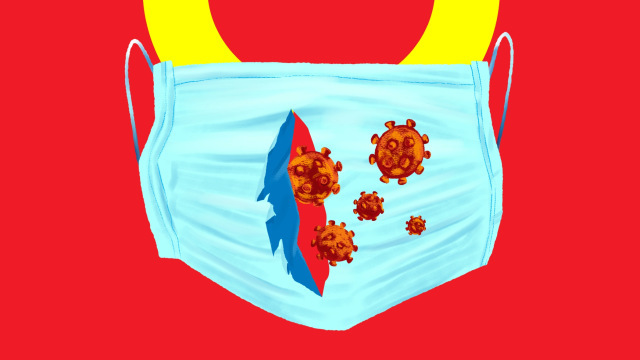
Virus corona dari Wuhan, China, sudah menjalar ke 155 negara. Indonesia yang semula tampak santai dengan memilih memberi diskon tiket pesawat dan insentif untuk influencer kini tampak gelagapan menghadapi wabah bernama Coronavirus Disease-2019 (Covid-19).
Hingga Selasa (17/3) ada 172 warga Indonesia terinfeksi corona, 5 di antaranya meninggal dunia. Namun banyak orang percaya bahwa jumlah riil di lapangan melebihi data yang dikeluarkan pemerintah secara resmi. Sebab fasilitas kesehatan yang ada belum cukup untuk menampung warga yang hendak melakukan tes, dan lebih banyak lagi warga yang tidak mampu mengakses fasilitas tes kesehatan baik karena jarak atau biaya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya belum berpikiran untuk memberlakukan karantina atau lockdown secara lokal maupun nasional. Berlawanan dengan pernyataan Jokowi, pemerintah provinsi Kalimantan Timur justru tetap berinisiatif untuk memberlakukan lockdown di wilayahnya. Sementara pemerintah daerah lainnya, seperti Malang, meski tak menyebut kebijakannya dengan lockdown tetapi berniat membatasi penduduk yang masuk atau meninggalkan wilayah kota Malang.
Wabah virus corona yang telah menjadi pandemi global bukan kali pertama terjadi. Jauh sebelum bernama Indonesia, wilayah kepulauan nusantara ini juga telah beberapa kali dilanda wabah penyakit mulai dari malaria hingga pes.
Dalam buku berjudul Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural misalnya menyebut malaria yang mewabah di Batavia sejak 1733. Wabah tersebut setidaknya menewaskan hampir 100 orang per tahun setelah pandemi menjalar.
Menurut sejarawan Universitas Indonesia, Agus Setiawan, saat itu VOC belum menyadari sumber mewabahnya malaria. Mereka beranggapan gaya hidup penduduk yang tinggal di pemukiman padat lah yang jadi musababnya. Butuh waktu puluhan tahun untuk menyadari bahwa pandemi itu disebabkan oleh protozoa parasit bernama Plasmodium malarie yang ditransmisikan melalui medium nyamuk.
Setelah itu upaya pemberantasan jentik nyamuk pun dilakukan dengan menutup pertambakan di wilayah utara Batavia. Hingga tahun 1900-an, malaria masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Menurut buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia, pada tahun 1911 didirikan Jawatan Kesehatan Sipil untuk melakukan penyelidikan dan pemberantasan malaria. Upaya tersebut berlanjut hingga tahun 1924 dengan adanya pembentukan Biro Malaria Pusat atau Centrale Malaria Bureau yang menggalakkan riset soal malaria.
Buku tersebut menceritakan bahwa, “Saat itu para mantri malaria ditugaskan menentukan jenis nyamuk dan jentik, memeriksa persediaan darah, mengadakan pembedahan lambung nyamuk serta membuat peta wilayah.”
Wabah lainnya yang pernah menimpa nusantara yakni cacar, kolera, dan pes. “Padatnya penduduk di Jawa membuat kontak penyakit lebih cepat, intens, dan cepat menyebar,” ucap Agus. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan Sumatera di masa kolonial ketika wabah hanya menjangkit satu desa dan bisa terisolir lebih cepat karena terbelah oleh ngarai atau sungai besar.
Cacar
Mengutip buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia, cacar pertama kali menjangkiti Batavia pada 1644. Penyakit tersebut masuk ke Batavia lalu menyebar ke seantero Jawa melalui anak-anak budak belian yang dibawa dari negeri kepulauan di dekat Afrika, Mauritius (Isle de France).
Untuk mengatasi wabah yang diakibatkan oleh virus dan menyerang kulit ini, pemerintah kolonial Belanda hanya memeriksa dan memberi vaksin terhadap pribumi yang memiliki riwayat kontak dengan orang Eropa. Namun wabah tersebut terus menjalar, sehingga vaksin akhirnya diberikan juga kepada pribumi. Hingga akhir abad ke 18, tingkat kematian bayi karena cacar berada di angka 10-20 persen.
Pemberian vaksin saat itu terkendala oleh kurangnya petugas kesehatan di lapangan. Sementara cacar telah menewaskan buruh-buruh pekerja perkebunan dan melumpuhkan ekonomi. Untuk menjalankan program vaksinasi itu, pemerintah kolonial kemudian mendidik pribumi di beberapa rumah sakit.
Alasannya, selain demi menambah petugas kesehatan, tapi juga karena keengganan mereka untuk turun langsung di lapangan. “Karena orang-orang Eropa enggak mau terjangkit penyakit Asia. Dia enggak punya imunnya, itu alasannya,” komentar Agus.
Pemerintah kolonial juga kemudian membangun Sekolah Dokter Djawa di Batavia pada 1851 dan menggratiskan seluruh biaya pendidikan selama masa studi dua tahun. Pembuatan dan pendistribusian vaksin cacar pun mengalami perkembangan.
Kemajuan mulai terlihat tahun 1884 ketika dr. A. Schukink Kool berhasil membuat vaksin di Jatinegara dengan menggunakan sapi sebagai tempat pembiakan. Lalu tahun 1926 dr L. Otten berhasil menyempurnakan pembuatan vaksin dari larutan dalam gliserin menjadi vaksin kering in vacuo. Setelah itu, cacar tak lagi mewabah di Indonesia.
Kolera
Wabah satu ini diperkirakan masuk ke Indonesia pada 1821. Penyakit akut dan menular yang disebabkan bakteri ini biasa ditandai dengan buang air terus menerus dan muntah-muntah.
Catatan seorang pegawai kolonial urusan pribumi, Roorda van Eysinga, menuliskan dalam Verschillende Reizen en Lotgevallen bahwa pada satu hari di Batavia bisa saja terdapat 160 orang mati akibat kolera. Mereka mengalami kejang-kejang hebat dan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Akibatnya, kolera menyebabkan kepanikan luar biasa di kalangan Eropa. Wabah tersebut menyebar lebih cepat dibandingkan penyakit epidemi lainnya semisal malaria.
Dikutip dari Historia, pada 1864 kolera merenggut nyawa sebanyak 240 orang Eropa. Sementara tingkat kematian di kalangan penduduk pribumi mencapai dua kali lipat dari jumlah tersebut. Persebaran bakteri kolera biasanya menular lewat air minum, makanan, dan kontak langsung.
Usaha menyetop kolera dilakukan dengan mengembangkan vaksin. Tahun 1911 vaksin kolera mulai dibuat oleh Nyland. Meski vaksin sudah diproduksi sampai 1920 kolera tetap mewabah setiap tahun. Wabah kolera baru berhenti pada 1927.
Pes (Sampar)
Mengacu pada buku Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia jilid II , pes masuk ke Indonesia pada akhir 1910. Sejak saat itu sampai tahun 1952 pes telah menyerang kurang lebih 240.000 orang di Pulau Jawa. Artinya, setiap hari sekitar 6.000 orang terjangkit. Jumlah penderita terbanyak tercatat pada 1934, sebanyak 23.275 orang terjangkit. Angka mortalitas penyakit pes pun sangat tinggi. Ribuan orang meninggal akibat penyakit tersebut.
Pes sendiri adalah penyakit disebabkan oleh bakteri pes dan menular melalui kutu-kutu tikus (Xenopsylla cheopsis). Penyebarannya saat itu melalui angkutan beras. Dalam angkutan beras itu terdapat tikus-tikus yang terjangkit pes sehingga kemudian dari pelabuhan Surabaya menyebar ke Malang, Kediri, Madiun, dan Yogyakarta. Sementara itu, melalui pelabuhan Semarang penyakit pes masuk dan merembet ke Ambarawa, Salatiga, Magelang Wonosobo, Banyumas, hingga ke Purwokerto pada tahun 1919 .
Penyakit pes, menurut Agus, adalah salah satu wabah yang paling mengerikan yang pernah dihadapi masyarakat Indonesia. “Mengerikannya itu karena dibarengi dengan tanda petik, seperti kondisi pembiaran pemerintah kolonial terhadap sanitasi yang begitu buruk,” Agus menerangkan.
Pemerintah Kolonial saat itu, menurut Agus, justru begitu mengkhawatirkan banyaknya petani yang meninggal dunia akibat pes. Sebab, di masa penjajahan petani adalah aset. Mereka adalah tenaga kerja terampil tanpa perlu edukasi.
“Kenapa? Karena orang tuanya mendidik langsung. Petani-petani Jawa itu dari kecil bawa anaknya ke sawah, ke ladang. Melihat langsung cara bercocok tanam,” ujar Agus.
“Nah, pada titik wabah itu banyak yang meninggal. Jadi, yang dikhawatirkan sebenarnya itu masalah kapital, produksi. Jadi baru dia bergerak,” Agus menambahkan.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kolonial mulanya mencoba memperbaiki perumahan warga supaya tidak menjadi tempat bersarang tikus. Namun cara tersebut gagal. Vaksinasi yang dilakukan di waktu bersamaan juga tidak membuahkan hasil signifikan. Meski penderita tersembuhkan, sumber penyakit belum terbasmi saat itu.
Barulah pada 1952 penyemprotan DDT (diklorodifeniltrikloroetana) ke rumah-rumah dengan menyasar tempat persembunyian tikus menemukan hasil memuaskan. Pes menghilang dari rumah-rumah yang telah disemprot dan tidak kembali lagi.
