
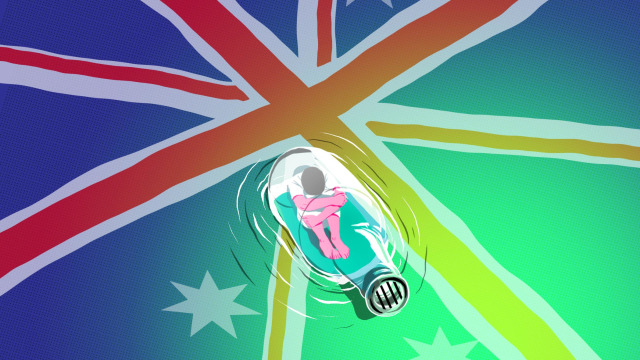
Tergiur gaji besar, anak-anak itu berani ambil risiko untuk pergi jauh mengembangkan layar. Mereka tak pernah bertanya pekerjaan apa yang sedang mereka lakukan. Hingga petaka datang menyeret mereka ke balik jeruji besi.
Bukan uang, malah duka dan trauma yang mereka bawa ketika pulang ke Indonesia. Berikut kisahnya.
***
Pusara itu hanya berupa gundukan pasir yang dikelilingi oleh batu-batu karang. Di ujung bagian yang dianggap sebagai kepala sebuah papan kayu terpatok. Guratan yang tertera hanya bertuliskan:
Erwin
L 28-2-95
W 24-2-12
Siang itu kami di antara lelaki kurus dan pendiam bernama Baco Ali ke makam Erwin di Desa Delua, Rote Barat Laut, Nusa Tenggara Timur. Ali adalah adik Erwin. Keduanya terpisah delapan tahun lamanya setelah sang ibu tutup usia. Sementara Ali mengikuti Bapaknya, Erwin hidup sendiri.
Ali kembali ke Rote pada 2009 setelah bapaknya meninggal. Pulang ke kampung halaman, ia tak bisa mendapati kakaknya berada di mana. Hingga satu hari di tahun 2010, Erwin pulang ke rumah. “Sakit dia. Ada bekas operasi di perutnya. Katanya dioperasi pas di Australia,” tutur Ali saat ditemui kumparan, 23 Agustus lalu.
Tapi reuni kakak beradik itu tak berlangsung lama. Tanpa sempat bercerita bagaimana mereka melalui nasib masing-masing, sakit yang diderita Erwin kambuh. Rasa sakit dari luka bekas operasi di perutnya menyerang, membuat Erwin terus mengerang.
“Katanya sakit di bekas operasinya itu. Dulu operasinya waktu itu usus. Cuma pegang (perut) begini aja dia. Terus kayak mau muntah-muntah dia,” tutur Ali sembari menirukan laku sang kakak.
Ali segera membawa Erwin ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, di Pulau Rote. Pihak RSUD Ba’a yang tak kuasa menangani Erwin merekomendasikan Ali agar membawa kakaknya ke kota.
Ia pun membawa Erwin menyeberangi laut dari Rote menuju Kupang. Setelah seminggu lebih dirawat di RSUD Prof WZ Johannes Kota Kupang, Erwin mengembuskan napas terakhir. “Katanya penyebab (kematiannya) bekas operasinya dulu itu,” kenang Ali.
Teman satu tahanan Erwin di Darwin Correctional Centre, Abdul Rayan, bercerita bahwa Erwin memang sempat dibawa ke rumah sakit. “Saat bermain bola voli bersama tahanan lain, Erwin hanya memegangi perut dan mengaku kesakitan. Dia nggak bisa berdiri lurus, dari situ langsung dibawa ke rumah sakitnya.”
Namun keesokan harinya Erwin sudah kembali dipulangkan. “Saya tanya, ‘Kamu sakit apa?’ Dia jawab sakit usus buntu,” kata Abdul. Ia dan Erwin, yang saat itu masih berusia awal belasan tahun, kemudian berpindah penjara. Mulai dari Penjara Hakea di Canning Vale, Australia Barat, hingga ke Penjara Regional Albany—dengan pengamanan maksimal untuk narapidana narkoba hingga pembunuhan.
Ketika di Albany, Erwin bertemu Colin Singer yang merupakan aktivis HAM Australia sekaligus peneliti di Indonesian Institute—lembaga nonpemerintah yang fokus pada perlindungan hak sipil. “This kid (Erwin) is very important for me. Dia adalah alasan mengapa saya melakukan ini (advokasi),” ucap Colin kepada kumparan di Westin Hotel, Jakarta Selatan, bulan lalu.
Pertemuannya dengan Erwin terjadi pada 2010. Saat itu Colin sengaja mengunjungi penjara Albany. “Anak-anak Indonesia yang kutemui di penjara itu bercerita bahwa Erwin sangat sakit. Dia mengerang kesakitan siang dan malam.”
Namun suatu hari, ketika Colin kembali berkunjung dia kaget bahwa Erwin sudah dipulangkan begitu saja. “Mereka mengirim pulang Erwin ke Kupang tanpa memberinya obat, uang. Tanpa apa pun. Karena jika dia meninggal di Australia akan ada proses formal, mereka sepertinya tidak menginginkan itu.”
Erwin hanya satu dari ratusan anak yang dipulangkan ke Indonesia setelah ditahan di Australia. Anak-anak itu ditangkap karena menjadi ABK (anak buah kapal) dalam pelayaran yang membawa puluhan imigran ilegal ke Negeri Kangguru.
Sebagian besar dari mereka berasal dari Nusa Tenggara Timur yang memang terbiasa melaut. Tergiur gaji besar, anak-anak itu berani ambil risiko untuk pergi jauh mengembangkan layar. Mereka tak pernah bertanya pekerjaan apa yang sedang mereka lakukan.
Misalnya saja Hasto. Sejak usia 9 tahun ia sudah terbiasa melaut mencari ikan. Di usia 11, Hasto terpaksa berhenti sekolah dan menjadi tulang punggung keluarga demi membiayai ibu dan adik perempuannya.
Satu ketika ia mendapat tawaran menjadi koki di kapal besar pemuat kayu di Kupang. Ia pun akhirnya berangkat dengan bayangan dirinya bisa mengarungi lautan di Indonesia dan mengirim uang untuk biaya sekolah sang adik satu-satunya.
Namun ketika kapal merapat di Surabaya ia mulai bertanya-tanya. “Merapat di daratan Surabaya tapi tidak di Tanjung Perak. Saya tidak tahu juga karena tidak cek GPS. Jam 12 malem, orang-orang Timur Tengah datang,” ucap Hasto.
Ia pun diperintahkan untuk mengatur makanan agar bisa mencukupi semua orang. “Karena cuaca buruk, mereka tidak mau makan. Hanya minum air saja.” Rasa penasaran membuat Hasto kemudian bertanya pada sang kapten.
“Kita mau bawa ke mana mereka ini?”
“Sudah diam, kamu ini terlalu banyak pertanyaan,” jawab si kapten saat itu.
Setiba di Sumba, si kapten menyuruh Hasto dan empat anak lainnya mengantarkan orang-orang dari Timur Tengah itu menggunakan kapal terpisah. “Hasto, mereka ini mau ke pulau kecil di sana. Nanti saya kasih tahu, nanti kamu kasih turun, lalu kamu balik,” ujar Hasto menirukan ucapan si kapten kepadanya.
Rasa senang menyergap karena itu artinya ia akan mengemudikan kapal sendiri, bukan lagi sekadar jadi koki. “Senang saya, tidak sadar. Merasa jadi punya kapal, karena dari kecil penginnya punya kapal,” ujarnya.
Hasto pun melanjutkan perjalanan. Hingga tiba datangnya malam. Pesawat patroli perbatasan Australia mengepungnya. Perasaan waswas lalu menyergap ia. “Saya tidak paham, saya tidak tahu kalau itu melanggar batas, saya tidak tahu itu patroli Australia. Mereka bilang setop.”
Hasto pun menghentikan kapal. Ia dan keempat ABK lainnya ditangkap karena diduga terlibat menyelundupkan imigran ilegal. “Saya ditanya dibayar berapa, seribu rupiah pun saya belum dibayar.”
Cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, Hasto meminta izin untuk menelepon keluarga. “Tapi saya lupa nomor teleponnya,” kata Hasto.
“Selama satu bulan setengah bolak-balikin angka kayak main togel. Sampai ketemu angka belakangnya. Sampai ketemu,” ucapnya mengingat pengalaman selama ditahan di Christmas Island Immigration Detention Center.
Karena tak ada uang yang bisa ia kirim, Hasto menyuruh adiknya untuk menjual motor demi membayar uang sekolah.“Saya stres, dua hari dua malam saya tidak bisa tidur, tidak bisa merokok. Mondar-mandir, mondar-mondar.”
Kurang lebih sebulan kemudian Hasto disidang dan terbukti tak bersalah. Ia pun dikirim pulang ke Bali.
Sementara Sandi Kasupa berani berlayar hingga merambah perairan Australia karena iming-iming Rp 15 juta yang bisa diperolehnya dalam sekali jalan. Tawaran yang datang kepadanya ketika ia berusia 14 tahun itu berasal dari sepupu sendiri. Alasannya semula untuk mencari ikan.
Sandi yang tiap pulang sekolah menemani sang ayah melaut tergiur mendengar tawaran tersebut. Maka Sandi pun izin pergi kepada orang tuanya, namun ia berangkat tanpa membawa surat identitas apapun.
Ia dan dua temannya diajak ke Surabaya terlebih dahulu sebelum akhirnya tiba di Bandara Soekarno Hatta. Dari sana, Sandi dibawa ke Pelabuhan Ratu melalui jalur darat. Sandi terkejut dan mulai menaruh curiga ketika melihat kapal yang dinaiki dipenuhi perempuan, laki-laki, ataupun anak-anak berwajah Timur Tengah.
Seingatnya, total penumpang yang dibawanya mencapai 69 orang. Selain para imigran ilegal—yang baru diketahuinya kemudian—kapal tersebut juga membawa banyak persediaan makan seperti beras, air, dan sayur-sayuran.
Meski semua tak sesuai janji, Sandi tak kuasa untuk balik kanan kembali ke Kupang. “Tak punya anggaran buat pulang,” katanya. Maka ia pun mulai berlayar entah menuju ke mana.
Hingga akhirnya ia mencapai perairan Australia dan dikepung tentara. Dalam kondisi panik, niatan untuk terjun ke laut sempat terbersit di kepalanya. “Mau lompat, tapi kaptennya bilang jangan. Karena di sini kan banyak ikan ganas, hiu,” ucap Sandi. Maka ia pun dibawa ke tahanan imigrasi di Pulau Christmas.
Sandi tergolong mujur karena pengakuannya sebagai anak berusia 14 tahun dipercaya aparat. Ia hanya ditahan beberapa bulan sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia melalui Bali pada 2014.
Hal berbeda dialami oleh Iwan Lailu, warga Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Iwan ditipu kenalannya, seorang kapten kapal di Pelabuhan Tenau, Kupang. Ia diminta ikut mengantarkan imigran gelap dengan modus ajakan pergi melaut.
Iwan ditangkap pada 2010 ketika ia baru menginjak usia 16 tahun. Namun, aparat Australia mengira Iwan sudah dewasa sehingga ia dijebloskan ke tahanan orang dewasa
Di sana ia mengalami cidera di area pinggul karena tertimpa tiang gawang. Iwan pun dilarikan ke sebuah rumah sakit di pulau tersebut. Setelah dirawat selama dua hari, Iwan diterbangkan ke sebuah rumah sakit di negara bagian Perth untuk dioperasi. Sebuah pen penyangga ditanam di bagian pinggul kirinya. Butuh waktu tiga bulan bagi Iwan untuk memulihkan diri
"Setelah selesai operasi baru dinyatakan sebagai anak-anak," kata Iwan. Setelah itu, ia mengalami perlakuan berbeda. Misalnya, pemerintah Australia menyediakan seorang petugas keturunan Malaysia bernama Azma yang dipekerjakan untuk mengurus para imigran. Ia pun mendapat perhatian lebih khusus dari petugas tersebut. "Pengen makan apa tinggal kasih tahu Pak Azma, dia masak," kata Iwan.
Dua tahun ditahan di Australia, Iwan akhirnya pulang setelah dinyatakan tak bersalah.
Masing-masing dari mereka tak mau lagi sembarang berlayar meski dengan iming-iming gaji besar. “Kena tipu lagi nanti itu,” ucap Hasto.
Sementara Sandi menegaskan ia tak lagi mau menginjak perbatasan. “Trauma banget, saya enggak mau lagi ke sana, ke perbatasan. Enggak lagi.”
Apalagi mengingat cidera fisik yang mereka bawa pulang setelah keluar dari penjara.
Menurut laporan Komisi HAM Australia (AHRC) berjudul An Age of Uncertainty yang dirilis pada tanggal 27 Juli 2012 di Sydney, pemerintah Australia memenjarakan lebih dari 180 anak Indonesia dalam kurun waktu 2008-2011. Beberapa diperlakukan secara kasar dan bahkan mendapat pelecehan seksual.
Banyak dari mereka telah melalui masa panjang di tahanan imigrasi tanpa dakwaan dan mendekam di penjara dewasa menunggu masa sidang. Dalam rapat perlemen pemerintah Australia pada 2011, para anggota dewan sepakat bahwa semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dalam dokumen berjudul Australian Government response to the Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee report: Crimes Amendment (Fairness for Minors) Bill 2011, pemerintah Australia menyatakan sulit untuk menerka usia seseorang. “Orang bisa dengan mudah berbohong dan mengaku anak-anak.”
Sementara Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia Judha Nugraha mengatakan, “Kita hadir untuk melakukan pendampingan hukum, menjamin hak-hak yang bersangkutan dalam sistem hukum negara setempat. Nah pada kasus ini, dia ditahan dan di bawah umur, kita prioritaskan untuk segera dipulangkan.”
Menurut Judha, karena kasusnya satu per satu berbeda, maka penanganannya berbeda. “Masing-masing kasus punya dinamikanya sendiri. Anak ini data kependudukannya sulit karena di daerah.”
Ketidaklengkapan data identitas dan atau kependudukan yang dimiliki anak-anak tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa. Maka, penanganan dirasa cukup hingga mereka pulang ke tanah air.
Sementara bagi Collin, anak-anak yang sempat mendapat perlakuan tak adil karena ditahan di penjara untuk orang dewasa dan sebagainya patut mendapat kompensasi dari pemerintah Australia. “Tapi untuk mendapat kompensasi itu bukan hanya sulit tapi juga rumit.”