Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.101.0
ADVERTISEMENT

“I’m not going to give you a question. You’re a fake news!” sembur Trump. Jarinya menuding-nuding wartawan yang duduk tercenung di depannya.
ADVERTISEMENT
Seberapa keras wartawan CNN tersebut mencoba meminta kesempatan untuk bertanya pada Donald Trump, sang presiden ke-45 Amerika Serikat itu tak menggubris, “Aku tak akan memberimu pertanyaan. Tolong diam.”
Bagi Trump, CNN dan Buzzfeed adalah media yang cuma bisa menelurkan fake news. Berita bohong. Hoaks. Namun demikian, dunia bisa sampai memiliki pria 70 tahun berambut pirang itu sebagai pemegang kendali senjata nuklir terbesar di dunia, juga disebabkan --mau diakui atau tidak-- oleh andil berita bohong.
Di sinilah cerdiknya Trump. Ia dengan fasih ia membolak-balikkan kenyataan. Ketika ia menuduh media-media mainstream seperti CNN menuduh pemerintahannya yang bukan-bukan, berbagai pihak justru telah membuktikan bahwa kemenangan dalam pemilihan presidennyalah yang justru dibantu oleh keberadaan fake news itu sendiri. Ironisnya lagi, berita-berita bohong tersebut justru diproduksi oleh tim pemenangannya sendiri --dan, ssst, Rusia.
ADVERTISEMENT
Kasus Amerika Serikat yang masih terus berjalan tersebut menunjukkan bahwa berita bohong maupun hoaks dapat merusak tatanan bernegara, politik, dan demokrasi itu sendiri. Juga jangan lupakan bagaimana masyarakat di level bawah AS tercerai berai gara-gara hoaks-hoaks yang tak berdasar --yang juga mudah sekali kita temukan di dalam negeri dengan hoaks-hoaks antiminoritas yang membawa intimidasi maupun perpecahan antar etnis.
Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat? Banyak yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia kurang kritis dalam membaca berita, sehingga tidak mau repot-repot mengkrosceknya ke media-media lain soal kabar hoaks tersebut. Meski begitu, menghindari media hoaks tak semudah yang diperkirakan.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Kristiono, pernah berujar bahwa masyarakat di Indonesia menyukai hal-hal yang heboh. “Ini berbahaya, karena bisa jadi perilaku. Mereka bisa memproduksi hoaks agar bisa menimbulkan kehebohan,” katanya.

Meski begitu, menurut Dannagal Young, peneliti dari University of Delaware, Amerika Serikat, menyalahkan pembaca yang menyebarkan berita bohong atau hoaks merupakan tindakan yang tidak adil apabila dilihat dari perspektif kognitif.
Melalui penelitiannya selama satu dekade, Young menemukan bahwa otak manusia merespons secara khusus informasi-informasi unik nan trivial ketimbang informasi lainnya. Apalagi ketika informasi tersebut dibumbui humor, seperti misalnya satir ataupun ketika suatu hal dianggap lucu dan menarik oleh pembaca.
ADVERTISEMENT
“Hal-hal yang punya konteks lebih menarik akan lebih mudah diingat oleh otak Anda,” ucap Young.
Memang, otak manusia memiliki kemampuan untuk memproses informasi dan mengingat fakta-fakta yang melakukan verifikasi terhadap hoaks-hoaks yang dikonsumsi sebelumnya. Meski begitu, walaupun argumen yang menyatakan hal tersebut adalah hoaks sangat kuat, hal-hal yang lebih trivial apalagi yang memiliki unsur humor akan lebih mudah diingat oleh otak.
“Setelah Anda memasukkan berita bohong di kepala Anda, ia akan tetap di situ selamanya. Anda tidak bisa tidak memikirkan hal itu,” ucap Young.
Hal ini dicontohkan dengan kalimat-kalimat yang, meskipun belum tentu benar, selalu kita percaya, seperti: “Trump itu bodoh”. Meski belum tentu benar, apa yang sudah tertanam di pikiran kita, dengan segala kehebohan Trump menjadi presiden AS, akan sangat sulit untuk dilupakan.
ADVERTISEMENT
Baca juga: Sejarah Hoaks dan Andilnya dari Masa ke Masa
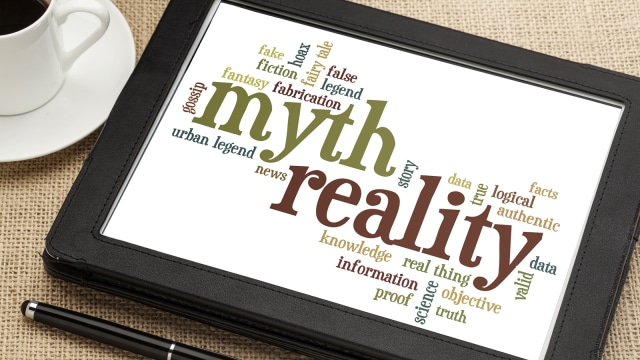
Parahnya lagi, keadaan media sosial sekarang membuat masyarakat terjebak pada apa yang dinamakan The Filter Bubble. Menurut penulis bernama Eli Pariser, internet membuat kita hanya mendapatkan apa yang kita sukai dan sudah setujui sebelumnya.
Hal ini didasarkan pada algoritma Google ataupun Facebook yang selalu merekam perilaku kita di internet. Pada gilirannya, internet akan menampilkan pada kita hal-hal senada dari apa yang selama ini kita konsumsi sebelumnya, bahkan ketika informasi-informasi tersebut merupakan hoaks.
Dan itu belum semuanya. Sebuah penelitian berjudul When Corrections Fail menjelaskan bahwa informasi koreksi, atau pembetulan, atau ralat, atau penjelasan bahwa sebuah informasi yang sebelumnya telah beredar ternyata hoaks, tidak mampu mengurangi mispersepsi yang telah terjadi sebelumnya.
ADVERTISEMENT

Sebuah kelompok yang sudah memercayai suatu hoaks secara kolektif, kecil kemungkinannya akan mengubah pikiran mereka setelah diberi informasi soal pembetulan informasi tersebut. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Brendan Nyhan dan Jason Reifler dari universitas Michigan dan Georgia tersebut menjelaskan adanya kemungkinan yang lebih buruk, yaitu “backfire effect”.
Efek tersebut, sederhananya, menyebut bahwa koreksi atas suatu hoaks justru akan menimbulkan kebingungan lain dan meningkatkan mispersepsi dari tingkat sebelumnya. Alasannya, senada dengan teori The Filter Bubble, adalah karena seseorang lebih sering mendapat apa yang sudah dia percayai, dan hanya mau memercayai apa yang dia suka.
Alih-alih menambah wawasan dan membuat seseorang makin bijaksana, internet era kini ditakutkan justru membuat pemikiran seseorang makin sempit dan bebal.
ADVERTISEMENT
