Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Konten dari Pengguna
Mata Uang Kerontang untuk Pramoedya
26 Februari 2025 11:58 WIB
·
waktu baca 7 menitTulisan dari Ahmad Mathori tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
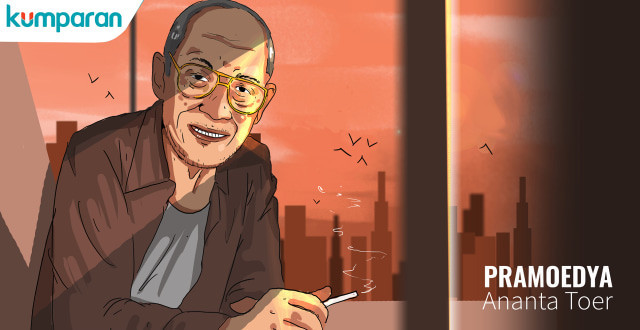
ADVERTISEMENT
Buku dengan sampul didominasi warna hijau dan coklat muda bertuliskan Bumi Manusia itu saya tutup perlahan seraya mereka ulang memori singkat tentang perjalanan atraktif sang tokoh utama, Minke. Menyusul itu, terlintas potret sang penulis dengan latar belakang buku bertumpukan serta mesin tik usang miliknya yang seketika membuat saya berkesimpulan mengagumi salah satu “Penulis Terpenting” yang dimiliki bangsa ini, ialah Pramoedya Ananta Toer (Pram).
ADVERTISEMENT
“Ini baru dari satu karyanya saja, lho.” Gumam saya sambil meletakkan buku tersebut di lemari berbahan kayu, lalu bergegas menghubungi kawan melalui gawai pintar dengan pesan bertuliskan; “Bro, saya mau balikin (mengembalikan) buku. Nanti saya ke rumah, ya.”
Buku yang saya pinjam dari kawan itu barangkali adalah satu dari banyaknya karya Pram yang (mungkin) paling fenomenal. Walau tentu saja pendapat tentang itu sangat bisa melahirkan dialektika perdebatan panjang di antara para pembaca karya-karyanya Pram, karena mungkin perbedaan masing-masing konteks yang ditangkap oleh mereka.
Tapi bagaimanapun, harus diakui, bahwa novel berjudul Bumi Manusia memang sefenomenal itu. Saking fenomenalnya, ia telah diadaptasi ke dalam sebuah film layar lebar sekitar lima setengah tahun silam dan berhasil mendarat mulus dengan capaian yang cukup signifikan.
ADVERTISEMENT
Kabar tentang capaian pada filmnya yang baru saya ketahui sebelum menulis catatan singkat ini pun seolah semakin meyakinkan saya bahwa berbicara tentang Pram, barangkali adalah sosok yang telah melampaui tajuk utama dalam konstelasi sastra sebagai disiplin yang melekat padanya. Lebih jauh dari itu, ia terlihat seperti warisan budaya yang dengan kompleksitasnya, mampu bersemayam dalam semangat kolektif manusia yang hidup di atas tanah bumi Ibu Pertiwi.
Tak ayal kemudian kalau di seratus tahunnya, banyak orang dari berbagai penjuru turut serta merayakannya.
Fenomena itu menuntun saya pada penangkapan sederhana tentang apa yang menjadi benang merah bagi pertemuan ribuan ekspresi para pembaca Pram. Hingga membuat saya bertemu pada satu kesimpulan, ialah, sebuah frasa bernama; “pengalaman membaca.”
ADVERTISEMENT
Kesan itu saya tangkap saat sedang menggulirkan gawai untuk memenuhi keperluan berselancar di media sosial dan melihat ribuan ekspresi yang mengudara dengan riang, seolah menyiratkan sesuatu yang saya asumsikan seperti cara kerja sebuah transaksi. Maka dengan begitu, pengalaman membaca adalah mata uang yang menjadi syarat mutlaknya.
Sehingga saya mulai membuat tafsiran naif tentang besaran “mata uang” yang akan berlaku sebagai nilai tukar pada gelanggang perayaan Se-Abad Pram. Mungkin, bagi mereka yang telah melahap habis karya-karyanya Pram adalah mereka yang bermata uang paling besar dalam hal ini. Begitu pun berlaku sebaliknya. Dimana, bagi seseorang seperti saya yang hanya bermodalkan Bumi Manusia, maka—hampir pasti—kerontang sekali mata uang yang saya miliki.
Kenyataan tersebut membawa kegusaran tersendiri pada diri saya. Sebab di satu sisi, saya merasa bahwa kenaifan saya terletak bukan hanya pada pendapat tentang pengalaman membaca sebagai mata uang di perayaan Se-Abad Pram, tetapi juga terbersitnya kegembiraan karena berkesempatan menyaksikan seratus tahun berdirinya nama besar seorang penulis yang saya kagumi bahkan sejak sebelum membaca karyanya.
ADVERTISEMENT
Posisi di ‘tengah-tengah’ yang saya rasakan ini seolah menjadi tempat tumbuhnya dua percabangan rasa yang masing-masing kutubnya tidak saling berdekatan. Saya ingin katakan bahwa situasinya seperti sebuah fenomena ambivalen—mungkin.
Entah bagaimana itu bisa terjadi, tapi konteks utama yang menjadi juara di pikiran saya adalah ekspansivitas rasa malu pada mata uang yang saya hendak tukarkan dalam siklus pertukaran ekspresi di perayaan Se-Abad Pram. Sebab ia sangat kerontang.
Untuk itu saya menjadi teringat pada satu ceramah dari pengampu filsafat di sebuah kesempatan saat menjelaskan tentang kapital (modal) dalam klasifikasi yang dibuat oleh Pierre Bourdieu. Sosok sosiolog berkebangsaan Prancis yang dikategorikan dalam postmodernisme itu memasukkan entitas budaya dalam teori modal yang dibuatnya.
“Ingat, ya. Modal itu bukan hanya tentang ekonomi, lho.” ucap si pengampu yang berbekal materi presentasi sebagai tonggak alur saat menjelaskannya.
ADVERTISEMENT
Sehingga sampai di sini, apa yang dikatakan oleh sang pengampu filsafat itu semakin mendekatkan saya pada konteks tentang kerontangnya sebuah mata uang, yang dalam hal ini berlaku sebagai alat tukar pada perayaan Se-Abad Pram.
Mengapa demikian? Singkatnya, bahwa modal budaya, yang salah satu refleksinya adalah melalui pengalaman membaca, maka kecil sekali jumlah modal yang dimiliki jika hanya Bumi Manusia sebagai pegangannya.
Saat sudah sadar akan sedikitnya modal budaya yang saya miliki, sialnya, saya coba mencari pembelaan dengan berlindung pada karakter sastra yang sangat inklusif. Sehingga hal itu mendorong saya untuk beranggapan bahwa pola perhitungan yang digunakan dalam mengukur besar/kecilnya suatu modal budaya yang dimiliki oleh seseorang, tidaklah sesederhana seperti apa yang saya kemukakan.
ADVERTISEMENT
Tapi bagaimana pun, ia tetaplah menjadi sebuah catatan khusus bagi saya pribadi yang sedang belajar menjadi adil sejak dalam pikiran.
Dialog Besar
Frasa “adil sejak dalam pikiran” barang tentu langsung mengarahkan kita pada sosok pembuatnya, yaitu; Pram. Kutipan tersebut mewakili pertemuan saya dengan Pram—sosok peretas zaman yang dengan gemilang menghadirkan semesta multikonteks pada dialog tak berkesudahan. Pasalnya, saya terlebih dahulu bertemu dengan kutipan tersebut sebelum sempat membaca karyanya.
Sehingga dalam momentum perayaan Se-Abad Pram, memori-memori yang bahkan terbilang kecil pun muncul bersama dengan euforia untuk kembali mendalami dialog besar dari karya-karyanya Pram yang lain.
Namun saya mengerti betul, bahwa proses memperbanyak modal budaya melalui pembacaan pada karya-karyanya Pram, adalah pekerjaan yang seakan tak berujung. Karena setiap halaman yang dilahirkan oleh Pram melalui mesin tik reot miliknya, menyiratkan bagian dari percakapan panjang yang terus beresonansi melintasi ruang dan waktu.
ADVERTISEMENT
Dari Pram, kita temui teks demi teks yang tak terisolasi dan seolah memancing percakapan-percakapan lain yang kemudian membentuk semestanya sendiri. Lebih jauh, pendapat saya tentang Pram kini tidaklah sekedar menilainya sebagai sosok sastrawan yang karya-karyanya telah dinikmati oleh warga dunia. Tetapi juga ia bertransformasi menjadi narasi utama dalam pergumulan setiap ide yang haus akan bentuk ideal.
Konteks di atas terbentuk dalam pikiran saya justru saat saya menangkap ekspresi dari para pembaca karya-karyanya Pram lainnya. Seolah menggambarkan suatu dialog besar sedang terjadi.
Saya tidak dapat menangkap kesemuanya, namun, untuk yang memiliki kedalaman seperti Muhidin M. Dahlan, deklarasi Pramis sebagai jalan yang dipilihnya adalah simbolisasi dari cara pandang hidup yang tepat. Sosok sejarawan berartikulasi membumi macam Hilmar Farid, dengan apik menyesapi setiap kontribusi Pram terhadap kemajuan peradaban dan mempelihatkan dengan terang sisi mendalam seorang sastrawan.
ADVERTISEMENT
Tidak berhenti sampai di situ, spirit intelektual langka yang dipancarkan oleh Pram, membuat seorang Indonesianis, Remco Raben, menyusuri semesta Pramoedya hampir di seluruh perjalanan akademisnya.
Gerbang Pembuka
Sampai di sini, kenaifan saya terasa semakin kontekstual. Bahkan ia berdiri sembrono dengan memaksakan kehendak vis-à-vis pada tokoh-tokoh hebat tersebut sebagai kesan tidak langsung yang ditimbulkannya. “Sudah jelas timpang, malah Anda paksakan juga!” Gumam saya pada diri sendiri.
Kendati pun begitu, barangkali sikap seperti yang saya gambarkan di atas—secara tidak langsung juga—adalah sikap pongah yang dimiliki oleh sebuah bangsa dengan ‘cepat berpuas diri’ sebagai salah satu karakter utamanya.
Karakter itu tidak datang dari kehampaan, melainkan ia telah mengakar kuat sejak bangsa ini menyadari bahwa kekayaan alam negerinya sangat mudah untuk didapatkan. Sehingga kita—mungkin saja—tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana cara mendapatkan sesuatu dengan upaya yang sepadan.
ADVERTISEMENT
Begitupun dengan pengalaman membaca—buku. Masifnya informasi hasil dari disrupsi zaman, mendorong tidak hanya satu dua orang untuk berkesimpulan cepat atas suatu informasi yang didapatkannya. Didukung oleh angka minat baca kita yang tiarap, seolah meyakinkan kenyataan pahit yang sudah kita amini dengan implisit.
Tidak ada tawaran ide selain kesadaran saya memetik detail pada gelanggang perayaan Se-Abad Pram yang secara tidak langsung telah menyalakan api semangat literasi dengan memasuki Pram sebagai pintu gerbang awalnya, seraya berucap kepadanya; “Apakah tidak suka membaca buku adalah salah satu karakter dari bangsa Indonesia yang engkau bayangkan, Pram?”
Selamat seratus tahun, Pramoedya!
Paus Fransiskus wafat di usia 88 tahun pada Senin pagi (21/4) akibat stroke dan gagal jantung. Vatikan menetapkan Sabtu (26/4) sebagai hari pemakaman, yang akan berlangsung di alun-alun Basilika Santo Petrus pukul 10.00 pagi waktu setempat.

