Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Solidaritas Sepakbola: Efisiensi Anggaran dan Tantangan Gerakan Keadilan Sosial
21 Februari 2025 11:21 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Maulana Alif Rasyidi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
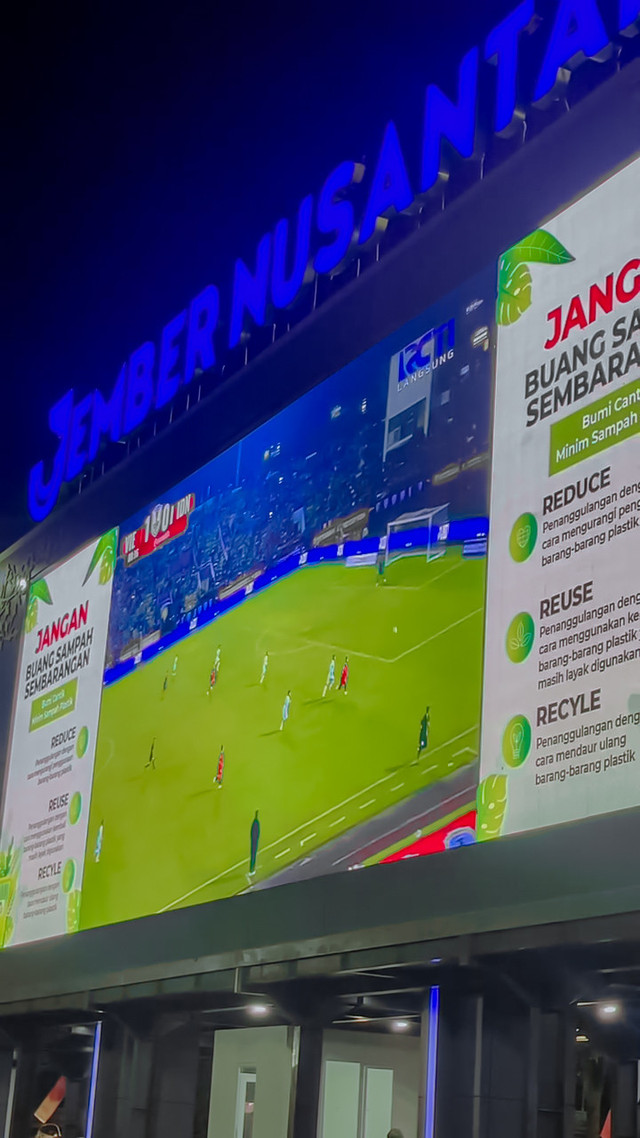
Mengubah Kesadaran Kolektif Sepakbola Menjadi Kekuatan Perjuangan Keadilan Sosial
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Sepakbola di Indonesia telah menjadi lebih dari sekadar olahraga—ia adalah manifestasi identitas kolektif yang membentuk solidaritas organik masyarakat. Tatkala berdiskusi perihal sepakbola, maka petani, nelayan, pegawai, abang bakso, tukang becak, tukang cukur, pedagang kaki lima, penjaga warung, hingga pimpinan daerah bisa menyatu dalam rasa yang sama. Intensitas perhatian publik terhadap tim nasional, yang tercermin dari rata-rata 45.000 penonton per pertandingan, menunjukkan apa yang Antonio Gramsci sebut sebagai "momen historis" dimana kesadaran kolektif bertransformasi menjadi kekuatan sosial-politik. Fenomena ini memperkuat tesis Benedict Anderson dalam "Imagined Communities" (1983) bahwa nasionalisme terbentuk melalui ritual-ritual kolektif yang menciptakan perasaan kebersamaan melampaui batas-batas primordial.
Solidaritas organik tersebut sebetulnya berpotensi menjadi instrumen pengawasan terhadap kebijakan PSSI dan Kemenpora, bahkan seluruh kebijakan pemerintah lainnya, mengingat kemenangan timnas merupakan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Lebih jauh, momentum kolektif ini dapat menjadi katalis (alat) dalam mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran era Presiden Prabowo yang berdampak struktural pada pembinaan atlet nasional, pendidikan, kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial. Namun, muncul pertanyaan kritis : apakah dikotomi artifisial antara sepakbola dan keadilan sosial telah menghalangi potensi transformatif dari solidaritas suporter? Apakah perasaan yang sama saat timnas berlaga tidak bisa direorganisir ulang untuk mengkawal isu-isu ketidak-adilan sosial yang kerap difragmentasi (dipecah kekuatan) oleh pemerintah sesempit pada urusan koalisi dan oposisi? Mengapa jumlah berita tentang isu efisiensi anggaran di Kemenpora atau federasi kurang dominan terdengar? Sebab, persoalan struktural terkait keadilan sosial seharusnya menjadi sorot utama anak bangsa, sama halnya tatkala Timnas Indonesia sedang berlaga.
ADVERTISEMENT
Solidaritas Suporter : Kuasa Rakyat atau Kuasa Elit
Perlu disadari bahwa meski solidaritas organik suporter menyimpan potensi perubahan sosial yang transformatif, namun realitas menunjukkan bahwa sepakbola Indonesia justru menjadi instrumen yang efektif dalam mengalihkan perhatian publik dari isu-isu struktural. Hal tersebut terlihat dari dua kasus emblematik: pertama, tragedi Kanjuruhan 2022 yang menewaskan 135 nyawa, dimana narasi publik berhasil diarahkan pada aspek teknis keamanan stadion, mengaburkan problematika fundamental dalam tata kelola sepakbola nasional. Kedua, saat gelombang demonstrasi menentang UU Cipta Kerja pada Oktober 2020, PSSI menggelar 12 pertandingan timnas dalam dua bulan, secara efektif mengalihkan fokus media dari isu perburuhan ke euforia olahraga.
Pola pengalihan isu ini diperkuat oleh struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Data menunjukkan 8 dari 18 klub Liga 1 pada tahun 2023 dimiliki konglomerat yang juga menguasai media mainstream dan memiliki afiliasi politik. Dominasi ini dipertegas dengan penguasaan hak siar Liga 1 oleh Grup MNC senilai Rp 4,5 triliun (2022-2027), menciptakan kontrol narratif yang komprehensif. Patronase politik terhadap suporter juga terlihat dari peningkatan dana hibah (156%) dan alokasi tiket gratis (180%) yang mencapai puncaknya pada momentum-momentum politik krusial.
ADVERTISEMENT
Fenomena ini sejalan dengan apa yang Guy Debord ucapkan dalam "Society of the Spectacle" (1967) tentang transformasi realitas sosial menjadi hanya sebatas tontonan yang mendepolitisasi kesadaran. Berbicara soal suporter di stadion misalnya, demografi penonton stadion yang sebelumnya masih bisa diakses “wong cilik” , kini bergeser ke kelas menengah-atas sekaligus menggerus basis tradisional suporter yang lebih militan. Korporatisasi kelompok suporter, seperti transformasi The Jakmania menjadi PT Jakmania Utama dengan omzet miliaran rupiah, dan kemunculan Bonek Store, merepresentasikan mutasi gerakan sosial menjadi entitas bisnis yang steril dari agenda perubahan melawan ketidak-adilan sosial.
Intervensi Kesadaran Hegemonik yang Harus Dibongkar
Transformasi sepakbola yang sebenarnya dapat digunakan sebagai medium perlawanan namun kemudian beralih menjadi instrumen depolitisasi sesungguhnya mengungkap bekerjanya tiga lapisan hegemoni yang saling menguatkan. Pertama, sebagaimana diidentifikasi Gramsci dalam "Prison Notebooks" (1930), kapitalisme olahraga telah menciptakan kesepakatan yang menormalisasi pemisahan sepakbola dari fungsi kritisnya sebagai ruang artikulasi kepentingan publik. Mekanisme ini bekerja melalui apa yang Gramsci sebut sebagai "common sense"— yang mana suporter secara tidak sadar menerima posisinya sebagai konsumen pasif, alih-alih aktor politik yang memiliki kapasitas transformatif.
ADVERTISEMENT
Lapisan kedua dari hegemoni ini beroperasi melalui apa yang Paulo Freire identifikasi sebagai defisit kesadaran dialektis dalam "Pedagogy of the Oppressed" (1968). Ketidakmampuan suporter mencapai tahap conscientização (kesadaran kritis) membuat mereka gagal memahami hubungan dialektis antara pengalaman konkret mereka sebagai penggemar sepakbola dengan struktur ekonomi-politik yang lebih luas. Akibatnya, kritik yang muncul seringkali terjebak pada level permukaan—seperti harga tiket atau performa tim—tanpa menyentuh problematika struktural seperti oligarki dalam tata kelola sepakbola atau implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap masa depan olahraga nasional.
Lapisan ketiga, mengacu pada analisis McCann dalam "Rights at Work" (2006), adalah absennya kerangka mobilisasi hukum yang memungkinkan transformasi kemarahan kolektif menjadi tuntutan hukum yang sistematis. Tanpa infrastruktur hukum yang memadai, energi protes suporter tercerai-berai dalam aksi-aksi sporadis yang mudah dikooptasi atau direpresi, alih-alih terkonsolidasi menjadi gerakan reformasi yang berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
Interaksi kompleks antara hegemoni kapitalisme olahraga, defisit kesadaran dialektis, dan absennya kerangka mobilisasi hukum telah menciptakan paradoks dimana solidaritas organik suporter justru menjadi instrumen yang melanggengkan ketidakadilan struktural. Namun, sejarah mencatat bagaimana suporter sepakbola dapat menjadi alat perubahan sosial, seperti terlihat dalam Revolusi Jasmine Tunisia 2011, yang mana ultras memainkan peran krusial dalam menggulingkan rezim Ben Ali melalui mobilisasi massa di stadion-stadion. Untuk mengaktivasi potensi transformatif serupa di Indonesia, diperlukan intervensi multi-dimensi: Pertama, pembentukan "supporter trust" independen yang menggabungkan fungsi advokasi hukum dengan edukasi politik; Kedua, pengembangan "conscientização" (kesadaran kritis) melalui forum-forum diskusi yang menghubungkan isu sepakbola dengan problematika struktural seperti efisiensi anggaran; dan Ketiga, membangun aliansi strategis dengan gerakan civil society untuk memperkuat kapasitas legal-formal dalam menghadapi kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Hanya dengan mengintegrasikan dimensi kesadaran, organisasi, dan mobilisasi hukum inilah solidaritas organik suporter dapat bertransformasi dari sekadar spektakel menjadi kekuatan riil dalam memperjuangkan keadilan sosial.
ADVERTISEMENT

