Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Inilah Alkisah Kata “Menabok” dan "Menggebuk" yang Pernah Menjadi Sabda Penguasa
30 April 2025 7:01 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Mohamad Jokomono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
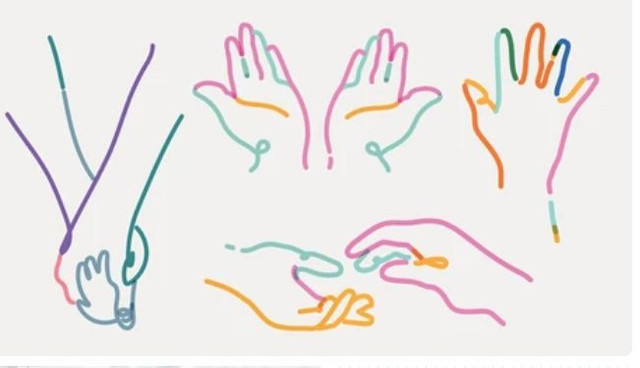
Kata “menabok” dan “menggebuk” tak pelak lagi pernah hadir sebagai bagian dari sabda penguasa di Republik Indonesia terkasih ini. Tulisan ini mencoba sekadar merekamnya sebagai peristiwa politik yang pernah terjadi. Hanya itu. Dan, dipastikan steril dari semangat pengagungan atau pengultusan terhadap subjek-subjek yang diceritakan.
ADVERTISEMENT
Alkisah. Saat itu, dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, muncul isu bahwa kandidat presiden Joko Widodo merupakan keturunan dari keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). (Catatan: Saya tidak ingin menyinggung soal ijazah insinyurnya yang masih saja dipersoalkan hingga sekarang).
Setelah Joko Widodo pada akhirnya terpilih menjadi Presiden Ke-7 Republik Indonesia, pada kisaran akhir November 2018, dia tidak lagi kuasa menahan rasa geregetan. Kemudian, dia pun mengeluarkan statemen, ingin menabok pihak-pihak yang hingga saat itu masih terus getol mengisukan dirinya serts kedua orang tuanya terlibat PKI. Kalau tidak salah, ini saat dia ingin maju lagi dalam Pilpres 2019.
Kata “me.na.bok” sudah ada sebagai sublema di Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI Dalam Jaringan (KBBI VI Daring). Ia berasal dari lema “ta.bok” yang mendapat awalan “meng-“ dan kemudian mengalami proses morfologis dan peleburan fonetis /t/, sehingga terbentuklah kata tersebut. Bukan “men.ta.bok”.
ADVERTISEMENT
Artinya, kira-kira memukul dengan telapak tangan (bisa disebut “menampar”) kepala atau bagian tubuh yang lain, seperti pipi, orang lain sebagai pelampiasan rasa kesal atau marah.
Penggunaan kata “me.na.bok” ini sejurus kemudian mengingatkan saya pada kata “meng.ge.buk”. Pada 1989, Jenderal (Purnawirawan) TNI Angkatan Darat Soeharto, pernah menggunakan kata ini. Meski tidak dalam format morfologis yang berprefiks. Tetapi, hanya bentuk dasarnya saja, yaitu “ge.buk”.
Sratemen yang terlontar pada saat itu, dan yang masih terpatri di ingatan saya kira-kira begini: “Kalau inkonstitusional, akan saya gebuk.” Kalimat ini dia tujukan untuk pihak-pihak yang ingin menggantikan kekuasaannya lewat jalan yang menurut pandangannya, dilakukan dengan cara-cara tidak konstitusional.
Belakangan, saya menemukan informasi tambahan dari buku Benny Moerdani yang Belum Terungkap (Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), pernyataan itu disampaikan ketika Pak Harto sedang berada dalam seusai melawat ke Beograd, Yugoslavia.
ADVERTISEMENT
Dan, ketemulah saya pada siapa-siapa yang mungkin akan bertindak institusional itu. Buku tersebut memuat penuturan jenderal bernana lengkap Leonardus Benjamin Moerdani itu, bahwa The Smiling General (namun saat menyampaikan pernyataan itu tidak tersenyum sama sekali) menegaskan, tidak peduli jenderal atau menteri, kalau berbuat inkonstitusional, pihaknya tidak segan-segan menggebuknya.
Efek Lebih Besar
Kata “meng.ge.buk” lebih memiliki efek kekuatan yang lebih besar daripada “me.na.bok”. Sesuai dengan rujukan pemaknaan versi KBBI VI Daring, tindakan ini juga mempunyai realisasi memukul, tetapi tidak cukup hanya dengan telapak tangan sebagaimana “me.na.bok”.
Tindakan “menggebuk” menggunakan alat pemukul yang berat dan besar. Dengan demikian, tingkat kemungkinan efek keparahan dari tindakan “meng.ge.buk” cenderung lebih berat dari “me.na.bok”.
ADVERTISEMENT
Pada hemat saya, baik kata “me.na.bok” maupun “meng.ge.buk”, sama-sama merupakan diksi dari retorika pemimpin negara yang mewakili ungkapan hati sebagai upaya naluriah untuk mempertahankan kekuasaan.
Yang berbeda, kata “me.na.bok” ala kandidat petahana Joko Widodo ketika maju lagi pada Pilpres 2019, merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaan selama satu kali dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan amanat konstitusi, jabatan presiden Republik Indonesia hanya dua periode pasca-Reformasi 1998.
Sementara itu, kata “meng.ge.buk” ala Jenderal Besar Soeharto, untuk mempertahankan kekuasaan selama lima tahun. Dan, kemudian dapat mencalonkan diri lagi untuk periode lima tahunan selanjutnya hingga jumlah yang tidak terhingga.
Isu PKI
Satu lagi perbedaan yang mencuat dari Presiden Kedua Republik Indonesia dan Presiden Ketujuh Republik Indonesia tersebut terkait dengan isu PKI.
ADVERTISEMENT
Jika dahulu, Presiden Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan “meng.ge.buk” lawan-lawan politiknya dengan pemberian label bahwa pandangan dan tindakan mereka ditunggangi kelompok yang berpaham komunis alias PKI.
Justru sebaliknya Joko Widodo harus berupaya “me.na.bok” pihak-pihak yang merundung dirinya dan keluarganya secara politis sebagai subjek yang di masa lalu konon terlibat dengan PKI.
Respons Manusiawi
Respons keras Joko Widodo yang ingin “me.na.bok” pengusung isu PKI terhadap diri dan keluarganya merupakan ekspresi kejengkelan yang manusiawi.
Erich Thohir, ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, saat itu memetaforakan semut yang kecil saja (simbol kelemahan) ketika diinjak melakukan perlawanan.
Soal binatang yang dimetaforakan, kadang ada yang menyebut cacing. Dalam sebuah dialog pemain kesenian tradisional Jawa, ketoprak (bukan nama makanan lo), saya pernah mendengar ungkapan begini: cacing wae yen dipidak mesti mbanggel (cacing saja kalau diinjak pasti melawan).
ADVERTISEMENT
Mungkin kalau semut, sumber kelemahan itu pada tubuhnya yang kecil mungil. Adapun cacing, simbol kelemahan itu direpresentasikan pada gerakannya yang lamban dan tubuhnya yang lunak serta juga tidak besar.
Perlawanan Rasional
Joko Widodo pun tak pelak lagi dia harus “me.na.bok” tudingan itu. Perlawanan paling rasional, yaitu dengan mengetengahkan alasan, dia yang lahir pada 1962, saat kejadian ketegangan politik kekerasan yang bernama Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) 1965 itu. Saat kerjadian berkecamuj, usianya baru tiga tahun.
“Masak ada PKI balita. Ini tidak masuk di nalar,” begitu kira-kira ucap sanggahannya. Dan, tentang kedua orang tuanya, dia mempersilakan kepada semua pihak yang berkepentingan (secara politik) untuk menanyakan di lingkungan sekitar tempat ayah bundanya pernah tinggal, juga para saksi sejarah, soal kebersihan mereka dari keterlibatan dengan paham komunis.
ADVERTISEMENT
Kita semua tentu maklum, menyaksikan betapa keras upaya seorang Joko Widodo tidak memberi pembiaran sedikit pun agar isu tersebut melekat erat pada dirinya. Dan, kemudian banyak orang yang terpersuasi untuk memercayainya. Karena itu, dirinya pun berusaha “me.na.bok” dengan berbagai varian strategi. Halus atau kasar.
Pukulan Telak
Tudingan terlibat dengan PKI atau bahkan sekadar menjadi simpatisannya semata, itu merupakan pukulan telak bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan posisi sebagaimana yang menjadi harapannya.
Bisa jadi, tindakannya itu hampir sama dengan Barack Obama yang dengan tegas menepis kuat-kuat bahwa dirinya seorang muslim pada saat pemilihan presiden di Amerika Serikat pada 2009 lalu.
Di Negeri Paman Sam itu, hingga dewasa ini, seorang muslim akan sulit terpilih menjadi presiden. Sama dengan di Indonesia, seorang yang terlibat PKI atau menjadi simpatisannya, tidak akan mungkin terpilih menjadi presiden.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, dapat dengan mudah terbaca sebagai pagina buku yang terbuka lebar-lebar, upaya Joko Widodo berusaha keras “me.na.bok” isu bahwa dirinya terlibat PKI. Yah, dia melakukannya dengan cara yang lebih lunak daripada strategi “meng.ge.buk” ala Soeharto kepada lawan-lawan politiknya. ***
■ Mohamad Jokomono, S.Pd., M.I.Kom., purnatugas pekerja media cetak.

