Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Konten dari Pengguna
"Takbir Cinta Zahrana": Tarik-Menarik Kekuatan Male-Feminist dan Male Masculine
23 April 2025 10:19 WIB
·
waktu baca 13 menitTulisan dari Mohamad Jokomono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
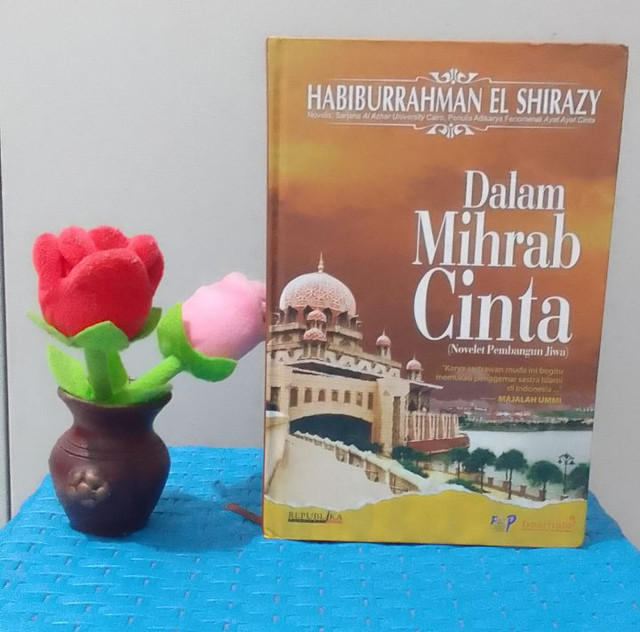
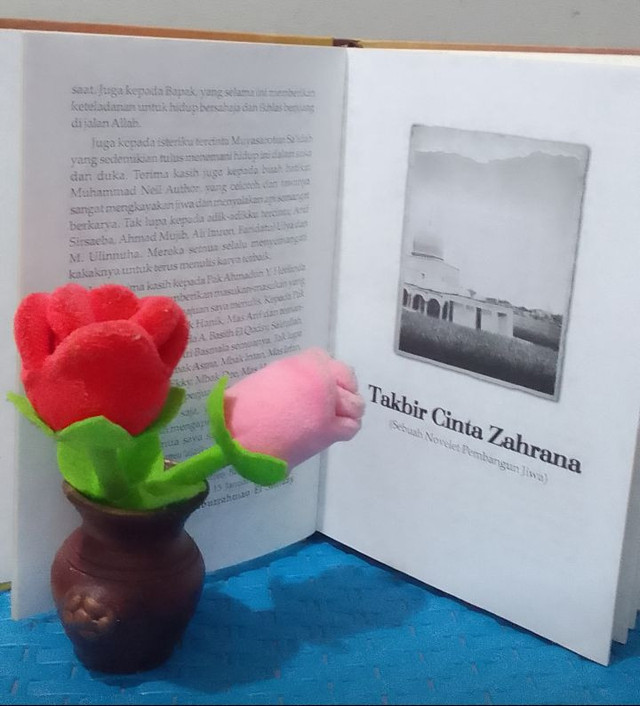
ADVERTISEMENT
Habiburrahman El Shirazy. Siapa yang tidak mengenalnya? Laki-laki kelahiran Semarang, 30 September 1976 yang merupakan alumnus Universitas Al Azhar Kairo ini, pada umumnya kerap dihubung-hubungan dengan dua karya monumentalnya, Novel Ayat-Ayat Cinta (cetakan pertama, Desember 2004) dan Ketika Cinta Bertasbih (terdiri atas dua buku, cetakan pertama, November 2007).
ADVERTISEMENT
Artikel ini memberikan fokus perhatian pada novelet (novel pendek) Takbir Cinta Zahrana. Novelet ini terbit dalam satu buku di bawah naungan judul Dalam Mihrab Cinta, bersama dua novelet lain, yaitu Dalam Mihrab Cinta (sekaligus judul antologi novelet ini) dan Mahkota Cinta. Buku antologi novelet ini terbit perdana pada Juni 2007.
Novelet Takbir Cinta Zahrana, menurut penulisnya, Habiburrahman El Shirazy (2006: 8), berangkat dari proses kreatif yang sebagian ceritanya merupakan kisah nyata. Sesuai dengan judulnya (versi filmnya Cinta Suci Zahrana), protagonis dalam novelet ini adalah Zahrana
Karakter perempuan ini mencoba menyempurnakan keseimbangan kehidupannya dengan tetap merawat berkah karier akademiknya hingga jenjang S-2 dengan pencarian cinta sucinya yang penuh kelok liku.
ADVERTISEMENT
Habiburrahman sebagai laki-laki penulis fiksi, saat “menakdirkan” dunia naratifnya berkarakter protagoniskan perempuan, dalam karyanya ini cenderung berupaya menempatkan posisi dirinya sebagai male-feminist.
Terma ini merujuk pada artian, laki-laki yang memiliki kesadaran gender yang penuh pencerahan akan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan. Atau menurut bahasa Dzuhayatin (2000: ix-x), laki-laki yang memiliki kesadaran gender yang tidak “terhenti di depan pintu rumah. (Sementara itu) Di dalam rumah (tangga)nya sendiri (dia) tetap berperilaku sebagai patriarch.”
Pendefinisian male-feminist di atas barangkali terlalu menyederhanakan persoalan. Karena ternyata di belakang terma male-feminist atau male feminism atau apa pun istilahnya tersimpan pertanyaan-pertanyaan kritis.
Contohnya Sail (dalam Gillis, Howie, Mufrod, editor., 2004: 97) yang mempertanyakan: Dapatkah laki-laki menjadi feminis? Apakah feminisme laki-laki (male feminism) dapat hidup terus? Apakah secara politik dibutuhkan?
ADVERTISEMENT
Jika ia merupakan sentral progresi dari perkembangan kesadaran budaya antipatriarkal yang menurut Showalter dalam Literature 13, adalah “Feminin, Feminis, dan (F)erempuan”, dapatkah laki-laki memiliki berbagai urusan yang terkait dengan persaudaraan perempuan (sisterhood)?
Jika perempuan “membutuhkan sesedikit mungkin kehadiran laki-laki agar mereka lebih merasa nyaman” (Greer via Sail dalam Gillis, Howie, Mufrod, editor., 2004: 97), kemudian datang “feminisme laki-laki“ yang mungkin ingin tampil menjadi pemadam dari masalah ketidaksetaraan gender dan akibat ketidaktahuannya justru itu lebih menyerupai tindakan penyabotasean?
Dan, setiap feminis gelombang ketiga biasanya mereka akan tergoda untuk melancarkan pertanyaan: apakah keadilan sosial dan seksual membutuhkan laki-laki yang lebih dari sekadar profeminis?
Saya sudah tentu tidak dapat menutup hal-hal kompleks di balik terma male-feminist ataupun male feminism di atas. Tetapi demi kepentingan praktis tulisan ini, versi definisi yang cenderung mengabaikan kompleksitas di belakang- nya, saya manfaatkan untuk melempangkan jalan analisis.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya, tentang terma male-masculine merupakan pinjaman dari Dzuhayatin ketika menulis kata pengantar untuk buku Kris Budiman yang berjudul Feminis Laki-laki dan Wacana Gender (2000).
Terma male-masculine ini dalam konteks ini saya maksudkan sebagai sosok antonim dari male-feminist, laki-laki dengan kesadaran gender yang belum tercerahkan, masih terdominasi kekuasaan patriarkal dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
Tarik-Menarik
Habiburrahman El Shirazy berada dalam pusaran tarik-menarik antara dia sebagai male-feminist dan dia yang juga sekaligus male-masculine dalam karya noveletnya, Takbir Cinta Zahrana, ini. Karena itu, tulisan sederhana ini melakukan perumusan masalah sebagai berikut:
Pertama, pada bagian-bagian teks yang manakah dalam Novelet Takbir Cinta Zahrana yang menunjukkan Habiburrahman El Shirazy berlaku sebagai male-feminist?
ADVERTISEMENT
Kedua, pada bagian-bagian teks yang manakah dalam Novelet Takbir Cinta Zahrana yang menunjukkan Habiburrahman El Shirazy menjadi male-masculine?
Landasan Teori
Teori yang akan saya gunakan dalam mengkaji Novelet Takbir Cinta Zahrana ini adalah semiotik. Zoonen (1994: 75-76) mengemukakan, bagi strukturalis, berbagai tanda khusus dengan demikian memperoleh makna tidak hanya dari relasinya dengan tanda-tanda lain dengan sistem yang sama (syntagma). Tetapi, juga dari relasi tanda-tanda itu dengan sistem yang berlawanan (paradigma).
Menurut Barthes (via terjemahan Inggris Heath, 1977: 51), dalam sistem secara keseluruhan fungsi-fungsi struktural terjadi polarisasi. Pada satu sisi, terdapat sejenis kondensasi paradigmatik (paradigmatic condensation) pada level konotator (yaitu perkataan dalam arti luas [broadly speaking], simbol-simbol), yang memiliki tanda-tanda yang kuat (strong sign), berserakan (scattered).
ADVERTISEMENT
Sementara itu pada sisi lain, terdapat “arus” sintagmatik pada level denotasi. Tidak akan terlupakan bahwa sintagma selalu sangat berkaitan erat dengan bahasa lisan (speech). Dan, itu sungguh-sungguh merupakan “wacana” ikonik (iconic “discourse”) yang ternaturalisasi simbol-simbolnya.
Tanpa mengharapkan, lanjut Barthes (via terjemahan Inggris Heath, 1977: 51), penyimpulan yang terlalu cepat dari citra semiologi (semiotik) secara umum, walaupun membentuk spekulasi bahwa dunia dengan makna total telah berkesan melakukan secara internal (secara struktural) antara sistem sebagai budaya dan sintagma sebagai alam.
Karya-karya komunikasi massa semua terkombinasi, melalui bermacam-macam (diverse) dan dengan berbeda-beda (diversely) dialektika yang sukses dengan saya tarik alami cerita, diegesis, sintagma, dan kejelasan budaya.
Dalam pada itu Zoonen (1994: 76) menekankan, pada artikulasi khusus tanda-tanda terdapat “kode-kode” (codes) dan “kovensi-konvensi” (convensions) dibagikan oleh anggota-anggota budaya dari sistem tanda yang memulai untuk menyediakan petunjuk bagaimana memahami sistem-sistem tanda.
ADVERTISEMENT
Berger (1982) dalam Zoonen (1994: 76) memberi contoh jalan kode-kode Barat dari bahasa tubuh (body language) memberikan makna pada sudut pandang kamera dan gerakan-gerakan. Kode-kode lain yang biasanya memberi pada makna terhadap artikulasi tanda adalah kode-kode feminimitas, maskulinitas, dan heteroseksualitas.
Tanda, sintagma, paradigma, kode, dan konvensi, ungkap Zoonen (1994: 76), adalah elemen-elemen kunci dalam proses yang berbeda dari signifikansi, sebuah jalan tanda-tanda menjadi begitu bermakna dengan adanya kultur. Barthes (1957) dalam Zoonen (1994: 76) membedakan denotasi dan konotasi, atau signifikansi tataran pertama dan kedua (first and second order signification).
Sementara itu, Chandler (1994: 92) mengemukakan, konotasi dan denotasi sering terdiskripsikan dalam terma-terma level-level representasi (levels of representation) atau level-level makna (levels of meaning).
ADVERTISEMENT
Roland Barthes mengadopsi dari Louis Hjelmslev tentang nosi yang berlainan dengan tataran signifikasi (order of signification) (Barthes, 1957; Hjemslev, 1961: 114 dalam Chandler, 1994: 92).
Tataran pertama signifikasi adalah denotasi, ujar Chandler (1994: 76). Pada level ini, tanda terdiri atas penanda (signifier) dan petanda (signified). Konotasi merupakan tataran kedua signifikansi yang menggunakan tanda denotatif (penanda dan petanda) sebagai penanda dan melekatkanya pada petanda tambahan.
Dalam kerangka kerja ini, konotasi merupakan sebuah tanda yang berasal dari penanda tanda denotatif (dengan demikian denotasi memandu ke suatu mata ran-tai konotasi).
Kecenderungan ini, lanjut Chandler (1994: 92) menyarankan, bahwa denotasi merupakan hal pokok yang mendasari dan menjadi makna primer, dengan banyak komentator lain yang telah meragukan.
ADVERTISEMENT
Barthes kemudian memprioritaskan konotasi dan pada 1971 mencatat, tidak lagi mudah memisahkan penanda dari petandanya, suatu ideologi literal alias harfiah (Barthes, 1977: 166 dalam Chandler, 1994: 92).
Chandler (1994: 92) mencatat, formulasi ini menggarisbawahi poin bahwa “apakah penanda atau petanda yang tergantung pada keseluruhan level yang mendapatkan sentuhan operasi analisis: petanda pada satu level dapat menjadi penanda pada level lain” (Willemen, 1994: 105). Ini mekanisme dengan tanda-tanda yang tampaknya menandakan sesuatu yang sarat makna berganda.
Zoonen (1994: 76) mengemukakan, konotasi atau tataran kedua signifikasi memuat nilai budaya yang tersembunyi (latent culture) dan kepercayaan yang terekspresikan sebagai tanda atau sistem tanda. Ini bisa berupa bentuk asosiasi atau narasi-narasi yang komplet, pelabelan dengan “mitos” (myth) sebagaimana pandangan Roland Barthes.
ADVERTISEMENT
Seperti contoh Zoonen tentang “kucing hitam”, yang menurut mitos di Belanda merupakan isyarat konotatif yang menunjukkan ngalamat (bahasa Jawa) peruntungan buruk (omen of bad luck).
Di lingkungan masyarakat lain, konotasi kucing hitam yang terbentuk dari latent culture-nya bisa jadi malah berlainan sama sekali, ia mungkin menjadi suatu pertanda keberuntungan atau kebahagiaan. Dan, kata Zoonen, di sejumlah lingkaran feminis, konon kuncing hitam merujuk pada konotasi pemikiran sebagai penanda spiritualitas.
Male-Feminist
Pendeskripsian tokoh protagonis Zahrana, sebagai sosok perempuan yang memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri dalam menentukan langkah kehidupannya, merupakan penanda teks (secara naratif) yang menunjukkan Habiburrahman tengah berada dalam posisi male-feminist. Kekuasaan perempuan atas dirinya sendiri, barangkali inilah tanda konotasi yang memuat ideologi feminisme.
ADVERTISEMENT
Salah satu contoh upaya deskripsi Habiburrahman di posisi male feminist yang menunjukkan tanda konotasi kekuasaan perempuan atas dirinya sendiri adalah kebebasan Zahrana menentukan keputusan untuk menolak lamaran Sukarman, dekan fakultas teknik sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka di Semarang, tempat dia menjadi salah seorang pengajar tetapnya.
Zahrana tidak mudah menyerah pada konstruksi sosial yang menganggap perempuan dengan usia 30-an dan belum menikah adalah perawan tua, yang seharusnya merasa beruntung ada laki-laki yang sudah berminat melamarnya dan seharusnya menerimanya dengan tangan terbuka tanpa pertimbangan neko-neko.
Habiburrahman berada dalam posisi male-feminist ketika memenangkan Zahrana dengan pilihannya untuk memegang kekuasaan atas dirinya sendiri itu daripada menyepakati konstruksi sosial, bahwa dirinya perawan tua yang seharusnya menerima lamaran siapa pun laki-laki, tidak peduli apakah laki-laki itu seperti Sukarman yang memiliki reputasi kurang baik dalam relasinya dengan perempuan-perempuan bukan muhrimnya.
ADVERTISEMENT
Di bawah ini kutipan tanda konotasi dengan ideologi feminis yang menyiratkan betapa Zahrana memang benar-benar berkuasa atas dirinya sendiri dan menggunakan kekuasaan itu untuk menetapkan yang terbaik bagi jalan hidupnya.
Lima belas menit basa-basi akhirnya Pak Darmanto, juru bicara Pak Karman, masuk pada inti kedatangan,
“... dan maksud kedatangan kami adalah untuk menyambung persaudaraan dan kekeluargaan dengan keluarga Bapak Munajat. Kami bermaksud menyunting putri Bapak Munajat, yaitu Dewi Zahrana untuk saudara kami Bapak H. Sukarman, M.Sc. Alangkah bahagianya jika maksud dan tujuan kami dikabulkan.”
Ayahnya menjawab dengan suara renta yang terbata-bata,
“Pertama ... tama, ka ... kami sekeluarga menyampaikan rasa terima kasih atas silaturahminya. Kami juga bahagia. Bagi ka ... kami lamaran ini adalah suatu bentuk penghormatan. Dan jika bisa kami akan membalas-nya dengan penghormatan yang le ... lebih baik. Namun masalah jodoh hanya Allahlah yang mengatur. Putri kami sudah sangat dewasa. Dia lebih berpendidikan dari kami berdua. Dia bisa memutuskan sendiri mana yang baik baginya. Itu yang bisa kami sampaikan.”
ADVERTISEMENT
Masalah sudah jelas. Semua tamu melihat ke arahnya. Ia tahu bola sekarang ada di tangannya. Dialah yang paling berkuasa di majelis itu. Ia berusaha untuk tenang. Setenang ketika ia membantu argumen mahasiswa yang dibelanya dalam sidang skripsi.
“Saya pernah mendengar Baginda Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, ‘Al ‘ajalatu minasy syaithan. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Saya tidak mau mengecewakan siapa pun. Termasuk diri saya sendiri. Maka perkenankan saya untuk menjawabnya tiga hari ke depan. Saya akan langsung sampaikan kepada Pak Karman yang saya hormati. Maafkan jika saya tidak bisa menjawab sekarang,”
Ada sedikit gurat kekecewaan di wajah Pak Darman dan Pak Karman. Namun keduanya tidak bisa bersikap apa pun kecuali setuju. Bu Merlin tersenyum tanda setuju. Yang lain bisa memahami dan memaklumi. Hanya Pak Munajat, ayahnya, yang meneteskan airmata mendengar jawaban putrinya itu. Ia sudah tahu ke mana arah perkataan putrinya itu.
ADVERTISEMENT
Menjelang magrib rombongan itu pamit. Zahrana langsung ke kamarnya mengatur waktu yang tepat untuk disampaikan pada Pak Karman. Ia tersenyum, dengan senyum yang susah diartikan.
(Habiburrahman, 2010: 21-23)
Kekuasaan atas dirinya sendiri sebagai perempuan itu, sedikitnya tertuang dalam kalimat-kalimat “Masalah sudah jelas. Semua tamu melihat ke arahnya. Ia tahu bola sekarang ada di tangannya. Dialah yang paling berkuasa di majelis itu” dan kalimat-kalimat “Ada sedikit gurat kekecewaan di wajah Pak Darman dan Pak Karman. Namun keduanya tidak bisa bersikap apa pun kecuali setuju”.
Kalimat-kalimat tersebut merupakan penanda yang menyiratkan petanda “Zahrana sebagai perempuan memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri dalam menentukan pasangan hidup”. Ini sebuah relasi penanda-petanda yang memuat ideologi yang profeminis.
ADVERTISEMENT
Kekuasaan atas dirinya sebagai perempuan, juga Habiburrahman deskripsikan dalam teks manakala Zahrana menerima pinangan Hasan, mantan mahasiswanya yang lebih muda empat tahun darinya. Hasan meminang Zahrana dengan perantara ibundanya, ibu dokter Zulaikha.
Dalam bagian ini, pada hemat saya, setidaknya terdapat dua hal yang patut tercatat dalam kaitannya dengan salah satu ideologi feminis “perempuan berkuasa menentukan kehidupannya sendiri”.
Pertama, Zahrana mengekspresikan “kekuasaan dirinya sebagai perempuan yang berhak menentukan kehidupannya sendiri” dengan menentang mitos “diam sebagai tanda persetujuan” atas lamaran Hasan via sang bunda, ibu dokter Zulaikha itu.
Bertalian dengan hal itu, Zahrana justru mengekspresikan persetujuannya dalam bentuk syarat “akad nikahnya harus berlangsung pada malam hari itu juga, bakda shalat Tarawih”.
ADVERTISEMENT
Kedua, seluruh sikap Zahrana itu pada akhirnya bermuara pada hakikatnya dia tengah berupaya melabrak latent social construction di kalangan masyarakat Jawa, bahwa menurut kepantasan yang berlaku di lingkungan sosial budaya kelompok etnis ini “kurang pas pasangan suatu istri, yang perempuan lebih tua usianya”.
Atau, setidaknya masyarakat Jawa masih belum terbiasa menganggap wajar pasangan suami istri dengan usia istri yang lebih tua. Dan, ini biasanya muncul dalam bentuk rerasan atau glenak-glenik (bahasa Jawa) di tempat tidur di antara pasangan suami istri lain dengan komposisi usia yang “normal” (baca= usia suami lebih tua dari usia istri).
Berikut kutipan teks yang penulis maksudkan, di dalamnya terdapat tanda-tanda konotasi atau tataran kedua signifikasi yang memuat nilai budaya tersembunyi (latent culture) dan kepercayaan yang terekspresikan sebagai tanda atau sistem tanda.
ADVERTISEMENT
“Saya lebih tua dari Hasan, Bu. Dia cocoknya jadi adik saya.”
“Syariat tidak menentukan batasan umur. Ibu memang lebih tua. Tapi tidak terpaut jauh. Cuma empat tahun. Hasan umurnya 29. Mukanya memang baby face. Bagi saya sendiri tidak masalah. Toh suami saya juga lebih muda dua tahun dari saya.”
“Saya belum bisa menerima, Bu.”
“Kenapa? Kata ibu tadi Hasan sudah pantas menikah dan memiliki istri. Apa lagi? Apa ada dalam diri Hasan ada suatu cacat yang menurut ibu layak ditolak lamarannya?’
Zahrana diam. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia masih belum tahu apa yang terjadi. Hasan melamarnya? Bagaimana mungkin? Tapi ibunya sedemikian serius. Apa yang harus ia putuskan. Zahrana tetap diam.
ADVERTISEMENT
“Diam berarti menerima. Saya pamit, ....”
Zahrana tersentak mendengar Bu Zul mau pamit. Ia berdiri mengikuti Bu Zul yang sudah berdiri.
“Ibu benar-benar serius?
“Iya.’
“Kalian sudah tahu kekuranganku dan mau menerimaku?”
“Iya. Tak ada manusia yang sempurna.”
“Kalau begitu saya terima, tapi dengan syarat.”
“Apa syaratnya?”
“Akad nikahnya nanti malam bakda shalat Tarawih di masjid. Biar disaksikan oleh seluruh jamaah masjid. Maharnya seadanya saja.”
Kini gantian Bu Zul yang tersentak kaget. Ia tidak menduga Zahrana akan mensyaratkan begitu.
“Apa nggak sebaiknya akadnya setelah Idul Fitri saja.”
“Tidak. Ibu sudah tahu kan cerita saya selama ini. Apa ibu ingin saya mati kaku gara-gara saya tidak jadi nikah lagi. Saya tidak ragu dengan keseriusan ini. Saya hanya khawatir ada hal-hal di luar kekuasaan kita yang membatalkan rencana itu. Bagi saya lebih baik ya nanti malam, atau tidak sama sekali.”
ADVERTISEMENT
Bu Zulaikha memandang wajah Zahrana lekat-lekat. Wajahnya teduh, sangat berkarakter.
“Baiklah. Dalam hal ini saya tidak memutuskan sendiri. Saya akan bicara dengan anak dan keluarga. Saya pamit dahulu. Setelah magrib nanti saya telepon.”
Dokter berjilbab itu pulang setelah bersalaman dengan Zahrana dan ibunya. Zahrana memandang sedan dokter itu hingga hilang di tikungan. Ada kebahagiaan menyusup dalam hatinya. Tapi juga ada kecemasan. Ia memang lagi bahagia. Namun untuk membentengi diri agar ti-dak kecewa lagi setelah kebahagiaan berada di depan mata, ia menganggap dialognya dengan Bu Zul tadi hanya main-main. Dialog latihan orang bermain drama atau sandiwara.
***
ADVERTISEMENT
Azan magrib berkumandang. Tanda waktu buka puasa tiba. Zahrana meneguk kolak dan makan mendoan. Ada kenikmatan luar biasa saat buka. Kenikmatan yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Hanya orang-orang yang berpuasa yang bisa merasakannya. Pembicaraan dengan Bu Zul itu tidak Zahrana sampaikan kepada ibunya. Ia tak ingin ibu-nya kecewa jika yang diharapkan tak terjadi lagi.
Setelah shalat Magrib, Zahrana mendapat telepon dari Bu Zul.
“Bu Zahrana. Mengenai keputusan syarat yang Bu Zahrana ajukan, ini ibu langsung dengar sendiri suara Hasan ya.”
Suara di handphone Zahrana lalu berubah.
“Bu Zahrana, ini Hasan. Saya setuju dengan syarat ibu. Ibu siapkan wali dan saksinya, saya akan siapkan maharnya dan penghulunya. Kami sekeluarga insa Allah berangkat sekarang, dan kami shalat Isya di masjid dekat rumah Ibu.”
ADVERTISEMENT
“Kau serius Hasan?”
“Iya Bu.”
“Kau bisa mencintaiku?”
“Iya Bu.’
“Kalau begitu, jangan kaupanggil aku ibu. Panggil aku dik. Dik Zahrana. Coba kau bisa nggak?” Zahrana merasa tak perlu malu.
“Saya coba ... Dik Zahrana, tunggu aku di masjid.”
Mata Zahrana berkaca-kaca mendengarnya. Ribuan hamdalah menyesak dalam dada.
(Habiburrahman, 2020: 80-83)
Konvensi masyarakat Jawa tentang “kediaman perempuan sebagai tanda persetujuan” merupakan penanda konotatif dari petanda konsep “perempuan tidak berkuasa atas dirinya sendiri”.
Habiburrahman dalam kapasitas posisinya sebagai male-feminist tidak menginginkan itu terjadi pada diri Zahrana. Karena itu muncullah paragraf yang berisikan kalimat-kalimat berikut: “Diam berarti menerima. Saya pamit, ....” Zahrana tersentak mendengar Bu Zul mau pamit. Ia berdiri mengikuti Bu Zul yang sudah berdiri.“Ibu benar-benar serius?“Iya.’ “Kalian sudah tahu kekuranganku dan mau menerimaku?” “Iya. Tak ada manusia yang sempurna.” “Kalau begitu saya terima, tapi dengan syarat.”
ADVERTISEMENT
Kalimat dialog terakhir yang mengeksplisitkan penerimaan lamaran Hasan dengan sertaan syarat merupakan simbol konotatif tentang betapa Habiburrahman menunjukkan citra Zahrana sebagai sosok perempuan yang tidak ingin nasibnya tergantung pada interpretasi orang lain terhadap sikap diamnya.
Zahrana menyandang citra pendeskripsian sebagai sosok perempuan yang secara tegas menolak mitos “kediaman perempuan adalah persetujuan”. Latent culture ataupun latent social construction yang berada di belakang tanda ini menghidupi sikap perlawanan Zahrana.
Dia tidak ingin ada anggapan, bahwa penerimaannya terhadap lamaran Hasan, karena interpretasi ibu dokter Zulaikha (ibunda Hasan) atas sikap “diam”-nya. Dia ingin menunjukkan “kekuasaan sebagai perempuan yang berkuasa atas dirinya sendiri”. Karena itu, dia menyatakan penerimaannya secara eksplisit lewat pernyataan bahwa dirinya bisa menerima lamaran itu.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya mengenai konvensi usia pasangan suami istri yang menurut konstruksi sosial masyarakat Jawa cenderung teranggap sebagai “normal”, manakala usia yang laki-laki lebih tua (bahkan hingga selisih belasan tahun) daripada yang perempuan.
Tanda yang tidak sepi dari latent social construction ini pun muncul dalam bagian teks ini. Habiburrahman berada dalam posisi profeminis melalui ucapan tokoh ibu dokter Zulaikha: “Syariat tidak menentukan batasan umur. Ibu memang lebih tua. Tapi tidak terpaut jauh. Cuma empat tahun. Hasan umurnya 29. Mukanya memang baby face. Bagi saya sendiri tidak masalah. Toh suami saya juga lebih muda dua tahun dari saya.”
Dan, Zahrana menjawab perlawanannya atas penindasan tanda konvensi “normal” tentang usia laki-laki seharusnya lebih tua dari pasangan perempuannya, dengan kesediaannya untuk menikah dengan Hasan.
ADVERTISEMENT
Laki-laki yang berusia empat tahun lebih muda darinya, mantan mahasiswanya sendiri, yang dahulu pernah menjadi mahasiswa bimbingan skripsinya sebelum dia mengundurkan diri sebagai pengajar tetap di universitas swasta terkemuka di Semarang setelah dia menolak pinangan Sukarman, dekan fakultas teknik perguruan tinggi itu.
Dan, pada malam kedua di Bulan Suci Ramadan itu, apa yang diharapkan Zahrana terjadi. Akad nikah setelah shalat Tarawih disaksikan oleh jamaah yang membludak. Sebagian besar adalah tetangga Zahrana. Mereka turut terharu. Saat akan nikah, ibu Zahrana menangis tersedu-sedu. Beberapa ibu-ibu juga menangis.
Malam itu Zahrana sangat bahagia. Hasan juga merasakan hal yang sama. Usai akad nikah, Hasan mengajak Zahrana naik mobilnya menuju hotel termewah di tengah Kota Semarang. Di dalam hotel, dengan penuh kekhusyukan Zahrana menunaikan ibadahnya sebagai istri. Ibadah yang sudah dia tunggu-tunggu bersama seorang istri.
ADVERTISEMENT
(Habiburrahman, 2010: 83-84)
Male-Masculine
Dalam Novelet Takbir Cinta Zahrana, selain menunjukkan diri sebagai sosok male-feminist dalam “kesyahduan kreativitasnya”, Habiburrahman juga terkadang tak kuasa berkelit dari sergapan nalurinya sebagai male-masculine.
Habiburrahman menempatkan diri sebagai male-masculine, menggunakan pola deskripsi yang kurang feminist friendly, manakala dia menggambarkan Zahrana yang menyerah pada konstruksi sosial, bahwa sudah seharusnya perempuan berusia 34 tahun seperti dirinya telah memiliki keluarga dengan satu atau dua anak.
Hal itu terasa sekali, ketika Habiburrahman mendeskripsikan penyesalan Zahrana, kenapa dahulu dia tidak menerima cinta dari sejumlah laki-laki yang pernah coba mengendap-endap di teras kehidupan asmaranya.
Sentuhan male-masculine itu terasa betul pada cara Habiburahman yang merasa perlu mendeskripsikan kesuksesan laki-laki yang pernah tertolak cintanya oleh Zahrana. Ini bisa jadi merupakan kesadaran promaskulin, semacam solidaritas sesama laki-laki, ada ketakrelaan jika martabat gendernya jatuh terpuruk.
ADVERTISEMENT
Ada-ada tanda-tanda yang berfungsi konotasi untuk melehke (bahasa Jawa) Zahrana dengan seolah hendak mengatakan, “Kamu, Zahrana, telah keliru dengan keputusanmu menolak laki-laki yang dahulu coba mencintamu. Mereka kini menjadi orang sukses dan hidup berbahagia bersama keluarga masing-masing.”
Berikut kutipan teksnya:
Ia terkadang menyalahkan dirinya sendiri, kenapa tidak menikah sejak masih duduk di S-1 dahulu? Kenapa tidak berani menikah ketika si Gugun yang mati-matian mencintainya sejak duduk di bangku kuliah itu mengajaknya menikah? Ia dulu memandang remeh Gugun. Ia meng- anggap Gugun itu tidak cerdas dan tipe lelaki kerdil. Sekarang si Gugun itu sudah sukses jadi pengusaha cor logam dan baja di Klaten. Karyawannya banyak dan anaknya sudah tiga. Gugun sekarang juga punya usaha travel umrah di Jakarta. Setiap kali bertemu, nyaris ia tidak berani meng-angkat muka.
ADVERTISEMENT
Kenapa juga ketika selesai S-1 tidak langsung menikah? Kenapa ia lebih tertantang masuk S-2 ITB Bandung? Padahal temannya satu angkatan si Yuyun menawarkan kakaknya yang sudah buka kios pakaian dalam di Pasar Beringharjo Jogja. Saat itu, kenapa ia begitu tinggi hati. Ia masih memandang rendah pekerjaan jualan pakaian dalam. Sekarang kakaknya Yuyun sudah punya toko pakaian dan sepatu yang lumayan besar di Jogja. Akhirnya ia menikah dengan seorang santriwati dari Pesantren Al-Munawwir, Krapyak. Dan sekarang telah membuka SDIT di Sleman.
(Habiburrahman, 2010: 14-15)
Bisa jadi Habiburrahman masih ingin melanjutkan “balas dendam’-nya sebagai male-masculine, tatkala hasil dari ikhtiar Zahrana setelah sowan ke Bu Nyai Sa’adah Al Hafidhah, istri K.H. Amir Arselan, pengasuh utama Pesantren Al Fatah, memunculkan dialog yang mengaksentuasikan betapa “perempuan dengan usia yang tidak lagi muda” akan sulit mendapatkan jodoh selevel.
ADVERTISEMENT
“Saya yakin tidak mudah mencari yang selevel denganmu, Anak- ku. Jujur saja kalau misalnya ada yang selesai S-2 umurnya sama dengan-mu, dia akan memilih yang lebih muda darimu. Lelaki itu umumnya punya ego, tidak mau istrinya lebih pinter dan lebih tua darinya. Tapi ya tidak semua lelaki lho. Sekali lagi, tidak mudah mencarikan jodoh yang pendidikannya seperti kamu, juga saleh. Kalau boleh tahu, kalau pendidikannya tidak setinggi kamu bagaimana?”
Zahrana mengerti maksud Bu Nyai. Segera ia menjawab,
“Saat ini status, strata, kedudukan sosial, pendidikan, dan lain se-bagainya tidak jadi pertimbangan saya Bu Nyai. Saya hanya ingin suami yang baik agamanya. Baik imannya dan bisa jadi teladan untuk anak-anak kelak. Itu saja.”
ADVERTISEMENT
(Habiburrahman, 2010: 44-45)
Paling tidak, sebagaimana pernyataan Zoonen, konotasi atau tataran kedua signifikasi memuat nilai budaya yang tersembunyi (latent culture) dan keper- cayaan yang terekspresikan sebagai tanda atau sistem tanda.
Konotasi yang terbentuk dari perkataan Bu Nyai, ”Jujur saja kalau misalnya ada yang selesai S-2 umurnya sama denganmu, dia akan memilih yang lebih muda darimu. Lelaki itu umumnya punya ego, tidak mau istrinya lebih pinter dan lebih tua darinya” cenderung menguatkan Habiburrahman pada posisinya sebagai male-masculine dalam teks ini, dan secara tegas merayakan pemihakan kepada dan kemenangan untuk laki-laki.
Setidaknya laki-laki yang usianya tidak muda lagi, masih memiliki kekuasaan untuk memilih perempuan-perempuan muda, bahkan dengan tingkat pendidikan tinggi. Tidak ada konstruksi sosial yang memandang sebagai hal tidak “normal”, ketika laki-laki yang sudah tidak muda lagi menikahi perempuan yang lebih pantas menjadi anaknya.
ADVERTISEMENT
Tetapi, konstruksi sosial yang berada di belakang ungkapan Jawa, wong lanang iku eleka tetep wenang, pada realitasnya cenderung membatasi keleluasaan perempuan yang sudah tidak muda lagi untuk menikah dengan laki-laki yang lebih muda darinya.
Dan, karena itu “perempuan yang tidak muda lagi serta melajang”, walaupun dengan gelar S-2 seperti Zahrana, bahkan dengan persetujuan Zahrana sendiri yang hanya mensyaratkan keinginannya akan suami yang baik agamanya. Baik imannya dan bisa jadi teladan untuk anak-anak kelak, Habiburrahman kemudian mempertemukan dia dengan Rahmad, laki-laki lulusan madrasah aliyah yang bekerja sebagai penjual kerupuk keliling. Sulit untuk terpungkiri, pencerita yang laki-laki itu hendak mengatakan, “Ini lho, nasib perempuan pemilih. Kenapa dahulu kau tolak pinangan Gugun dan kakaknya Yuyun?”
ADVERTISEMENT
Ini barangkali merupakan semacam “pelajaran” dalam penakdiran naratif seorang Habiburrahman dalam ayunan langkah sebagai seorang male-masculine terhadap Zahrana, perempuan yang beberapa kali mencampakkan cinta sejumlah laki-laki. Sampai akhirnya Habiburrahman “membunuh” tokoh Rahmad ini melalui kejadian tertabrak kereta api, demi melempangkan jalan bagi Zahrana untuk mendapatkan jodoh yang relatif sepadan baginya, Hasan.
Muslim Feminism
Sisi male-feminist seorang Habiburrahman El Shirazy, bisa jadi datang dari muslim feminism. Menurut Saadalah (dalam Gillis, Howie, Mufrod, editor., 2004: 219), muslim feminism di sebagian besar tempat memperjuangkan kesetaran, keadilan, dan pemberdayaan dalam konteks Islam.
Muslim feminist seperti Asma Barlas, Leila Ahmed, dan Fatima Mernissi, untuk menyebut sedikit nama, membongkar status quo interpretasi terhadap Islam yang terdominasi laki-laki dan akulturasi yang melayani penguatan terhadap perempuan sehingga dapat berkelit dari penaklukan laki-laki.
ADVERTISEMENT
Interpretasi dan akulturasi ini, tandas Saadalah (dalam Gillis, Howie, Mu- frod, editor., 2004: 219), seharusnya terpahami sebagai terpisah dari teks-teks Islam, sebagaimana Amy E. Schwartz menekankan, “Islam sudah pada tempatnya terpahami sebagai refleksi dari suatu pencerahan dan egalitarianisme ... praktik-praktik kurang terpuji terhadap kaum perempuan sebagai warga negara kelas dua yang bukan merupakan nilai-nilai intrinsik islami yang sejati atau syariah. Dengan demikian, terdapat suatu perbedaan yang jelas dalam tujuan-tujuan dan strategi-strategi Muslim feminist dan Islamist feminist.” Habiburrahman dengan Zahrana-nya mungkin tengah bergerak menuju ke sana.
Daftar Pustaka
Barthes, Roland (Heath, Stephen; penerjemah bahasa Inggris). (1977). Image Music Text. New York: Hill and Wang.
Chandler, Daniel. (1994). Semiotics for Beginner. http://www.aber.ac.uk/media/Documents/58B/semiotic.html.
ADVERTISEMENT
Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (2000). Menakar Stamina Seorang Male-Feminist: Sebuah Pengantar. Dalam Kris Budiman, Feminis Laki-laki & Wacana Gender. Magelang:Indonesia Tera.
Habiburrahman El Shirazy. (2006). “Takbir Cinta Zahrana”. Dalam Antologi Novelet Dalam Mihrab Cinta. Cetakan ke-10. Jakarta-Semarang: Penerbit Republik dan Pesantren Basmalah Indonesia.
Saadalah, Sherin. (2004). Muslim Feminism in the Third Wafe: A Reflective Inquiry. Dalam Stacy Gillis, Gillian Howie, dan Rebecca Munfrod (editor), Third Wave Feminism: A Critical Exploration. New York: Palgrave MacMillan.
Shail, Andrew. (2004). You’re Not One of Those Boring Masculinists, Are You? The Question of Male-Embodied Feminism. Dalam Stacy Gillis, Gillian
Howie, dan Rebecca Munfrod (editor), Third Wave Feminism: A Critical Exploration. New York: Palgrave MacMillan.
ADVERTISEMENT
Zoonen, Liesbet van. (1994). Feminist Media Studies. London, Thousand Oak, New Delhi: SAGE Publications.
■ Mohamad Jokomono, S.Pd., M.I.Kom, purnatugas pekerja media cetak.

