Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Ini Itu Sama Saja, Preman juga!
17 Juni 2017 14:12 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB
Tulisan dari Rulli Rachman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Kartono sepertinya sudah berdiri sepuluh menit di depan pintu rumah bercat putih gading kusam itu. Maklum, ia sedang menyiapkan mentalnya untuk bertemu dengan pak Karyo, mantan dosen pembimbingnya dulu itu. Pertemuan yang tertunda terus. Kartono sudah lama berniat untuk sowan ke pak Karyo. Tapi kesibukan dengan beberapa project sangat menyita waktu Kartono. Kartono memang masih terlibat langsung dalam beberapa pekerjaan perusahaan kecilnya.
ADVERTISEMENT
Kalau diingat-ingat, Sebenarnya sejak lima tahun sebelumnya, Kartono sudah berniat untuk membuat usaha. Jadi enterpreneur istilah bekennya! Kartono begitu berapi-api tiap kali mendengarkan seorang motivator berorasi, “Bangsa ini butuh enterpreneur-enterpreneur muda. Karena jumlah enterpreneur bangsa sampai saat ini hanya 2 persen dari sekian populasi penduduknya! Malu dong sama bangsa tetangga yang bisa mencapai 13 persen jumlah wirausahanya!”. Kartono manggut-manggut semangat. Dadanya panas. Seakan api obor olimpiade yang diarak marathon berkilo-kilo meter itu baru dinyalakan didalam dadanya.
“Hebat banget ini motivator. Masih muda, perlente, pengusaha, kaya pulak!”, pikir Kartono dalam hati.
Sejak saat itu Kartono jatuh cinta pada sang motivator. Tiap buku motivasinya yang berseri dan berjilid-jilid seperti sinetron Tersanjung itu dilahap habis.
ADVERTISEMENT
Dan Kartono menjadi makmum yang taat pada sang motivator. Ia bongkar gudang belakangnya, ia keluarkan koleksi barang-barang antiknya, semuanya untuk dijual ke tukang loak. Uang hasil penjualannya? Semuanya ia habiskan untuk sedekah, tanpa tersisa satu sen pun. Kartono coba mempraktekkan salah satu metode yang dibilang mujarab oleh sang motivator, yakni bahwa dengan makin banyak bersedekah niscaya makin dibukakan pintu rezekinya. Dengan otak yang dijejali ilmu teknik sekian tahun, Kartono membuat persamaan garis linear: bahwa semakin banyak ia sedekahkan, pasti makin banyak ia dapatkan timbal balik dari Tuhan.
Ternyata hasilnya tidak seideal persamaan matematika yang ia rumuskan itu. Makin lama Kartono mikir, “kok malah saya jadi perhitungan ya sama Tuhan!”. Ini sepertinya gak bener, pikirnya. Kok jadi kita transaksi jual beli sama Allah. “Pokoknya ya Gusti, saya sudah sedekah sekian ribu rupiah ya. Mudah-mudahan diterima dan saya dapet balesan sekian juta ya Gusti. Amiiinn…”. Duh!

ADVERTISEMENT
Sejak saat itu Kartono berhenti mengikuti kata-kata mulia dari sang motivator.
Tok tok. Kartono mengetuk pintu rumah pak Karyo yang memiliki warung sembako kecil disamping halaman.
“Assalamualaikum pak Karyo.”
“Waalaikumsalam. Eh kamu Kartono! Ayo masuk sini.” Pak Karyo melepas kacamata-nya sembari meletakkan Koran Pikiran Bangsa terbitan pagi yang baru sempat dibacanya setelah buka puasa.
“Nggih, Pak." Jawab Kartono sopan. Biar bagaimanapun, Kartono selalu hormat pada pak Karyo, gurunya itu. Walaupun sering dimaki dan dibilang bodoh saat jaman bimbingan skripsi dulu, Kartono tetap segan pada beliau. Karena kalau saja pak Karyo tidak tegas dan galak padanya, mungkin saja dia masih terjebak dalam dunia game online yang meracuninya hingga lupa kuliah.
“Gimana kabar kamu Kartono? Sepertinya tambah sehat. Sibuk apa sekarang?”
ADVERTISEMENT
“Anu pak Karyo… Sekarang saya punya usaha sendiri. Masih kecil-kecilan sih. Coba-coba jadi konsultan.”
“Woo lah bagus itu, No! Memang harus begitu anak muda.”
“Nggih, pak.”
“Jadi wirausaha itu bagus, No. Karena itu berarti kamu membuka lapangan pekerjaan buat orang lain.”
“Nggih, betul pak”. Kali ini Kartono menjawab sembari tersenyum kecut. Sepertinya pak Karyo mood-nya lagi bagus nih, pikir Kartono dalam hati.
Ingatan Kartono kembali lagi pada lima tahun yang lalu. Saat pertama kali ia mengutarakan niatnya untuk berwirausaha pada Pak Karyo. Apes, bukannya pujian atau nasehat yang ia dapat, yang ada malah omelan dengan suara nyaring dan cempreng khas mantan dosennya itu.
“Kamu itu, kuliah bertahun-tahun kok udah berniat wirausaha. Terus ilmu termodinamika, perancangan mesin, perhitungan roda gigi, analisa kegagalan material dan lain-lain itu mau kamu apakan? Ha mbok kerja dulu! Ngikut orang dulu, praktekkan dulu ilmu kamu, kumpulkan modal dulu, baru wirausaha!” kata pak Karyo. Lantang, keras dan tanpa jeda ambil napas.
ADVERTISEMENT
Kartono ciut nyalinya. Tapi dasar karakter orang bangsa ini – ngeyel, makin dilarang justru makin penasaran. Nasehat pak Karyo yang diseganinya pun tak digubris. Dia tetap nekad untuk berwirausaha. Makanya dia baru berani sowan setelah lima tahun. Dia baru berani menunjukkan batang hidungnya setelah perusahaannya punya kantor sendiri, walaupun masih ngontrak sama pihak yang menyewakan ruang kantor yang bukan wujud kantor (baca : virtual office).
“Iya pak Karyo, Alhamdulillah. Usaha saya sudah cukup lumayan. Oya saya kesini mau curhat sesuatu pak.”
“Gimana gimana, No? Kok kayaknya penting sehingga kamu jauh-jauh kesini ke Kota Geulis.”
“Ya pak. begini. Saya itu awal-awalnya dapet klien pabrik-pabrik kecil. Mereka banyak mengeluhkan soal performa mesinnya dan minta saya untuk menganalisanya. Namanya pabrik kecil, sing penting mesin mereka beres. Mesin oke, produksi lancar, wis cukup. Makanya mereka gak macem-macem pak.”
ADVERTISEMENT
“Macem-macem gimana maksudnya, No?”
“Begini pak. mereka itu gak macem-macem. Maksudnya gak minta ‘jatah’ sama sekali pak. Ya saya bersyukur toh. Ketemunya klien yang seperti ini. Tapi minggu lalu saya dapet tawaran pekerjaan dari salah satu kementerian urusan bangsa.” Papar Kartono.
“Lho bagus dong. Artinya level kamu sudah meningkat, sampe dipanggil sama kementerian urusan bangsa. Gak sembarang vendor lho, bisa tembus kementerian itu.”
“Ya pak. Saya juga cukup senang dapat kesempatan itu. Tapi anu e pak… Mereka minta dihitung, kira-kira mereka bisa dapet ‘jatah’ berapa persen…”.
Kali ini pak Karyo terdiam.
“Lha saya gak sreg to pak. Itu kan sama saja namanya aksi preman. Itu kan uang bangsa. Bukan hak mereka to', Pak. Mereka sih menyebutnya uang tabungan, Pak. Nanti buat dibagi-bagi kata salah satu pimpinannya.”
ADVERTISEMENT
Pak Karyo menghela napas panjang.
“Trus gimana, No? Kamu jadi ambil pekerjaan di situ gak?”, Tanya pak Karyo.
“Ya masih mikir-mikir ini, Pak. Sekarang ini kan mau Lebaran, Pak. Saya perlu pekerjaan ini buat bayar THR”, jawab Kartono lirih dan berat. Tenggorokan Kartono mendadak kering, padahal tadi ia buka puasa dengan minum es degan dan sop buah. Buat Kartono, ini bukan masalah sepele. Bukan mau terlihat sok idealis, tapi ia merasa ada yang tidak benar. Bahwa dia sedang berhadapan dengan masalah klasik bangsa ini, persoalan yang sudah dianggap bukan persoalan. Urusan uang pelicin yang dianggap wajar dalam berbisnis bagi sebagian orang.
Tapi Kartono tetap merasa ini salah. Setidaknya itu menurut kata hati kecilnya. Dan entah kenapa kali ini ia ingin sekali-kali mendengarkan hati kecilnya itu.
ADVERTISEMENT
“Begini, No. Saya mengerti perasaan kamu. Memang itu tidak benar. Dan kamu akan banyak temui praktek semacam itu. Ya kembali ke kamu saja, gimana enaknya. Saya punya cerita. Dulu saya pernah punya teman, Kardiman namanya. Dia sama persis seperti kamu, memikirkan apa ini benar gak ya. Ini halal gak ya. Itu halal gak ya. Ini sepertinya salah deh. Begitu terus. Sampai akhirnya dia stress, karena menurutnya tidak ada pekerjaan yang halal dan benar-benar bersih di dunia ini.”
“Terus, terus… Gimana tuh nasib teman bapak, Kardiman itu?”
“Lho gimana toh, No. Kan saya bilang, dia stress. Akhirnya dia memilih untuk berdiam diri saja, gak ngapa-ngapain. Dan sampai seusia saya ini, dia masih tinggal sama orangtuanya. Tidak berkeluarga.” Jelas pak Karyo.
ADVERTISEMENT
Kartono kembali terdiam. Sebenarnya dia juga pernah mendapat nasihat dari koleganya. Bahwa dalam berbisnis dia harus siap wal afiat menghadapi praktek-praktek seperti ini.
“Kamu tau ndak, kenapa kita harus zakat. Ya untuk ini bro. Untuk membersihkan harta kita ini. Harta dan uang yang kita dapat lewat transaksi abu-abu seperti ini. Jadi makanya santai saja lah. Yang penting bayar zakat, beres!”, kata salah seorang teman Kartono, seorang keturunan Arab yang punya usaha kontraktor sipil.
Dipikir-pikir lagi, Kartono juga tidak mau nasibnya berujung seperti Kardiman, teman pak Karyo itu yang katanya malah jadi stress. Kartono tetap merasa bahwa ia adalah salah satu putra terbaik bangsa yang harus berkontribusi positif untuk bangsanya ini.
ADVERTISEMENT
“Idealis itu harus, No. Itu namanya kita punya prinsip. Dulu saya juga sempet mroyek sana-sini. Ya kamu tau lah, gaji dosen seperti saya berapa sih. Makanya saya perlu pemasukan yang lain. Tapi akhirnya berhenti juga. Karena saya gak suka keluarkan uang jatah seperti itu. Makanya pas ada modal sedikit, saya buka warung sembako kecil di rumah. Lumayan lah.”
Kartono manggut-manggut. Ia setuju dengan pak Karyo. Sepertinya berdagang sembako itu lebih aman, gak neko-neko lah. Dan bisa terhindar dari praktek uang pelicin seperti yang sedang ia pusingkan.
“Pak Karyo, maaf pak. Ada yang mau ketemu.” Kirun, asisten rumah tangga pak Karyo meng-interupsi perbincangan Kartono dan pak Karyo.
“Oya sebentar ya, No. Run, tolong bikinkan kopi buat tamu saya ini ya,” Pak Karyo memerintahkan Kirun sambil berlalu.
ADVERTISEMENT
Setelah tiga teguk kopi hitam yang di-request Kartono pada Kirun untuk dibikin tanpa gula, pak Karyo kembali ke ruang tamu. Wajahnya tampak tegang, sedikit berbeda dengan saat sebelum meninggalkan Kartono tadi.
“Ada siapa pak? Kok sepertinya tamunya penting.” Tanya Kartono heran.
“Anu … itu, No… Tiap minggu dia datang ke warung. Biasa, minta ’Jasa keamanan’…” []
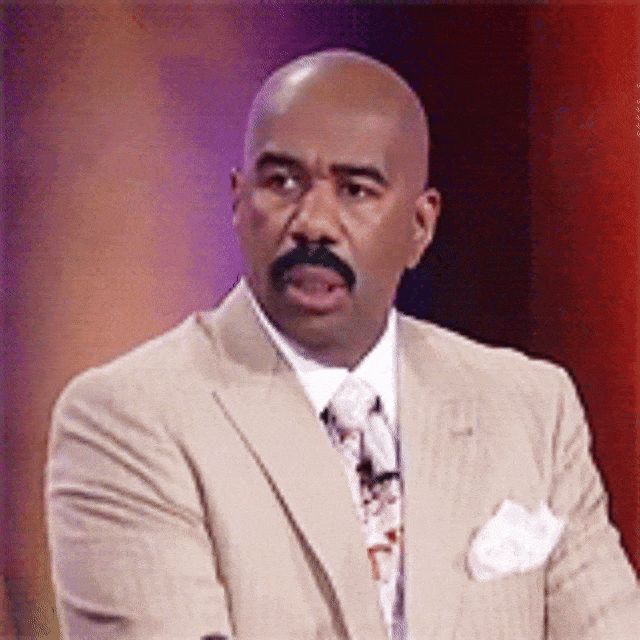
***
*) Terinsipirasi esai “2.000 Mayat Mencari Keadilan” karya Danarto

