Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Konten dari Pengguna
Rayakan, Jangan Membatalkan: Merangkul Perbedaan Lewat Budaya dan Konteks
14 Januari 2025 12:16 WIB
·
waktu baca 4 menitTulisan dari Timothee Kencono Malye tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
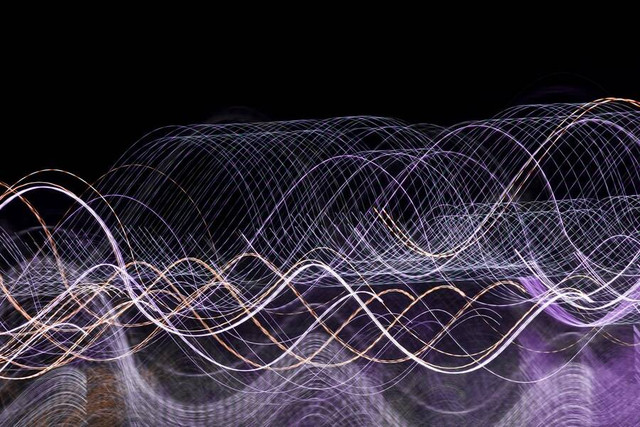
ADVERTISEMENT
Dunia modern dipenuhi dengan keberagaman budaya yang diperkaya oleh berabad-abad migrasi, perkawinan lintas budaya, dan pertukaran gagasan. Namun, di tengah era politik identitas dan gerakan woke, keberagaman ini sering kali menjadi senjata. Upaya yang bertujuan baik untuk mendorong inklusivitas justru kerap membungkam dialog terbuka, menggantikan rasa ingin tahu dengan kehati-hatian yang berlebihan. Untuk sepenuhnya merayakan kekayaan perbedaan kita, kita harus menaruh perhatian pada konteks budaya yang mendalam yang membentuk perilaku manusia, sambil menolak dogma kaku yang dibawa oleh politik identitas.
ADVERTISEMENT
Manusia dibentuk terutama oleh lingkungannya (nurture), yang memengaruhi praktik, nilai, dan perspektif masyarakat secara keseluruhan. Studi dalam psikologi perkembangan, seperti yang dilakukan oleh Urie Bronfenbrenner, menunjukkan bagaimana konteks sosial dan budaya membentuk perkembangan individu. Sebagai contoh, seorang anak yang dibesarkan dalam masyarakat kolektivis seperti Jepang mungkin menginternalisasi nilai harmoni dan saling ketergantungan, sementara anak di budaya individualistis seperti Amerika Serikat cenderung memprioritaskan ekspresi diri dan kemandirian.
Meski boleh jadi genetika sedikit-banyak memainkan peran dalam keberagaman sifat manusia, fokus pada faktor budaya dan lingkungan menghindarkan kita dari jebakan determinisme biologis yang reduktif. Praktik budaya—termasuk tradisi kuliner, bahasa, dan ekspresi seni—sangat dipengaruhi sejarah dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata hasil biologi. Misalnya, keragaman gaya musik di dunia mencerminkan bukan predisposisi genetik, melainkan pengaruh geografi, teknologi, dan identitas komunitas.
ADVERTISEMENT
Namun demikian, politik identitas sering kali menyimpang dari tujuannya, membungkam perayaan keberagaman ini. Dahulu alat untuk mempromosikan diskusi yang saling menghormati, kini ia berubah menjadi kerangka kaku yang mengontrol bahasa dan pemikiran. Politik identitas dapat dijadikan sebagai alat kontrol massa yang efektif. Dengan memprioritaskan keseragaman ideologi di atas kebebasan berpikir, pendekatan ini berisiko menekan pluralisme yang justru ingin dilindungi.
Ambil contoh bahasa. Penelitian oleh ilmuwan kognitif Lera Boroditsky menunjukkan bagaimana struktur linguistik membentuk persepsi. Penutur bahasa yang memiliki gender seperti Spanyol atau Jerman sering mengkategorikan objek berbeda dari penutur bahasa tanpa gender seperti Mandarin. Temuan ini menyoroti bahwa praktik budaya, termasuk bahasa, tertanam dalam cara manusia mengalami dunia. Namun, atas nama inklusivitas, sebagian pendukung gerakan woke menyerukan reformasi bahasa yang menghapus kekhasan budaya, secara tidak sengaja menyamakan ekspresi manusia.
ADVERTISEMENT
Ekses gerakan woke—sebuah ideologi yang bertujuan mengatasi ketidakadilan sosial tetapi sering menyederhanakan isu kompleks—semakin memperkeruh diskursus ini. Tekanan untuk memberi label dan mempermalukan individu atas pelanggaran yang dianggap salah menumbuhkan perpecahan daripada pemahaman. Sebagai contoh, ketika seseorang menunjukkan pola umum dalam praktik budaya atau pencapaian, mereka berisiko dicap ofensif. Reaksi ini mengaburkan batas antara pengamatan dan prasangka, menghalangi diskusi yang bernuansa dan menjauhkan sekutu potensial.
Daripada membatalkan (“to cancel”) mereka yang mengakui perbedaan budaya, kita seharusnya menumbuhkan budaya ingin tahu dan saling menghormati. Mengakui perbedaan tidak berarti menegasikan kemanusiaan kita yang sama. Sebaliknya, hal itu menyoroti cara luar biasa manusia merespons tantangan kehidupan dan kebersamaan. Kecenderungan budaya cancel untuk menghukum sering kali mengabaikan niat, menyamakan pengakuan dengan kebencian. Pendekatan yang lebih konstruktif adalah mendidik masyarakat tentang cara membahas topik sensitif dengan empati dan ketelitian.
ADVERTISEMENT
Para pembuat kebijakan dan pendidik memiliki peran penting dalam membangun lingkungan ini. Kurikulum perlu menekankan keterkaitan antara budaya dan konteks, mengajarkan siswa untuk menghargai warisan mereka sendiri sekaligus warisan orang lain. Diskursus publik harus melampaui perdebatan yang terpolarisasi menuju komitmen bersama untuk saling memahami. Pemerintah juga harus berhati-hati, memastikan bahwa undang-undang anti-diskriminasi melindungi dari bahaya nyata tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
Untuk merayakan keberagaman secara autentik, kita harus menolak tirani kepekaan berlebihan. Perbedaan bukanlah kekurangan; melainkan fondasi inovasi, ketahanan, dan kreativitas. Baik melalui lensa budaya maupun pengalaman bersama, kaleidoskop cerita manusia layak untuk dikagumi, bukan dicela. Dengan mengenali dan menghargai perbedaan ini, kita menjunjung tinggi cita-cita kesetaraan dan inklusi yang ingin dicapai masyarakat.
ADVERTISEMENT
Kini saatnya merebut kembali wacana dari dogma politik identitas dan "wokeism". Dengan merangkul keberagaman budaya dan mendorong dialog terbuka, kita menegaskan sebuah kebenaran sederhana namun mendalam: keberagaman bukanlah masalah yang harus dipecahkan, melainkan harta yang harus dirayakan.
Paus Fransiskus wafat di usia 88 tahun pada Senin pagi (21/4) akibat stroke dan gagal jantung. Vatikan menetapkan Sabtu (26/4) sebagai hari pemakaman, yang akan berlangsung di alun-alun Basilika Santo Petrus pukul 10.00 pagi waktu setempat.

