Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.104.0

ADVERTISEMENT
“Gak mau, ah. Aku aja kalau sekolah sampai jam satu siang udah capek.”
ADVERTISEMENT
Sita, seorang anak murid kelas 12 (kelas 3) SMA Marsudirini Bekasi kesal saat mendengar waktu bersekolah akan ditambah hingga delapan jam sehari. Menurutnya, 8 jam di sekolah tidak kondusif untuk murid.
Sita merasa, durasi 7 jam sekolah yang kini ia jalani pun sudah begitu melelahkan. Belajar mulai jam 7 pagi hingga 14 siang membuat kepala penat dan tubuh lelah dikerat tenggat. Bahkan menambah satu jam lagi, dia enggan bukan main.
Tak cukup dibuat “kejang” dengan wacana pergantian sistem belajar 8 jam di sekolah, anak-anak didik pun acap dibuat bingung dengan perubahan kurikulum yang begitu cepat.
Misalnya saja saat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berubah menjadi Kurikulum 2013 (K-13). Kala itu, KTSP yang sudah berjalan dari tahun 2006 tiba-tiba diganti dengan K-13, dengan argumentasi Kurikulum 2013 akan lebih relevan dengan zamannya.
ADVERTISEMENT
Sekolah-sekolah pun kelabakan mengganti sistem pendidikannya. Anak didik yang semula memilih jurusan saat menginjak kelas 2 SMA, kemudian mengikuti kebijakan yang berubah dengan memilih peminatan/penjurusan sejak awal masuk SMA.
Sayangnya, tenaga pendidik saat itu belum sepenuhnya siap. Perubahan yang cepat dan mendadak membuat mereka tak punya cukup waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan kompetensi sesuai K-13.
Anak didik turut kalut. Sebagian dari mereka dibuat bingung oleh para guru yang belum terbiasa dengan cara mengajar ala K-13.
[Baca juga: Mau Dibawa ke Mana Pendidikan Indonesia?]

“Mulai masuk SMA sudah dipecah IPA dan IPS. Tapi, kurikulumnya kan waktu itu masih kontroversial karena gurunya belum pada siap. Jadi kami bingung karena guru nggak ngejelasin apa-apa dalam kegiatan belajar mengajar,” kata Sita.
ADVERTISEMENT
Hal serupa dirasakan Kania yang juga duduk di kursi kelas 12 SMA Marsudirini. Ia mengatakan, perubahan kurikulum dari KTSP ke K-13 lebih sering membuatnya bingung ketimbang paham dengan apa yang dipelajari di sekolah.
“(Rasanya) aneh, karena udah ngerasain KTSP, terus berubah jadi K-13, lalu tiba-tiba jadi KTSP lagi,” ujar Kania.
Ah, dunia pendidikan Indonesia memang kadang begitu absurd. Terlebih ketika kurikulum berubah amat cepat. K-13 hanya berlaku satu semester, sebelum akhirnya kembali diubah ke KTSP pada semester kedua.
Sita dan Kania yang sempat menyicipi dua sistem tersebut betul-betul merasakan kacaunya gonta-ganti kurikulum.
[Baca juga: 10 Kali Gonta-ganti Kurikulum Pendidikan]
Bila ditilik lebih jauh, KTSP dan K-13 memiliki perbedaan cukup tajam. Mulai dari indikator, cara belajar, hingga kompetensi yang ingin dicapai.
ADVERTISEMENT
Dalam KTSP, pendidikan berpusat pada potensi, kebutuhan, serta lingkungan anak didik. Dengan sasaran tersebut, kurikulum didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan anak didik yang tentunya memiliki relevansi dengan dunia karier.
Indikator penilaian KTSP pun berbeda dengan K-13 yang belakangan akan ditetapkan secara nasional. KTSP menekankan pada nilai angka sebagai indikator pengetahuan anak. Oleh sebab itu penilaian bersifat lebih kuantitatif --merujuk pada jumlah jawaban benar yang bisa dicapai oleh si anak.

Sementara K-13 yang menekankan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, menggunakan indikator yang bersifat kualitatif untuk mengukur tumbuh kembang anak. Angka yang diberikan pun memiliki pola berbeda --menggunakan angka 4 sebagai nilai tertinggi, dan indikator huruf alfabet A-F untuk menilai sikap, perilaku, dan pengetahuan.
ADVERTISEMENT
Perbedaan juga terasa dari sisi sistem belajar mengajar yang berlangsung di kelas. Dalam KTSP, kegiatan belajar mengajar masih kerap berpusat pada penyampaian materi oleh guru, dan anak didik cenderung lebih banyak menerima.
Sementara pada K-13, kegiatan belajar mengajar lebih banyak berpusat pada anak dan kreativitas mereka. Sikap proaktif dan kritis pun dibangun dengan membiasakan anak didik mencari materi ajar yang berkaitan dengan topik pilihan dalam pelajaran.
Sikap proaktif dan kritis tersebut dibentuk salah satunya melalui intensitas presentasi materi yang lebih padat dibanding dengan KTSP.
“K-13 lebih banyak presentasinya, walau gak beda jauh dengan jumlah presentasi saat KTSP,” kata Kania.
K-13 menuntut anak didik untuk lebih aktif dalam diskusi kelas. Sementara tenaga pendidik hanya berperan sebagai fasilitator untuk proses belajar mengajar tersebut.
ADVERTISEMENT
[Baca juga: “Mengurung” Anak Sehari Penuh di Sekolah]
Sita dan Kania bisa jadi lebih beruntung karena mengecap pendidikan di kota --yang walau karut-marut pendidikan masih terjadi, setidaknya proses adaptasi terhadap kurikulum baru lebih mudah dijalani karena sarana-prasarana yang lebih memadai, dengan kualitas dan kuantitas yang juga cukup mumpuni ketimbang di daerah-daerah.
Sementara, nun jauh di barat Kalimantan, Baskoro yang kini duduk di kelas 3 SMA di SMA 1 Putussibau, tak banyak mengecap K-13 sejak ia masuk SMA. Angkatan Baskoro ditetapkan untuk tetap memakai KTSP, sementara angkatan senior dan juniornya mulai menggunakan sistem K-13.
Walau menggunakan KTSP, Baskoro mengatakan guru-gurunya sudah mulai mencoba menerapkan cara belajar dengan gaya K-13. Harapannya, sekolah mereka tetap bisa berjalan seiring dengan perubahan kurikulum yang dicanangkan pemerintah.
ADVERTISEMENT
Baskoro pun menyadari terdapat perbedaan cukup mencolok antara KTSP dengan K-13. Dan ia melihat, masih terjadi kebingungan antara anak didik dan guru.
Proses adaptasi yang berjalan pun tak bisa serta-merta sukses, terlebih penyesuaian materi hingga sarana-prasarana membutuhkan waktu cukup panjang untuk bisa sepenuhnya berpindah ke sistem baru.
“Kalau yang saya rasakan, guru di sini belum siap untuk menjalankan sistem K-13 karena sudah terbiasa dengan KTSP. Secara keseluruhan belum siap,” ujar Baskoro.
Ketidaksiapan ini ia lihat dari interaksi guru dan murid yang seharusnya memakai sistem K-13 nyatanya masih tetap menggunakan gaya KTSP di mana guru lebih aktif dalam menyetir interaksi kelas.
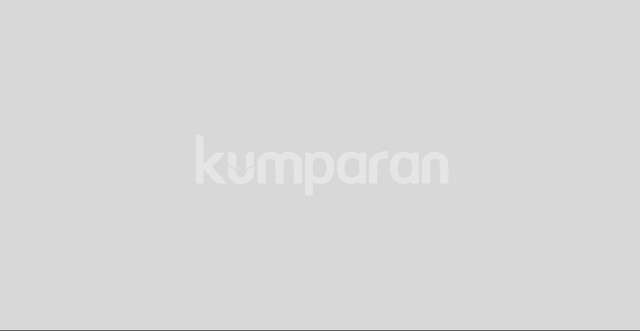
Begitu pelik kelindan dan dinamika perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Belum selesai urusan rumit KTSP dan K-13, kini mencuat aturan 8 jam di sekolah yang direncanakan berjalan mulai Juli 2017, saat tahun ajaran baru 2017/2018.
ADVERTISEMENT
Bagi sebagian anak murid, bayangan 8 jam di sekolah terasa bikin hati berat. Apalagi bagi mereka yang biasa menghabiskan waktu pulang sekolah dengan bermain bersama kawan-kawan di lingkungan rumah. Kesenangan itu tentu terancam terenggut.
[Baca juga: Buat Apa 8 Jam di Sekolah?]
Karina Adistiana, pakar psikologi pendidikan, berpendapat substansi perdebatan sebetulnya tak cuma pada masalah durasi, tapi teknis pelaksanaan aturan.
Ia pun menyayangkan jika terdapat penyeragaman dalam penerapan aturan 8 jam sekolah itu dari Sabang sampai Merauke. Ia menilai aturan tersebut sesungguhnya tidak kontekstual.
“Yang dipertanyakan bukan soal durasi, karena (kegiatan tambahan) itu sebenarnya gak harus di sekolahnya. Yang dipertanyakan adalah keseragamannya --memberlakukan sistem dari Sabang sampai Merauke yang kok sama, tapi arahnya ditarik ke pusat,” kata Karina kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (15/6).
ADVERTISEMENT
Karina mengatakan, mestinya aturan disesuaikan dengan konteks daerah. Sebab setiap daerah memiliki karakter sosial dan geografis yang beragam.
Penerapan aturan 8 jam per hari yang tersentralisasi pun dirasa Karina terkesan menafikan konteks lokal yang tak pernah sama satu sama lain di Indonesia.
Perlu juga diperhatikan, jika anak “terpenjara” 8 jam sehari di sekolah, kemungkinan ia stres akan lebih tinggi.
“Kalau kita bicara tentang daerah-daerah, (8 jam di sekolah) kurang memungkinkan jika dilihat dari segi geografis. Bisa-bisa anak didik harus berangkat sekolah pagi sekali, lalu pulang larut sekali karena kondisi alamnya,” ujar Karina.

Aturan 8 jam di sekolah, dalam sudut pandang Karina, bisa jadi efektif diterapkan pada pendidikan di kota-kota besar yang lengkap dengan kemudahan akses plus fasilitas.
ADVERTISEMENT
Namun, bisa jadi sistem ini sama sekali tak cocok bila harus diterapkan di daerah dengan konteks sosial masyarakat yang masih mengedepankan kegiatan sosial dan belajar di luar kelas ketimbang pendidikan dalam kelas semata.
Jika memang aturan tersebut ingin dibuat sekontekstual mungkin, menurut Karina, perlu kesiapan materi lokal yang mampu mendorong anak didik menjadi aktivis dan agen perubahan di tiap daerahnya.
Masalahnya, kurikulum pendidikan di Indonesia belum mampu menyajikan materi yang kontekstual di tiap daerah akibat standardisasi pendidikan yang terpusat di kota-kota besar. Dan konteks kedaerahan kerap kali tertinggal --dan dibiarkan ditinggal-- di belakang.
Pula, Karina melihat sesungguhnya aturan 8 jam di sekolah lahir tanpa ada landasan filosofis dan data yang jelas. Aturan ini seakan diciptakan tanpa dipikir secara matang dan tak berdasarkan pertimbangan.
ADVERTISEMENT
“Dalam audiensi yang berjalan dari tahun lalu, perdebatan sudah muncul begitu kencang. Banyak yang mempertanyakan apa landasan filosofisnya? Datanya mana? Itu yang seharusnya dibuka ke publik. Kenapa harus 8 jam? Apa pertimbangannya?” kata Karina.
Soal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah menyinggungnya. Kebijakan 8 jam di sekolah, menurut dia, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang di dalamnya memuat beban kerja guru (yang PNS).
Pasal 52 ayat (2) PP tentang Guru menyebut beban kerja guru --yakni merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, serta membimbing dan melatih peserta didik-- paling sedikit dalam seminggu memenuhi 24 jam tatap muka (4,8 jam sehari) dan paling banyak 40 jam (8 jam sehari).
ADVERTISEMENT
“Jika kita kedepankan kinerja guru sebagaimana standar yang berlaku bagi ASN (aparatur sipil negara), maka sekolah harus menyesuaikan hari sekolah jadi 5 hari seperti 5 hari kerja,” kata Muhadjir.
Jadi, ujarnya, program 8 jam di sekolah akan menguntungkan guru, namun ia jamin tak bakal merugikan murid, karena kebijakan lebih menekankan pada pembangunan karakter.

Perjalanan menuju pendidikan yang lebih baik masih begitu panjang. Semoga bangsa ini tak jengah meneteskan peluh untuk mencapai pendidikan yang lebih memanusiakan manusia.
