Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
ADVERTISEMENT

pada masa kanak-kanakku
setiap jam tujuh pagi
aku harus seragam
bawa buku
harus mbayar
ke sekolah
ADVERTISEMENT
Remaja kurus kering itu bersiap berangkat ke sekolah. Terlihat jelas ia bukan pelajar teladan. Baju seragam tak rapi. Ujung kemeja putih yang seharusnya dimasukkan ke dalam celana biru, malah dikeluarkan. Berantakan.
Badung. Itulah kesan kawan-kawan sekelasnya tentang si kerempeng. Dia sering bercanda dan ribut sendiri, sampai dimarahi ketua kelas dan guru.
Ah, siapa bisa lupa si badung? Kenangan tentangnya, tentang masa sekolah 37 tahun silam bersamanya, tak jua lapuk dari ingatan teman-temannya.
Si badung kemudian dikenal dengan nama Wiji Thukul, sang penyair pemberontak yang ditakuti rezim Orde Baru, mata badai dalam sejarah Indonesia, orang yang hilang tak tentu rimbanya --dengan puisi-puisi karyanya yang menggema melintasi masa.
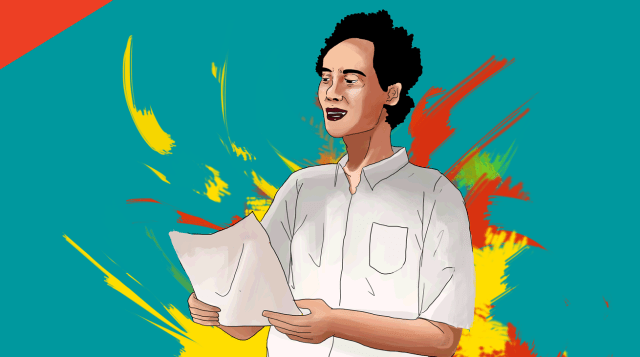
“Yang namanya Thukul itu bikin gaduh terus di kelas. Dia sepertinya enggak bisa ngomong pelan. Pas istirahat, kadang juga pas jam pelajaran, dia teriak-teriak. Dia sering dimarahi ketua kelas, dimarahi guru-guru,” kata Suparno, teman sekelas Thukul di SMP Negeri 8 Surakarta.
ADVERTISEMENT
Kepada kumparan, Minggu (15/1), Suparno yang kini menetap di Purworejo, Jawa Tengah, berbagi kenangan masa sekolahnya bersama Wiji Thukul --yang dulu bernama Widji Widodo.
Suparno ingat jelas, Thukul muda punya temperamen keras. Ia bukan seorang peragu. Gaya bicaranya pun ceplas-ceplos, seakan tak ada yang ia takuti di dunia.
“Dia itu berangasan, cengengesan terus. Omongannya kasar. Orang ndeso kluthuk lah,” kata Suparno. “Walau saya ini urakan juga, tapi termasuk serius dibanding Thukul,” imbuhnya.
Tembok sekolah tampaknya tak cocok dengan jiwa muda Wiji Thukul. Ia tak betah. Bagi dia, dinding-dinding sekolah mengungkung kebebasan dirinya. Sejumlah peraturan ia labrak. Paling sederhana ya soal baju seragam.
Baju seragamnya yang morat-marit jadi bentuk perlawanan kecilnya. Sebuah mula. Benih “kun” dalam proses “fayakun” yang panjang. Sepercik api dari jiwa berontak yang muskil tenang.
ADVERTISEMENT
Lakunya yang harusnya diam, diteriakkan. Batinnya meronta: buat apa?
pada masa kanak-kanakku
aku jadi seragam
buku pelajaran sangat kejam
aku tidak boleh menguap di kelas
aku harus duduk menghadap papan di depan
sebelum bel tidak boleh mengantuk
“Wiji itu agak bandel. Saking sering bercanda di kelas, dia dinilai nakal sama guru, Mbeling,” kata Daryanti, tetangga kampung sekaligus teman sekelas Wiji Thukul di kelas 3A SMP Negeri 8 Surakarta.
“Anak itu ngomongnya kasar. Sukanya misuh. Kalau dia teriak-teriak ‘asu’ itu sudah biasa. Kalau jengkel, dia mengumpat-umpat sendiri,” imbuh Suparno.
Suparno dan Daryanti bercerita terpisah, namun keduanya sepakat akan satu hal: Thukul badung.
Meski demikian, Thukul tak pernah sampai kurang ajar, tak pernah berkata kasar, kepada guru-gurunya.
ADVERTISEMENT
“Kalau pas ada guru, enggak pernah teriak yang gimana-gimana,” ujar Suparno, menggali ingatan yang terkubur bertahun-tahun lalu.
katanya aku bodoh
kalau tidak bisa menjawab
pertanyaan guru
yang diatur kurikulum
Sebadung-badungnya Thukul, ia tetap baik di mata Daryanti. Ia menilai Thukul sebagai sosok sederhana, di rumah maupun di sekolah.
“Wiji itu anaknya nyantai, lucu. Ngguya-ngguyu, ketawa-ketawa saja. Sukanya gojek, guyon,” ujar ibu dua anak itu, ikut tertawa mengenang tawa Thukul.
Perempuan yang kini menjadi dosen di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta itu lantas menirukan seloroh Thukul.
“Ayo ning omahe Daryanti, golek pelem,” ujarnya. Artinya kira-kira, “Ayo ke rumah Daryanti, ambil mangga.”
Jika musim mangga, ujar Daryanti, Thukul dan teman-teman mereka memang sering main ke rumahnya. “Manjat pohon mangga di depan rumah.”
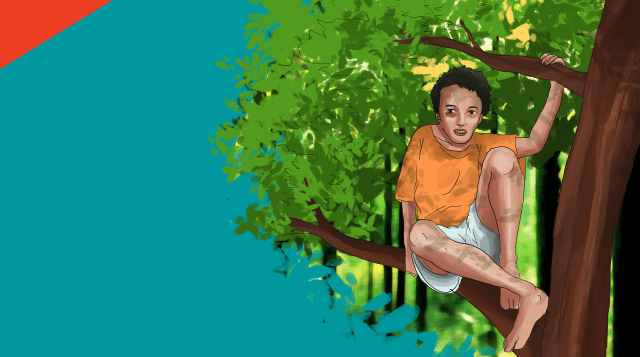
Rumah Daryanti yang dekat dengan tempat tinggal Thukul membuatnya sedikit banyak mengenal keluarga Thukul.
ADVERTISEMENT
Thukul sekeluarga ialah rakyat jelata, dengan kondisi ekonomi pas-pasan, tak seberuntung orang lain. Ayah Thukul, Kemis Harjosuwito, menghidup keluarganya dari menarik becak.
Kemis kerap bertandang ke toko kelontong milik ibu Daryanti untuk sekadar membeli rokok atau penganan.
“Rumah saya kan di pinggir jalan ya. Nah, kebetulan ibu saya buka warung. Jadi saya sering lihat bapaknya si Wiji itu. Pak Kemis mangkal becak dekat rumah saya,” kata Daryanti.

aku dibentak dinilai buruk
kalau tidak bisa mengisi dua kali dua
aku harus menghafal
mataku mau tak mau harus dijejali huruf-huruf
Mau bagaimana lagi, Wiji Thukul muda memang tak suka belajar di kelas. Ia sampai kerap dimarahi Daryanti, kawannya.
“Ya sebenarnya bukan memarahi,” kata-kata Daryanti tertahan di tenggorokan. “Lebih seperti memberi tahu, mengingatkan teman,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
Kebetulan, waktu itu Daryanti ketua kelas. Mengingatkan teman yang badung semacam Thukul adalah hal biasa baginya.
Tapi Thukul tetaplah Thukul, dengan sukma bak bara api menggelegak.
aku harus tahu siapa presidenku,
aku harus tahu ibukota negaraku
tanpa aku tahu
apa maknanya bagiku
Tentu saja, bukan cuma Thukul yang punya perasaan seperti itu. Mungkin banyak anak sekolah, dari dulu sampai sekarang, yang memendam pikiran serupa.
Bedanya, Thukul menyuarakannya dengan lantang. Jiwanya burung rajawali. Terbang garang tak bisa dikekang.
penjara sekalipun
tak bakal mampu
mendidikku menjadi patuh
Adik Thukul, Wahyu Susilo, amat memahami isi hati sang kakak. Ia sepakat pendidikan tak hanya bisa didapat di bangku sekolah, tapi juga lewat pembelajaran di alam terbuka, di lingkungan sekitar, dengan metode-metode yang membebaskan.
ADVERTISEMENT
Thukul bukannya tak peduli pendidikan. Ia bahkan berhenti sekolah agar adik-adiknya bisa bersekolah, agar biaya pendidikan yang berat dipikul keluarganya dicurahkan untuk adik-adiknya.
“Dia sendiri tetap membaca buku. Dia memberi jalan keluar ketika aku masuk kuliah dan enggak punya biaya, dengan dia menjadi loper koran,” tutur Wahyu mengingat perjuangan kakaknya untuk dia.

Kesempatan yang diberikan Thukul kepada Wahyu untuk mengenyam pendidikan, hingga kini menjadi peninggalan yang paling berharga dari sang kakak.
Wahyu tahu benar pendidikan seperti apa yang diinginkan Thukul: pendidikan membebaskan sebagai jalan untuk melawan kekuasaan lalim.
Sejak muda, Thukul telah memulai perjalanannya menuju kegigihan sikap, jiwa juang yang meneriakkan: tirani harus tumbang!

Kenali Wiji Thukul lebih dalam
ADVERTISEMENT
