Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Orkestra Rindu Wani dan Fajar Merah untuk Wiji Thukul
26 Januari 2017 12:11 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:19 WIB
ADVERTISEMENT
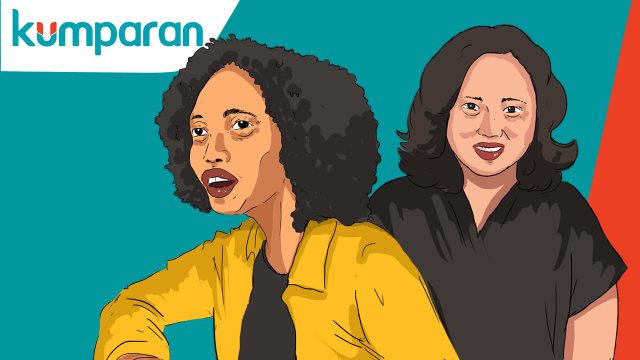
Gelap dan mendung kian pekat kala Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah masuk ke pelataran Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Fajar tampak memanggul gitar di punggung.
ADVERTISEMENT
Cuaca yang kurang bersahabat malam itu, Selasa (24/1), rupanya tak menyurutkan niat seratusan orang yang sudah menunggu momen langka tersebut.
Wani dan Fajar menampilkan musikalisasi puisi pada acara Ngamen Puisi. Mereka tampil bersama. Fajar memainkan gitar, sedangkan Wani membacakan puisi.
kaulempar aku dalam gelap
hingga hidupku menjadi gelap
kausiksa aku sangat keras
hingga aku makin mengeras
kau paksa aku terus menunduk
tapi keputusan tambah tegak
Derita Sudah Naik Seleher, puisi Wiji Thukul, dibawakan Fajar dan Wani dengan tempo meledak-ledak.
Penonton tersirap magi penampilan mereka. Fajar dan Wani seperti menyajikan orkestra kemarahan dan kerinduan dengan begitu indah.
Barangkali, memang begitu jika rindu dan derita sudah sampai naik seleher.
19 tahun sudah kedua anak WIji Thukul itu tak pernah berjumpa ayah mereka –yang hilang tak tentu rimbanya.

Usai penampilan singkat musikalisasi puisi itu, Wani berjalan menjauhi kerumunan. Gerimis mulai turun. Dan tetes air mata bergulir di pipi Wani.
ADVERTISEMENT
Dengan wajah sendu, ia mengajak kumparan duduk di sebuah kafe di depan bioskop Empire XXI di kawasan Cikini itu.
Sedih hati Wani sudah terasa sejak ia keluar dari salah satu pintu teater bioskop yang baru saja selesai menayangkan film Istirahatlah Kata-Kata.
Saat itu ia menangis, dan salah seorang kawannya mencoba menenangkan dengan memeluk dia.
“Sudah ya nangisnya,” kata sang teman.
Perlahan, tangis Wani mereda. Dari matanya yang basah, terpancar sorot getir bercampur tegar.
Wani dan Fajar datang ke Empire XXI di Cikini untuk memenuhi undangan khusus acara nonton bareng Istirahatlah Kata-Kata.
Film tersebut menceritakan pelarian Wiji Thukul dari Surakarta, Jawa Tengah, ke Pontianak, Kalimantan Barat, saat ia menjadi buron mulai pertengahan 1996.
ADVERTISEMENT
Catatan pelarian itu kemudian berujung hilangnya dia. Hingga detik ini, tak ada yang tahu di mana Thukul berada.

Wani tampak sentimental. Meski sempat surut, air matanya kembali tumpah. Memori sang ayah memenuhi alam pikirnya, tak mau lepas dari benak Wani.
“Saya mengenang bapak setiap kali saya melihat ibu,” ujar Wani membuka perbincangan.
Sang ibu, Siti Dyah Sujirah atau biasa dipanggil Sipon, tinggal di Solo, satu rumah bersama Fajar. Sementara Wani tinggal bersama suami dan putri kecilnya yang berusia 4 tahun.
Wani bercerita, tiap masuk ke rumahnya di Solo itu, dadanya selalu sesak. Apalagi saat berbincang dengan ibunya, topik tentang sang ayah selalu muncul.
“Apapun yang kami bicarakan, ujung-ujungnya selalu bapak. Entah obrolan ringan atau berat, selalu ujung-ujungnya bapak,” kata Wani.
ADVERTISEMENT
“Selain itu, ketika melihat adik saya, dia sangat mirip dengan bapak,” ujarnya.
Kerinduan kerap muncul tiba-tiba.
“Bahkan ketika melihat anak dengan suami saya, jadi teringat bapak. Ingat ketika saya dulu diajak ke toko buku, diajak lihat kereta. Kenangan sebatas anak usia 8 tahun,” kata Wani.
Dari sekian momen pedih itu, Wani merasa yang terberat adalah ketika ia harus tumbuh dewasa di masa-masa sulit sembari mendampingi ibunya.
“Ketika mengingat bapak, pernah ada perasaan marah. Pernah ada perasaan tidak terima. Bertanya kenapa ini menimpa keluarga kami,” tutur Wani.
Nada geram terdengar dari suara perempuan itu.
“Saya (waktu itu) ingin tahu apa yang dilakukan bapak di luar rumah, dan kenapa bapak bisa membuat masyarakat demikian heboh,” lanjut Wani.
ADVERTISEMENT
Meski Wani remaja marah bukan main, ia sadar pengorbanan sang ayah tak sepenuhnya sia-sia
“Toh bapak seperti ini dampaknya bagus. Kita merasakan kebebasan seperti sekarang,” ujar Wani, kini paham sepenuhnya.
Jika kami bunga
Engkau adalah tembok itu
Tapi di tubuh tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!
Dalam keyakinan kami
Di manapun -- tirani harus tumbang!
Kemarahan Thukul yang tercermin dalam puisi-puisinya, menjalar ke hati Wani ketika ia harus merasakan dampak dari seorang ayah yang menjadi buron.
Ada satu adegan yang terekam jelas dalam benaknya dan memicu rasa kegeramannya.
“Saya ingat bagaimana marahnya saya ketika melihat rumah diobrak-abrik dan beberapa karya bapak diambil.”
ADVERTISEMENT
Nada Wani lantas meninggi.
“Bahkan gambar-gambar saya yang bertuliskan ‘Wani’ juga diambil. Padahal ‘Wani’ itu memang nama saya, bukan wani yang artinya berani!”
Wani begitu marah.
Wani, sebagaimana arti namanya, memang pemberani. Hingga detik ini, kendati nasib ayahnya tetap misteri dan periode hidupnya sempat diliputi nestapa, ia tetap berdiri.
Semua ketegaran yang ia punya, kata Wani, karena sang ayah: Wiji Thukul.
“Bapak tidak pernah mementingkan kepentingannya sendiri. Dia selalu mengingat banyak orang. Selalu ingin membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak itu kelewat baik, makanya sampai hilang,” ujarnya.

Fajar Merah. Anak kedua Wiji Thukul itu amat mirip dengan Thukul muda.
Berambut panjang sebahu, berkaus oblong dibalut kemeja flanel, Fajar tampak seperti mahasiswa jurusan seni. Betul-betul jelmaan sang ayah.
ADVERTISEMENT
Ia duduk bersila di pelataran bioskop yang ramai dilewati lalu-lalang orang. Di tempat itu, sekitar satu jam, kami mengobrol santai.
“Saya tidak punya kenangan dengan bapak,” kata Fajar.
Wajar saja, Fajar masih kecil saat Wiji Thukul buron. Ingatannya samar.
“Aku mengenal bapak ya lewat tulisan, puisi, omongan orang, dan film,” lanjutnya dalam bahasa Jawa campur Indonesia.
Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak
Kau kehendaki adanya
Engkau lebih suka membangun
Jalan raya dan pagar besi
Bagi Fajar, membaca puisi bapaknya adalah media terbaik untuk bisa berinteraksi dengan sang ayah.
Lewat puisi-puisi yang ia baca itu, sosok Thukul yang tak pernah ia temui 19 tahun terakhir ini seolah menyatu dengan raganya.
ADVERTISEMENT
“Manusia ada karena karya, dan setelah tak pikir ya nyawa bapak itu ada di karya-karyanya,” ucap Fajar.
“Hingga akhirnya cara saya memaknai dan menghormati bapak ya lewat melagukan puisi bapak.”
Fajar bercerita, seni adalah tempat peraduan terbaik baginya untuk bertemu dengan sang bapak. Itulah yang terjadi sekarang.
Sementara Thukul seorang penyair, Fajar adalah penyanyi. Napas keduanya sama: intim dengan puisi.
“Karena aku seneng seni juga, dan aku tahu karya puisinya (bapak) adalah sesuatu yang berarti karena bisa hidup beribu-ribu tahun lamanya.”

Soal film Istirahatlah Kata-Kata, Fajar mengaku senang. Menurutnya, balutan kesunyian yang dihadirkan dalam film tersebut terasa tepat untuk menggambarkan masa kaburnya Thukul.
“Apik iki, seneng wae, cocok wae dinggo aku.” Artinya kurang lebih, “Bagus ini, cocok denganku."
ADVERTISEMENT
Menurut Fajar, Istirahatlah Kata-Kata “Menceritakan masa pelariannya (Thukul). Dan karakternya yang dibuat sunyi benar-benar menarik. Keadaan sunyi itu waktu ketika pikiran dan perasaan berkecamuk tidak karuan.”
Kesunyian Thukul benar-benar diresapi Fajar dan Wani. Bagi mereka, Thukul adalah abadi.
yang gelisah mengajakku pulang
aku tahu aku tak sendirian
sesenyap apapun di manapun
Ikuti jejak Thukul pada rangkaian kisah berikut
