Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Ikhtiar Sapardi dalam Kelindan Bahasa
19 Juni 2017 9:52 WIB
·
waktu baca 7 menitDiperbarui 28 Juli 2022 22:54 WIB

Tulisan ini diawali dengan sebuah bantahan terhadap apa yang dituduhkan pada Sapardi, atau pada puisi-puisinya.
Beberapa pihak mengatakan Sapardi menutup diri dari realita kehidupan masyarakat. Bahwa ia tenggelam dalam tradisi nyanyi sunyi yang dimulai Amir Hamzah --salah satu sastrawan Pujangga Baru yang punya perhatian khusus pada tema pertentangan batin dan sisi personal jiwa manusia.
Sapardi, sederhananya, dianggap “tak banyak mengangkat masalah bangsa yang jadi perhatian orang banyak”.
Namun penyair memang tak harus berkubang dalam kolam narasi politik atau semangat berbangsa dan kebangsaan. Penyair, dan sastrawan secara umum, punya peran sama penting dalam bidangnya masing-masing. Setidaknya, begitulah yang diyakini seorang Sapardi Djoko Damono.
Menemuinya di sela-sela kegiatan pascapensiun sebagai guru, Kamis (8/6), Sapardi mengonfirmasi keyakinannya tersebut. Ia menyatakan ulang, bahwa penting melihat seorang penyair (dan kepenyairannya yang juga berarti sajak-sajak sebagai hasil jerih payahnya) lewat medan perangnya yang adil, yaitu pertempuran di padang bahasa.
“Kalau seorang penyair berjasa bagi masyarakat dan bangsanya, jasanya itu adalah dalam mengembangkan bahasa yang baru,” ucapnya dalam sebuah film pendek berjudul Aku Ingin (2005) yang disutradarai Tonny Trimarsanto.
[Baca juga: Menemui Sapardi di Juni Basah Miliknya]
Bagi Sapardi, sukses tidaknya seorang penyair paling utama diukur dari segi kebahasaan. Menurutnya, pemikiran filsafat yang dalam dan berliku adalah urusan filsuf. Sementara budi pekerti, moral, politik, sosial, agama, dan lain sebagainya seharusnya tak menjadi the sole purpose seorang penyair.
Pernyataan Sapardi tersebut bukan bermaksud mengotakkan penyair dan sastrawan terbatas pada bahasa. Sah-sah saja apabila seorang penyair menjatuhkan pilihan isi karyanya ke hal-hal material yang punya banyak resonansi aktual di masyarakat. Itu pilihan.
Meski begitu, adalah ketika puisi, meminjam kata-kata Joko Pinurbo, menjadi “tenggelam dan hilang di arus mahadalam” hingga “arwahnya menjelma menjadi pusaran air berwarna hitam”-lah yang ditakutkan Sapardi. Ia tak mau penyair-penyair lain terlalu terpaku pada isi sehingga hilang manfaat kebahasaannya.
“Sastrawan kita hanya mengandalkan isi, tapi tidak pada keterampilan menguasai bahasa. Jadi ya tidak bisa berkembang secara pesat,” ucap Sapardi menyoal fokus melenceng dari banyak penyair, meski gelagat itu disebutnya telah membaik.
Padahal, tak jarang puisi-puisi tersebut hanya menjadi repertoar di kerumunan kawanan politisasi puisi, yang kemudian Sapardi sebut tak jarang dan tak lebih dari sekedar “lebah tanpa sengat”.
Maka Sapardi tak lagi pusing ketika ditanya apa sebetulnya yang bisa disumbangsihkan oleh golongan penyair ke peradaban.
“Penyair, penulis cerita pendek, novelis itu kan namanya seniman bahasa, yang dihasilkan dengan seni bahasa. Dia tidak bisa berbuat lain kecuali memperbaiki bahasanya,” ucapnya kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (8/6).
“(Jadi hasilnya) bukan pemikiran atau filsafat yang baru. Atau moral yang baru, itu urusan kiai. Atau budi pekerti, itu urusan guru. Tapi urusan penyair adalah bagaimana menyegarkan bahasa yang sudah dikotori oleh sesuatu seperti sekarang,” kata dia.
Mungkin Sapardi teringat kondisi di awal dekade 60-an, ketika penetrasi huru-hara politik sampai terasa ke panggung kebudayaan dan sastra.
Menurut Hasan Aspahani dan Bakdi Soemanto dalam bukunya, Sapardi Djoko Damono: Karya dan Dunianya, Sapardi merupakan penandatangan dokumen Manifesto Kebudayaan.
Hasan juga menyebut, Sapardi harus mengalami masa represi: ia menulis dengan nama samaran dan berhenti mengajar karena mendapat tudingan-tudingan dari pihak sebelah.
[Baca juga: Kata Mereka tentang Puisi Sapardi Djoko Damono]
September 1963, sekumpulan seniman dan cendekiawan menandatangani dokumen Manifesto Kebudayaan, yang sering dicibir dan disingkat dengan sebutan Manikebu (sperma kerbau). Lewat Manifesto Kebudayaan, para seniman itu menggugat kondisi kebudayaan, termasuk sastra, yang saat itu selalu harus diujungpangkalkan ke dalam politik.
Saat itu, harian resmi Partai Komunis Indonesia (PKI), Harian Rakjat, dan Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) sebagai underbouw-nya kurang lebih menguasai palagan sastra nasional. Apalagi ketika itu Sukarno tengah gencar-gencarnya memuja baris kiri politik, sementara seruan Njoto bahwa “Politik adalah Panglima!” itu diperdengarkan deras-deras: dominasi itu klop sudah.
Manikebu kemudian dicap kontrarevolusioner, dan penggeseran posisi pengusung Manikebu hingga kampanye sengit memojokkan mereka terjadi sampai pertengahan tahun 1965. Bahwa kemudian setelah peristiwa G30S sejarah berbalik arah dan PKI serta underbouw-nya macam Lekra dibantai habis-habisan oleh rezim Soeharto, tentu tetap harus disikapi dengan adil dan seterang-terangnya.
Meski tergolong ke satu sisi, karya-karya Sapardi cenderung lebih halus. Ia memeram amarah. Peristiwa puluhan tahun lalu itu baginya mungkin hanya sebuah episode yang nahas, tak perlu luka-dukanya ia teruskan ke karya-karyanya.
Ditanya penyair asal Kutai, Aspahani, pada wawancara tahun 2005, apakah seorang Sapardi memang berusaha menahan amarah, Sapardi enteng saja bercanda, “Ya, tentu. Orang marah hanya bisa demo, nggak bisa nulis puisi, hahaha.”
Karya Sapardi tetap tenang, berpusing pada hal-hal yang dianggap orang setia pada kesunyian dan dekat dengan kematian (misalnya pada sajak berjudul TBC yang menceritakan tentang ia yang menderita TBC dan kematian yang terasa begitu dekat. Puisi tahun 1961 tersebut diungkap dalam arsip-arsip puisi lawasnya pada Makassar International Writer Festival 2017 Mei kemarin).
Puisi-puisi Sapardi berdiri di tengah-tengah, antara konvensi dan avantgardisme sastra, menjadi titik moderat di antara dua kutub (misalnya saja Lekra vs Manikebu) yang saling hantam dan meniadakan.
[Baca juga: Sapardi dan Kisahnya tentang Hujan Bulan Juni]
Tapi mungkin dari pengalamannya itulah Sapardi bersiteguh. Baginya, seorang penyair dan sastrawan secara umum adalah orang-orang yang wajib punya kemampuan berbahasa lebih tinggi ketimbang orang rata-rata. Maka konsekuensinya jelas, karyanya harus terus melambungkan keadaan berbahasa yang ada saat ini, memperbarui terus dan terus.
Sapardi berucap, memang sudah seharusnya bahasa menjadi tujuan para sastrawan. Dan ini bisa dilakukan tak hanya lewat puisi, namun juga karya bahasa lain yang punya peluang membawa “bahasa baru”. Caranya, menurut Sapardi, adalah dengan pengamatan yang serius dan konsisten terhadap bahasa yang berkembang.
“Jadi begini, bahasa itu kan lisan. Dan bahasa lisan cepat sekali berkembang, tiba-tiba ada kata ciyus dan macem-macemlah,” beber Sapardi mencontohkan. “Dan kalau itu tertangkap oleh sastrawan, lalu ditulis, kan abadi dia. Nah, itu baru namanya salah satu cara untuk menyegarkan bahasa.”
Proses mengalihdimensikan bahasa yang beredar (dalam bentuk bunyi) menjadi sesuatu tertulis (menjadi kata --gambar dan simbol dari bunyi) membuat peran sastrawan seharusnya tak tergerus zaman.
Mereka yang punya kemampuan bahasa lebih tinggi itulah yang seharusnya punya usaha keras untuk meremajakan bahasa.
“Dengan demikian, dia secara langsung atau tidak langsung, memperbaiki, menyegarkan bahasa. Kalau tidak dia akan lecek (kusut) kan? Masa saya menulis dengan cara Chairil Anwar, siapa yang mau baca?” kata Sapardi.
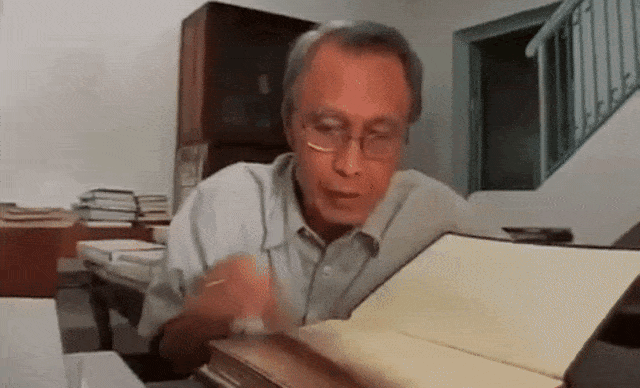
Bahkan, lanjut Sapardi, pengamatan yang dilakukan para sastrawan dengan memilih dan mencomot unit-unit bahasa ke dalam karya mereka, tak hanya berdampak baik buat sastra itu sendiri, namun juga Bahasa Indonesia secara umum.
Sastrawan, secara otomatis, memegang peran amat penting dalam menentukan masa depan bahasa nasional. Terutama menyikapi kemunculan unit-unit bahasa baru yang didominasi oleh kegiatan di dunia maya dan pergaulan anak muda, termasuk bahasa-bahasa yang kerap kita sebut dengan bahasa alay.
“Apa dikira bahasa sekarang bukan bahasa alay dulu? Kalau misalnya bapak saya mendengar saya ngomong, ya pasti ngamuk, ‘Ngomong opo?’” canda Sapardi.
Menurutnya, penggunaan bahasa-bahasa gaul anak muda harus disikapi dengan wajar.
“Sama dengan kalau kita marahin anak kita menggunakan bahasa yang aneh-aneh, itu ya kita yang salah, bukan anaknya yang salah. Memang bahasa harus berkembang dengan cara itu. Kalau perkembangannya itu tidak begitu benar, dia akan berhenti,” jelas Sapardi.
Dan memang demikian. Justru lewat pengucapan sehari-hari itulah debat bahasa terjadi. Kata-kata yang dianggap pantas akan bertahan, dan yang dinilai mengada-ada akan musnah.
“Dalam sejarah dan dunia kepenulisan di manapun, pembaruan sastra selalu berasal dari keinginan pengarang untuk mengambil, mengangkat bahasa lisan orang biasa itu ke dalam karya sastra,” katanya.
Sastrawan, menurut Sapardi, tak akan pernah mati.
Dalam setiap bulir kata yang terus direproduksi khalayak luas, napas mereka turut mewujud, tak surut.
