Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0

Louisa May Alcott, sastrawan asal Amerika Serikat, pernah menulis sebuah kalimat pada karyanya berjudul Jo’s Boys (1886).
“The youngest, aged twelve, could not conceal her disappointment, and turned away, feeling as so many of us have felt when we discover that our idols are very ordinary men and women.”
Mencatut dari keseluruhan cerita, kalimat di tahun 1886 itu kemudian menjadi sebuah ungkapan terkenal, yang intinya: never meet your hero. Jangan pernah temui pahlawan Anda.
Alasannya sederhana, namun kerap menimbulkan respons, “Ah, betul juga.”
Sebab, ketika Anda menemui orang yang benar-benar Anda kagumi, Anda hanya akan menemui rentetan kekecewaan. Kekecewaan tersebut akan muncul ketika Anda tahu bahwa pahlawan yang selama ini Anda puja adalah orang biasa saja.
Ia mungkin tak sepintar itu, ia bisa saja tak semenawan itu, ia bisa jadi hanya membual selama ini, dan sederet hal mengecewakan lainnya.
“Pahlawan hanyalah manusia, dan persepsimu yang sudah terlanjur baik tentangnya tak pantas dihancurkan kenyataan,” kira-kira begitulah pesan adagium tersebut.
Namun, ketika di siang hari itu Sapardi membalas SMS ajakan saya untuk bertemu dengan kata-kata singkat, “Boleh saja,” saya melonjak girang dan berkeras dalam hati, “Masa bodoh denganmu, Louisa. Tahu apa kau soal Sapardi!”
Dan bertemulah saya dengan Sapardi, Kamis lalu (8/6).
[Baca juga: Sapardi dan Kisahnya tentang Hujan Bulan Juni]
Menemui Sapardi adalah bentuk ikhtiar kumparan untuk mengabadikan fragmen hidup salah satu penyair terbesar Indonesia dalam 50 tahun terakhir itu.
Lihatlah bagaimana puja-puji terucap bagi Sapardi: Goenawan Mohamad pernah berkata, “Puisi-puisinya harus (karena layak) dicemburui,” Andries Teeuw berujar puisi-puisi Sapardi “sangat mengejutkan dalam segala kesederhanaannya,” dan Slamet Rahardjo dengan lugas berujar bahwa Sapardi, “Seperti puisinya saja, sederhana tapi mantap.”
[Baca juga: Kata Mereka tentang Puisi Sapardi Djoko Damono]
Sapardi disebut-sebut telah memperbarui dunia sastra Indonesia. Ia menjadi penengah antara konvensi dan avantgardisme sastra, menjadi titik moderat di antara dua kutub (dulu Lekra vs Manikebu) yang pada suatu masa pernah saling berebut panggung.
Saking berpengaruhnya, puisi-puisi Sapardi disebut-sebut menjadi pijakan bagi ribuan sastrawan lain yang lahir setelahnya untuk menemukan gaya bahasa mereka sendiri.
Meski begitu, mau-tak mau harus diakui, Sapardi terkenal karena beberapa butir puisinya yang melejit meninggalkan ratusan puisinya yang lain. Aku Ingin (1989), Hujan Bulan Juni (1989), Di Restoran (1989), Yang Fana Adalah Waktu (1978) dan Tuan (1980) adalah beberapa puisi yang melambungkan namanya. Beberapa karena penghargaan bertaraf internasional, beberapa karena musikalisasi puisi yang masyhur, dan beberapa lainnya karena seringnya mereka menjadi penghias di berbagai undangan pernikahan orang-orang.
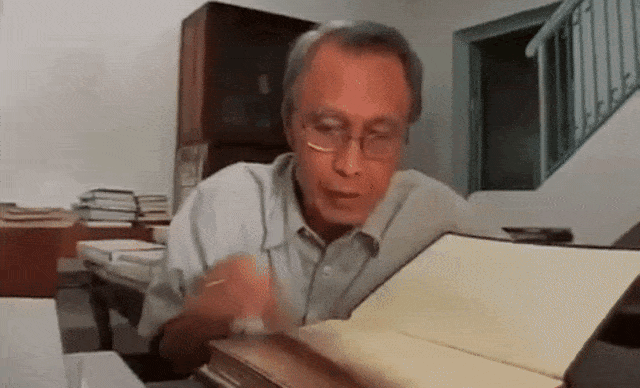
Meski akhirnya tak sampai satu jam kami bertukar kata-menyambung rasa, tetap saja banyak hal yang selama ini tersembunyi dan berhak diketahui publik.
[Baca juga: Ikhtiar Sapardi dalam Kelindan Bahasa]
Sayang sekali rasanya, apabila beberapa puluh tahun dari sekarang, seorang muda harus kesulitan ketika ingin mengetahui sosok di balik sastrawan besar zaman bapak-ibunya --sama ketika kita kesulitan merangkai jejak kehidupan Chairil Anwar di dekade 40-an.
Dan untuk alasan itu, juga separuh meromantisasi suasana dengan menautkan waktu wawancara di Juni yang basah ini, kami bersusah payah agar catatan sederhana nan tak seberapa ini sampai ke tangan Anda --dan mungkin ke beberapa generasi setelahnya.
Dan memelintir kata-kata ia-yang-sedang-kita-bicarakan saat ini, semoga betul: yang fana adalah waktu, Sapardi abadi.
